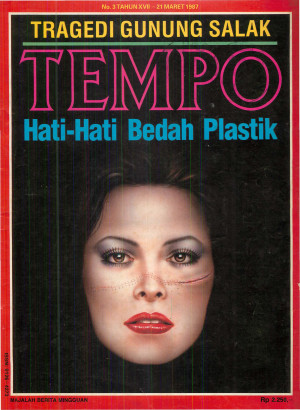PAK De, alias Romo, alias Srj, alias Siradjudin, tiba-tiba menjadi tokoh terkenal. Dukun dari Pasar Rebo, Jakarta Timur itu disangka sebagai pelaku pembunuhan Peragawati Dice Budimuljono dan seorang nyonya lain, Endang. Ia belum tentu bersalah: selain ia membantah, di luaran banyak cerita tentang kasus itu. Dan jangan lupa, tentunya, kepada asas praduga tidak bersalah. Tetapi Pak De telanjur menjadi gunjingan. Berbagai media massa membuat gambar, identitas, dan profilnya dalam berbagai gaya: ada yang menyingkat namanya, ada yang memuat fotonya dengan mata tertutup, ada yang memuat nama serta gambarnya terang-terangan. Pak De tidak protes, juga tidak marah. Di sela-sela persidangannya, ia malah bercanda dengan wartawan tentang kesebelasan Persebaya, favoritnya. Juga tidak ada protes dari belasan pengacaranya. Tetapi Dewan Kehormatan (DK) PWI, dalam siaran persnya, tiba-tiba memperingatkan media massa agar tetap mematuhi Kode Etik Jurnalistik, terutama pasal 3 ayat 7, yang menentukan pemberitaan sidang pengadilan harus menaati asas praduga tidak bersalah. Selain itu, kode etik mengingatkan agar penyiaran nama lengkap, identitas, dan gambar seorang tersangka dilakukan dengan penuh "kebijaksanaan" (pasal 3 ayat 8). Sebelum soal Pak De, sejak Agustus 1986 sampai dengan Februari 1987, tidak kurang dari 29 buah peringatan dikirimkan DK PWI ke berbagai penerbitan di tanah air karena soal asas itu. Menurut Dewan, ke-29 penerbit itu dalam periode tersebut telah melanggar Kode Etik Jurnalistik: menyiarkan nama dan identitas pelaku kejahatan dengan lengkap. Tentu saja peringatan itu mengagetkan. Soalnya, sejak kode etik dilahirkan, baru kali ini pemberitaan nama lengkap dan foto seorang terdakwa menjadi soal serius. Asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), yang mendasari hukum pidana kita, menunjuk kepada pengertlan bahwa tidak seorang pun dianggap bersalah sebelum ditentukan demikian oleh putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Asas itu sebenarnya lebih ditujukan kepada para penegak hukum, baik polisi atau jaksa maupun hakim. Berkat asas itu, polisi tidaklah perlu memukuli seorang tersangka hanya untuk mengorek keterangannya jaksa janganlah terlalu berambisi, menghalalkan semua cara demi membuktikan tuduhan yang dibuatnya dan hakim, lebih penting, diharap tidak menyimpulkan kesalahan si terdakwa sebelum perkara diperiksanya. Tapi bagaimana dengan pers? Tidak satu pun ketentuan hukum mengatur cara wartawan memberitakan jalannya sidang. Alih-alih dari itu, hukum acara perkara pidana Indonesia bahkan tegas memegang prinsip "persidangan terbuka untuk umum" -- kecuali dalam perkara anak-anak dan kasus susila. Tujuannya tak lain agar masyarakat, juga pers, bisa mengontrol jalannya pengadilan, termasuk ditaati atau tidaknya asas praduga yang tadi itu. Bukankah tidak bisa dipungkiri bahwa media massa berperan besar dalam mengungkapkan praktek-praktek tercela di pengadilan? Di awal persidangan yang terbuka itu jaksa akan menyebutkan nama lengkap terdakwa berikut aliasnya, alamat, pekerjaan, bahkan tempat lahirnya. Begitu pula ketika terdakwa dituntut hukuman atau divonis. Para wartawan, yang bebas hadir dalam sidang, selain diizinkan memotret juga sering diberi kesempatan oleh majelis hakim mengabadikan tersangka, sebelum pemeriksaan mulai. Adakah dengan praktek seperti itu hakim, jaksa, bahkan pembela, melanggar asas praduga tidak bersalah? Begitu pula pers yang memberitakan fakta-faktanya? Atau masyarakat yang menyaksikan Jalannya sidang dan kemudian menceritakannya kepada tetangga? Pelanggaran baru terjadi, tentunya, bila hakim belum-belum sudah berpihak kepada jaksa. Atau bila pers belum-belum sudah memojokkan terdakwa. Bagi pihak terakhir itu, kenyataan bahwa seseorang yang kebetulan duduk di kursi pesakitan harus dianggap tidak bersalah -- dan memang punya kemungkinan divonis bebas sebelum jatuh keputusan haklm yang berkekuatan tetap, haruslah tercermin dari berita dan tulisan yang didapat dari liputan sidang. Pembuat Kode Etik Jurnalistik memahami hal itu. Sebab itu, kode etik tadi hanya menyebut keharusan media massa menghormati asas praduga tidak bersalah dan "bijaksana" dalam menyiarkan nama lengkap, identitas, dan gambar terdakwa -- tanpa larangan yang tegas untuk memuat nama lengkap, antara lain. Dengan kata bijaksana, sebenarnya telah diletakkan kepercayaan yang besar kepada pers untuk berbuat. Ke-bijaksana-an pemberitaan berarti pers jangan ikut-ikutan jadi hakim, jangan pula kepingin jadi pembela. Dan harus bisa, idealnya, menempatkan diri sebagai pelapor obyektif. Dan sikap obyektif yang dituntut itu jelas tidak akan terjamin dengan terutama penulisan nama terdakwa dengan inisial, misalnya, atau penutupan foto terdakwa dengan garis hitam. Tanpa foto pun, dan dengan seribu singkatan nama, pers bisa saja mencari berbagai ulah memojokkan seorang tersangka -- seperti juga bisa bersikap netral, sesuai dengan asas praduga, kendati memuat nama lengkap dan gambar terang-terangan. Kebijaksanaan seperti itulah, tentunya, yang lebih sesuai dengan prinsip pers yang "bebas dan bertanggung jawab". Apalagi para terdakwa, terutama tokoh-tokoh terkenal (Dharsono, Fatwa, dan Widodo Sukarno, misalnya) barangkali saja akan merasa lebih terhormat bila foto diri mereka tampil di media massa dengan safari dan senyum mengambang -- ketimbang foto dengan adegan mereka diseret polisi dengan mata tertutup. Kendati hanya dengan nama inisial, siapa, sih, yang tidak kenal mereka? Di Amerika Serikat, Inggris, dan negara Anglo Saxon lain tidak seorang pun diperkenankan memotret di ruang pengadilan. Ini sekadar bandingan. Tapi wartawan di sana bebas mengabadikan tersangka di luar ruangan sidang -- dan, tentu saja, memuat nama lengkap berikut foto-fotonya di koran mereka. Bahkan persidangan perkara anak-anak, yang untuk pers kita ditabukan dimuat, nama lengkap dan foto si tersangka -- di Amerika -- diperkenankan dipasang. Akibat kebijaksanaan pemberitaan seperti itu pulalah kita, di Indonesia, bisa mengenal John Hinckley yang dituduh mencoba membunuh Presiden Ronald Reagan, atau para terdakwa narkotik di Malaysia. Dari beberapa negara Eropa Kontinental, tempat pers juga diperkenankan memotret di ruang sidang (aliran yang dianut sistem peradilan kita), para pemirsa TVRI bisa menyaksikan suasana persidangan para tersangka mafia di Italia. Padahal, harus diakui, kekuatan pers Barat -- Amerika, terutama -- dalam membentuk opini masyarakat melebihi pers kita. Tidak ada yang menuduh mereka telah melanggar asas presumption of innocence -- asas yang, hanya sebagai rumusan, kebetulan saja kita impor dari dunia belahan sana. Juga dalam semangat Pancasila, hanya dengan cara terbukalah -- dan bukan cara lain -- media massa bisa mengemban tugas informasi dan kontrol sosialnya, sambil memegang peranan dalam proses penegakan hukum. Barangkali diperlukan sebuah diskusi mendalam untuk ini? Bayangkan, andai kasus Pak De baru bisa diberitakan secara utuh setelah perkara itu mendapat vonis dari Mahkamah Agung, mungkin sekitar lima tahun lagi. Bagaimana sebenarnya menerjemahkan rasa keadilan hukum, khususnya kepada para tersangka, sekaligus melayani hak para warga negara untuk tahu, tanpa sekadar terjatuh ke dalam kungkungan huruf-huruf yang formalistis?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini