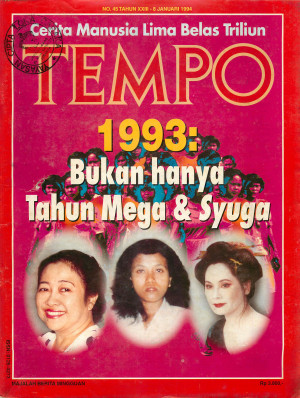PROF. Dr. Komar Kantaatmaja, 53 tahun, mencuat namanya tatkala ia tampil piawai di Pengadilan Tinggi Singapura dalam kasus gugatan harta peninggalan H.A. Thahir. Jurus hukum yang dilemparkan oleh guru besar hukum internasional Universitas Padjadjaran yang kala itu bertindak sebagai anggota tim ahli hukum Pertamina ini membuat kubu Kartika -- istri almarhum Thahir -- mati langkah. Sebagai saksi ahli ia ikut menentukan kemenangan Pertamina dalam perebutan harta peninggalan sebesar US$ 78 juta itu. Selain mengajar, bersama bekas Menteri Luar Negeri Prof. Mochtar Kusuma-Atmadja, ia membuka kantor law firm. Sejumlah perusahaan besar menjadi klien dia. Untuk mengetahui gambaran sebagian wajah hukum dagang Indonesia, wartawan TEMPO Aries Margono berkesempatan berbincang-bincang dengannya, di kantornya yang mewah, di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta. Petikannya: Hukum dagang (KUHD) kita, siapa pun tahu, sudah jauh ketinggalan dibanding negara maju. Tapi, bagian apa saja yang dirasa paling lemah, yang tak bisa mengantisipasi gerak zaman? Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel) kita sudah satu abad lebih usianya, tentu saja amat ketinggalan. Di Belanda sendiri, kitab undang-undang itu sudah diubah. Yang diatur dalam KUHD adalah lebih bertumpu pada masalah-masalah yang muncul saat itu. Soal hipotek kapal terbang, mana ada? Juga yang menyangkut modal ventura, sama sekali tak disinggung. Kalaupun ada peraturan perseroan terbatas (PT), belum memadai sama sekali, karena yang disebut PT di situ, share-nya masih kecil. Dalam peraturan tentang PT, yang harus dilindungi adalah pemegang saham. Jadi, bagaimana supaya direktur kelakuannya tidak merugikan pemegang saham. Kalau sekarang diberlakukan, jelas sudah tidak klop. Sebab, yang dilindungi bukan cuma pemegang saham, tapi bagaimana mengatur secara baik hubungan dengan pihak ketiga. Di sektor itulah yang kini sering timbul masalah. Dulu lebih menekankan perlindungan intern, tapi sekarang lebih bersifat ekstern. Bagaimana peraturan yang menyangkut kepailitan? Dalam aturan yang ada, kalau ada PT yang mau pailit, ya, pailit saja, karena yang dimaksud PT adalah modal kecil. Tapi dalam kasus Bank Summa, kita banyak mengambil pelajaran, terutama yang menyangkut "perasaan hukum" kepailitan. Seharusnya ketentuan-ketentuan kepailitan dibedakan antara perusahaan yang menghimpun dana masyarakat, perusahaan BUMN, perusahaan yang go public, dan PT yang dimiliki antarprivat. Jika perusahaan penghimpun dana pailit, yang menjadi korban akhirnya memang nasabah. Waktu Bank Summa ambruk, banyak yang teriak harus mendahulukan kepentingan umum. Tapi apa yang dimaksud kepentingan umum? Prioritas utama adalah pajak, kemudian pegawai bank, kredit yang pakai agunan hipotek, utang- utang preferen, dan kalau ada sisa baru nasabah. Menurut undang-undang kepailitan, memang seperti itu aturannya. Jika ini dibiarkan, saya khawatir bisa membuat resah orang yang mendepositokan uang ke bank, karena jika bank bangkrut ia dipaksa ikut menanggung. Kembali ke peraturan PT. Sejauh mana pengaruh kelemahan itu terhadap transaksi bisnis? Jelas, berpengaruh sekali. Peraturan tentang PT kita dasarnya adalah aturan-aturan tua, yang menyebut bahwa PT itu modalnya kecil, dan dibuatnya harus di hadapan notaris dengan biaya yang sudah ditentukan, sekian permil dari modal. Jika modalnya kecil seperti yang dimaksud dalam KUHD, tak soal. Tapi sekarang kan kebanyakan yang dihadapi perusahaan multinasional dengan modal miliaran rupiah. Akibatnya, jika ada transaksi besar, mereka tak menggunakan hukum Indonesia, tapi kebanyakan Singapura. Kalau pajaknya dirasa besar di Singapura, masih bisa lari ke Irlandia yang terkenal kecil. Lihat saja Garuda atau Sempati, mereka juga melakukan perjanjian hukum di luar Indonesia karena di sini ongkosnya terlalu tinggi. Selama ini banyak transaksi multinasional yang menundukkan diri pada hukum asing. Apakah karena mereka kurang percaya pada sistem hukum di Indonesia? Mungkin. Ada proses hukum di sini yang sering jadi sorotan. Contohnya, dikalahkannya bank asing dalam sengketa utang- piutang dengan nasabahnya. Masalahnya, karena pinjaman itu tidak dilaporkan ke Bank Indonesia seperti disyaratkan. Padahal, itu kan cuma kewajiban administratif yang tidak menyebabkan batalnya perjanjian. Ternyata, hakim menilai itu masalah substansial sehingga pinjaman dibatalkan. Logikanya orang utang kan harus mengembalikan? Kasus semacam itu bisa membuat kapok bank asing. Dalam kasus yang sama, anehnya, di Indonesia hakim yang satu sering berbeda keputusan dengan hakim yang lain. Akibatnya, pencari keadilan sulit mencari pegangan hukum. Selain itu, juga menyangkut budaya masyarakatnya. Umumnya kita ke pengadilan tujuannya hanya satu: ingin menang. Karena yang menjadi tujuan menang, mereka berusaha menempuh segala cara. Kendati kalah, maunya juga menunda kekalahan dengan melakukan banding sampai kasasi, yang memakan waktu. Lain dengan masyarakat maju. Mereka datang ke pengadilan tujuannya mencari keadilan. Hal-hal seperti di atas itulah yang kemudian mempengaruhi pilihan hukum investor asing. Untuk masa datang, bagaimana mengejar ketertinggalan di sektor hukum? Diperlukan pakar total. Bisa dicontoh dalam pengembangan teknologi dan ekonomi. Bidang teknologi ada Habibie yang didukung oleh Dewan Riset Nasional, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, ada BPIS, juga IPTN. Hampir semua yang diputuskan oleh badan pendukung pengembangan teknologi dilaksanakan Pemerintah. Bidang ekonomi juga beruntung karena memiliki pemikir semacam Prof. Widjojo Nitisastro. Ia didampingi oleh sejumlah ahli, dan hasil keputusannya juga mendapat dukungan Pemerintah. Di lapangan hukum kita memerlukan orang semacam itu, yang energik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini