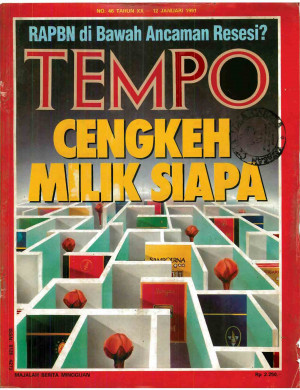NASIB buruk menimpa Ardaniah, 17 tahun. Karena lamaran Salim, 21 tahun, yang sudah lama naksir dirinya ditolaknya, ia tewas ditusuk tetangganya itu di Pasar Payung, Kandangan, Kalimantan Selatan, pertengahan Desember lalu. Sedangkan Ridwan, kernet oplet, terpaksa masuk rumah sakit di Palembang gara-gara soal sepele. Seorang calo di Terminal Lemabang di kota empek-empek itu, karena tak diberinya uang Rp 100, menusuk perutnya dengan pisau. Rupanya, pisau merupakan barang yang hampir selalu ikut dalam kegiatan sehari-hari bagi penduduk. Kalau pembawa pisau terpepet, senjata ini spontan bicara. Inilah salah satu yang membuat Sumatera Bagian Selatan menduduki peringkat pertama dalam angka pembunuhan. Diperkirakan, seperlima dari total pembunuhan di Indonesia terjadi di daerah ini. "Penyebab paling mendasar karena ada kebiasaan masyarakat membawa senjata tajam," kata Mayjen. Putera Astaman, Kapolda Sumatera Bagian Selatan, beberapa waktu lalu. Hal serupa juga terjadi di Banjarmasin, hingga membuat kesal Kapolresta Letkol. Alfian Anwary. Setiap hari karena cekcok sedikit saja jatuh korban akibat tusukan. "Kalau diadakan razia, mungkin bisa didapat sekarung senjata tajam dan keris dalam sehari," kata Alfian kepada Almin Hatta dari TEMPO. Sepanjang 1990 di wilayah Polda Kalimantan Selatan dan Tengah terjadi 423 kasus penganiayaan berat. Hampir semua kasus itu berupa penusukan dengan keris dan belati. Pelakunya berusia 18 sampai 40 tahun. Menurut Drs. H. Ramli, Kepala Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional Kanwil Departemen P dan K Kalimantan Selatan, bagi orang Banjar membawa senjata tajam itu arena kebiasaan. Mereka merasa aman kalau ada keris di pinggangnya. "Ini sebagai pakaras, mempertebal rasa percaya diri, sama seperti orang-orang tua Banjar yang memakai kopiah atau peci. Boleh jadi kebiasaan itulah yang berlangsung hingga sekarang, apalagi kalau senjata dianggap punya nilai magis," kata Ramli. Kebiasaan membawa senjata tajam ini menarik perhatian Mustafa Abdullah, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Bersama timnya, 1988, ia meneliti selama empat bulan untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan alasan memakai senjata. Penelitian dilakukan pada 600 lelaki usia 15 tahun ke atas. Mereka diambil dari tiga daerah yang diduga penduduknya biasa membawa senjata tajam, yaitu Kota Madia Palembang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kecamatan Pagaralam di Kabupaten Lahat. Responden dibagi dua kelompok, yang berpotensi menggunakan senjata dan biasa membawanya. Sedangkan yang tidak potensial lagi memakai senjata yang dibawanya, yaitu para tahanan yang masuk bui karena aksinya memainkan senjata tajam. Kalangan yang berpotensi misalnya penjual senjata tajam, kepala desa, atau eks kepala adat. Kepala adat, yang disebut pasirah itu, dipilih karena umumnya mereka memiliki keris pusaka. Untuk para tahanan diutamakan yang memiliki sosial budaya di tiga daerah terpilih. Hasilnya, responden menganggap senjata tajam adalah alat yang mutlak dimiliki sebagai pelengkap pakaian sehari-hari. Ini terbukti dengan banyaknya responden mempunyai senjata. Bahkan, di Pagaralam jumlahnya 92%. Walau memiliki senjata tajam ini sudah mentradisi, tak semua responden terbiasa membawanya bila ia keluar rumah. Motivasi utama yang mendorong para lelaki itu membawa senjata adalah untuk bela diri. Sekitar 68% responden membawa alat itu di pinggang, diikat di kaki, atau dimasukkan dalam tas. Yang lainnya (11%) menyebutkan alat itu bisa dipakai setiap saat, 18% mengatakan alasan lain, dan hanya 3% yang menyebutnya untuk "kepuasan" diri. Kebiasaan seseorang memiliki dan membawa senjata tajam tidak dipengaruhi faktor umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan status perkawinan. Penggunaan senjata tajam amat dipengaruhi nilai sosial budaya masyarakat atau kelompok kerabatnya. Istilah seganti setungguan di Pagaralam adalah refleksi adat setempat untuk menjelaskan "nyawa ganti nyawa". Di masyarakat pun, terutama yang jauh dari pusat kota, masih ada anggapan: yang berani berkelahi dan membunuh adalah orang yang top dan dianggap pahlawan. Ini terbukti dari motif kejahatan penggunaan senjata tajam di Sumatera Bagian Selatan selama 1983-1986. Hanya 33% kejahatan bermotif ekonomi. Sisanya, setelah diteliti, menunjukkan hubungan antara motif ekspresif dan pembelaan diri. Para korban perampokan, misalnya, berpendapat lebih baik "mendahului membunuh daripada dibunuh". Banyaknya alasan memiliki dan menggunakan senjata tajam ini membuat pihak Polda sampai melancarkan Operasi Senjata Tajam Juli 1988-Juli 1989. Operasi yang diikuti razia itu sukses. Ketika ada razia di stasiun kereta api, 21 Juni 1989, dari 1.890 penumpang hanya 8 orang yang membawa senjata tajam. Di akhir operasi, beberapa kawasan di Palembang dinyatakan bebas senjata tajam. Namun, operasi ini tidak menyelesaikan masalah. Terbukti dari tindakan kriminal penggunaan senjata tajam selama 1989 disita 2.689 senjata. Ini meningkat. Tahun sebelumnya 2.064 buah. Seharusnya, ujar Mustafa Abdullah, penyelesaian kebiasaan ini dilakukan secara bertahap. Operasi senjata tajam tak dilakukan sekali gebrak, tapi secara terus-menerus di daerah yang disebut sebagai calon kantong bebas senjata. Setelah terlaksana, baru ada pemberitahuan tentang daerah kantong tersebut dan terakhir kantong itu benar-benar sudah sebagai daerah bebas senjata. Polda Sumatera Bagian Selatan bukannya diam saja dengan terus meningkatnya penggunaan senjata tajam. Sampai sekarang, mereka masih terus mengadakan razia dengan rutin dan cukup banyak yang kemudian diproses di meja hijau. Rata-rata mereka diganjar 3-4 bulan penjara. Menurut tim peneliti dari Universitas Sriwijaya, penyelesaian tuntas masalah ini yakni mempersiapkan kondisi masyarakat ketika sanksi diterapkan. Untuk itu, kebijaksanaan yang dikeluarkan harus memperhatikan nilai sosial budaya masyarakat setempat. Diah Purnomowati, Bersihar Lubis, dan Aina Rumiyati Aziz
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini