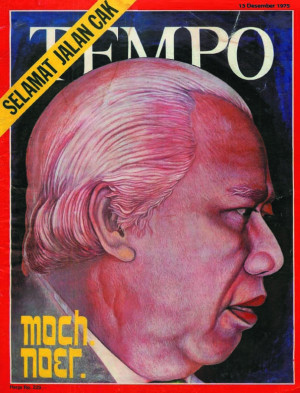INGAT Adolf Eichmann? Ia seorang petinggi Jerman Nazi, yang 14
tahun yang lalu telah dihukum oleh pengadilan Distrik Jerusalem.
Setahun kemudian Mahkamah Agung Israel menguatkan putusan
pertama. Eichmann, yang kala itu berada di dan sudah jadi
warganegara Argentina, tidak diserahkan Argentina (kepada
Israel) atas dasar perjanjian ekstradisi. Adolf yang Eichmann
diculik oleh sekelompok pemuda Yahudi militan.
Westerling, yang lari ke Singapura tahun 1950, pernah dimintakan
ekstradisi oleh Indonesia. Rupanya negara peminta ingat akan
adanya perjanjian ekstradisi antara Inggris dan Belanda, pada
saat Nusantara masih bernma Hindia-Belanda. Atas dasar pasal II
Aturan Peralihan UUD 45, Indonesia menganggap Perjanjian itu
tetap berlaku antara Indonesia--sebagai penerus Hindia
Belanda--dan Inggeris. Pemerintah Singapura, waktu itu jajahan
Inggeris, menolak keberlakuan perjanjian tersebut. Ekstradisi
ditolak. Westerling terus kembali ke negerinya. Untung saja, ia
tak sempat mengalami nasib penculikan seperti halnya Eichmann,
walaupun ia dituduh keras melakukan pembantaian terhadap rakyat
Indonesia di Sulawesi Selatan.
Belum Pecah Kabar
Penyerahan penjahat primer dilakukan lewat perjanjian bilateral.
Ia merupakan acara tersendiri hubungan antar bangsa. Bagaikan
jembatan emas ia menghubungkan antara dua negara dalam
mengusahakan atau menciduk pelaku-pelaku kejahatan, yang akibat
kemajuan teknologi dapat berlenggang-kangkung dari satu tempat
ke tempat yang lain. Dalam perkara Factor v. Laubenheimer,
1933, ditunjukkan bahwa prinsip hukum internasional tak mengenal
acara penyerahan yang terpisah dari perjanjian Pandangan umum di
AS bahkan sampai mengatakan, tak ada kekuasaan yang dapat
menyerahkan penjahat ke negeri lain tanpa adanya perjanjian
(walaupun tentu ada kekecualian). Kalaupun dulu-dulunya ada
negara yang menyerahkan seorang penjahat, maka itu hanya
merupakan kewajiban moral saja.
Jembatan emas pertama telah dibangun Indonesia dan Malaysia.
Indonesia malah sudah mengundangkan perjanjian itu, disebut
sebagai Undang-Undang Nomor 9 tahun 1974. Sekarang sedang direka
perjanjian serupa oleh Indonesia dan Pilipina, dan baru bulan
lalu para Ketua Delegasi Indonesia dan Muangthai memarap
kesepakatan mengenai hal sejenis. Dengan Singapura? Belum pecah
kabar, biar sudah ada kasus Westerling, biar arus interaksi
antara kedua negara berseberangan itu tidak tanggung-tanggung.
Bob Liem
Di luar rentang ASEAN, kabarnya Australia juga sudah didekati.
Maklumlah Indonesia toh titian antara benua atas dan benua
bawah. Terbunuhnya kapten kapal Waikelo di pelabuhan Hongkong
beberapa tahun lalu, plus mengganasnya pembunuh Bob Liem di
tempat yang sama, agaknya cukup mengalihkan perhatian orang pada
Hongkong - artinya pada Inggeris. Pada kasus pertama si
tersangka diserahkan kepada pemerintah Indonesia lewat proses
deportasi alias pengusiran. Dalam hal Bob Liem harus diakui
usaha Polri via Interpol (namun organisasi kepolisian
internasional itu, gagal mendekati pemerintah Austria untuk
menyelesaikan penyerahan Tan Tjong Hoa, yang dituduh terlibat
dalam manipulasi bank). Sementara itu? seperti dikatakan Letnan
Kolonel Sidarto, Kepala Dinas Penerangan MABAK, kepada TEMPO dua
pekan lalu, yang dapat dilakukan fihak kepolisian hanyalah
pendekatan-pendekatan saja. "Resminya memang denganperjanjian
ekstradisi itu", tambahnya.
Sebagai perjanjian, apa mengapanya terserah pada dua fihak yang
punya urusan. Tak ada peraturan hukum internasional universil
yang mendikte mereka. Umumnya negara-negara menyerahkan
kebijaksanaan tersebut pada pemerintah mereka masing-masing.
Namun tak semuanya puas dengan kebijaksanaan eksekutif tersebut.
Lalu adalah undang-undang ekstradisi nasional. Tugasnya menjadi
kompas bagi pemerintah yang bersangkutan untuk melihat
kejahatan-kejahatan apa saja yang bisa ditawarkannya kepada
sebuah negara lain dalam perundingan ekstradisi. Belgia di tahun
1833, pertama sekali mempunyai perundangan ekstradisi lokal.
Tahun 170 Inggeris mengikuti. Saat itu, selama bertahun-tahun
publik Inggeris anti perjanjian ekstradisi, sebab hal itu
merupakan musuh besar terhadap kebebasan manusia perorangan, dan
juga terhadap kewenangan sebuah negara untuk memberikan suaka
kepada pelarian politik. Indonesia dicanangkan akan mempunyai
sebuah undang-undang ekstradisi nasional. Bersamaan dengan
pengajuan tiga Rancangan UU lain dua pekan lalu (tentang
Narkotik, Kejahatan dalam Penerbangan serta Perubahan
Undang-Undang Kewarganegaraan), RUU Ekstradisi diniatkan
menggantikan kedudukan Beslit Kerajaan tentang Penyerahan
Orang-Orang Asing 1883.
Tanpa Sais
Biar belum ada perundangan lokal, dalam hal berjanji pasal
ekstradisi dengan negara lain, Indonesia tidak lalu bagai sado
tanpa sais. Negara itu mengikatkan dirinya pada "azas-azas umum
yang sudah diakui dan biasa dilakukan dalam hukum internasional
mengenai ekstradisi", seperti terbaca dalam Penjelasan
Undang-Undang Pengesahan Perjanjian ekstradisi dengan Malaysia
di atas. Antaranya, pertama disebut azas kriminalitas ganda
(double criminality): bahwa jenis kejahatan yang bersangkutan
haruslah merupakan tindak pidana, baik menurut sistim hukum
Indonesia maupun Malaysia. Namun begitu. sekali Mahkamah Agung
AS, dalam menafsirkan perjanjian ekstradisi dengan Inggeris,
berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan tertuduh adalah
kejahatan yang dapat diekstradisi, walaupun perbuatan itu bukan
merupakan tindak pidana menurut hukum negara bagian minuis, di
mana tertuduh ditemui. Demikian kasus Factor v. Laubenheimer di
atas.
Kedua, azas bahwa pelaku kejahatan politik tidak akan
diserahkan. Ini prinsip baru. Sebab sebelum 1830, penjahat
politik ada juga yang diekstradisi. Tapi khalayak waktu itu
mulai memprotes tindakan semacam itu. Inggeris adalah kampiun
penentangnya. Mudah saja, kejahatan politik, punya hakikat yang
lain, tapi dalam, ketimbang kejahatan cabut nyawa orang,
misalnya. Lagipula apa itu kejahatan politik? Ada yang
membedakan antara kejahatan politik murni (seperti pengkhianatan
atau penghasutan) dan kejahatan politik nisbi (pembunuhan
sebagai akibat pemberontakan), walaupun kedua jenis itu galibnya
dikecualikan dari perjanjian ekstradisi. Pada kategori pertama,
ada tekanan pengertian pada perlawanan terbuka untuk menggaet
kekuasaan, sehingga masalahnya, bak kata Hakim Denman dalam
kasus Re Castioni, 1891, "apakah berdasarkan fakta-fakta, telah
jelas bahwa orang itu yang bertindak sebagai satu dari
sekelompok orang terlibat dalam tindakan kekerasan yang
mempunyai sifat politik dengan sebuah tujuan politik, dan
sebagai bagian dari gerakan politik". Sebuah kasus agak baru, Ex
parte Kolekzynski, 1955, menunjukkan bahwa ekstradisi ditolak
karena adanya konflik ideologi yang kencang. Pelaut-pelaut
Polandia telah menggagahi kapten sebuah kapal Polandia, dan
membawa kapal itu ke pelabuhan Inggeris untuk kemudian meminta
suaka di sana. Permintaan ekstradisi dari Polandia ditolak
Inggeris, karena pelaut-pelaut itu akan dihukum untuk
pelanggaran politik, jika mereka kembali ke negerinya. Dalam
pada itu pencabutan nyawa kepala negara atau anggota familinya,
umumnya tidak dimasukkan dalam jenis kejahatan politik.
Perjanjian ekstradisi Indonesia-Malaysia mencantumkan pandangan
demikian (pasal 3 ayat 2). Juga dalam konsep akhir perjanjian
ekstradisi dengan Pilipina.
Lalu ketiga, azas untuk tidak menyerahkan warganegara sendiri.
Banyak negara sependapat dengan azas ini, bahkan ada pula yang
mencantumkan dalam konstitusi mereka. Akan halnya Inggeris,
sebaliknya, di tahun 1879 telah menyerahkan seorang WN-nya
kepada Austria, dimana kemudian ia digantung. Orang tersebut
terbang ke Inggeris, setelah baru saja membunuh bininya di
Tyrol. Sedang pada hemat AS, kata "persons" juga mencakup WN
dari negara yang diminta untuk mengekstradisi, kecuali bila hal
sebaliknya dikatakan terus terang. Dari itu, tatkala di tahun
1910, Italia meminta diserahkannya Charlton - seorang WN
AS--dari negeri Paman Sam itu--sebab ia terlibat pembunuhan di
Italia--pemerintah AS mengabulkannya. Mahkamah Agung kemudian
menyokong sikap eksekutif ini - begitu tutur perkara Charlton v.
Kelly, 19 12.
Atau Pare-Pare
Teringat kembali pada Adolf yang Eichmann, ada sarjana yang
menilai bahwa dari waktu ke waktu, penculikan, pengusiran dan
lain-lain upaya telah menggantikan kedudukan perjanjian
ekstradisi. Praktek di AS, misalnya mempertontonkan bahwa
seseorang yang dibawa kembali dengan kekerasan atau tipu
muslihat, kemudian ditahan di AS, dapat diadili tanpa
mempersoalkan cara orang itu dibawa masuk ke negara pengadil.
Maka dalam Ker v. Illinois, 1886 Mahkamah Agung sana menolak
eksepsi bahwa pengadilan itu tidak punya yurisdiksi karena
hadirnya tertuduh disebabkan ia diculik. Pembela Eichmann pun
sempat bersuara hampir senada. Pemeriksaan terhadap pembantai
orang-orang Yahudi itu, di Israel dan setelah penculikannya dari
luar negeri, katanya bertentangan dengan hukum internasional dan
melampaui batas yurisdiksi badan peradilan Israel. Mahkamah
menjawab, dalam menilai kejahatan terhadap hukum sesuatu negara,
baik pengadilan di AS, Inggeris maupun Israel telah menganut
prinsip hukum yang mapan: bahwa kodisi penahanan serta cara
membawa kembali si tertuduh masuk ke dalam negara yang hukumnya
dilanggar, tidak relevan dengan pokok perkara yang dituduhkan
kepadanya. Dan pengadilan di negara-negara itu, kata Mahkamah
lagi, telah secara konsisten menolak memeriksa kondisi-kondisi
tersebut.
Dan Westerling, bagaimana kalau ia diculik, dulu, atau sekarang?
Bapak Hakim Ketua di Jakarta Pusat atau Pare-Pare mungkin akan
berpidato seperti hakim-hakim Israel di atas. Kepuasan yuridis
barangkali terteguk juga. Konsekwensi diplomatik sebaliknya,
dapat pula menyusul. Argentina dalam peristiwa Eichmann, sempat
menyampaikan protes ke Dewan Keamanan PBB berhubung penculikan
warganegaranya itu. Sambil menyatakan tiada maaf bagi kejahatan
terhadap umat manusia itu, Argentina mengingatkan, perbuatan
yang mempengaruhi kedaulatan suatu negara anggota PBB, bila
diulang akan membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.
Namun negara Amerika Latin itu tidak meminta dipulangkannya
Eichmann. Barangkali berfikir: buat apa, sih?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini