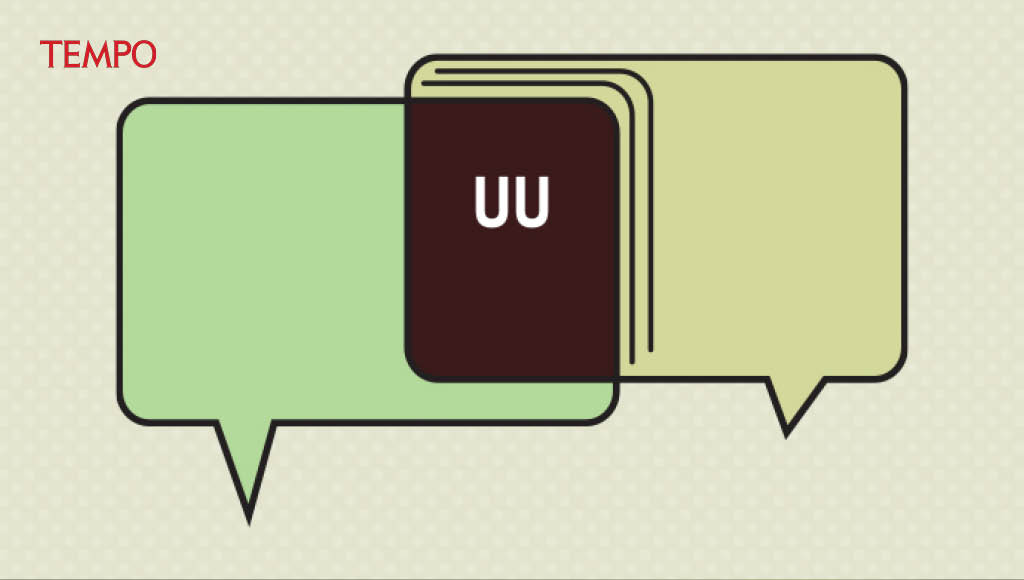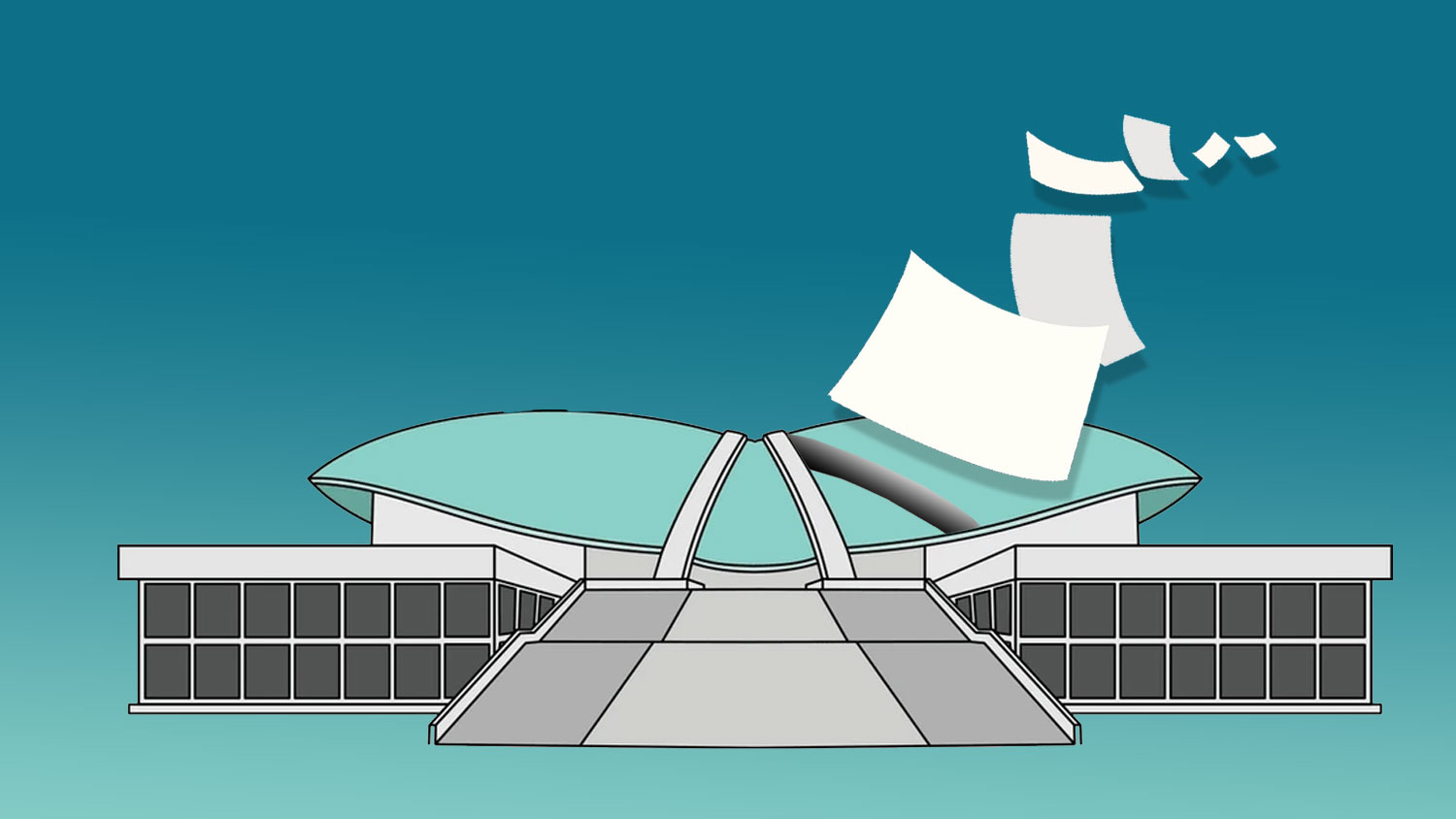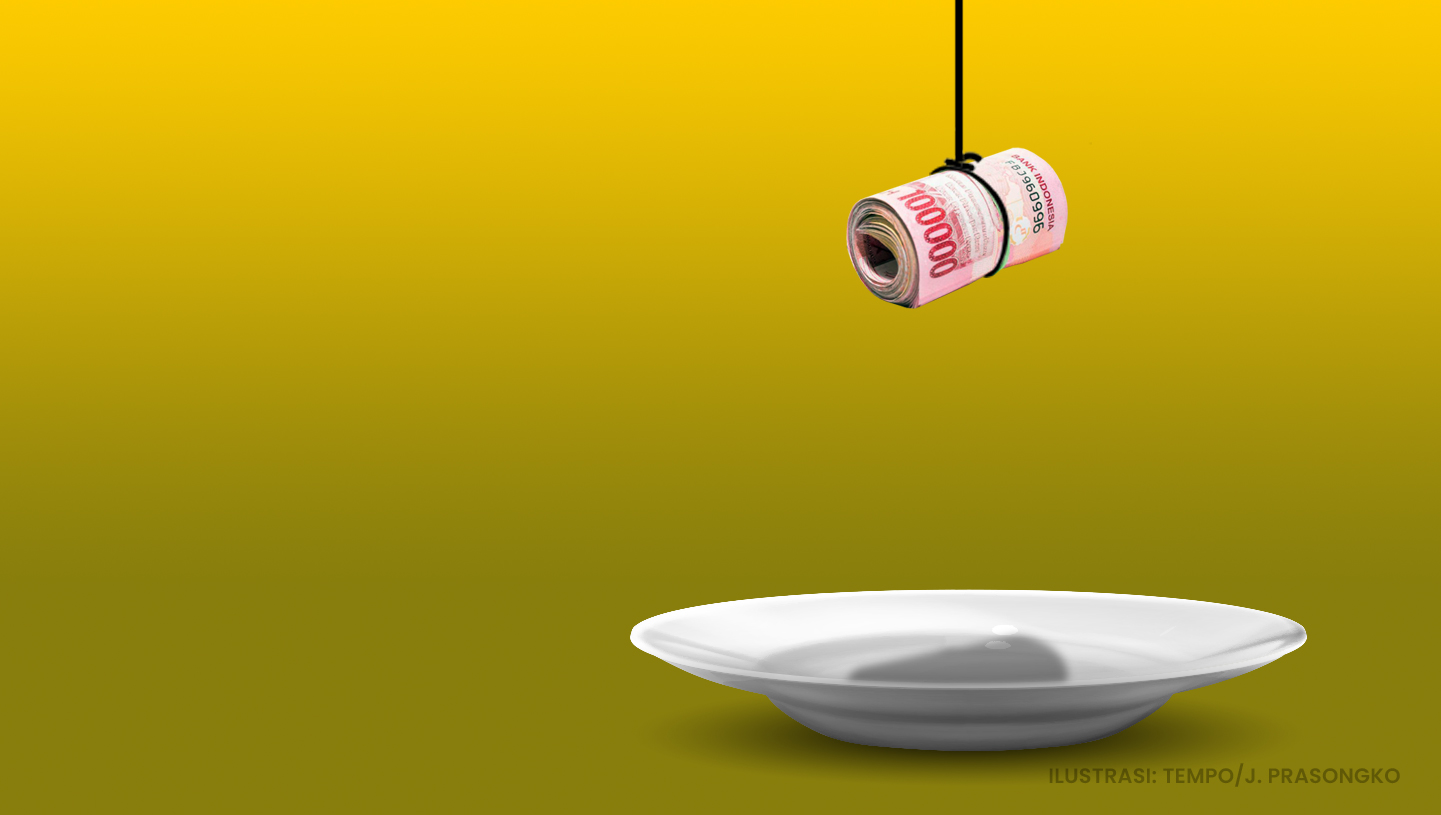Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
SAYA tak pernah ke Taman Mini. Maaf, saya koreksi: seumur hidup hanya satu kali saya ke Taman Mini Indonesia Indah, pada suatu malam, ketika mesti hadir dalam sebuah resepsi pernikahan. Saya akhirnya melihat salah satu bagian TMII dari dekat--hanya salah satu bagiannya. Itu di tahun 2016, hampir dua dasawarsa setelah Orde Baru runtuh.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sejak 1971, sejak “taman” itu berdiri, saya punya kaul tak akan datang melihat apa pun yang disajikan di sana selama Orde Baru berkuasa....
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Taman Mini dibangun dengan disertai protes--serangkaian protes yang dihentikan dengan kekerasan. Para mahasiswa, bersama sejumlah warga negara, menganggap rencana ambisius itu membuang-buang uang negara 10,5 miliar (angka rupiah di awal 1970-an) untuk sesuatu tanpa manfaat jelas bagi rakyat di pelosok-pelosok--tapi harus diadakan karena ini gagasan istri presiden yang tak bisa dibantah.
Dengan brutal protes dihentikan. Mahasiswa yang ikut dalam aksi menentang diserang pasukan setengah gelap. Ada yang terluka bacok, ada yang terluka tembak, beberapa orang ditahan, termasuk Arief Budiman.
Protes itu gagal. TMII dengan lancar dibangun.
Tentu, sejak itu ia telah menghibur jutaan orang. Tapi saya tetap tak ingin ke sana. Saya tak bisa untuk tak melihatnya sebagai sebuah Kitsch yang monumental. Kitsch: sesuatu yang berpretensi sebagai karya “klasik” tapi sebenarnya hasil selera buruk.
Di TMII, produk “budaya” itu memang buruk: malam itu, keluar dari resepsi perkawinan, saya datangi anjung “Jawa Tengah”. Saya lihat sebuah tiruan Borobudur: wagu dan mendesak ruang halaman yang sempit--sebuah tempelan yang tak perlu. Seluruh bangunan berusaha tampak eksotis, “ber-jawa-jawa”, tapi terasa kempis dan palsu. Sementara itu, ada sebuah gerbang mirip Istana Dongeng Disneyland didirikan, dengan warna oranye mencorong. Kitsch seluruh dunia bersatu. Dan sebagaimana produk selera buruk yang lain--seperti film sinetron di televisi--ia bisa menyenangkan orang banyak, tapi pada dasarnya hanya kehebohan yang kosong.
Sebuah Kitsch, ya, juga sebuah klise. TMII dibangun dengan konsep yang hanya mengulang-ulang ke-bhinneka-an yang beku. Ini kelanjutan cara penguasa Belanda melihat keanekaragaman “Hindia Timur”. Dengan tatapan kolonial, dengan hasrat menguasai secara efektif, penduduk kepulauan ini disusun jadi satuan-satuan etnis yang ajek.
Ada niat divide et impera dalam konstruksi itu. Tapi ini juga bagian rasionalisme birokrasi. Memerintah adalah mengontrol, mengontrol adalah membangun obyek yang “manageable”. Penguasa pun membuat kategori, taksonomi, “penggolongan” dari perbedaan-perbedaan yang ada. Dalam penggolongan ada abstraksi. Dengan abstraksi, ke-bhinneka-an atau “perbedaan” yang konkret dijadikan bungkusan yang rapi--tanpa konflik, tanpa hibriditas, tak bermutasi.
Dan kita membawa klise tua, bahwa Indonesia sebuah bangsa yang terdiri atas “suku-suku”. Tapi saya tak tahu (mungkin juga Anda tak tahu) sejak kapan pengertian “suku” lahir, bagaimana sebuah “suku” terbentuk, apa pula arti kata itu, dan dari mana sebuah “suku” dinamai, oleh siapa.
Saya sangat terkesan telaah dan penelitian Daniel Perret dari École française d’Extrême-Orient, yang dibukukannya dalam Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatra Timur Laut (terbit di Jakarta tahun 2010).
Perret membahas sebutan “Batak”. Di abad ke-18, “Batak” disebut sebagai sebuah “bangsa”. Seratus tahun kemudian istilah yang dipakai volk. Tapi konsep ini juga dianggap tak cocok mencakup pluralitas kenyataan; maka berlakulah kata volken, bentuk jamak. Kata “rakyat Karo” juga tak mencerminkan kenyataan di lapangan: di balik kesatuan yang kurang-lebih koheren itu “tersembunyi suatu keanekaan suku yang berasal dari berbagai daerah”. Maka “suku” Batak dalam kenyataan adalah “suku-suku Batak”. Bahkan dipersoalkan benarkah “agama Batak” sesuatu yang tunggal.
Mungkin sebab itu, seperti ditunjukkan Perret, sebutan “Batak” tak ada dalam sastra prakolonial. Pustaka Kembaren dan Pustaka Ginting, yang terbit akhir tahun 1920-an, tak memuat sebutan “Batak” atau “Karo”; nama marga saja yang disebut. Bahkan, dalam pustaka Toba ataupun Simalungun, tak ditemukan kata “Batak”. Seorang antropolog yang mengunjungi dataran tinggi Danau Toba pada awal abad ke-20 mencatat, tiap penduduk “Tanah Batak” selalu “menyebut dirinya sesuai dengan nama sukunya”. Sebutan “Batak” dimaksudkan buat semua orang yang berasal dari suku-suku lain, tanpa kecuali.
Tapi kini kita lupa itu. Kita mau gampangan. Administrasi wilayah, media massa, dan sensus mengabaikan betapa rumitnya identitas. Orang mau praktis. Maka arti “Batak” disederhanakan: “Batak” sama dengan “bukan-Melayu”, “bukan- Aceh”…sebaliknya, seterusnya. Dengan “dekonstruksi”, Perret menunjukkan identitas sebagai proses; maknanya selalu minta ditangguhkan. Tak ada definisi yang berlaku abadi, tak ada sifat dasar “Batak” atau “Aceh”, atau “Jawa”....
“Batak” hanya kita mengerti dalam différance.
Tapi Taman Mini tak mengerti itu. Beda dilambangkannya dengan sesuatu yang sudah jadi: bangunan rumah. Dalam hasrat orang-orang yang membangun TMII, identitas harus jelas. Bila perlu dengan mengabaikan yang lain: joglo mewakili Jawa Tengah, seraya melupakan rumah Kudus; rumah gadang Minangkabau membuat kita lupa ada Mentawai di Sumatera Barat. TMII mencerminkan pandangan yang hanya menerima hidup sebagai status quo--seakan-akan dalam tiap fenomena, dalam tiap beda, hanya ada sifat yang kekal.
Tapi kita tahu, status quo hanyalah stabilitas palsu. Zaman berubah. “Orde Baru” runtuh. TMII jadi banal. Meskipun Kitsch dan klise berlanjut, dan kita--sesuai dengan norak kita masing-masing--masih melihat keanekaragaman bangsa kaku seperti anjung-anjung Taman Mini.
GOENAWAN MOHAMAD
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo