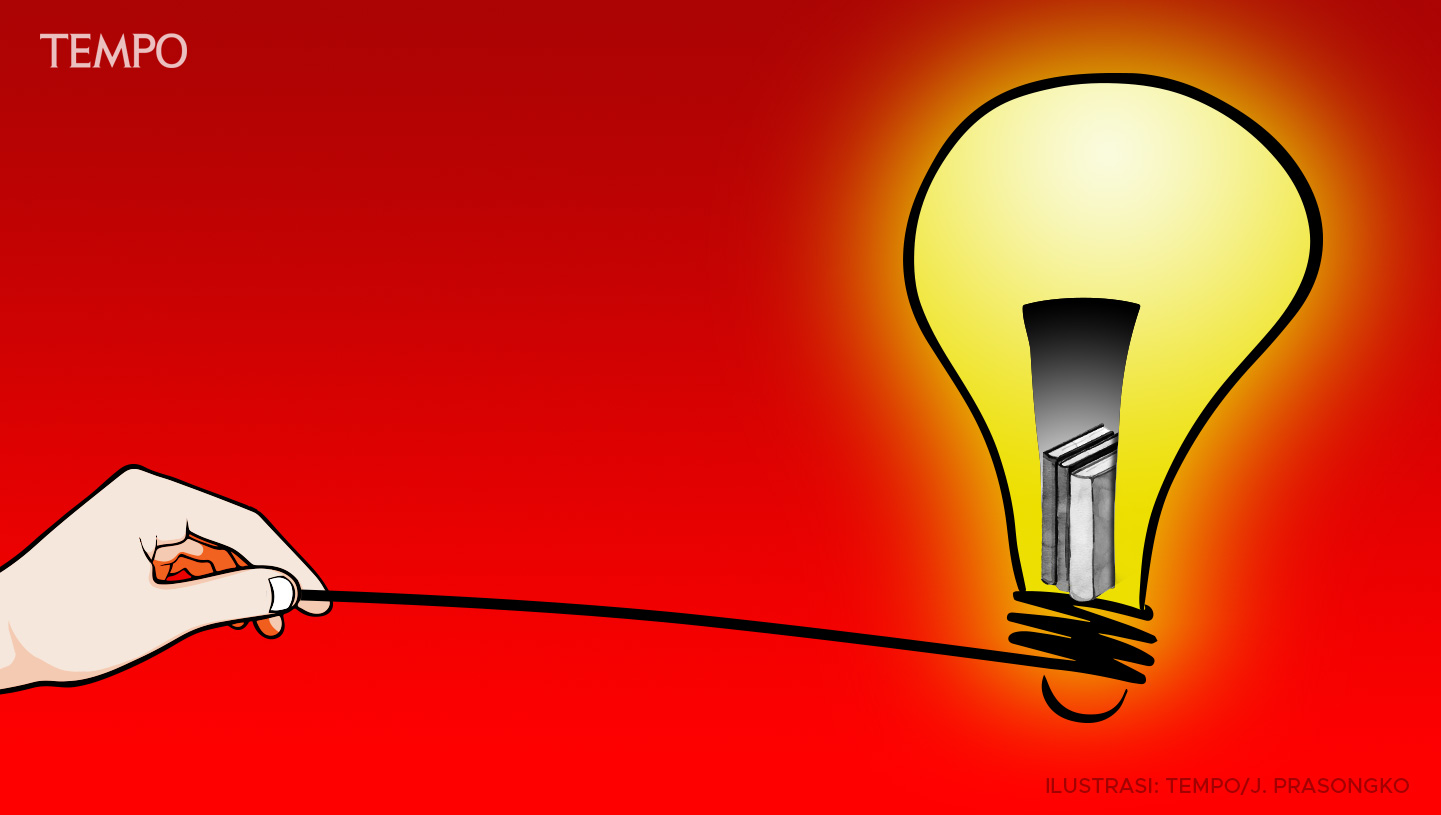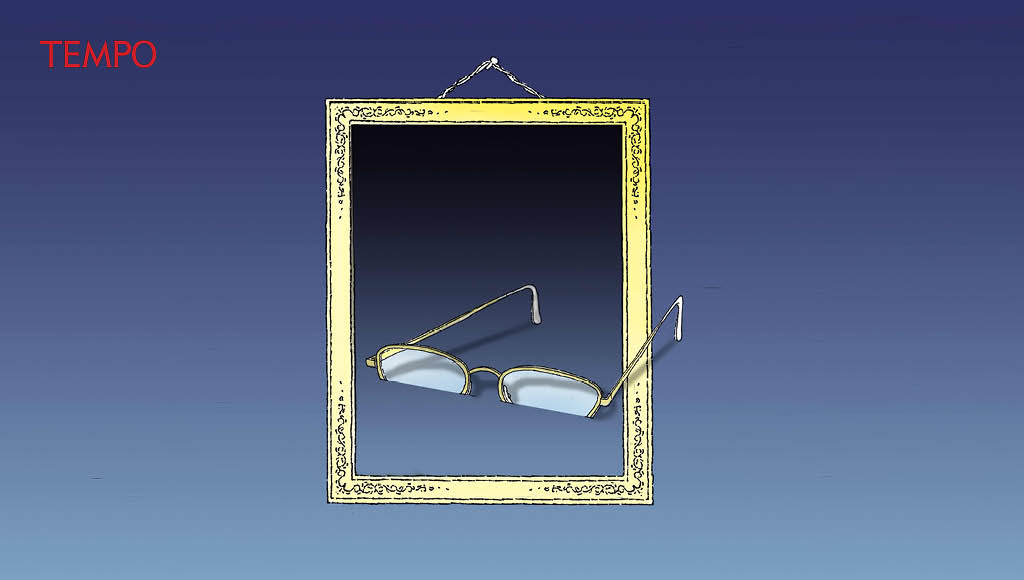Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
KRISIS berlangsung tepat terjadi saat ini, tulis Antonio Gramsci dari dalam penjara Kota Turin pada 1930. “Ketika yang lama tengah sekarat, sementara yang baru tak kunjung lahir. Pada masa peralihan (interregnum) seperti ini, berbagai bentuk gejala yang mengerikan (morbid symptoms) akan muncul di hadapan kita.”
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo