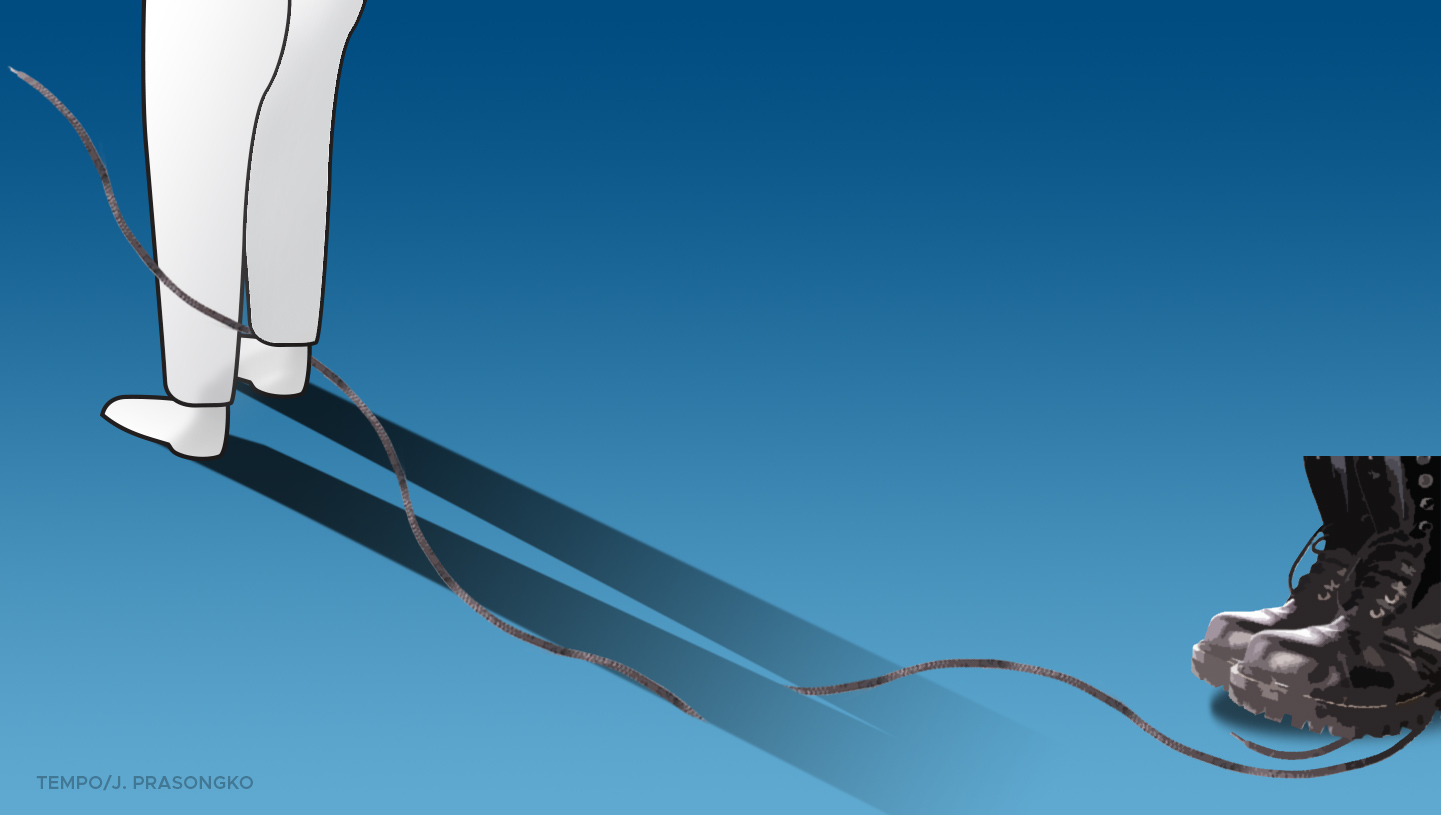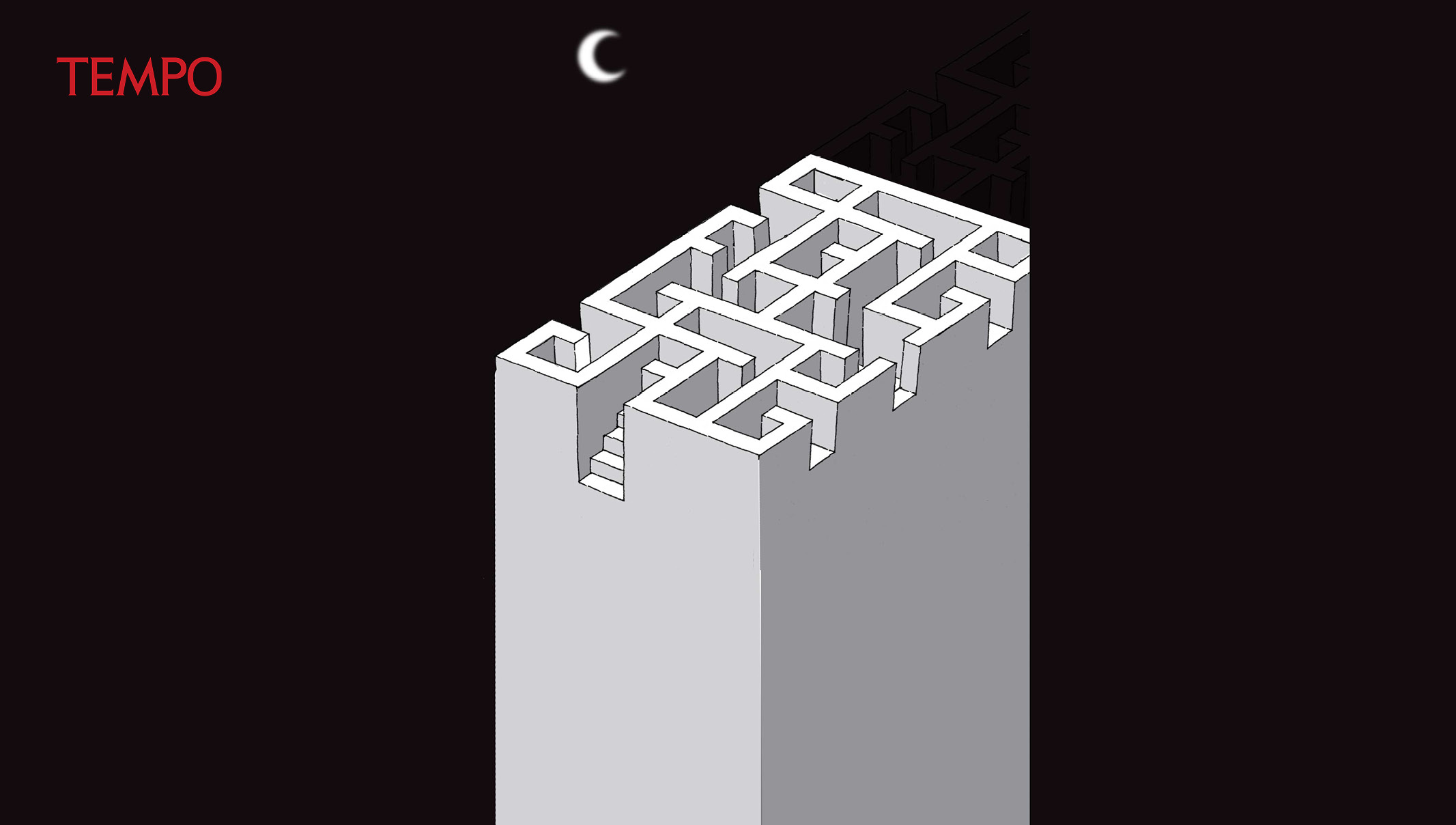Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
POLITIK Jerman, khususnya di bagian timur negara itu, tampak sedang bergerak ke kanan. Pekan lalu, hampir saja partai kanan ekstrem Alternative für Deutschland (AfD) memenangi pemilihan di Negara Bagian Brandenburg: meraih suara 29,2 persen, sedikit di bawah Partai Sosial Demokrat (SPD), partai penguasa yang mendapat 30,9 persen. Di Negara Bagian Thuringia, AfD menang, bahkan di Saxony menang telak.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Tuturan Progresif Sejarah"