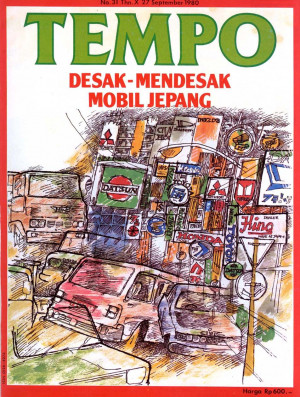"Semoga Tuhan menyelamatkan kita dari pemberontakan baru."
KALIMAT itu menutup sebuah surat bertanggal 16 September 1831.
Pengirimnya dari Jawa. Penerimanya di Negeri Belanda. Di kedua
tempat yang sangat berjauhan itu, orang baru saja selesai
menyaksikan pemberontakan Diponegoro yang dahsyat ....
Siapa penulis surat itu dirahasiakan. Yang pasti, ia seorang
Belanda penting di tanah jajahan, yang ingin menumpahkan
keluhannya kepada temannya, mungkin seorang yang berpengaruh di
dekat pusat kekuasaan di Den Haag. Hampir 100% isi surat itu
adalah cercaan kepada Sistem Tanam Paksa di Pulau Jawa -- dan
kepada tokoh besar yang menerapkan sistem itu, Gubernur-Jenderal
J. van den Bosch.
"Belum pernah sebelumnya di Jawa berkuasa seorang despot yang
sekeras-kepala dan mau menang sendiri seperti J. van den Bosch,"
sembur surat itu.
Van den Bosch mungkin bukan tiran terbengis dalam sejarah Jawa,
tapi pasti ia orang yang percaya bahwa orang Jawa goblok dan
bahwa Sistem Tanam Paksa adalah jalan yang baik. Van den Bosch
mungkin bukan Iblis, tapi pasti bahwa sistem yang
dilaksanakannya dengan gemuruh itu telah banyak menimbulkan
kesengsaraan.
Tentu, bukan maksud van den Bosch untuk membuat rakyat Jawa
sengsara. Ia bahkan bicara bersedia berkorban untuk
membahagiakan mereka. Ia hanya tak setuju dengan "impian
filantropik" yang ingin membahagiakan orang Jawa dengan cara
memberi rakyat berkulit coklat itu hak asasi yang aneh-aneh bagi
mereka sendiri. Bahwa kemudian ada ekses ....
"Memang pedih untuk mengakui, bahwa keadaan rakyat Jawa
sedemikian mengejutkan."
Itu adalah sepotong kalimat yang ditulis oleh L. Vitalis,
seorang bekas inspektur Tanam Paksa, di tahun 1851 --dengan
ilustrasi yang memang muram: laporannya dari awal 1835 dari
daerah Priangan. Di sanalah mayat petani bergelimpangan karena
capek dan lapar, disepanjang jalan antara Tasikmalaya dan Garut,
Arjawinangun dan Galo. Dan bila mereka dibiarkan saja, tak
dikuburkan, itu karena alasan Bupati yang kalem: "Di waktu
malam, harimau akan menyeret mereka."
Bersama dengan itu, sistem van den Bosch menyeret pertanian Jawa
ke dalam suatu impasse. Sejak inilah apa yang terkenal sebagai
"involusi pertanian" sesedikit demi sedikit mengakar di Jawa.
Ahli anthropologi Clifford Geertz telah melukiskan keadaan itu
dan kata "involusi" telah jadi buah bibir di kalangan ahli ilmu
sosial Indonesia, namun barangkali ada gunanya melihat kembali
cirinya.
Inti dari kebuntuan itu adalah kemiskinan, yang dibagi-bagi.
Hidup bersama diatur ke dalam suatu harmoni di permukaan, ketika
penduduk kian bertambah dan tanah yang jadi keropos itu kian
menyempit. Risiko dihindari, konflik ditelan, karena dalam etika
hidup yang pas-pasan itu (seorang penulis menyebutnya sebagai
"subsislence ethic") satu langkah yang salah bisa menenggelamkan
habis.
"Semoga Tuhan menyelamatkan kita dari pemberontakan baru," tulis
seorang Belanda di tanah jajahan tahun l831 Tapi bahkan
pemberontakan pun tak bisa mengguncang, sebab tenaga terbatas,
tujuan terlalu bersahaja, sementara bahaya demikian besar hingga
pak tani harus sekaligus menangis seraya bermimpi. Ahli sejarah
Sartono Kartodirdjo dengan sangat bagus telah melukiskan
pergolakan-pergolakan petani di Jawa itu: teruncam dari tanah,
mereka angkat senjata, kemudian kalah, mati, sementara Ratu Adil
tak kunjung tiba.
Bahkan PKI pun, di tahun 1948 dan 1965, gagal. Tak cukup
kekuatan terbina di sela-sela pematang dan padi.
Tapi yang tak bersuara bukanlah berarti orang yang mati. Atau
yang tak berubah. Terutama bila kemiskinan, yang dulu dibagi,
sekarang hanya dijejalkan kepada yang terlemah, dan desa-desa
tak bisa lagi menampung, dan kota jadi sumpek "Saya sadar saya
telah bersikap pahit," tulis Multatuli. Tapi bisakah ia
sebaliknya?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini