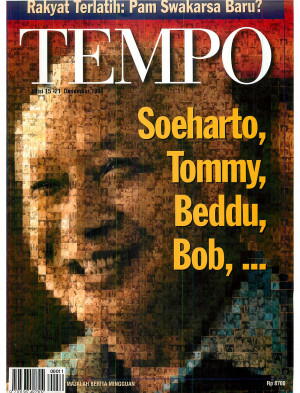Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Soal peran ABRI?antara lain?di lembaga legislatif yang pada akhirnya menghambat partisipasi politik masyarakat inilah yang sampai Jumat pekan lalu masih digugat oleh mahasiswa yang memprotes dwifungsi ABRI. Kejadian Jumat itu bukan yang pertama dan bukan pula yang terakhir. Sejak aksi-aksi mahasiswa dan anggota masyarakat lainnya tahun 1970-an, peran ABRI di fungsi-fungsi sosial dan politik sudah digugat habis. Namun sampai hari ini hasilnya belum maksimal.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo