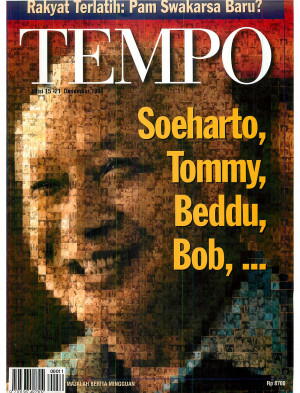Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
PUNP? PUN? Itu singkatan dari Pancasila, UUD 45, Negara Kesatuan, dan Pemerintah. "Jadi sekarang kami bukan lagi alat pemerintah melainkan alat negara," tambah perwira tadi sambil menjelaskan pelepasan P terakhir dari doktrin tadi tidak berupa perintah tertulis pemimpin ABRI melainkan, "Kebijakan yang kami sepakati bersama," tuturnya.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo