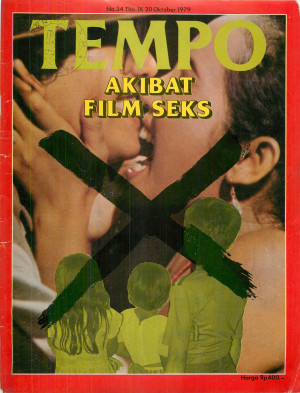Empat bulan lalu orang terkejut ketika terbetik berita 5 gereja
terbakar di Simpang Kanan, Aceh Selatan. Disusul dengan
membanjirnya para pengungsi dari sana ke Kabupaten Dairi dan
Tapanuli Tengah, Sum-Ut. Ternyata itu bukan sengketa antara
Aceh-Batak atau Islam-Kristen. Di bawah ini laporan wartawan
TEMPO Bersihar Lubis yang meninjau desa Saragih, tempa
penampungan para pengungsi itu.
DESA Saragih, di mana itu? Kalau anda berada di Sibolga, naiklah
bus sejauh 66 km, lewat jalan bergelombang. Turunlah di Barus.
Lalu silakan naik perahu motor selama 4 jam di sungai Sitapus
menuju Nanjur.
Maaf, sampai di sini jalan putus. Anda masih harus jalan kaki
sejauh 20 km lagi, lewat proyek perkayuan pemegang HPH. Di
sanalah anda bisa berjumpa dengan sekitar 6.000 pengungsi
beragama Kristen asal Simpang Kanan, Aceh Selatan yang sudah
mukim sejak 4 bulan sejak pertengahan Juni lalu.
Arus pengungsi itu bermula dari pembakaran 5 gereja di Aceh
Selatan. Tapi menurut Pangdam I/Iskandar Muda Brigjen RA Saleh,
hingga akhir Juni itu sudah sekitar 60% para pengungsi kembali
ke tempat semula. Bahkan mulai 11 Oktober lalu, seluruhnya
diantar pulang oleh para petugas Koramil dan Komandan Resor
Kepolisian setempat.
Menurut rencana, Sabtu 13 Oktober lalu diselenggarakan upacara
perdamaian secara adat antara 2 kelompok yang saling
bertentangan di Lae Butar, kecamatan Simpang Kanan, Aceh
Selatan. "Selepas perdamaian itu, semuanya akan kembali seperti
sediakala," ujar Doria Hutabarat, Camat Barus, Tapanuli Tengah.
Meski begitu, ada pengungsi yang masih was-was. "Kami sebenarnya
percaya jaminan keamanan yang dijanjikan," ujar Jore Tumanggor,
37 tahun, dengan tanggungan 6 jiwa termasuk isteri. Tapi
khawatir, orang-orang Simpang Kanan masih tidak menyukai
keadirannya.
Daerah Baru
Lebih-lebih setelah teman-temannya yang pulang ternyata kembali
lagi ke Saragih. Kabarnya banyak rumah pengungsi yang
ditinggalkan itu pada kosong, sementara dinding dan atap sengnya
pun pada copot.
Itu tak berarti semua pengungsi tak mau pulang. Terutama setelah
para pejabat kecamatan memberi penerangan 9 Oktober lalu. Naras
Manik, 65 tahun, misalnya lebih suka pulang. "Kalau di sini
terus, uang bisa habis," katanya. Pemda di sana memang
membagikan beras tapi tidak mencukupi kebutuhan. Disampaikan 3
tahap, tiap setiap orang menerima 5 kg, lalu 3 liter, terakhir 2
liter lagi. "Pokoknya saya harus pulang, meskipun harus jalan
kaki 2 hari," tambah Naras.
Keberatan para pengungsi untuk pulang, konon juga lantaran
mereka tertarik pada rencana Pemda Sum-Ut membuka proyek
pemukiman dan persawahan baru seluas 5.000 ha di Saragih. Karena
jumlah penduduk Saragih sendiri cuma 710 orang, maka para
pengungsi pun berharap bisa menetap dan mencari makan di daerah
baru itu.
Tapi kalaupun ingin tetap tinggal, Camat Hutabarat mmta agar
mereka mengusahakan surat ijin pindah dari amat Simpang Kanan
dulu. "Hingga kelak tidak dianggap sebagai penduduk liar," ujar
Camat lagi. Yang pasti, sementara kehidupan di Simpang Kanan
Aceh Selatan sudah mulai pulih, para pengungsi pun tampaknya
juga mulai betah tinggal di desa Saragih.
Adakah sengketa ini antara 2 suku Aceh-Batak atau Islam-Kristen?
Ternyata tidak. Menurut cerita G. Tumanggor, 40 tahun,
Sekretaris Kepala Desa Saragih, pertentangan ini antara
orang-orang Fakfak Dairi sendiri. Pertentangan itu, begitu
dikisahkan, sudah muncul sejak awal abad 19 lalu, ketika
nenek-moyang mereka masih tinggal di Kabupaten Dairi.
Konflik berlanjut sampai ketika 1890 sekelompok orang Fakfak
Dairi mengungsi ke Aceh Selatan. Bermukim di sana, mereka lantas
memeluk agama Islam. Di sana mereka juga dikenal dengan sebutan
"Boang Fakfak", artinya orang-orang Fakfak yang membuang diri.
Mungkin karena di kabupaten Dairi konflik itu terus berlangsung,
sekelompok orang Fakfak lainnya pada awal abad 20 mengungsi lagi
ke Aceh Selatan. Tapi mereka kebetulan sudah beragama Kristen.
Selama bertahun-tahun sebenarnya mereka hidup rukun, sampai
terjadinya pergeseran dalam tingkat kehidupan beberapa tahun
lalu.
Beberapa tahun belakangan ini kelompok Fakfak Dairi yang datang
belakangan ke Aceh Selatan rupanya banyak yang berhasil
menguasai roda perekonomian di sana, "mulai dari perdagangan
getah, angkutan darat dan laut," tutur Tumanggor. Bahkan kedua
kelompok itu pun bersaing pula dalam menduduki kursi di kantor
kecamatan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini