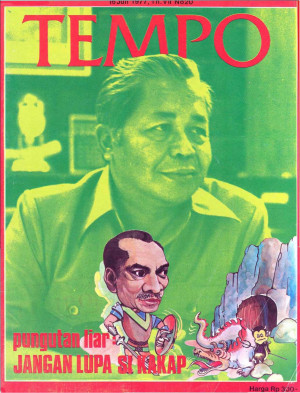SAMPAI berapa jauh masalah kemiskinan jadi urusan agama?
Dalam diskusi panel pembinaan suasana keagamaan di Jakarta
(lihat tulisan Sutjipto Wirosardjono hal 44) ternyata soal itu
dianggap cukup relevan Pada kesempatan itu diedarkan teks
ceramah Ali Sadikin yang diberikan di Masjid Salman ITB Bandung
bulan puasa tahun lalu -- dan dinyatakan merupakan pendorong ide
penyelenggaraan diskusi kali ini. Teks itu ada membentangkan
masalah penangulangan hal-hal sekitar kemiskinan itu.
Dicantumkan: 60%, penduduk Jakarta hidup di kampung-kampung
miskin yang sama sekali tak sehat 60% anak usia-sekolah di
tahun 1966 tak kebagian bangku. Gedung sekolah sangat kurang
juga guru. Sistim pendidikan dasar ambrol akibat kekurangan
biaya. Sedang bendahari Kota waktu itu dalam keadaan kosong
pemsukan dari pajak tak memadai.
Itulah sebabnya ditempuh cara-cara mengeduk dana yang oleh orang
yang tak suka disebut sebagai "cara inkonvensionil.
Maka rehabilitasi pun dimulai. Tapi betulkah dengan itu -- kalau
memang ini masalahnya -- tingkat hidup golongan terendah
penduduk Jakarta cenderung menaik?
Prasarana H Rosihan Anwar, mengulang data tentang 40%, penduduk
Jakarta dengan penghasilan terendah Golongan ini yang di tahun
1967 menerima 18,3% dari seluruh pendapatan masyarakat Jakarta
di tahun 1970 menerima hanya 11,6%.
Ceramah Gubernur itu sendiri menyebutkan satu hal yang mungkin
sering dilupakan orang, bahwa Jakarta merupakan "tempat
terdamparnya lapisan terbawah yang terhempas dari kemiskinan
ekonomi dan kemiskinan sosial dari seluruh tanah air."
Nah. Adakah hal-hal tersebut seharusnya termasuk perhatian
agama? Ataukah tugas agama memang hanya mempersoalkan amar
ma'ruf nahi munkar (menyuruh yang baik, mencegah yang jahat)
dalam pengertian "konvensionil"?
Setidak-tidaknya diskusi yang diselenggarakan di Balai Kota dan
Gedung DPRD itu menunjukkan bahwa: menggunakan dalil baku ajaran
agama menurut bunyi kata per kata, memang, lebih mudah daripada
memecahkan persoalan dilihat dari kompleksitas masalah. Teks
Gubernur itu misalnya ada mencantum kan pendapat ulama pembaharu
Ibnul Qaiyim, yang membagi 'munkar' menjadi empat: munkar yang
bisa dihapus, munkar yang hanya bisa diperkecil, munkar yang
kalau dihapus diduga akan menimbulkan munkar yang sama, dan
munkar yang bila dihapus ditakutkan akan menimbulkan munkar yang
lebih besar. Dan dalam Islam, kata ceramah itu juga dikenal
prinsip idhthirar (darurat). Tetapi pokok ini justru tidak
dibahas bahkan oleh para peserta diskusi yang secara prinsipil
menolak segala bentuk munkar.
Rupanya dimensi sosial agama (dikalangan umat) tidak cukup
muncul di permukaan. Lebih menonjol ialah dimensi peribadatan
dan hukum fiqh formil. Inimenunjukkan perimbangan yang masih
berat sebelah dalam hal penafsiran ajaran - oleh para ulama, dan
seterusnya para muballigh. Seorang laji yang rajin sembahyang
misalnya, rajin sedekah dan membangun masjid, tapi dalam praktek
menempuh hidup "kapitalistis" dengan secara tak langsung memeras
saudara sauaranya yang lebih lemall dalam kenyataan masih bisa
lebih dihargai daripada seorang yang tidak terkenal alim tapi
banyak berbuat jasa kemanusiaan - yang tampaknya tak ada
hubungannya dengan agama.
Itulah antara lain sebabnya mengapa banyak peserta diskusi jua
pemrasaran Abdurrahman Wahid, yang menolak pernyataan bahwa
perkembangan agama seperti yang terlihat di Jakarta benarbenar
sudah berarti, dengan hanya melihat bangunan-bangunan fisik -
dan ramainya pengeras suara. Atau dengan mengemukakan bahwa
Partai Persatuan kemarin unggul di DKI, seperti dinyatakan Omar
Tusin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini