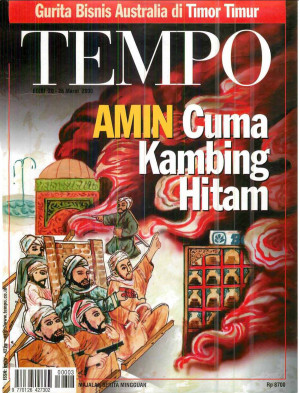GRAFITI coret-moret memaki Sjamsul Nursalim itu tersebar di seantero dinding wilayah pertambakan udang di Kabupaten Tulangbawang, Lampung.
''Sjamsul Nursalim VOC! Sjamsul Nursalim PKI!"
Dan suasana mencekam masih menggumpal. Dua pekan silam, dua anggota Brimob dan sekaligus ajudan pribadi Sjamsul tewas oleh amukan petani tambak udang. Amarah massa tak bisa dibendung setelah salah satu rekan mereka ditembak mati anggota Brimob itu, menyusul unjuk rasa di kawasan PT Dipasena Citra Darmaja.
Kerusuhan berdarah itu sebenarnya hanya sebuah klimaks dari keresahan yang telah menahun.
Seluas 16.250 hektare dan terbesar di Asia Tenggara, kawasan pertambakan Dipasena telah beroperasi sekitar 10 tahun. Usaha itu dikelola dengan model yang umum diterapkan pula dalam perkebunan: konsep inti dan plasma. Dipasena sebagai inti, sementara para petani di sekelilingnya sebagai plasma. Tujuan awalnya tentu saja baik, inti akan membantu plasma dalam teknik budidaya dan pemasaran, sebaliknya plasma wajib menjual produknya kepada inti.
Dalam praktek, ia tak semulus itu. Sengketa terjadi. Dan tiga pekan silam itu, sedianya akan berlangsung dialog antara Sjamsul—pemilik Dipasena—dan para petani. Sayang, dialog itu berakhir dengan keributan berdarah.
Penjelasan resmi aparat cenderung menyalahkan para petani, yang agresif. Namun, petani punya alasan untuk marah. Di pintu gerbang Tanggul Penangkis—salah satu lokasi di areal—siang itu Sjamsul berpidato dengan ungkapan yang menurut para petani bernada provokatif. ''Siapa itu yang bicara! Apa sudah tidak betah lagi?" kata sang konglomerat saat mendengar ada petani menggerundel. ''Plasma kan tidak bekerja. Maka, jangan minta gaji penuh!"
Para petani tersinggung. Melihat gelagat kurang baik, Sjamsul lari ke mobilnya sembari berteriak, ''Tembak saja!". Dor, dor, dor. Salakan tak tertahankan keluar dari pistol seorang pengawalnya. Seorang petani tambak, Ruswandi (30 tahun), langsung tersungkur. Darah muncrat menjijikkan. Matanya tertembus pelor panas. Spontan, massa mengamuk. Sjamsul lolos, tapi dua pengawalnya mati dihakimi masa.
Hari-hari ini, menyusuri kanal-kanal pertambakan—selebar 50 meter dengan kedalaman 4 meter—orang akan melihat kawasan itu relatif lengang karena operasinya dibekukan. Areal itu dikuasai satgas tambak bersama dua peleton polisi bantuan Polres Lampung. Orang-orang yang masuk atau keluar lokasi Dipasena diperiksa.
Sengketa itu sebenarnya sudah berlangsung lama. Telah beberapa tahun terakhir para petani mengeluh. Tahun lalu, mereka menginap berhari-hari di Kantor Gubernur Lampung, mengadukan nasib. Mereka melakukan hal yang sama di DPR Senayan, pertengahan Februari lalu. Namun, nasib tak berubah; hanya frustrasi yang mereka dapat.
Menurut para petani, Dipasena seenaknya mematok harga udang secara rendah. Lebih dari itu, secara sepihak, pada Januari 2000, Sjamsul memangkas biaya hidup bulanan petambak (BHBP)—semacam gaji untuk petani—sampai separuhnya. Menurut kesepakatan yang ditandatangani pada 3 September 1998, setiap bulan petambak mendapat jatah Rp 500 ribu plus tunjangan in natura (bahan pokok) senilai Rp 175 ribu. Ini yang membuat petani berang. Mereka menolak mengambil jatah yang dipangkas jadi Rp 250 ribu itu.
Untuk bertahan mencukupi kebutuhan sehari-hari, petani tak kurang akal. Mereka lalu beternak ikan nila dan menjual ikan asin dengan harga murah ke luar areal. Mereka juga tahu diri dengan hanya membatasi setiap RT (20 kepala keluarga petambak) maksimum menjual 100 kilogram. Tapi, Sjamsul melarang usaha kecil-kecilan itu.
Petani yang mencoba menjual produknya ke luar areal berhadapan dengan para centeng swasta. ''PAM Swakarsa" itu direkrut dari para anggota perguruan pencak silat Paku Banten. Jawara-jawara silat yang biasanya dipakai Gubernur Lampung, Oemarsono, untuk menghadapi demonstrasi mahasiswa dan aktivis LSM ini sering berlaku kejam. ''Kami diperalat perusahaan," kata Tubagus Sufyan Jamran, sekretaris umum Paku Banten, saat ditemui TEMPO di sarangnya di kawasan Garuntang, Bandarlampung.
Pada 29 Februari 2000, bersama centeng-centengnya, Sjamsul sendiri dengan arogan melakukan penyitaan paksa ikan asin milik petani sebanyak 2 kuintal. Terjadilah kemudian gelombang pemogokan besar-besaran yang melumpuhkan tambak, dan terjadi ketegangan antarkelompok—sampai klimaksnya, ya, tumpahnya darah itu.
Menyusul keributan itu, banyak pihak mulai serius menjadi mediator antara petambak dan perusahaan, tapi belum ada kata sepakat baru.
Tim Pelaksana Perjuangan Petani Tambak (TP3T), badan mediator yang dibentuk oleh PRD, berhasil melakukan negosiasi dengan pihak manajemen Dipasena. Hasilnya, BHBP menjadi Rp 400 ribu, plus in natura Rp 175 ribu. ''Ini kemampuan maksimal perusahaan," kata Irwan Gusman, Accounting Manager Dipasena. Tapi kesepakatan itu ditolak mentah-mentah oleh Perhimpunan Petambak Plasma Udang Windu (P3UW), organisasi terbesar bagi petani plasma Dipasena. Mereka tetap bersikukuh dengan kesepakatan BHBP Rp 500 ribu, plus in natura Rp 175 ribu. ''Petani tambak yang menjadi anggotaTP3T cuma 112 orang. Jelas, mereka tidak bisa disebut mewakili plasma yang jumlahnya 9.000 orang," kata Parjono, Ketua I P3UW.
Jadi? Tampaknya mayoritas petani tambak (semua 15 blok tambak) akan nekat bertahan hidup, meski kondisi makin pas-pasan. Ibarat orang dicelupkan, asal kepala masih di luar untuk bernapas, mereka tetap bertahan. Begitulah nasib mereka.
Tengok kondisi Sajuri (30 tahun), yang tinggal bersama istri dan anaknya di blok 15 jalur 37. Tiga bulan lalu, rumah panggung dengan tipe 36 itu dilengkapi dengan pesawat TV, radio, dan sebuah kulkas. Perlengkapan yang tergolong mewah untuk petambak. Kini barang-barang yang dibanggakan itu menguap. ''Harta benda saya sudah ludes untuk menyambung hidup," katanya lirih. Pilu, memang. Apalagi, anaknya sakit, dan Puskesmas—fasilitas Dipasena—sudah berhenti melayani. Dokter dan perawat yang bertugas sudah ''menyelamatkan diri" keluar dari lokasi.
Satu persoalan lagi yang bakal melilit orang-orang seperti Sajuri ini adalah utang. Ini soal rumit yang diakui Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri Kwik Kian Gie, BPPN, dan kalangan DPR pusat. Kepada setiap plasma, Sjamsul mengucurkan pinjaman senilai Rp 135 juta lewat Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) miliknya. Pinjaman itu terdiri atas kredit investasi sebesar Rp 90 juta dan kredit modal Rp 45 juta dengan bunga 15 persen, plus provisi 0,5 persen setiap 12 bulan untuk keseluruhan kredit.
Saat pinjaman diteken, petani diming-imingi bahwa kredit akan lunas delapan tahun. Cicilannya dengan cara memotong hasil panen. Untuk bisa melunasi utang tepat waktu, petani dengan luas tambak rata-rata 2.000 meter persegi itu harus bisa memproduksi 800 kilogram udang windu. Setelah semua berjalan mulus, tambak akan menjadi milik petani. Ironisnya, memasuki 1999, harapan untuk memiliki tambak bukan makin dekat di depan mata. Sebaliknya, tanpa dinyana, utang petani membengkak drastis. Tak syak, ini akibat naiknya harga dolar.
''Itu risiko bisnis," komentar Irwan Gusman. Menurut dia, saat penandatanganan akad kredit di depan notaris, utang sudah ada dalam nilai dolar. Saat itu, BDNI sebagai bank pemberi pinjaman tidak punya rupiah, lalu disodorkan dolar. Ini tentu bisa dipertanyakan, apa betul tidak punya rupiah. Tapi Irwan menampik tuduhan bahwa perusahaan berusaha mengakali petani dan berlaku tak fair dalam perjanjian.
''Kami berusaha setransparan mungkin. Kalau para plasma mau hitung-hitungan, mereka bisa datang ke kami. Akan kami berikan hitungannya," katanya. Persoalannya: petani-petani lugu itu tentunya tak tahu persoalan kurs atau bahayanya berutang dengan uang Paman Sam, yang bisa bakalan melambung atau jatuh. Sehingga, dengan tanpa syak wasangka apa pun, mereka menerima kesepakatan.
Selain itu, pihak perusahaan menyalahkan bahwa mayoritas petani hanya mampu menghasilkan 500 kilogram. Menurut mereka, itu bukti bahwa petani gagal merawat tambak hingga tak bisa berproduksi seperti yang diharapkan. Itu yang membuat petani tak bisa menepati cicilan. Tapi entah ini sekadar tipu muslihat atau bukan. Buktinya Sajuri di atas. Ia menerima akad kredit pada 1995. Tiap kali panen, ia menghasilkan udang 1 ton. Artinya ini melebihi patokan target volume udang yang ditetapkan perusahaan. Anehnya, jumlah utangnya makin bertambah. ''Menurut perusahaan, saat ini utang saya mencapai Rp 500 juta lebih. Waduh..., saya tidak mengerti dari mana datangnya angka itu, Mas," ia mengeluh.
Kini tambak udang berada di tangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), seiring dengan kolapsnya BDNI milik Sjamsul Nursalim. Petani sendiri menuntut BPPN—yang menguasai aset Nursalim—untuk menyerahkan surat kepemilikan tambak kepada para petani. Tapi, BPPN menolaknya. BPPN tetap membebankan penyelesaian pembayaran utang kepada petani. Totalnya sebesar Rp 2,807 triliun.
Masa depan petani makin terlihat suram. Dalam kesepakatan antara TP3T dan manajemen juga tidak ada pembahasan soal utang. Sementara Sjamsul Nursalim ditanggung BPPN, sebaliknya nasib petani makin apes. Padahal, sejatinya hubungan plasma dan inti bukanlah relasi buruh dan majikan, melainkan hubungan kemitraan yang sederajat. Tapi memang orang kecil selalu kalah melulu.
Seno Joko Suyono, Setiyardi
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini