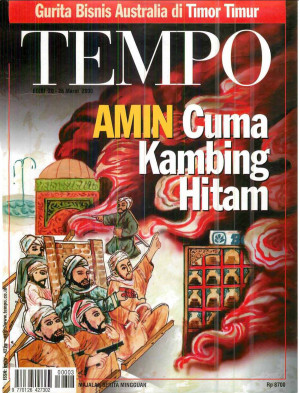SMU Negeri 8 Jakarta menyiapkan pasukan khusus. Bukan untuk maju tawuran, tapi untuk mempercepat pelajaran. Sebanyak 18 siswa sekolah favorit itu terpilih untuk menyingkat masa pendidikan dari tiga menjadi dua tahun. Bagi siswa-siswa yang berotak encer ini, kurikulum 1994 yang sering dikeluhkan terlalu padat dan membebani itu tampaknya masih mungkin dipadatkan lagi.
Jika uji coba ini sukses, satu pertanyaan sentral dan "laten" dalam dunia pendidikan kita akan berdengung kembali: benarkah kurikulum 1994 terlalu berat? Atau justru sebaliknya, terlampau ringan?
Beban kurikulum merupakan perdebatan tak berujung. Kurikulum 1994 sering menjadi kambing hitam bagi rendahnya tingkat pemahaman siswa karena sekolah cuma mengejar target materi. Kurikulum yang diadopsi dari Eropa itu sering dinilai terlalu berat untuk ukuran Indonesia. Di Eropa saja, kurikulum itu cuma diberikan kepada 30 persen siswa, sedangkan 70 persen sisanya menerima pelajaran yang lebih rendah. "Anak Indonesia bukan bodoh," kata pengamat pendidikan Peter Drost, "cuma dipaksa menelan beban yang mestinya cuma untuk anak pintar."
Sebaliknya, tak sedikit juga yang menilai kurikulum 1994 terlalu gampang. Anak-anak cerdas sering menjadi bosan. Gerak pengajaran dinilai kurang rikat. Akibat tarik-ulur perdebatan seperti ini, kurikulum—yang selama ini seperti telah menjadi mantra keramat pendidikan—berkali-kali dibongkar-pasang.
Untuk menjawab pertikaian yang tak pernah berakhir itu, pemerintah kini menyiapkan jalan tengah: menyesuaikan kurikulum dengan kemampuan dan daya tangkap siswa. Penyesuaian semacam inilah yang diuji coba SMU Negeri 8 Jakarta. Mereka yang berotak encer masuk kelas khusus dengan kurikulum ekstrapadat, sedangkan yang rata-rata masuk ke kelas biasa. Yang jongkok? "Silakan ke jalur lambat," kata Elida Agoes, Kepala Sekolah SMU Negeri 8. Rencananya, kurikulum "bertingkat" akan dimasyarakatkan mulai akhir tahun nanti.
Eloknya, kurikulum "tailor-made", yang dibuat sesuai dengan kebutuhan, itu bukan cuma dimaksudkan untuk mengakomodasi kemampuan siswa, tapi lebih dari itu juga untuk memilah bakat-bakat emas sejak dini. Kelak, jika kurikulum jahitan ini sudah berjalan lancar, hanya siswa lulusan "jalan tol" yang bisa berlanjut ke sekolah umum dan universitas. Siswa jalur lambat cuma boleh meneruskan pendidikan ke sekolah kejuruan atau paling banter akademi. Bagaimana dengan yang rata-rata? "Mereka akan terus diseleksi sampai ketemu 'jurusan' yang sesuai, bekerja, atau melanjutkan kuliah," kata seorang pejabat di Departemen Pendidikan Nasional.
Dengan cara memilah "emas dari loyang" sejak dini itu, jalur pendidikan tiap siswa sudah dipandu sejak awal. Jurus ini dianggap bisa mengatasi tingkat kegagalan siswa SMU dalam memasuki perguruan tinggi. Menurut sebuah penelitian, 85 persen lulusan SMU gagal meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi—bukan karena tak kebagian kursi, melainkan lantaran nilainya tak memadai. Celakanya, jebolan SMU—yang sejak semula memang tidak dibekali keterampilan untuk bekerja, tapi disiapkan agar melanjutkan pendidikan—ini akan memperbanyak jumlah angkatan kerja tanpa keahlian. Mereka cenderung menganggur atau bekerja tanpa keterampilan.
Dalam sistem kurikulum berjenjang, siswa di jalur lambat (yang disiapkan untuk bekerja) akan lebih banyak menerima pelajaran keterampilan. Mereka akan dicekoki muatan lokal—yang disesuaikan dengan karakter lapangan kerja di daerah masing-masing—sebanyak-banyaknya.
Tapi soalnya: apakah penyesuaian kurikulum ini akan mengatasi seluruh problem pendidikan? Andi Hakim Nasution melihat tantangan pendidikan kita bukan melulu terletak pada kurikulum. Yang lebih mendesak adalah kualitas guru yang masih memprihatinkan. "Kita harus menghidupkan kapal perang lama," katanya seperti memberi resep.
Maksud Andi adalah suatu metode untuk melahirkan guru-guru berkualitas melalui kursus B1—seperti yang pernah dilakukan pada 1960-an. Dalam kursus dua tahun itu, calon guru diseleksi ketat. Selain itu, mereka cuma dibekali satu mata pelajaran pilihan plus metode pengajaran. Ini sangat berbeda dengan calon guru dari IKIP, yang harus menelan 60 mata kuliah.
Barangkali kurikulum untuk pendidikan guru juga mesti dibuat berjenjang—disesuaikan dengan kemampuan.
Agung Rulianto, Ardi Bramantyo
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini