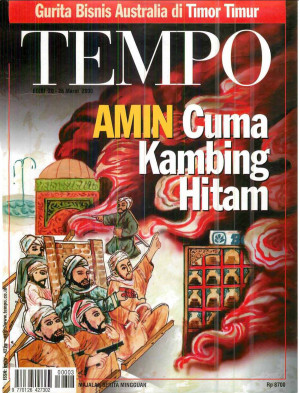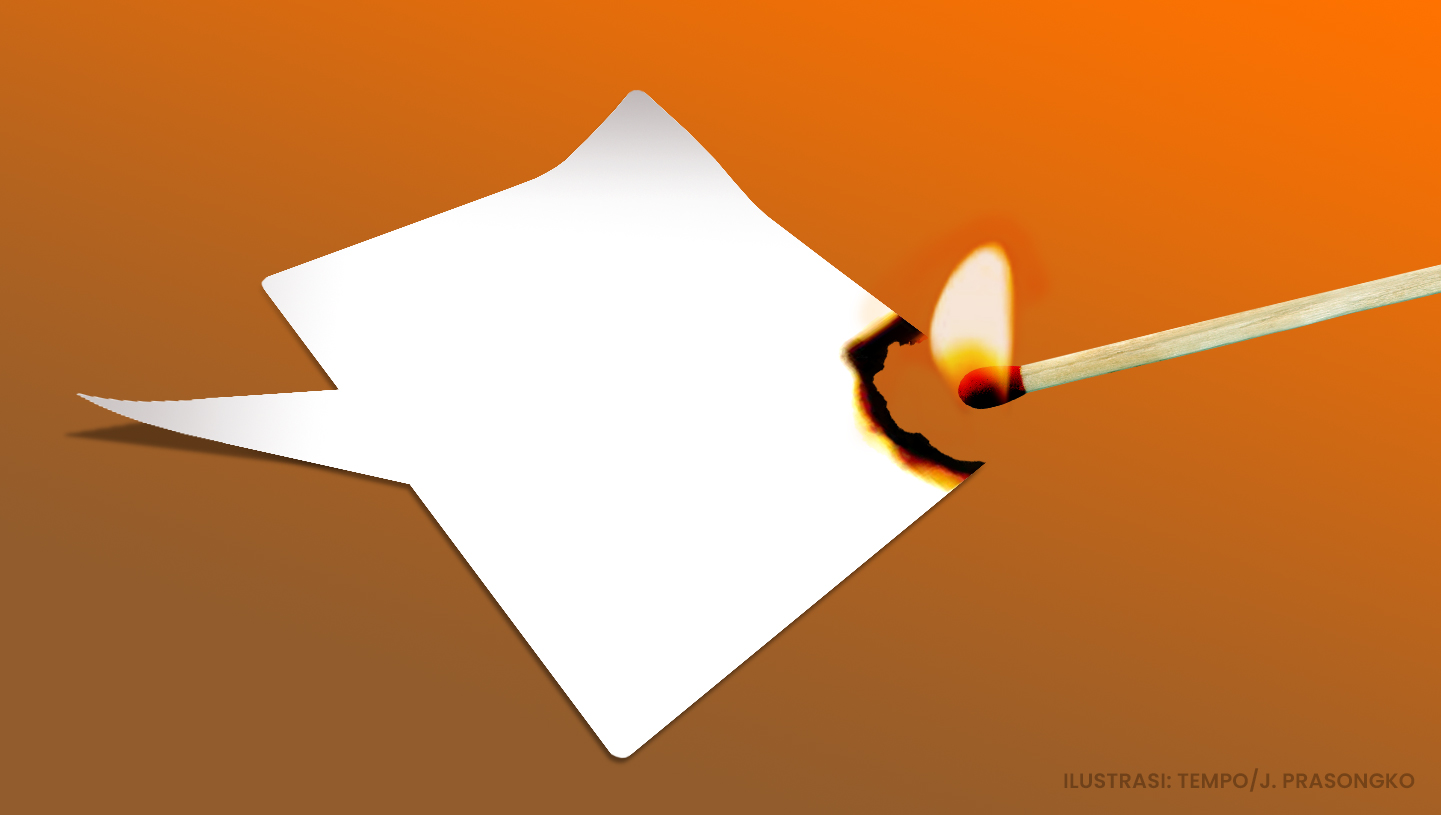Panen raya beras di Indonesia bukannya disambut rasa syukur, tapi disongsong dengan panik dan gelagapan. Panik di kalangan elite pengambil keputusan, panik juga (ditambah putus asa) di masyarakat petani dan buruh tani yang jumlahnya mencapai 34 juta jiwa. Kalaupun Menteri Pertanian Mohammad Prakosa tersenyum-senyum di layar kaca, senyum itu mengembang lebih karena rasa gugup, ketimbang rasa yakin bahwa harga gabah bisa didongkrak lebih tinggi. Pak Menteri yang masih muda ini seperti tercemplung ke dalam kegalauan yang luar biasa: kali ini beras begitu melimpah tapi semuanya tiba-tiba jadi serba salah. Gudang Bulog dipenuhi (sebagian) dengan beras impor, nah, itu jelas salah. Panen sukses dari sawah ke sawah, itu pun rupanya bisa dianggap salah. Di tengah kegagalan politik perberasan ini, yang paling menonjol adalah kenyataan bahwa bangsa kita tidak mampu mengurus keperluan pangannya sendiri. Buktinya, ketika produksi beras bagus sekali, nasib petani justru terpuruk lebih dalam lagi.
Kalau mau bicara jujur tentang politik perberasan, sepanjang sejarah republik, tokoh yang paling mengerti posisi kunci beras dalam stabilitas politik negeri ini adalah mantan presiden Soeharto. Selama 32 tahun Orde Baru, Bulog hampir tidak pernah meleset dalam menjamin kebutuhan beras konsumen di satu sisi, sekaligus mampu menciptakan harga beras yang wajar bagi petani. Seiring dengan itu, waduk-waduk besar dibangun (ingat Kedungombo!), pabrik pupuk juga dibangun, bibit unggul ditanam, lalu pada 1986 Indonesia mampu berswasembada beras. Luar biasa!
Sukses swasembada membuat banyak orang terlena. Indonesia tampil sebagai bangsa pemakan beras terbesar di dunia, tapi pada saat yang sama tidak berusaha membangun institusi pertanian yang memajukan petani dan membuatnya tangguh secara ekonomi. Balai pembibitan tidak bekerja maksimal, penyuluh pertanian tak bisa diandalkan, koperasi tani menjadi sarang korupsi, dan Bulog merambah ke berbagai komoditi lainnya dan menjadi pemungut rente yang mengerikan. Dari sinilah, politik perberasan versi Soeharto yang semula canggih itu mulai tergerogoti.
Sejauh ini belum terlihat adanya strategi perberasan dari pemerintahan Gus Dur. Kebijakannya yang pertama adalah memberlakukan bea masuk beras 30 persen. Kebijakan ini sudah bagus, tapi terjegal di kubu importir yang tergiur harga murah lalu memasukkan beras sebanyak-banyaknya. Kebetulan, Departemen Pertanian dan Departemen Perdagangan tidak awas. Yang satu tampaknya tidak mencoba memprediksi hasil panen, sehingga tidak berjaga-jaga. Adapun yang satu lagi tidak mendapat data yang akurat tentang volume beras impor atau barangkali juga tidak melihat adanya keterkaitan antara volume itu dan nasib petani Indonesia.
Kedua blunder itu semestinya tidak perlu ditolerir. Seiring dengan itu, strategi jangka pendek Rizal Ramli—Kepala Bulog yang baru—untuk secepatnya membeli gabah, menunda impor beras, dan merundingkan bea masuk beras yang lebih tinggi dengan IMF, hendaknya didukung oleh pihak-pihak terkait. Barangkali inilah cara terbaik untuk melindungi petani, yang selama ini telah menjadi bumper paling tangguh dalam melenturkan tekanan krisis ekonomi. Biarkan bumper itu tetap berfungsi dengan mengatrol harga gabah dan menampung hasil panen. Untuk itu, diperlukan dana Rp 6-7 triliun—jumlah yang bukan apa-apa dibandingkan dengan kucuran BLBI yang mencapai Rp 164 triliun. Dan mengingat produksi beras Vietnam dan Thailand masih tetap melimpah sampai beberapa tahun ke depan, sebaiknya dari sekarang Bulog mempersiapkan politik perberasan yang canggih, bersih, dan tidak gampang panik. Ini bukan berarti kebutuhan akan grand strategy bidang ekonomi diabaikan, tapi politik perberasan jelas lebih mendesak. Malah, amat sangat mendesak.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini