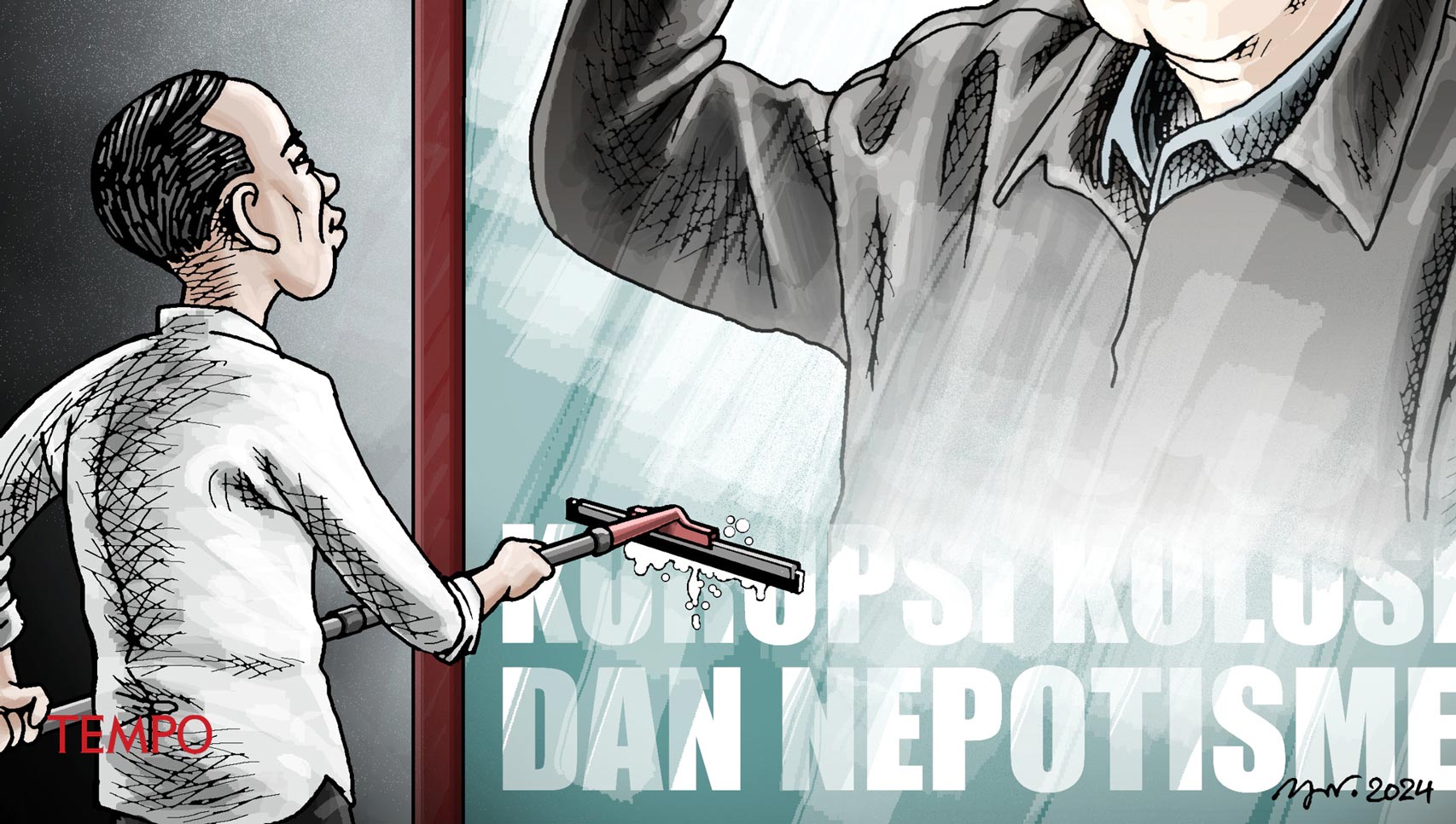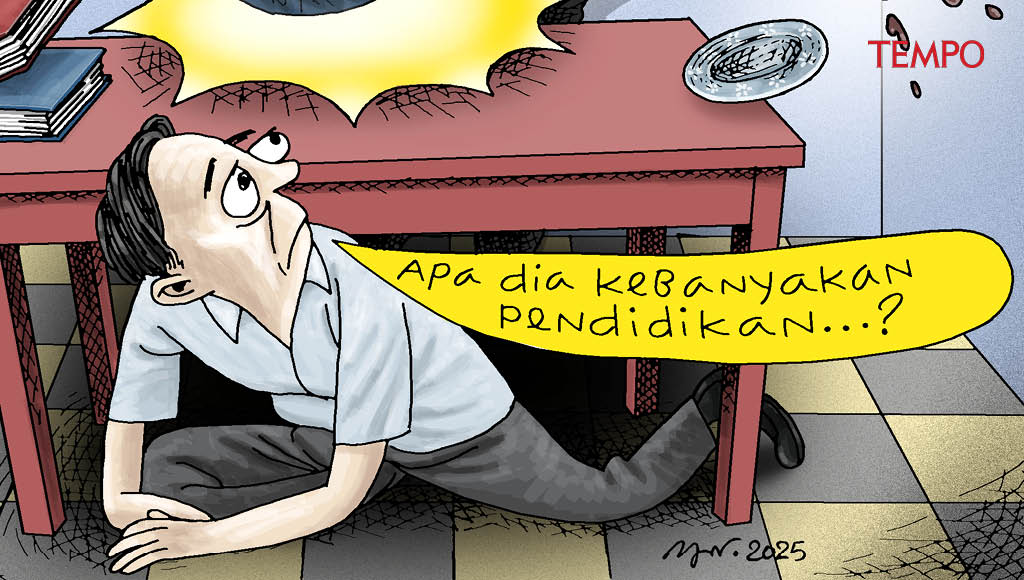TIHINGAN adalah sebuah banjar kecil yang terletak 7 km di barat
Kota Klungkung, Bali Di desa inilah, dibuat gong, gamelan dan
berbagai perangkat alat musik Bali. Menurut catatan Pemda
setempat, 99% dari 179 kk (kepala keluarga) yang ada di banjar
ini mempunyai kebolehan membuat alat-alat musik tradisional
daerah ini. Dan tidak kurang dari 28 pera pembuat gong masih
lestari hingga kini di Tihigan. Masing-masing perapen mempunyai
pekerja sekitar 25 - 50 orang.
Tempat kerja mereka biasanya pengap dan gelap. Tidak tampak ada
peralatan modern, selain sebuah kikir hasil buatan luar negeri.
Sisanya, hanyalah sebuah batu kali besar sebagai alas, sepit
besi buatan sendiri, palu baja seberat 4 kg bertangkai kayu, dan
tumpukan-tumpukan arang. Dengan bercelana kolor saja punggung
para pekerja yang hitam tampak mengkilat karena keringat.
Ditambah abu yang memenuhi ruangan sempit dan percikan bara yang
bagaikan kunang-kunang, cukup menimbulkan suasana kerja yang
khas.
Tembaga, Timah, Menyan
Sama seperti sistem pengairan (subak) orang Bali, para pande
gamelan ini tergabung dalam sebuah kesatuan yang disebut sekehe,
sebagai bagian kecil dari perkumpulan pura (dadiya). Rata-rata
mereka berpenghasilan Rp 1.000/hari. Itu kalau ada pesanan.
Kalau pesanan sedang sepi, "ya kami ngebon sana-sini," ujar
Wayan Mustika, salah seorang pande. "Kadang-kadang, sebulan
lamanya, belum tentu ada yang memesan," ujar Pan Kondri, yang
usianya telah 75 tahun, dan mempunyai anak buah 20 orang.
Para pande gamelan ini biasanya mendapat pesanan lewat pedagang
perantara. Sebuah gong bergaris tengah 14 cm, misalnya, mereka
jual sekitar Rp 300.000. Dan kalau ditelusur sampai ke pembeli
yang memerlukannya, harga tersebut nyaris menjadi dua kali
lipat.
Satu set gamelan Bali komplit, harga rihingan Rp 4,5 juta.
Dikerjakan dalam waktu 55 hari, oleh sekitar sepuluh tenaga
kerja. Bahan baku kuningan atau tembaga (bisa juga dicampur)
yang diperlukan, sekitar 300 kg. Umumnya, nereka tidak mendapat
kesulitan untuk inendapatkan bahan baku ini. Harga bahan baku Rp
5.000/kg, "tapi kami lebih senang beli kuningan atau tembaga
rongsokan," kata Pan Kondri, "karena harganya lebih murah."
Pan Kondri tidak menerangkan secara terperinci bagaimana proses
dan campuran logam sehingga gamelan bisa selaras dengan kuping
si pendengar. Tetapi para pembuat gamelan di Kecamatan
Bekonang, Kabupaten Sukoharjo, Surakarta, mempunyai tradisi
berpuasa, tidak tidur, selamatan, sebelum mereka mencetak
gamelan. Bahkan dari campuran logam dan timah (berbanding 3: 1)
ini masih lagi diberi campuran yang bersifat mistis seperti
kemenyan, gula Jawa dan bunga sesaji. Kelompok pembuat gamelan
di Bekonang (kini dengan lima buah "pabrik") dipimpin oleh
seorang empu yang dipanggil Panji Sepuh.
Mungkin karena lebih banyak yang memesan, harga gamelan dari
Sala ini lebih mahal ketimang yang dari Bali. Resowiguna, 58
tahun, yang mempunyai "pabrik" gamelan sejak 1955 (dan yang
paling banyak menerima pesanan dan paling besar usahanya di
Bekonang), memutuskan, mutu gamelanna dibagi dalam empat kelas.
Mulai dari lp 15 juta untuk kelas satu tiap sct ampai sekitar
Rp 7 juta untuk kelas terendah.
Sebagian besar para pande gamelan ini mempunyai pekerjaan lain,
yaitu bertani. Barangkali karena sambilan itulah, waktu
pembuatannya tak dapat tepat. Misalnya sebuah gong besar dapat
makan waktu 12 hari. Itu pun belum rampung, karena masih harus
dilaraskan suaranya. Apalagi gong kualitas kelas satu, bisa
makan tempo satu bulan. Karena untuk kualitas ini harus lebih
teliti dan paling tidak dikerjakan oleh 12 orang.
Berapa penghasilan pengrajin gamelan di Bekonang? Harga
gamelannya memang lebih tinggi, tetapi "gaji" pengrajinnya tidak
dapat dikatakan memadai bagi kepandaian khusus ini. Untuk sebuah
gong kualitas unggul, Panji Sepuh cuma menerima Rp 25.000 untuk
masa kerja sekitar empat minggu.
Upah pengrajin gamelan Sunda, lebih rendah lagi. Sekitar Rp
5.000 - Rp 20.000 seorang untuk kerja selama seminggu.
Perbedaan upah ini juga tergantung dari keahlian si pengrajin
masing-masing.
Seperangkat gamelan Sunda yang dikerjakan oleh enam orang
(tukang cor, tukang cetak, tukang ukir kayu dan tukang laras
suara) bisa selesai dalam tempo dua minggu. Gamelan degung
perunggu tipe A, dengan ancak ukir dari kayu jati, harga
seperangkatnya Rp 3,5 juta. "Tapi saya senang, semakin banyak
orang menaruh perhatian pada kesenian Sunda," kata Adis, 60
tahun, pemilik pembuatan alat-alat musik Sunda, Myang Sari, di
Bandung.
Mayang Sari setahunnya rata-rata mendapat pesanan dua atau tiga
perangkat gamelan perunggu dan 12 perangkat gamelan terbuat dari
besi. Yang belakangan ini lebih murah harganya, di samping
bahan bakunya pun lebih mudah didapat. Biarpun pesanan atau upah
rendah, "tapi saya bekerja di sini karena panggilan jiwa seni,"
ujar Encir, 60 tahun, yang telah sembilan tahun bekerja di
Mayang Sari. Demikian pula Ferry, 40 tahun, yang telah lima
tahun bekerja di tempat yang sama sebagai penyetel lempengan
besi menjadi instrumen yang melahirkan musik yang merdu.
Caranya? "Yang, sulit diterangkan. Itu mah pakai perasaan,"
tuturnya.
Memang alat bagi tukang stem nada, seperti dikatakan Sundoro
Widoatmojo dari Bekonang, "cuma telinga dan jiwa pendengaran
dan rasa." Sejak 1961 dia sudah jadi tukang melaras nada. Setiap
instrumen yang setengah rampung, misalnya bonang, harus
"dicicipi" dulu oleh kuping Sundoro. "Kalau ada yang belum
sreg," kata Sundoro, "jiwa saya akan bereaksi." Dia kemudian
menyuruh tempa atau kikir lagi bonang tersebut sampai nadanya
terdengar selaras.
Para pembuat alat musik tradisional ini rupanya tidak tertarik
untuk melaksanakan pembaruan cara membuat gamelan. Karena ini
berarti mengubah sistem manajemen mereka. Di Tihingan misalnya,
pernah sebuah bank ingin membantu pengrajin gong. "Tapi kami
menolak," ujar Wayan Waspa Susana, perbekel desa tersebut.
Mereka enggan terlibat utang, karena pemasaran tidak bisa
diandalkan.
Di Bekonang, Surakarta, semua pengrajin gamelan bergerak secara
mandiri. Tidak ada bantuan modal dari bank pemerintah atau badan
kesenian swasta. ASKI (Akademi Seni Karawitan Indonesia) atau
PPKJ (Pusat Pengembangan Kebudayaan Jawa) yang ada di Sala,
paling banter memberikan bimbingan berupa pembinaan kualitas.
Ini berarti secara tak langsung membina pemasaran pula. "Tapi
profesi ini bisa diandalkan," kata Yuyun, yang ayahnya mempunyai
Mayang Sari di Bandung. Yuyun membuktikan, bahwa walaupun
ayahnya cuma seorang pensiunan guru Konservatori Karawitan
Sunda, "dia bisa menghidupi dan menyekolahkan kami limabelas
bersaudara." kata Yuyun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini