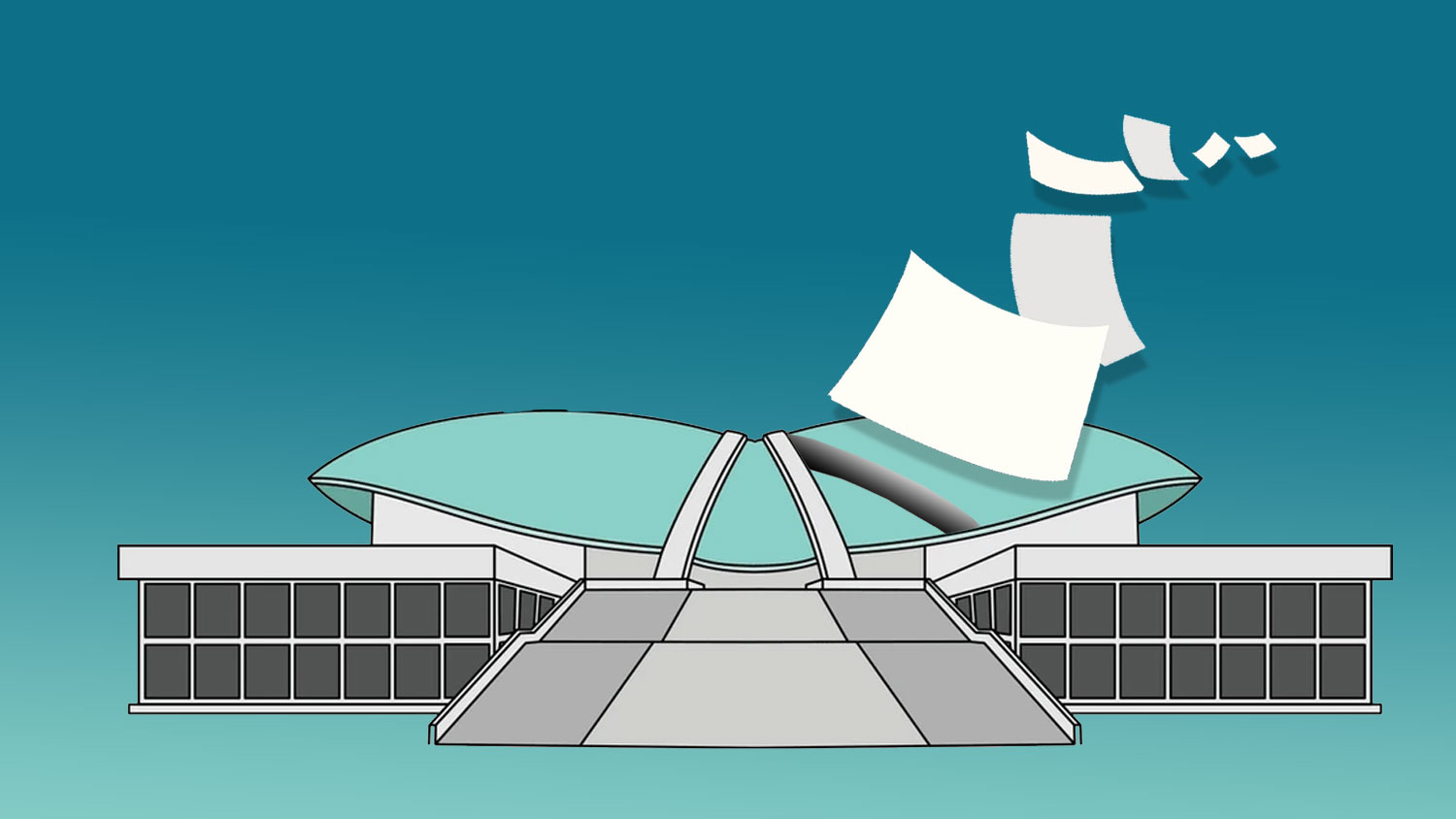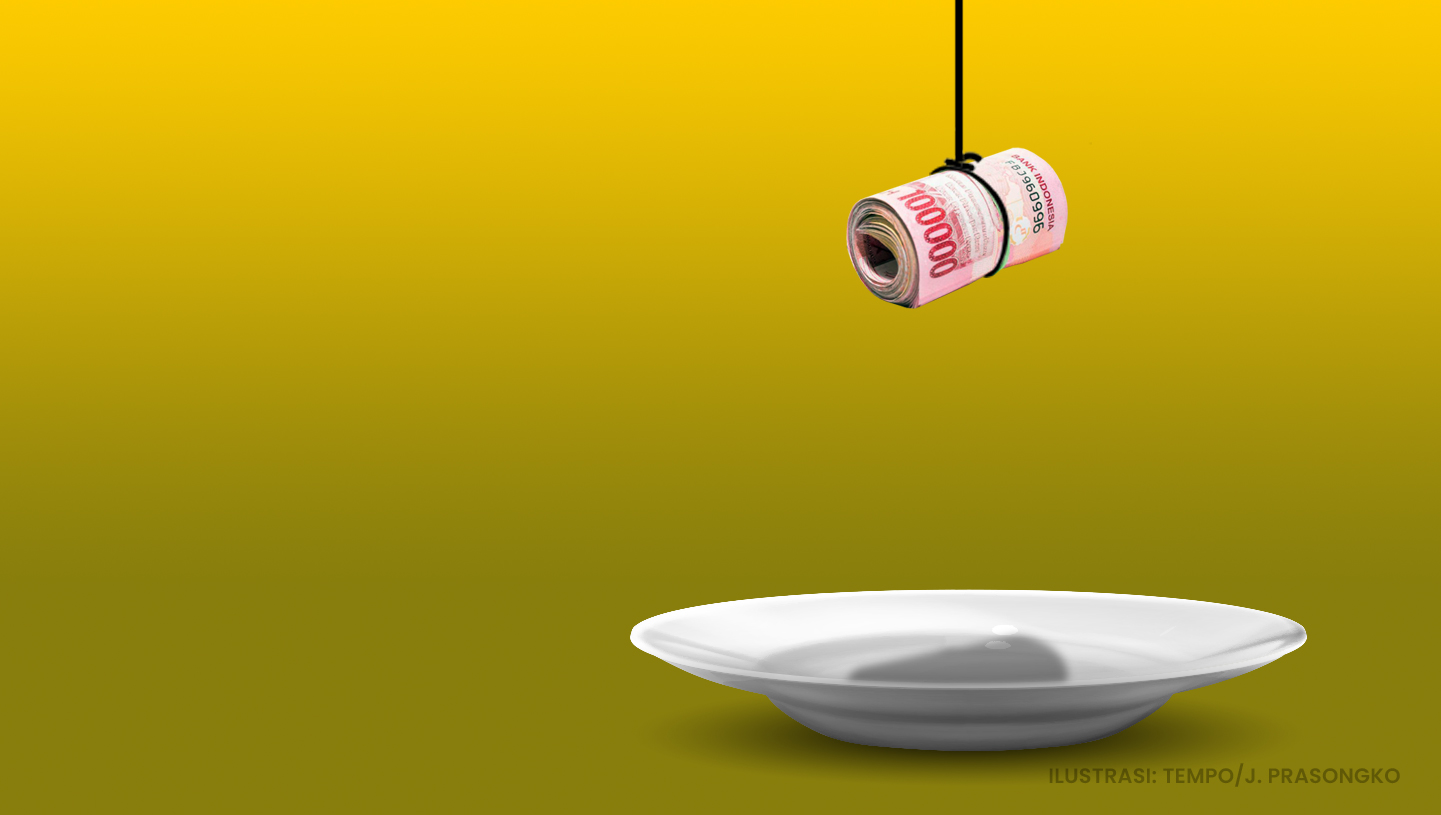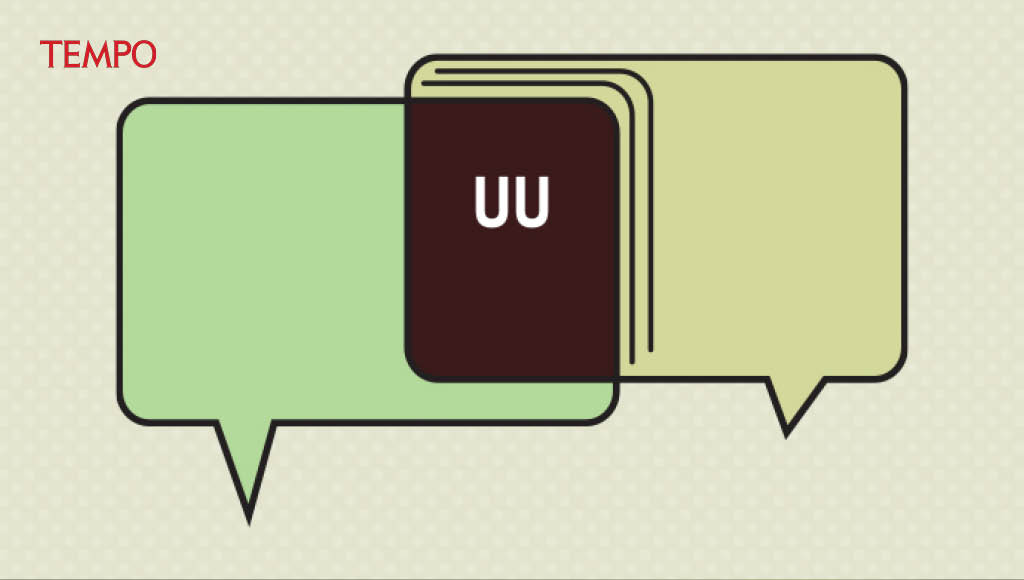DARI ruang tengah saya dengar radio sedang mendendangkan sebuah
lagu. Lagu lama. Telah sejak di sekolah menengah saya mendengar
lagu itu.
"Jiko den kana maso dahulu
Jatuah nan badarai si aie mato
Alah sansai yo badan, oi
Sungguh mati, sampai kini saya tak pernah tahu, mengapa air mata
harus berderai mengingat masa lalu itu. Apakah masa lalu itu
demikian indahnya, dan hari kini demikian pahitnya terasa
sehingga rasa sedih tak lagi dapat dibendung? Ataukah,
sebaliknya? Demikian baiknya keadaan sekarang, sehingga lintasan
kenangan ke masa lalu menyebabkan derita lama terasa lagi.
Entahlah, sukar bagi saya untuk menebak.
Barangkali bukanlah lirik dari lagu yang berhiba-hiba ini yang
salah, tetapi pertanyaan saya. Saya mencari logika pada sesuatu
yang bersifat puitis. Bisa juga demikian halnya. Tetapi lebih
mungkin lagi ialah bahwa sebenarnya kenyataan yang melatar
belakangi lirik itu tidaklah penting. Yang ditangisi bukan
apa-apa, tetapi kenyataan bahwa hari lalu telah hilang.
Kelampauan adalah suatu kehilangan. Dengan begini lirik ini
hanyalah bisa dianggap sebagai pernyataan kekalahan. Kalah dalam
melawan waktu yang telah berlalu.
Bukanlah maksud saya berfilsafat-filsafatan. Filsafat bukanlah
cangkir kopi saya, kata suatu ungkapan. Soalnya begini.
Baru-baru ini dengan sangat gembira saya menerima suatu undangan
untuk menghadiri silaturahmi sebagai lanjutan dari reuni yang
telah kita adakan." "Reuni" dengan kawan-kawan lama.
Saya menyesali diri, karena tak ada di kota pada waktu itu.
Namun sesungguhnya, bukanlah undangan itu benar yang menjadi
pikiran (nah, ini plagiat saya terhadap gaya seseorang), tetapi
keterlarutan saya kepada suasana kerinduan. Hanya seketika,
tetapi begitu mendenyut. Sekejap saya sadar hahwa saya telah
latah dalam . . . ya, apalagi kalau bukan nostalgia, yang sedang
menjadi "mode" itu. Mode? Barangkali lebih dari itu. Bahkan
telah komersial.
Denyutan rindu adalah pengalaman sangat pribadi, mulanya. Ia
datang. Ia pergi. Kedatangannya tidak harus selalu ketika kita
mempertentangkan kemanisan dulu dengan kepahitan kini. Dan
kepergiannya juga tak selamanya harus seiring dengan keinginan
untuk membanding kenyamanan kini dengan kegetiran dulu.
Kerinduan kepada suasana kelampauan hanyalah pengingkaran
terhadap waktu, yang kini dalam kesadaran modern telah dijadikan
sesuatu yang bisa diukur sesuatu yang panjang atau pendeknya
dapat dipastikan.
Dengan bernostalgia waktu dipakai untuk tak berfungsi. Dalam
kesadaran teringkarilah apa pun perubahan yang telah dipaksakan
waktu. Yang ada hanya "suasana menetap", di mana kini dan
lampau terbaur dalam suatu keutuhan. Tahun-tahun yang dilalui
tak lebih daripada jam-jam - jam-jam yang hanya penting dalam
kencan, tetapi tidak dalam biografi.
Maka sejarah jadinya, juga dipaksa untuk tidak bisa bicara
apa-apa. Ketegangan antara kontinuitas dan perubahan, yang
merupakan bagian menetap dalam sejarah, dijadikan tak relevan.
Nostalgia adalah tingkat yang paling rendah dari pemberontakan
pada tirani waktu.
Betapa nikmatnya pemberontakan ini. Maka kita pun bersiul
menyanyikan lagu yang menguatkan suasana pemberontakan ini. Maka
selintas menjalar pertanyaan, "Ah. bagaimana kalau." Nostalgia
adalah puisi. Ia adalah pula pengandaian.
Tetapi kenikmatan ini akan menimbulkan permasalahan yang
sungguh-sungguh jika ia tak lagi disadari sebagai selingan yang
melintas dalam kehidupan. Suasana nostalgia akan menciptakan
realitas yang sangat tak ramah, jika ia dijadikan sebagai
patokan dalam menilai dan mengerti hari kini. Kegelisahan akan
melanda, serenta pengandaian yang ditimbulkannya menuntut
jawaban-jawaban yang tak akan pernah didapatkan.
Suasana nostalgia yang direntang-rentang hanyalah akan
melahirkan pengimpi yang sibuk "menciptakan" dan mengelus tempo
doeloe yang konon serba cerah. Pada "tempo doeloe" ini pula ia
meletakkan impian yang serba utopis. Lampau dan nanti mencair
dalam impian. Maka kemudian si-pengimpi akan berubah menjadi
pelari dari kenyataan kini.
Kerinduan yang dipakai sebagai ukuran dalam menilai hari kini
akan dapat menyebabkan seseorang menjadi reaksioner yang tak
hentinya menafikan keabsahan hari kini. Dalam kegelisahannya,
jadilah ia kemudian si pengumpat yang hanya sanggup melihat
aspek yang hitam dari hari kini.
Mungkin saya telah berlebih-lebihan. Bukankah yang asyik
bernostalgia adalah mereka yang sedang dan pernah sukses? Tetapi
inilah soalnya. Sukses dan nostalgia yang berkepanjangan adalah
kombinasi yang menimbulkan sikap tak perduli. Yang sah adalah
"tempo doeloe". Dan yang sukses kini? Ya, terimalah sebagai
kekarunan tanpa tanggung jawab.
Kehilangan sukses dan nostalgia berkepanjangan bukan saja
menista hari kini tetapi juga kehilangan kepercayan pada hari
nanti. Maka teriakkanlah pembangunan atau apa saja yang serba
baik untuk hari kini dan hari nanti setinggi langit, ia tak akan
mendengar.
Sementara itu, lagu lama dari ruang tengah makin mengecil. Alah
sansai yo badan, oi. Saya kembali kepada keasyikan kerja semula.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini