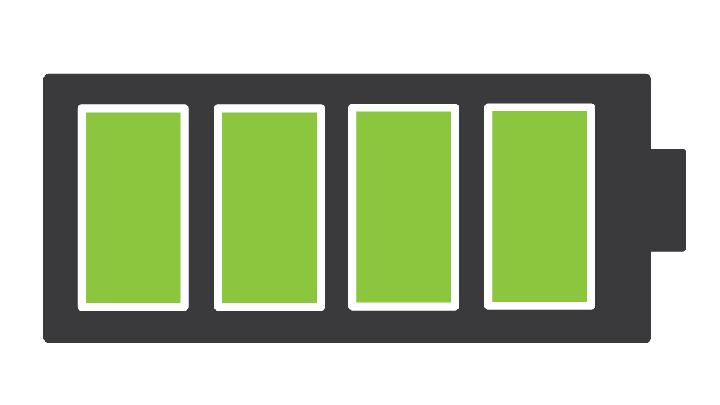ARSITEKTUR tradisionil makin populer di mana-mana. Potongan atap
joglo (Jawa) kini menghiasi gudang Bulog di seluruh Indonesia.
Daerah lain di luar Jawa juga mulai mengadaptir arsitektur asli
daerahnya pada corak bangunan masa kini. Baik arsitektur rumah
gadang (Minang), arsitektur tongkonan (Toraja), dan paling akhir
ini arsitektur tambi (Tolore, Sulawesi Tengah) mulai
diperkenalkan dalam bentuk bangunan modern.
Gedung DPRD Sulawesi Tengah, tempat berlangsung pelantikan
Gubernur Munafri minggu ini, telah dibanggakan oleh harian Sinar
Harapan sebagai "perpaduan antara arsitektur tradisionil
Sulawesi Tengah dan arsitektur modern, untuk pertama kalinya."
Perpaduan itu merupakan hasil perencanaan Dinas PU setempat.
Seluruh kompleks bangunan kembar tiga itu telah menelan biaya Rp
423 juta.
Modelnya memang rumah asli suku Tolore di pegunungan Takolekaju,
pedalaman Sul-Teng. Dalam bahasa sana, namanya tambi. Kecuali
atap bambunya yang harus diganti 40 tahun sekali, tambi tosae
(rumah orang dulu) di Bada dan Besoa yang seluruhnya terbuat
dari balok dan papan kayu koronia itu bisa tahan sampai ratusan
tahun. Di Besoa misalnya, ada satu rumah adat yang sudah 200
tahun umurnya, dan sudah dua kali digotong pindah kampung. Bukan
digotong dalam keadaan utuh -- beratnya nauzubillah. Tapi
dibongkar lagi. Ini memang mungkin karena tak ada sambungan
mati.
Apa Tahan Gempa?
Sambungannya yang seluruhnya tanpa paku itu membuatnya juga
tahan gempa. Gempa bumi memang suka menggelitik Teluk Palu
sampai Palopo. Makanya seluruh konstruksi bangunan merupakan
satu kesatuan yang seimbang. Mulai dari panggungnya, ruang
rumahnya, dan atap yang sekaligus berfungsi sebagai dinding.
Seluruh struktur itu bertumpu di atas empat batu pengalas tiang
panggung, yang menahan amblasnya tiang-tiang panggung rumah itu
ke dalam tanah. Sekaligus berfungsi sebagai bantalan getaran,
yang dalam dunia teknik sipil dikenal sebagai 'sambungan rol'.
Apakah gedung DPRD nan megah di Palu pun tahan gempa, seperti
rumah asli penduduk di pegunungan itu? Entahlah. Bangunan ini
hampir seanteronya dari beton, dengan fundasi dan sambungan
corcoran. Jadi mungkin sulit menahan getaran horisontal.
Para arsitektur dan pemborong memang sering melakukan adaptasi
yang hanya menyangkut bentuk, tanpa menyentuh fungsi dan isi
arsitektur tradisionil. Sebagai usaha supaya cantik dan
"berkepribadian". Atap joglo yang ditiru pada berbagai bangunan
modern sekarang, umumnya hanya perlambang kejawaan saja. Fungsi
atap yang lebar kemudian tinggi ramping menjulang itu, sebagai
'penjebak udara' dan penyejuk isi bangunan, seringkali tak
berlaku pada bangunan modrn beratap joglo -- sebab loteng dan
ruang di bawahnya disekat oleh langit-langit (plafon). Sehingga
terpaksa pasang AC juga kalau kepinginhawa sejuk.
"Modern" Dan Praktis
Di pedalaman Sulawesi Tengah sendiri, tempat arsitektur tambi
itu berasal, belum tampak usaha pemerintah melestarikan sambil
memperbaiki arsitektur tradisionil agar lebih memenuhi kebutuhan
manusia. Malah pesawat terbang MAF yang merupakan jalur
penghubung dengan lembah terpencil di sela gunung itu sibuk
mengangkut semen dan seng untuk proyek-proyek Inpres. Paik
puskesmas, sekolah, maupun balai desa Inpres. Atap seng dan
bangunan semen sudah dianggap lambang modernisasi, yang
pelan-pelan mulai menyingkirkan bangunan kayu beratap bambu
menurut struktur yang tahan-gempa.
Atap seng yang harus didatangkan dengan pesawat terbang -- atau
dipikul puluhan kilometer dari toko di kaki gunung --
sebelumnya sudah menghianati gereja dan mesjid. Dan setelah
itu gedung-gedung pemerintah. Maka orang pun mulai berfikir
'modern' dan praktis. Pemasangannya lebih cepat dari pada atap
bambu yang dipilah-pilah, lebih ringan, dan tak perlu mengupah
terlalu banyak orang.
Gejala serupa juga diamati oleh rombongan mahasiswa Arsitektur
dan Sosiologi UI yang kuliah kerja ke Tana Toraja (Sul-Sel)
September 1975. Dalam laporan kuliah kerja itu, anak-anak UI
agak menyayangkan hal itu. Ada keindahan dan kepribadian yang
spesifik Toraja dikorbankan pada penggantian atap bambu ke atap
seng itu. Seperti diungkapkan dalam salah satu kesimpulan
laporan "Ekspresi bentuk yang menggunakan atap bambu lebih
natural dari pada yang menggunakan seng atau sirap. "
Namun di samping pertimbangan estetika, atap bambu dapat tahan
lebih lama dari pada seng (sampai 40 tahun) karena terlindung
dari hujan dan panas matahari oleh lumut yang menutupinya.
Air Kotor
Di samping itu, bambu merupakan bahan baku lokal yang tak perlu
diimpor dari luar. Dan lebih cocok untuk sambungan ikat dan
jepit tanpa paku, yang bisa beresonansi dengan gempa. Karena
lebih berat dari pada atap seng, atap bambu itu pun tak mudah
diterbangkan angin ribut.
Itu tak berarti, tim Arsitektur-Sosiologi UI itu tak melihat
segi kelemahan pada rumah adat Toraja yang perlu diperbaiki.
Misalnya tak adanya kamar mandi dan kamar kecil di lingkungan
rumah. Rumah adat Toraja juga tak dilengkapi saluran air -- bak
air bersih maupun air kotor dan air hujan -- sehingga kolong dan
pekarangan rumah sering becek. Ventilasi udara minim sekali.
Rumah Toraja memang dibikin begitu rapat untuk mencegah serangan
hawa pegunungan di malam hari, tapi ada juga efek buruknya.
Penghuni rumah terpaksa banyak menyedot asap api pediangan di
ruang tengah, yang sekaligus berfungsi sebagai dapur.
Berbagai kelemahan arsitektur tradisionil Toraja itu juga tampak
pada arsitektur tradisionil Tolore. Kebudayaan kedua suku itu
memang banyak persamaan, begitu pula habitat mereka. Tantangan
yang lebih sulit dari pada seke= dar membuat tiruan rumah Toraja
atau tambi Tolore di ibukota propinsi adalah bagaimana
memperbaiki arsitektur tradisionil suku-suku pegunungan itu
hingga menjadi lebih sehat, tapi tetap murah, tahan lama, dan
tahan gempa. Tanpa menciptakan ketergantungan baru pada bahan
luar seperti semen dan - seng, dan tanpa menurunkan derajat
penduduk setempat menjadi kuli harian.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini