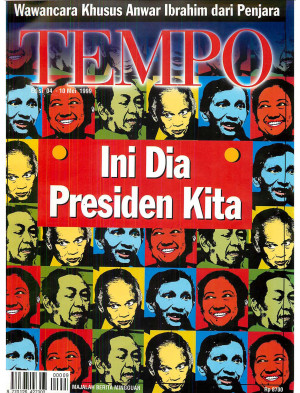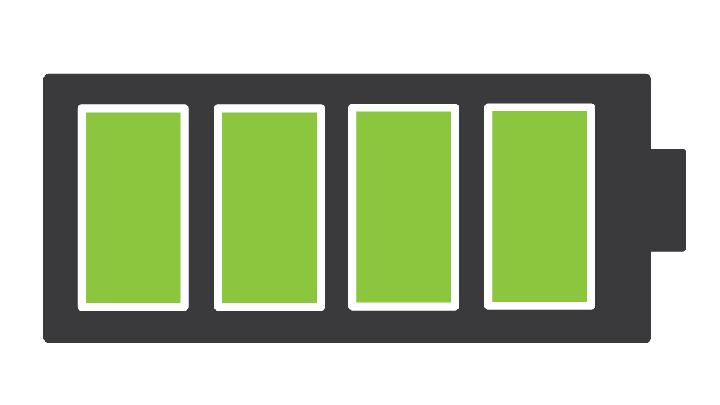Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
SEBUAH kejadian selalu memiliki dimensi sebab yang beragam dan bersinggungan serta mengundang rasa ingin tahu. Kasus penembakan dan pengeboman siswa di Columbine High School, Littleton, Denver, Amerika Serikat, akhir April lalu, masih meninggalkan rasa ingin tahu. Pertanyaan mengapa Eric Harris, 18 tahun, dan Dylan Klebold, 17 tahun, mampu membantai belasan siswa sekolah tersebut membutuhkan jawaban.
Pertanyaan besar itu pula yang dicoba dijawab majalah Newsweek, yang dalam penerbitan 3 Mei lalu menurunkan kajian ilmiah tentang pangkal musabab kekejaman yang dilakukan anak-anak. Sederet penyebab bisa disebut, misalnya punya akses yang mudah terhadap senjata api, hidup dalam lingkungan yang "menghalalkan" budaya kekerasan dan balas dendam, atau menjadi korban kekerasan orang tua.
Tapi, sebenarnya, tidak ada penyebab tunggal. Ilmu pengetahuan sekarang mungkin bisa menjelaskan kenapa tidak setiap anak yang punya akses mudah terhadap senjata api bisa otomatis menjelma menjadi seperti Harris dan Klebold. Kini mungkin juga telah bisa dijelaskan secara ilmiah mengapa tidak setiap anak yang merasa diasingkan lingkungannya--seperti dialami Harris dan Klebold itu--bisa melakukan pembantaian massal. Inti jawabannya, selain faktor lingkungan, ada faktor biologis yang membuat seseorang menjadi pembunuh.
Persoalan akar dari sebuah tindak kekerasan memang bukanlah hal sederhana yang bisa dijelaskan hanya dengan melihat problematiknya dari sisi genetika atau dengan melihat struktur tertentu pada otak. Tapi, bila gambar otak dilihat, akan terlihat gambaran yang lebih jelas bahwa suatu pengalaman ternyata memang mempengaruhi kondisi otak.
Pengalaman awal tampaknya punya daya pengaruh yang sangat kuat karena otak anak-anak lebih lunak dan lebih mudah dibentuk daripada otak orang dewasa. Menurut Dr. Bruce Perry dari Baylor College of Medicine, Amerika Serikat, seorang anak yang berulang-ulang "terpukul" stres--akibat disiksa, ditelantarkan, atau diteror--akan mengalami perubahan fisik pada otaknya. Stres yang terus-menerus, yang membuat otak mengeluarkan bahan kimia sebagai mekanisme melawan stres, rupanya mampu mengubah sistem hormonal yang dikendalikan otak. Akibatnya, si anak menjadi agresif impulsif dan sulit berhubungan dengan teman sebayanya.
"Lingkungan tempat seseorang dibesarkan memprogram sistem saraf untuk membuat dia menjadi lebih reaktif atau tidak terhadap stres," kata ahli biologi Michael Meaney dari Universitas McGill, Amerika Serikat. "Jika orang tua tidak peduli kepada anaknya, (otak) si anak kemudian akan menyimpulkan bahwa dunia ini tidak menarik dan menyebabkan ia harus selalu waspada," katanya.
Pada anak-anak lain, pengalaman yang berulang pada penderitaan dan kekerasan bisa membuat sistem hormon stres otak mereka tidak responsif dan "aus". Dengan kondisi otak seperti itu, muncullah anak-anak yang berjiwa antisosial. Tipikal mereka adalah mempunyai detak jantung yang lamban dan sensitivitas emosi yang timpang. Bahkan, mereka seakan tak peduli terhadap dunia sekelilingnya. Biasanya mereka suka mencederai binatang. Kip Kinkel, 15 tahun, yang membunuh orang tuanya dan menembak 24 teman sekolahnya, Mei tahun lalu, mempunyai sejarah kejiwaan seperti itu.
Contoh lain adalah Luke Woodham, yang membunuh tiga teman sekelasnya dan melukai tujuh teman sekolahnya di Pearl, Mississippi, juga di AS, dua tahun lalu. Sebelum melakukan pembantaian, ia mengadakan "upacara" dengan memukuli anjingnya, membungkusnya dalam sebuah tas, dan kemudian melemparkannya ke api.
Peran orang tua semakin penting dalam menghadapi anak-anak dengan problem seperti itu. Sebab, orang tua yang tidak peduli, jadinya, lebih jahat daripada kejahatan itu sendiri. Orang tua yang tidak bersahabat dan berjarak, tidak punya perhatian, dan pasif akan membentuk seorang anak menjadi kehilangan emosinya.
Perhatian orang tua yang kurang, secara umum, berpengaruh kecil terhadap kebanyakan anak. Tapi, pada bayi yang rentan, pengaruh ketiadaan kasih sayang akan sangat besar dan bisa berakhir tragis. Dr. Perry menemukan, ketidakacuhan itu memperlemah perkembangan lapis terluar otak sang anak, yang mengontrol sistem emosi, kepemilikan, dan kekerabatan sosialnya. "Pengalaman masa kecilnya menyebabkan kapasitasnya untuk membentuk hubungan sosial tak berkembang," katanya. Si anak, Perry melanjutkan, akan sulit berempati kepada orang lain. Mereka cenderung pasif dan merasa digerakkan oleh sesuatu di luar diri mereka.
Anak-anak yang kekurangan kasih sayang ini mencari "skenario" mereka sendiri yang sesuai dengan perasaan yang tersisihkan. Sementara itu, budaya pop sekarang ini menawarkan semua hal dengan banyak bahaya, dari musik sampai permainan di komputer. Kebanyakan dari "skenario" tadi menampilkan tokoh laki-laki yang jantan. Sedangkan mereka, anak-anak berusia 10-14 tahun, adalah populasi yang berisiko tinggi melakukan tindak kekerasan, dan terus meningkat.
Karena itu, meski komponen genetis bisa mengubah seseorang menjadi antisosial, ia bisa menjadi baik atau buruk bergantung pada lingkungan tempat ia tumbuh. Respons orang tua yang berbeda menghasilkan kondisi otak yang berbeda pula, serta tingkah laku yang berbeda pula. "Tingkah laku adalah hasil dari dialog antara otak dan pengalaman," demikian Debra Niehoff, pengarang buku terbaru The Biology of Violence, menyimpulkan. "Meskipun manusia dilahirkan dengan beberapa aspek biologis yang sudah ada, otak mempunyai banyak ruang kosong. Dari masa kanak-kanak, otak berfungsi sebagai pencatat yang merekam pengalaman kita dalam bahasa neurokemistri," kata Debra Niehoff.
Kondisi otak tak hanya dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan, tapi juga oleh beberapa penyakit otak. Apa pun penyebabnya, perubahan kondisi otak bisa membuat seseorang terdorong melakukan kekerasan. Luka pada lipatan frontal otak, misalnya, dapat mempengaruhi sifat apatis serta mendistorsi penilaian dan emosi. Dalam proses pemindaian oleh psikiater Daniel Amen dari California terhadap 50 pembunuh, ditemukan beberapa pola yang sama: sebuah struktur yang disebut cingulate gyrus (CG), yang terbentuk di sepanjang pusat otak, terlihat hiperaktif pada para pembunuh tadi.
CG beraksi seperti transmisi otak, memindahkan satu pemikiran ke pemikiran lain. Ketika CG rusak, orang terhenti pada satu pemikiran saja. Sementara itu, bagian lapis terluar otak yang bertugas sebagai pengawas otak justru bereaksi lamban. Jadi, jika seseorang mempunyai pikiran tentang kekerasan dan berhenti di situ tanpa ada pengawas, di situlah bencana berawal.
Karena itu, ada kesimpulan begini. Kecuali pada sedikit anak-anak, para pembunuh tadi sebenarnya bukanlah anak yang tak bermoral. Tapi tingkat moral mereka tidak normal. "Saya membunuh karena orang seperti saya diperlakukan buruk setiap hari," kata Luke Woodham, yang gemuk, pendek, dan berkacamata, yang membunuh tiga pelajar, "Dalam seluruh hidup saya, saya merasa menjadi buangan masyarakat, sendiri." Jadi, anak-anak ini, secara emosional dan fisik, terabaikan oleh mereka yang seharusnya mencintai mereka.
Agar anak-anak semacam ini mempunyai kemampuan untuk berkembang dan membangun hubungan yang sehat--dikontrol oleh sirkuit saraf--mereka harus diberi kasih sayang yang tidak terbatas. Kalau tidak, mereka akan hipersensitif dalam menilai ketidakadilan. Perasaan ketidakadilan sering dibarengi perasaan papa dan tidak berdaya. Tak aneh jika kemudian ada seorang pembunuh yang berkata, "Saya lebih suka dianggap sebagai pembunuh daripada dianggap tidak ada sama sekali."
Rustam F. Mandayun
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo