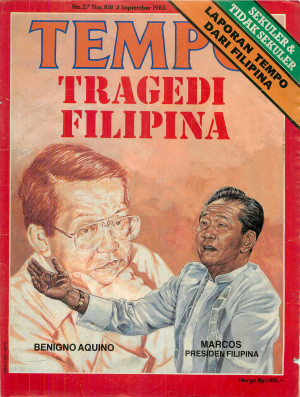PENDUDUK Irian Jaya, insya Allah, tahun depan sudah ikut
menikmati siaran televisi Australia. Selang beberapa tahun
kemudian, kalau tidak ada aral melintang, mata penduduk Sulawesi
dan sebagian Kalimantan terbuka pula untuk menonton siaran
televisi Filipina. Namun semua itu masih angan-angan.
Pelaksanaannya baru menjadi kenyataan bila kedua negara tadi
memulai program DBS (Direct Broadcasting Satellite), atau SSL
(Satelit Siaran Langsung), yang belakangan ini makin ramai
dibicarakan.
Di Jakarta, seminar sehari tentang "Indonesia Menjelang Era
Siaran Langsung Melalui Satelit DBS)" diselenggarakan 22
Agustus lalu di Studio Pusat Produksi TVRI. Dalam seminar yang
dikaitkan dengan ulang tahun TVRI itu, sebelas orang angkat
bicara, dengan moderator Drs. Willy Karamoy.
DBS sebetulnya bukan barang baru. Paling tidak, "ia mulai
diperdebatkan pada sidang luar biasa konperensi administrasi
radio internasional (WRAC) di Jenewa, 1963," ujar D.H. Assegaff,
salah seorang pembicara dalam seminar. Justru belakangan ini
masalahnya makin menarik, karena beberapa negara sudah sampai
pada langkah yang menentukan.
Dengan sistem ini, siaran radio dan televisi melalui satelit
langsung dipancarkan ke rumah-rumah. Stasiun bumi tak lagi
diperlukan. Satelit yang didisain khusus itu mempunyai daya
pancaran tinggi, sehingga antena kecil -- dengan diameter
sekitar satu meter di rumah pemakai bisa menangkapnya.
"Itulah perbedaan utamanya dengan satelit telekomunikasi biasa,"
kata Benny S. Nasution, Kepala Bagian Operasi Teknik Transmisi
Satelit Perumtel.
Selain antena parabolik, DBS juga membutuhkan converter. Alat
ini berfungsi mengubah frekuensi gelombang pancaran satelit,
menjadi frekuensi gelombang yang bisa ditangkap pesawat
televisi. Bila satelit menggunakan frekuensi dengan orde
gigahertz, frekuensi yang bisa ditangkap pesawat televisi hanya
berorde megahertz (106).
Pada satelit konvensional, converter itu dimiliki stasiun bumi.
Stasiun inilah yang menangkap gelombang dari satelit,
mengubahnya menjadi gelombang televisi (ultra high frequency
atau very high frequency), kemudian memancarkannya. Pada DBS,
converter pada antena parabolik langsung mengubah frekuensi, dan
melalui kabel menghubungkannya dengan pesawat televisi.
Sistem DBS tertentu dilengkapi dengan komputer. Alat ini
melakukan kontrol terhadap langganan yang alpa membayar. Sampai
batas waktu yang sudah ditetapkan, komputer ini secara otomatis
menghapus pulsa sinkronisasi, yang menampilkan dan mengatur
gambar di layar televisi.
Untuk pemilik siaran, DBS lebih menguntungkan. Biaya yang harus
dikeluarkan untuk membangun stasiun bumi (SB), tak lagi
diperlukan. Jangkauan juga akan semakin luas, sebab tidak lagi
tergantung pada SB.
Kini, "dengan sekitar 150 SB, TVRI baru menjangkau 20% sampai
25% wilayah Indonesia," ujar Ir. E. Jamin, Kepala Bagian
Teledefusi Antariksa LAPAN, yang memberikan makalah dalam
seminar.
Untuk menjangkau seluruh wilayah RI diperlukan sekitar 1.500 SB
plus pemancar. Bila harga per unit Rp 150 juta, maka biaya untuk
1.500 unit menjadi Rp 225 milyar. Jumlah ini masih ditambah
dengan biaya perawatan (5% dari investasi) dan pembulatan,
sehingga seluruhnya akan menjadi Rp 240 milyar.
Dengan DBS, stasiun bumi dan stasiun-stasiun pemancar akan
hilang, biaya perawatan juga tidak diperlukan. Yang harus
menguras kocek lebih banyak adalah pemirsa. Terutama untuk
membeli antena parabolik mini berikut converternya.
Untuk antena piringan berdiameter kurang dari satu meter,
diperlukan sekitar Rp 500 ribu Jepang konon sedang merancang
produksi massal antena parabolik ini, sehingga harganya bisa
ditekan antara Rp 100 ribu dan Rp 200 ribu.
Potensi DBS makin menarik perhatian ketika Kanada mengorbitkan
Anik-C melalui pesawat ulang-alik Challenger, bersamaan dengan
peluncuran Palapa B-1 kita. Inilah "satelit pertama yang
benar-benar mempunyai kemampuan untuk siaran langsung ke
rumah-rumah," tulis Dr. M. Alwi Dahlan dalam makalahnya di depan
seminar. Dosen komunikasi UI yang menjadi asisten Menteri KLH
itu kemudian meminta kesadaran kita, "bahwa teknologi tersebut
baru saja mulai diterapkan secara operasional."
Negara lain yang berambisi menggunakan DBS ialah Jepang,
Luksemburg, Swiss, Amerika Serikat, Australia, dan India. Dua
tahun lagi, Luksemburg dan Swiss akan meluncurkan Luxsa dan
Telsat.
Di kawasan Asia, Jepang paling galak mengembangkan teknologi
DBS. Sejak 1972 negeri ini melakukan percobaan Broadcasting
Satellite for Experimental Purpose (BSE). April 1978, dengan
roket Delta 2914 NASA dari Tanjung Canaveral, Florida, Amerika
Serikat, Badan Pengembangan Ruang Angkasa Nasional Jepang
(NASDA) meluncurkan BS-I yan dinilai sangat berhasil. Sukses
ini mendorong Jepang memastikan penerapan sistem DBS tahun
depan.
Di negeri kita, DBS tampaknya lebih banyak disoroti dari
dampaknya yang tidak sedikit. "Penyiaran melalui DBS dapat
menimbulkan peleburan atau spill over di kawasan negara lain,"
kata Direktur Jenderal RTF, Drs. H. Subrata. "Hal ini dapat
menyulitkan hubungan antarbangsa, khususnya dikhawatirkan dapat
berakibat negatif bagi negara-negara berkembang." Seminar 22
Agustus itu bahkan menyebut-nyebut peranan DBS dan hubungannya
dengan "Wawasan Nusantara."
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini