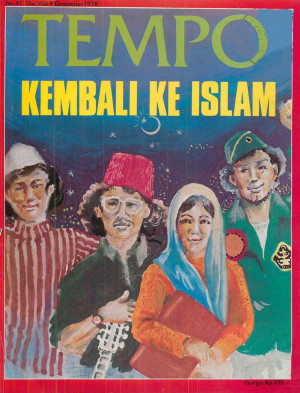HUSSEIN Ambadar, 56 tahun, bukan profesor fisika. Ia hanya
lepasan sekolah guru HIK zaman Belanda. Tapi ia selalu
menyelidiki apa saja. Sebelum ada mesin cetak plastik di
Indonesia, ia sudah membuatnya. Alat penekan cukup dari
dongkrak mobil saja. Mingu lalu, Hussein memperagakan lagi pada
pers ciptaannya yang terbaru pompa pengangkat air yang juga
dapat membuat air asin menjadi tawar.
Pompa desalinasi Ambadar itu sama sekali tak menggunakan
onderdil yang bergerak maupun motor bakar. Sumber tenaganya
hanyalah sinar matahari. Air asinnya 'disuling' dengan
menggunakan sifat elektro-statis dari plastik, dan diangkat
dengan prinsip pipa kapiler seperti pada tumbuh-tumbuhan.
Timbul ide itu padanya dua tahun lalu. Setelah menjual tanahnya
di Jl. M. T. Haryono, Jakarta, ketika itu anak-anaknya
mempersilakan dia bersenang-senang dengan bepergian ke luar
negeri. Tujuan pertama: Singapura. Hanya seminggu ia betah
tinggal di negeri Lee Kuan Yew itu.
Rupanya di Singapura penyakit ingin tahu dan bereksperimennya
kambuh. Terutama setelah membeli dan membaca, setumpuk buku
tentang pemanfaatan tenaga matahari di sana. Maka uang sisa,
yang tadinya tersedia buat berkeliling dunia, dialihkannya untuk
riset tenaga matahari.
Percobaan pertama dilakukannya di kolam renang kosong di
rumahnya di Gadog, Ciawi, Kabupaten Bogor. Hasinya kurang
memuaskan karena sinar mataharinya kurang terik. Lalu ia pindah
ke belakang rumahnya, dan dibangunnya menara penangkap sinar
matahari. Menara itu sekaligus dimaksudkan untuk mengetahui
seberapa tinggi air yang sudah disuling dapat diangkat ke atas.
Mula-mula, air pernah terdesak sampai 10 meter tingginya.
Kemudian menara dipertinggi sampai 18 meter. Ternyata air masih
sanggup melampauinya. Dibantu anak-anaknya, Hussein mengambil
kesimpulan: tenaga matahari masih dapat mengangkat air itu jauh
di atas batas ketinggian menaranya yang 'hanya' 18 meter.
Ciptaan Hussein Ambadar itu didorong oleh suatu kebutuhan
bagaimana menyuling air laut yang asin untuk keperluan industri.
Dan seperti biasanya, pabrik -- juga perumahan -- menggundkan
sistim distribusi air dengan memompanya ke atas menara penampung
terlebih dahulu.
Seluruh proses penyulingan serta pemompaan air ke atas menara
itu sampai sekarang masih banyak memboroskan bahan bakar fosil.
Ambadar Sr. lantas berfikir, mengapa tak menggunakan tenaga
matahari nan gratis itu saja?
Hampir dua tahun lamanya, ia tak pernah keluar dari rumahnya di
Ciawi itu. Zantar, 25 tahun, anaknya yang tadinya jual-beli
mobil disuruhnya berhenti berdagang agar bisa sepenuh waktu
membantu ayahnya. Hussein sendiri, kadang-kadang dari pagi
sampai sore nongkrong di atas menara yang tingginya 24 meter.
Untuk makanan dan keperluan lainnya, sang ayah tinggal memesan
lewat intercom saja.
Enam bulan lalu menaranya masih menghasilkan 20 liter air murni
sehari, sedang uang sudah keluar Rp 40 juta. Tapi berkat
percobaan semula, yang menggunakan tiga jenis pipa (besi,
aluminium dan tembaga), disimpulkan bahwa kolektor panas
matahari yang terbaik adalah pipa tembaga berdiameter kecil yang
dicat hitam dan dijajarkan rapat-rapat.
Teknologi Non-Mekanis
Berdasarkan kesimpulan itu dibuatlah kolektor panas yang luasnya
30 m2. "Tapi praktis yang berfungsi hanya sebagian saja, sebab
sinar matahari tak merata," tutur Hussein Ambadar kepada Widi
Yarmanto dari TEMPO yang pergi meninjau ke Ciawi. Panas matahari
di daerah pegunungan itu berkisar antara 19ø - 24ø C. Itupun hanya
antara jam 9 sampai 12 siang. Hasilnya sekarang adalah 200 liter
air murni per hari atau 25 liter per « jam. Ancar-ancarnya dengan
kolektor yang ada sekarang adalah memproduksi 600 liter air
murni/hari.
"Inilah teknologi non-mekanis dengan kerugian hampir nihil,"
tambah bekas guru sekolah itu. Tak ada enerji yang terbuang.
Juga tanpa bahan bakar fosil -- bensin, gas, atau batu bara.
Malah panas yang timbul di ruang penguapan alat itu, katanya,
"dapat digunakan membangkitkan listrik." Caranya, tak
dijelaskan.
Tapi mengapa di Ciawi? Mengapa tak di dekat laut, di mana sinar
matahari juga lebih terik? Alasannya sederhana saja. "Rumah saya
'kan di Ciawi, jadi perhatian dapat saya curahkan sepenuhnya,"
sahutnya.
Orang tua yang suka meneliti itu sekarang punya 13 anak.
Rumahnya bernomor 13, dengan 13 pohon pala di kebunnya. Dia tak
takut pada angka 13. Lalu, apa selanjutnya? "Istirahat dulu,
saya sudah capek," katanya. Tapi belum istirahat penuh, karena
dia segera berusaha mendaftarkan ciptaannya itu di lembaga paten
di Paris.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini