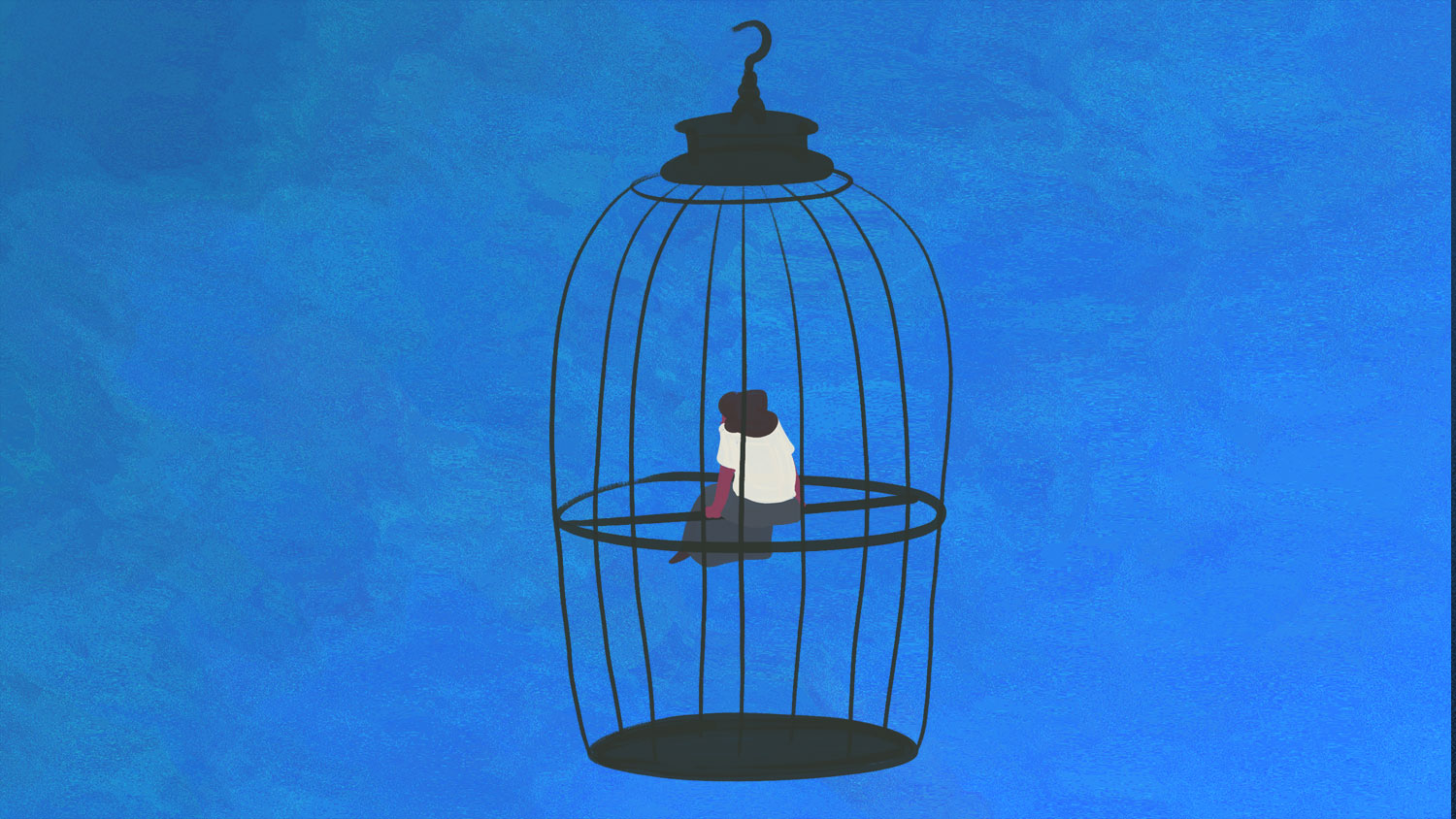M. NATSIR: SEBUAH BIOGRAFI Penulis : Ajip Rosidi Penerbit : PT Girimukti Pasaka, Jakarta, 1990, 319 halaman, Jilid I SALAH satu gejala yang menggembirakan dalam dunia penerbitan kita sejak pertengahan tahun 1970-an sampai sekarang ialah makin banyaknya diterbitkan buku biografi, otobiografi, memoir, dan jangan dilupakan, buku kenangan di hari ulang tahun seorang tokoh. Kalau kita akan berlagak ilmiah, tentu, tak akan sukar untuk mengatakan bahwa biografi "pasti lebih obyektif". Benar atau tidak, biarkan saja, tetapi bukankah biografi adalah hasil studi seorang penulis terhadap tokohnya? Tak mengherankan kalau perdebatan, "akademis" atau "kusir", sering melanda jenis penulisan ini. Banyak juga ahli yang mengatakan bahwa penulisan biografi bukan saja menuntut kemampuan teknis yang tinggi, serta pemahaman yang mendalam tentang human nature, tetapi juga kematangan sikap sebagai penulis, yang -- sialnya lagi harus sanggup menjaga jarak, meskipun simpati pada sang tokoh. Tetapi biarkan sajalah segala tuntutan yang serba ideal yang biasanya dihafal oleh para calon sarjana ini. Pada akhirnya, penulisan biografi lebih ditentukan oleh penghargaan (yang mungkin mulanya bersifat hipotetis) terhadap sang tokoh. Tanpa ini, biografi telah gagal sebelum dimulai. Selanjutnya, berbagai pilihan telah tersedia. Apakah tokoh hanya akan dilihat sebagai pribadi yang "bersejarah" (menurut Driyarkara) ataukah sebagai seseorang yang terlibat dalam proses dialog tanpa henti dengan lingkungan sejarahnya. Apakah ia akan disorot sebagai seorang yang bertindak dalam struktur ataukah yang mengadakan refleksi terhadap struktur lingkungannya itu? Berbagai kemungkinan lain tentu terbuka. Yang jelas ialah Ajip Rosidi, sang sastrawan, yang merangkap biograf, memulai studinya dengan penghargaan (bahkan juga cinta) terhadap sang tokoh yang jadi sasaran studi -- (dalam buku terdahulu) Syafruddin Prawiranegara atau (kini) Natsir. Penghargaan ini adalah hipotesa yang akhirnya menjelma menjadi pendapat. Tak kurang pentingnya, Ajip pun telah memilih. Dalam buku ini, ia menelusuri kehidupan Natsir sebagai cendekiawan yang mengadakan refleksi terhadap struktur lingkungannya. Ajip membicarakan juga kehidupan pribadi Natsir dan tindakan-tindakan yang dijalankannya -- mendirikan sekolah swasta, ikut organisasi dan partai politik, dan sebagainya -- tetapi kesemuanya hanyalah sekadarnya saja. Perhatian utama Ajip ialah pemikiran Natsir. Secara kasarnya, setidaknya pada jilid pertama ini, Ajip cenderung memperlakukan Natsir sebagai teks. Hal ini pulalah yang pernah dilakukan oleh Bernard Dahm terhadap Sukarno, dalam bukunya yang telah terkenal itu. Mungkin ini pilihan yang tepat juga. Periode yang diliput oleh jilid pertama (sampai dengan kejatuhan Hindia Belanda) memang sesungguhnya saat pertumbuhan Natsir sebagai seorang cendekiawan yang cemerlang, bukan waktu ia tampil sebagai seorang negarawan dan politikus yang, disukai atau tidak, ikut menentukan (dengan memakai gaya Bung Karno) "jalannya sejarah" kontemporer tanah air kita. Maka, saya pun teringat juga akan rasa penyesalan yang terselip dalam tulisan George Kahin (penulis buku klasik Nationalism and Revolution in Indonesia) yang terakhir, bahwa, gara-gara terlibat dalam perdebatan dan studi "masalah Vietnam", akhirnya proyek studinya yang telah dimulai, tentang "pemikiran Natsir", terbengkalai. Karena usia dan kesehatan, ia pun meragukan kemungkinan untuk melanjutkannya. Peter Burns sempat juga menulis sebuah monografi tentang salah satu masalah yang dibahas Natsir, yaitu hubungan Islam dan Pancasila. Tetapi, jelaslah, tanpa pengenalan yang mendalam pemikiran Natsir, sebagai bagian dari pengalaman hidupnya, sukar juga untuk membahas masalah ini secara mendalam dan fair. Dari sudut ini, peranan penting yang bisa dimainkan karya Ajip Rosidi makin kelihatan. Tetapi, terlepas dari cara Ajip "memperagakan" tokohnya, saya memang sangat terkesan dengan biografi intelektual Natsir. Baiklah saya akui saja lebih dulu, bahwa di samping Kumpulan Karangan I (Hatta), Dibawah Bendera Revolusi I (Soekarno), serta Pikiran dan Perdjoeangan (Sjahrir), Capita Selecta I dari Natsir adalah buku-buku yang saya senangi dan kagumi. Lebih daripada segala-galanya, saya terpukau oleh kecemerlangan pikiran, ketajaman perasaan, serta kedalaman idealisme yang terpantul dari tulisan-tulisan keempat anak muda yang berumur dua puluhan itu. Kekaguman saya bertambah, jika saya ingat pula diri dan lingkungan saya sekarang. Tetapi, kembali lagi ke biografi Natsir. Meski tidak eksplisit diuraikan Ajip, biografi Natsir memperlihatkan suatu evolusi yang menarik. Coba saja, perhatikan tulisan yang awal-awal, ketika ia barulah seorang teenager. Kesan yang segera tampak ialah seorang anak muda terpelajar Barat tampil sebagai pembela kebesaran dan kesucian agamanya. Le- bih penting lagi, pembelaan itu dilakukan dengan discourse, wacana, yang telah dominan, yaitu Barat. Lebih penting, discourse awal ini memperlihatkan Natsir, pada tahap ia sedang membuat garis-garis yang membatasi wilayah "haq" dengan yang "bathil". Ketika komitmen ideal sedang diperkuat dengan pengalaman dalam dunia wacana. Natsir menolak menerima beasiswa untuk melanjutkan pelajaran ke Sekolah Hakim Tinggi (yang kini disebut Fakultas Hukum) dan tidak pula memilih bekerja dengan gaji yang lumayan, tetapi mendirikan sekolah swasta yang sesuai dengan cita-citanya. Dan, ia baru saja tamat AMS, yang dari sudut status formal tak lebih dari SMA. Maka, periode belajar pun muncul. Dalam kehidupan sehari-hari ini, berarti Natsir sibuk mempelajari buku-buku paedagogik -- masa guru tak tahu ilmu mendidik? Tetapi, dalam teks, inilah saatnya ia sibuk memperkenalkan berbagai aspek dan episode dari sejarah kebudayaan dan pemikiran Islam. Kalau pada periode pertama, yang tampil adalah Natsir si pembela dan pembuat batas, maka kini yang tampil adalah Natsir yang sibuk menggali kebesaran yang terdapat dalam pilihannya. Selanjutnya, coba ikuti terus rangkaian tulisan-tulisannya, yang juga dikutip dalam buku ini. Kini, Natsir adalah seorang pemimpin sebuah sekolah swasta, yang cukup populer, tetapi tetap merana secara material. Situasi yang keras makin memaksanya untuk mempelajari dan mengamati serta memahami struktur dan dinamika politik di sekitarnya. Periode ketiga telah kelihatan -- Natsir tampil sebagai pengamat dan pembahas politik yang teliti dan nuchter, kata orang dulu. Demikian baik tulisan-tulisan Natsir sehingga saya payah membayangkan sejarawan yang bisa alpa terhadap tulisan-tulisan ini, jika bermaksud menulis situasi politik di saat-saat akhir Hindia Belanda. Dari biografi intelektual Natsir, periode ini bisa dilihat sebagai masa pendidikan politik yang aktif, ketika paradigma pilihannya dipakai sebagai alat untuk memahami dan menilai kenyataan politik. Tetapi sementara itu, proses lain telah menampakkan dirinya -- Natsir, sang pengamat dan penilai politik, mulai menampil- kan diri sebagai "ideologue", sang perumus ideologi politik. Betapapun kemudian Natsir lebih menonjol sebagai politikus yang bergerak dan berbuat dalam konteks struktur sosial politik tertentu, keempat tahap yang merupakan bagian integral dari biografi intelektualnya ini akan selalu tampil. Kekuatannya sebagai pemimpin didukung oleh karisma yang dipupuk oleh pengalaman ini. Kegagalannya dalam politik adalah pantulan yang murni dari dilema seorang cendekiawan moralis dalam kancah dunia kekuasaan. Tetapi, biarlah saya tak mendahului sang biograf. Kritik teks terhadap tulisan-tulisan Natsir akan lebih memperjelas corak perdebatan ideologis yang terpenting dalam sejarah kita, yaitu Islam sebagai ideologi politik. Kesan sepintas akan kelihatan bahwa ada aspek dari perdebatan itu yang hanya merupakan fase dalam pertumbuhan kesadaran, ketika batas-batas dan sifatnya harus dirumuskan. Tetapi ada pula yang memperlihatkan perdebatan antara keyakinan- normatif dengan pemahaman struktur dan sejarah. Dan, disadari atau tidak, ini adalah perdebatan tanpa henti, bahkan juga didunia demokrasi Barat. Ajip Rosidi berhasil melakukan verstehen, sebagaimana orang sono menyebutnya -- melihat dan merasakan situasi sesuai dengan penglihatan si aktor. Natsir bukan saja "obyek" studi, tetapi sekaligus adalah pembimbing untuk memahami zaman yang dialaminya. Hanya saja, seorang biograf, sebagai sejarawan, mempunyai luxury, kemewahan, yang tidak dimiliki aktor. Ia juga bisa melihat realitas lain, yang mungkin tersembunyi dari pandangan sang aktor. Barangkali inilah, menurut selera saya, kelemahan terpenting dari buku yang baik ini. Ajip kurang memakai kemewahan yang dimilikinya. Hanyalah hagiografi -- riwayat hidup yang mendewakan tokoh -- yang tak memancing perdebatan dan kritik, sedangkan biografi yang baik secara langsung ataupun sugestif mengajak pembacanya untuk merenungkan lagi hasil peragaannya. Dan Ajip telah berhasil. Taufik Abdullah
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini