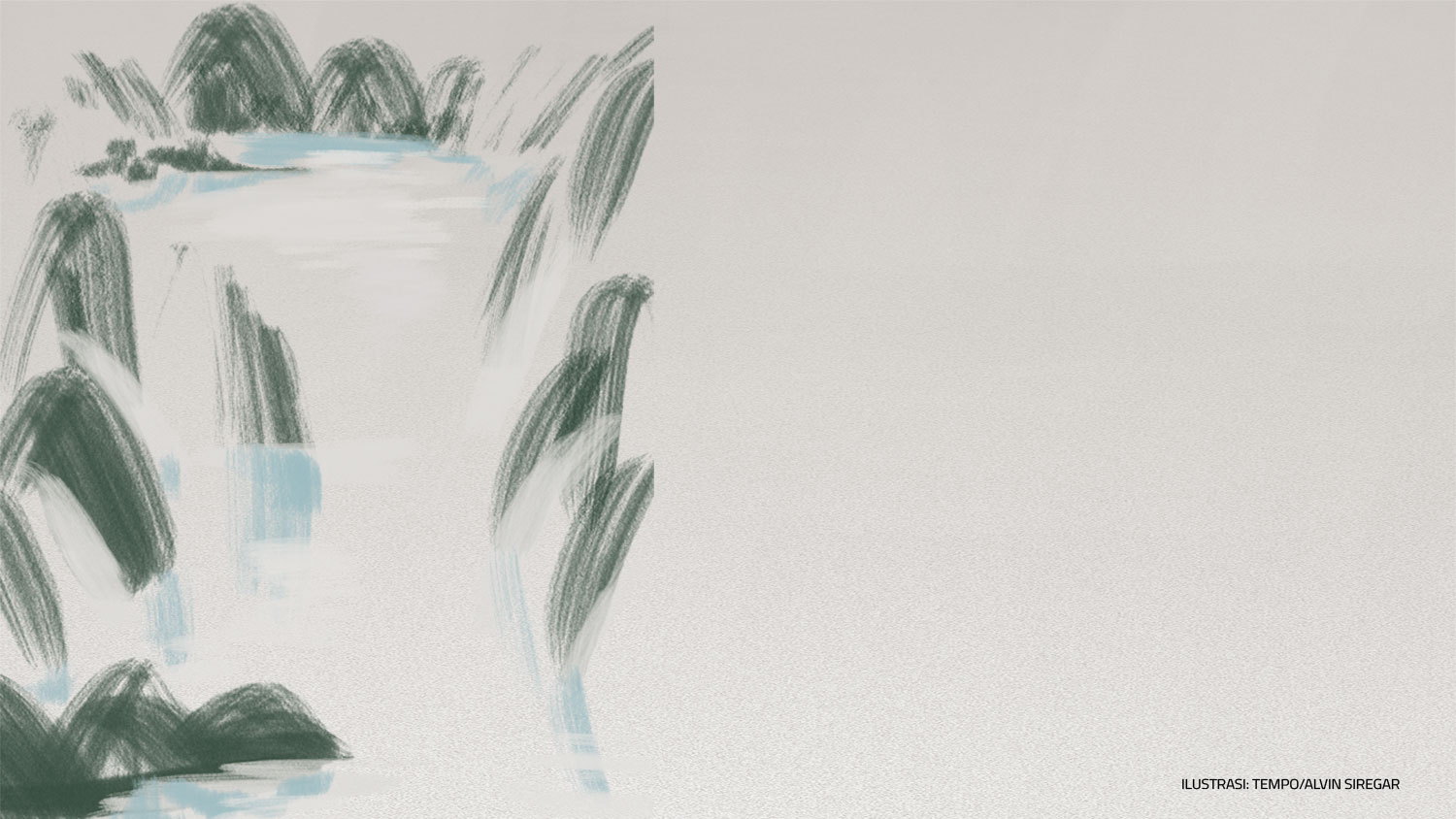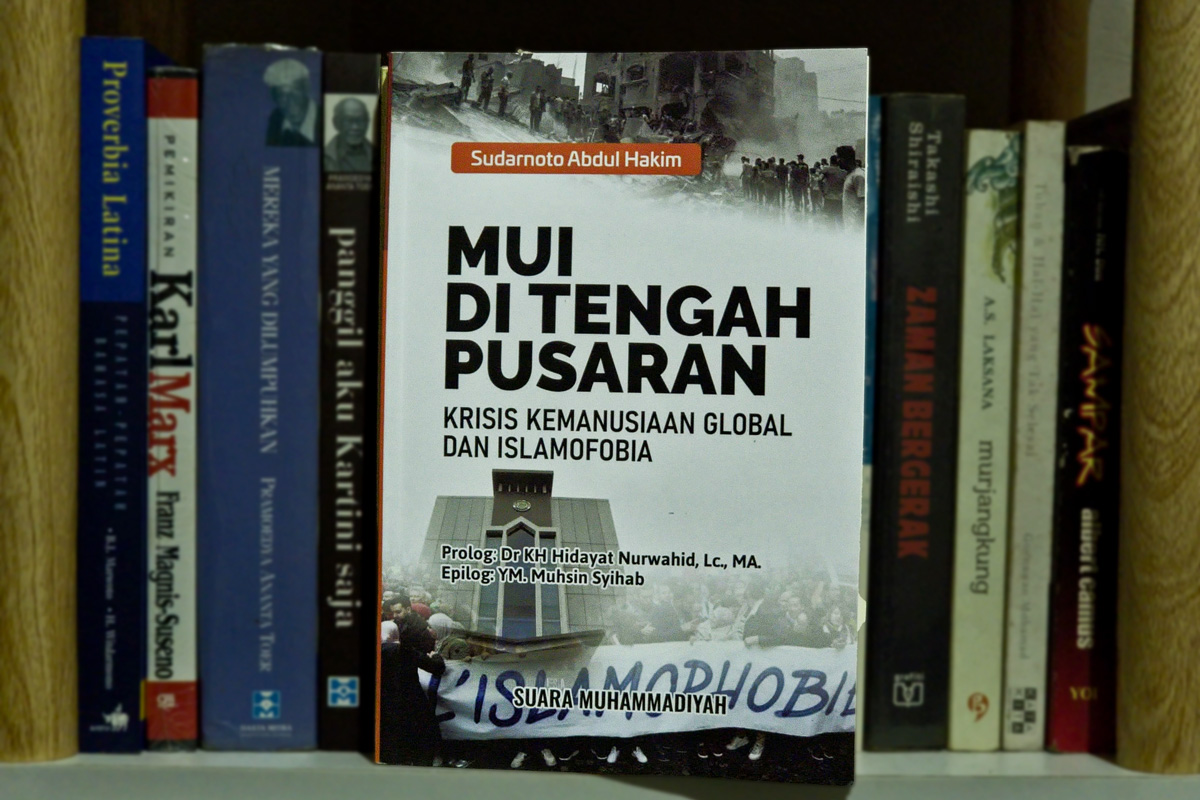Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Meraih mikrofon lalu berjalan mendekat ke panggung, penari Sutrianingsih menyapa penonton dengan centil layaknya penyanyi dangdut Pantura. Ia lalu melantunkan sebuah tembang dan menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan erotis. Penonton pun riuh. Namun dia tak membiarkan keriuhan itu terus berlangsung. Perempuan berkostum merah jambu itu berlalu begitu saja dalam kegelapan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sementara di panggung, sepasang penari laki-laki, salah satunya memakai cunduk mentul, yang semula meringkuk perlahan berdiri dan bergerak bersama menjelajah ruang dari ujung belakang ke depan atau berpelukan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menyusul gerak penari laki-laki tersebut, sepasang penari perempuan masuk dari arah berbeda. Yang satu bercunduk mentul, bergerak merendah hingga merayap-rayap. Sedangkan yang lain, perempuan berbaju merah jambu tadi, mengitari panggung sambil terus bergerak. Sepasang penari laki-laki dan perempuan berkostum hijau meninggalkan panggung lagi, penari merah jambu bergerak dalam iringan kendang yang sesekali mengentak.
Mereka kembali mengisi panggung dalam gerak koreografi lenggeran dengan iringan musik calung serta cengkok dan sesekali tembang Banyumasan oleh dua musikus. Pada penutup, tubuh penari sekaligus koreografer Otniel Tasman bergerak perlahan, gemulai dan luwes di bawah sorot lampu, berdiri mepet di bagian belakang tembok panggung Black Box. Selanjutnya, satu per satu para penari masuk kembali ke panggung, sambil membawa pisang dan memakannya perlahan, seperti pada permulaan mereka tampil.
Karya berjudul Cablaka itu dipersembahkan Otniel Tasman bersama empat penari lain dalam Salihara International Performance Festival di Black Box Salihara, Jakarta, Rabu-Kamis, 8-9 Agustus 2018. Koreografi ini didasarkan pada tarian rakyat Banyumasan, lengger, yang dikawinkan dengan gerak dangdut koplo. Dalam bahasa Banyumas, Cablaka berarti terus terang, apa adanya, dan blakblakan. "Saya ingin penonton tahu tentang masyarakat Banyumas dengan Cablaka, yang terbuka, lugas, tegas, dan kuat," ujar Otniel saat geladi resik pada Selasa lalu.
Otniel mencoba memotret fenomena yang berkembang di masyarakat ini. Lengger dalam sejarahnya adalah kesenian di tengah masyarakat agraris sebagai ritual ucapan syukur. Kesenian ini kemudian berkembang sebagai hiburan kaum menengah ke bawah untuk kemeriahan dan kebahagiaan. Sedangkan dangdut koplo menjadi simbol pemberontakan pemusik pinggiran terhadap kaum elite.
Otniel memadukan dasar gerak lengger dengan gerak-gerak kontemporer lain selama 60 menit pertunjukan. Namun ia tetap mempertahankan struktur lenggeran, musik calung, cengkok vokal Banyumasan, sambil menyisipkan gerak dan irama dangdut. Ada keterusterangan, keterbukaan, keberanian, serta kegembiraan tapi juga kepiluan dan sakit yang ikut ditampilkan dalam koreografi seniman ini. Hal itu terlihat dari gerak empat penari yang mendominasi panggung, yang kadang berpasangan, berkelompok, atau bergerak sendiri.
Otniel tampil pada permulaan bersama empat penari kemudian menghilang, lalu berjalan lagi masuk sambil mengenakan cunduk mentul lalu menyematkan cunduk mentul itu kepada salah satu penari laki-laki. Gerakan yang menyiratkan penderitaan dan kepedihan tampak saat penari merayap-rayap atau dalam iringan musik-gesekan rebab yang liris atau kata-kata yang menghidu rindu pada kekasih.
Namun pada saat lain begitu kental kegembiraan dengan perayaan dari cunduk mentul yang menghias kepala mereka atau iringan dangdut, termasuk ketika para penari menikmati pisang, yang menjadi simbol kenikmatan. Cunduk mentul, selain simbol perayaan, juga membuka tafsir lain bagi penonton sebagai kehidupan lintas gender. Bunga-bunga hiasan ini pada awalnya hanya dipakai di sanggul pengantin perempuan, kini bisa dipakai laki-laki.
Elemen musik yang diciptakan Gondrong Gunarto tak hanya menyuguhkan alat tradisional seperti calung dan kendang yang mengentak, tapi juga rebab yang liris, dipadu dentingan organ dan musik. Semua itu memperkuat efek dramatik koreografi ini.
Otniel Tasman lahir di Banyumas, Jawa Tengah, pada 1989. Ia mulai belajar menari sejak umur delapan tahun, dan mempelajari seni tersebut di SMKI Sendang Mas, Banyumas, lalu di Institut Seni Indonesia, Surakarta. Ia mengembangkan banyak gagasan kreatifnya dalam beberapa karya, seperti I Will Survive (2016), Sintren (2016), Stand Go Go (2017), dan Nosheheorit (2017). Karya terakhir ini bahkan ditampilkan perdana dunia di Festival Europalia 2017 di Belgia.
Otniel pun ikut terlibat dalam beberapa karya lintas disiplin bersama koreografer dan sinematografer, seperti Eko Supriyanto, Fitri Setyaningsih, Maxine Heppner, Daniel Kok, dan Garin Nugroho. Cablaka, yang diciptakan pada 2018, adalah karya produksi Komunitas Salihara. Ia mengeksplorasi lengger dalam banyak karyanya. DIAN YULIASTUTI
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo