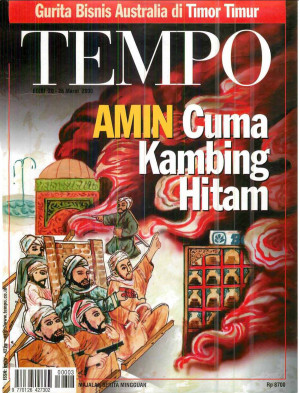Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sketsa yang dirampungkannya pada Oktober 1997 itu seolah cermin yang memantulkan sejarah pergumulan estetis sang maestro atas berbagai bentuk ekspresi: realis, abstrak, dekoratif. Tengok coretan bertajuk Nonton Striptease di Jepang, yang menampilkan lima orang cewek telanjang dengan berbagai tingkah lakunya, yang diungkap secara realis-ekspresif. Ini menunjukkan bahwa Widajat memang pada permulaannya adalah pelukis realis yang kuat. Itu juga terpantul pada gambar-gambar bertema sekitar kerusuhan PDI.
Pameran ini tidak menampilkan lukisan cat minyak yang digarap Widajat pada periode realis tahun 1950-an. Lukisan cat minyak tertua yang dipamerkan adalah Penculikan Dewi Sinta (1963). Caranya memiuhkan figur Sinta menandakan itulah era ketika gairah Widayat bangkit untuk berkarya dengan bentuk deformasi kubistis, yang kemudian berlanjut pada penemuan dekora-magis yang menjadi ciri khas dia.
Itulah dunia fantasi firdausi hutan dengan segala satwa liarnya: piranha, gajah, blekok, burung-burung, yang menjadi suatu khazanah yang terinternalisasi. Maklum, saat Widajat muda, pada 1930-an, ia menjadi mantri ukur di belantara tropis Sumatra. Dan magisme yang ditawarkannya bukan seperti fantasmagoria (imajinasi adi-duniawi) surealisme Amerika Latin yang penuh teror mimpi-mimpi bawah sadar, melainkan suatu tamasya lirisme flora fauna purbawi seperti ini. Ribuan (bintik-bintik) burung terbang membentuk formasi awan berarak atau bertengger bersama.
Melihat bagaimana binatang menjadi inti kesubliman Widajat itu, kita dipaksa merenungkan bahwa sejak dulu hewan tertentu dalam tradisi spiritualis menjadi lambang teofani. Berabad-abad di Eropa, seperti kata Jung, misalnya, ikan menjadi lambang profetik juru selamat. Katakomba-katakomba—gua bawah tanah—penuh coretan bertema ikan. Kecenderungan Widajat menggambar ikan pedalaman seperti coelacanth berdasarkan kesadaran rohani itu. Terlebih lagi, lelaki yang menurut sejarawan seni asal Belanda Helena Spanjaard menghayati mistisisme Jawa ini amat suka mengangkat tema perahu Nuh. Seolah ia berpendapat bahwa satwa-satwa liar di mana pun adalah sisa-sisa makhluk suci karena terselamatkan dari Sodom Gomorah.
Yang menarik adalah ketika Widajat—sejak 1990-an sampai kini—banyak menampilkan figur dengan semangat main-main kanak-kanak dengan menampilkan makhluk-makhluk aneh, lucu, bersayap. Ada yang merasa kehilangan dengan ekspresi barunya dan memandang kecenderungan barunya itu sebagai suatu hal yang "bukan Widajat". Dalam pameran ini, misalnya, 70 sketsnya yang mengekspresikan dunia kanak-kanak bisa terlalu enteng dibandingkan dengan skets-skets realisnya.
Dalam konteks ini, Widajat agaknya berpandangan naivisme, bisa juga nativisme. Sesungguhnya yang ia buru adalah semacam prinsip kebersahajaan orang-orang zaman dulu (seperti lukisan gua-gua) yang menggambarkan alam sekitarnya. Gagasan ini ini tampak pada karya instalasinya berjudul Bambu-Bambu (1999), yang ditampilkan sebagai totem.
Ada pendapat bahwa menempatkan totemisme sebagai fenomena keagamaan adalah suatu anakronisme. Sebab, dalam masyarakat tradisional, totemisme lebih sebagai suatu cara sistem klasifikasi metaforis daripada ekspresi sakralitas. Masyarakat modern mengungkapkan hal itu dengan bahasa lain: mereka yang menganggap totem sebagai sesuatu yang sakral cenderung terjebak dengan cara pandang etnosentrisme Barat yang ingin meneguhkan adanya kultur primitivisme yang berbeda dari dunia modern.
Nukilan pikiran Levi Strauss, antropolog Prancis, itu tentunya tak disetujui Widajat. Bagi pelukis sepuh ini, kepurbaan adalah pohon hayat yang menjadi energi hidup tak habis-habisnya. Sedemikian kuyupnya ia menyelam di alam primitivisme, bahkan rencananya marmer-marmer di salah satu pendapanya di museumnya di Mungkid, Magelang, akan digrafir dengan sketsa-sketsa demikian. Di usianya yang lebih dari 80 tahun, semangat purba itu telah terus-menerus membangkitkan semangatnya untuk mencari.
Seno Joko Suyono
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo