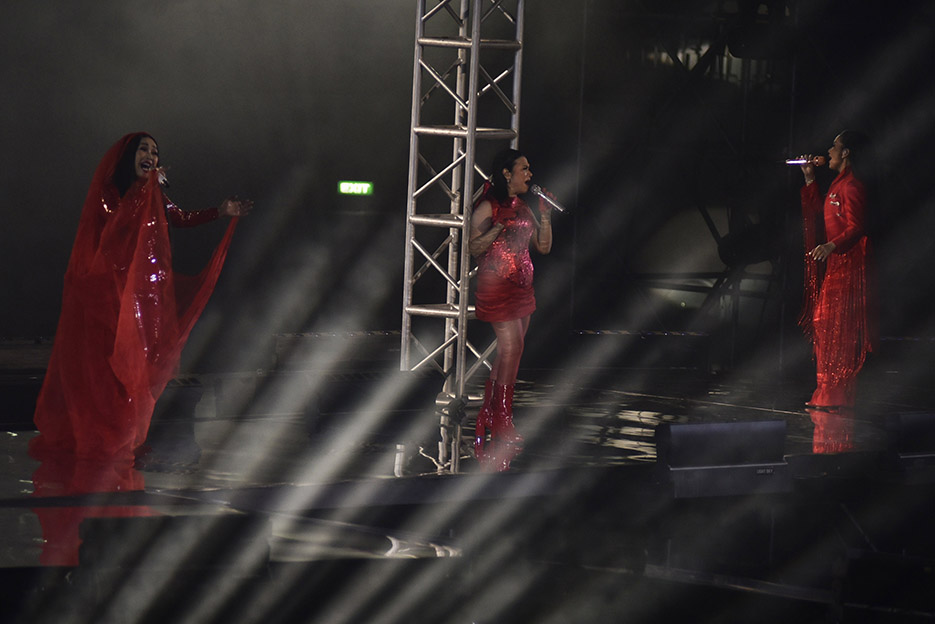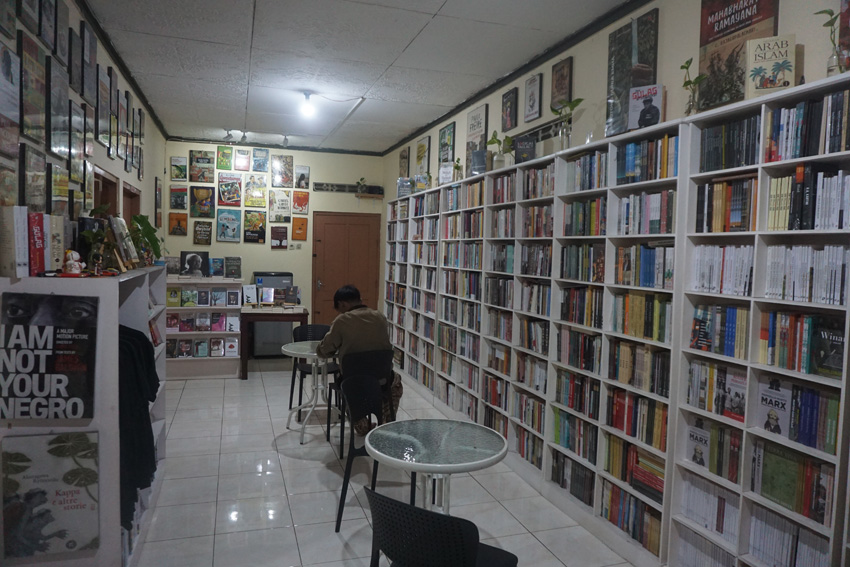Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru
Editor: Liza Hadiz
Penerbit: Pustaka LP3ES, Agustus 2004
Jumlah halaman: xxxvi + 464 halaman
Jika kita mau jujur sedikit saja dalam melihat wajah buruk "pembangunan" Orde Baru, kita akan melihat wajah "perempuan" di sana. Ada pertumbuhan ekonomi, naiknya investasi luar dan dalam negeri, munculnya gedung-gedung megah, dan sederet indikator prestasi ekonomi lainnya yang ternyata berbanding terbalik dengan kemiskinan, rendahnya lapangan kerja dan pendidikan, juga tidak banyak berperannya perempuan dalam proses perubahan yang terjadi. Dan posisi marginal dan subordinasi juga terjadi di bidang-bidang seperti media dan sastra serta pengaturan negara dalam seksualitas. Itu kira-kira isi kumpulan tulisan pilihan mengenai perempuan di era Orde Baru yang pernah dimuat dalam jurnal Prisma.
Meskipun demikian, wajah suram "perempuan" ini bukannya tanpa titik-titik kecerahan sama sekali. Tulisan Mely G. Tan, misalnya, melihat ada kemajuan dalam soal persamaan laki-laki dan perempuan—meski masih jauh dari soal integrasi sepenuhnya perempuan dalam usaha pembangunan. Statistik memperlihatkan bahwa jumlah perempuan terdidik naik tiga kali lipat dibandingkan dengan laki-laki, yang hanya dua kali lipat. Demikian juga partisipasi perempuan dalam lapangan kerja, yang meningkat secara signifikan di perkotaan. Kenyataan di pedesaan berbeda. Astrid Susanto menunjukkan keterlibatan perempuan dalam dunia kerja lebih bersifat imperatif, ikut membantu ekonomi keluarga, dan bahkan dalam banyak kasus menjadi tulang punggung ekonomi dan pendidikan anak dalam keluarga. Sementara itu, seperti bisa diduga, representasi perempuan dalam dunia sastra, novel, majalah, dan film tersubordinasi dan termarginalkan.
Yang sangat provokatif adalah tulisan Julia Suryakusuma yang bicara bagaimana negara Orde Baru mengatur dan bahkan mengontrol seksualitas warganya yang menjadi aparat birokrasi (pegawai negeri) melalui cara yang berlapis. Dimulai dari dasar falsafah negara, berbagai tatanan organisasi dan peraturan yang menyertainya, dan khususnya organisasi Dharma Wanita sebagai organisasi istri pegawai negeri. Sementara itu, sejarawan Onghokham dan wartawan Linda Cristanty menulis soal perempuan dalam langgam sejarah yang penuh paradoks. Menurut Linda, di satu sisi perempuan dilihat sebagai bagian dari konsep pemilikan seperti konsep Nyai, tapi di sisi yang lain, melalui institusi budaya seperti ini, perempuan bisa memperlihatkan kepiawaiannya dalam mengelola berbagai masalah, mulai dari keluarga hingga perusahaan suami. Sebaliknya, Onghokham melihat bagaimana seksualitas sangat berkaitan secara konkret dengan aspek kekuasaan yang menjadi landasan sebuah dinasti atau kerajaan.
Tapi harus disadari bahwa sebagian besar tulisan ini hadir di tahun 1970-an dan 1980-an, ketika wacana atau pemikiran yang muncul mengenai perempuan masih dilandasi asumsi bahwa perempuan tertinggal dalam proses-proses pembangunan. Karenanya, solusinya pun masih parsial dengan mengintegrasikan, yakni men-ciptakan kegiatan-kegiatan yang khas perempuan dalam pembangunan. Padahal, pembangun-an itu sendiri yang sebetulnya harus menjadi bagian dari atau ramah terhadap perempuan dengan melibatkan perempuan dalam setiap pengambilan keputusan dan adanya restrukturisasi di setiap institusi. Ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Konferensi Perempuan Sedunia Keempat di Beijing (1995).
Tulisan yang belakangan, seperti yang ditulis Ruth Indiah Rahayu, misalnya, sudah bicara melangkah dengan menawari perempuan menjadi bagian dari gerakan sosial, dan ini terlihat dalam gerakan-gerakan LSM perempuan, yang tidak hanya kritis terhadap kebijakan pembangunan Orde Baru, tapi juga menawarkan solusi alternatif yang lebih ramah perempuan. Yang patut dipuji memang tulisan editor, Liza Hadiz, yang secara baik memberikan wajah makro dari pembangunan dan perjalanan gerakan perempuan di tingkat internasional maupun domestik, baik dalam kemajuan isu dan rekomendasi dari Konferensi Perempuan Sedunia maupun perdebatan teoretis feminis yang bicara mengenai perempuan dengan segala dinamikanya. Bukunya yang sangat komprehensif ini, sayangnya, tidak dilengkapi dengan epilog yang menggambarkan situasi dan kondisi perempuan dewasa ini, dalam era reformasi dan krisis ekonomi, yang tentu akan sangat menarik dengan membandingkannya dengan masa Orde Baru.
Nur Iman Subono, staf pengajar Jurusan Politik FISIP UI
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo