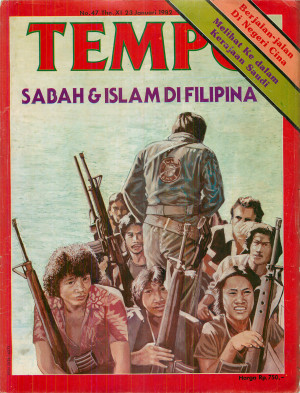Di tengah kemajuan industri dan ekonominya, orang Jepang takut
menanam modal dalam perfilman. Grafik mutu fiilm Jepang menurun.
Pekan film Kine Klub kali ini seperti menggambarkan penurunan
itu.
PEKAN Film Jepang di Taman Ismail Marzuki kali ini seperti hanya
hendak membuktikan tahun-tahun 1950-an adalah masa jaya dunia
perfilman Jepang. Dulu itu seakan susah dicari film Jepang
terbaik -- karena banyaknya film Jepang bermutu.
Dari enam film yang diputar 13 - 17 Januari kemarin, memang
empat film dibuat tahun 70-an, sebuah tahun 1980-dan hanya satu
karya 1952. Yang terakhir itu berjudul Ikiru (nasib), buah
tangan salah seorang sutradara besar Akira Kurosawa.
Ikiru tentu saja masih hitam-putih-dan dengan kamera yang
statis. Toh, dibanding lima film yang lain, justru gambar-gambar
film ini lebih banyak bercerita--dan menyentuh.
Inilah kisah seorang pegawai kotapraja, yang menjelang hari
pensiunnya-untuk pertama kali selama 30 tahun bekerja -- jatuh
sakit. Ternyata kanker.
Dan karena itu hidupnya tinggal bersisa 6 bulan. Tiba-tiba Kanji
Watanabe, pegawai itu, menyadari bahwa usianya selama ini telah
dijalaninya dengan lurus, datar dan tanpa masalah. Ia memang
bagaikan mummy--julukan yang diberikan kepadanya oleh seorang
gadis pegawainya. Ia pun berontak. Sebentar terlibat
mabukmabukan, lantas berupaya menghabiskan sisa hidup yang
singkat itu untuk sesuatu yang bermakna.
Setumpuk kertas di kantornya lantas diperiksany. Ia menemukan
satu permohonan --dari beberapa warga kota, yang dulu terlupakan
begitu saja. Isinya: agar sebidang tanah kosong di tempat
tinggal mereka dijadikan kebun untuk anak-anak. Sederhana,
bukan?
Di masa setelah Perang Dunia 11 itu, Jepang memang sedang
membangun negeri dengan gempita. Tapi warga kota itu agaknya
melihat, pembangunan hanya memperhitungkan sekitar ekonomi.
Tanah-tanah kosong, misalnya, tak dibiarkan terlalu lama
menganggur--dalam waktu singkat disikat dan berubah menjadi
jalan, perumahan, pabrik, pertokoan. Warga kota tiba-tiba
menjadi ngeri: anak-anak kehilangan tempat bermain .
Kanji Watanabe lantas mengambil permohonan itu -- dan
memperjuangkannya Dengan gigih, setindak demi setindak,
ditembusnya birokrasi pemerintah yang masa itu begitu memuakan.
Bahkan ada adegan: ketika Watanabe sedang menghadap walikota,
begitu saja Pak Wali mengalihkan pembicaraan dengan tamu
lain--rentang pertemuannya dengan seorang mahasiswi yang malam
harinya merangkap menjadi geisha.
Dengan suaranya yang serak, dan tubuhnya yang membungkuk,
pegawai tua ini mencoba meyakinkan berbagai pihak pentingnya
permohonan sejumlah warga kotanya. Ia pun mengalami diancam
sejumlah orang yang menginginkan tanahitu dibangun menjadi
pertokoan. Akhirnya susah-payah tak sia-sia. Dan persis di saat
itu pulalah agaknya hari terakhir tiba. Ia meninggal--di
lapangan yang telah diputuskan akan menjadi kebun anak-anak.
Makna Hidup
Tak hanya segi teknis, cerita atau skenario--atau pemain dan
sutradara-yang membuat film ini berkesan. Ikiru berkait dengan
masalah sosial Jepang tahun 50-an: secara halus tapi tajam:
pembangunan, orang-orang kecil yang terlindas dan birokrasi
pemerintah yang sungguh membuat putus asa. Juga merupakan potret
seorang manusia dalam mencari "makna hidup".
Ada jarak yang jauh antara Ikiru dan lima film yang lain. Bukan
hanya jarak waktu yang hanya 20-an tahun --ataupun jarak antara
hitam-putih dan warna dengan segala tipuan kameranya. Tapi jarak
suasana dan sermangat. Memasuki medio 60-an, perfilman Jepang
digasak televisi. Industri film pun sepi. Ini tragis, bila
diingat sejarah perfilman dan perbioskopan Jepang yang sudah
muncul sejak dini.
Alat-alat perfilman sendiri sudah dikenal orang Jepang menjelang
berakhirnya abad XIX. Bioskop petama dibangun di negeri itu
1903--ketika orang Eropa memikirkannya saja pun belum. Tahun
1904 lahirlah film cerita Jepang pertama. Dan tahun S0-an dunia
pun terkejut: Rashomon, karya Kurosawa, dibuat 1950, merebut
hadiah pertama di Festival Internasional Venice 1951.
Tapi betapapun film Jepang tahun 70-an "mundur", harus diakui
sisa-sisa kejayaan yang tetap tercermin. Entah ini sudah takdir,
boleh dikata tangan orang Jepang di bidang seni selalu menyentuh
segalanya dengan apik. Akibatnya segi artistik (setting, tata
rias & busana dalam film Jepang relatif tergarap dengan baik.
Bahkan dalam film-film yang dimaksud melulu hanya sebagai
hiburan, taruhlah Shogun's Ninja yang belum lama ini diputar di
beberapa bioskop di Jakarta, unsur keartistikan tetap harus
dipuji.
Adapun yang membedakan film-film pilihan Kine Klub DKI dengan
film Jepang hiburan melulu ialah pemilihan fokus cerita.
Bandingkan misalnya Tsugaru Jongara Bushi karya Koichi Saito,
yang diputar di hari keempat, dengan Sandakan yang belum lama
ini diputar di Jakarta.
Yang pertama, mengambil fokus perkembangan pribadi seorang
pemuda. Ia semula anggota gang di Tokyo. Karena membunuh, lantas
melarikan diri dengan kekasihnya, seorang hostes, ke dusun asal
si cewek. Di dusun itulah kenyataan-kenyataan pahit mengubah
pribadi si pemuda: dari seorang yang cuma mau enak mencari uang
dengan menodong menjadi pemuda yang mau bekerja keras (menangkap
ikan di laut) .lan merencanakan mengawini seorang gadis buta
dari dusun itu -- karena ccweknya hendak kembali ke Tokyo.
Lantas Sandakan. Meski film ini merupakan pengungkapan masalah
sosial, lagi pula berdasar kisah nyata pelacuran, nyaris dari
awal sampai akhir yang digambarkan hanya "penderitaan" para
pelacur itu. Sebab awal seorang gadis jatuh ke dunia pelacuran
pun sungguh umum kemiskinan. Masalah sosial yang lebih jauh
(misalnya pandangan masyarakat Jepang sendiri setelah pemerintah
menghapuskan pelacuran resmi) atau masalah spiritual (konflik
batin si pelacur) hanya disinggung sekejap.
Bagaimana pengambilan fokus cerita bisa menjadi ukuran mutu bisa
diberi contoh dengan Fuyu No Hana (sekuntum bunga di musim
dingin) karya Yasuo Furuhata yang diputar di hari terakhir.
Latar belakang cerita adalah dunia Yakuza, mafia Jepang. Tapi
fokus cerita tertuju hanya pada diri seorang anggotanya -- yang
merasa dibayangi akibat pembunuhannya: anak-anak yang menjadi
yatim. "Kamu bisa melawan hukum. Tapi tak mungkin melawan
(hukum) Tuhan," kata si tokoh itu. Bila saja film ini memang
untuk mengeruk uang, fokus blasanya akan bergeser dar-der-dor
para Yakuza membela gannya masing-masing.
Usaha yang sungguh-sungguh dari beberapa sutradara itulah yang
membuat Tadao Sato, kritikus film Jepang yang tiga tahun lalu
pernah ke Jakarta optimistis. Katanya, waktu itu: 10-15 tahun
lagi dunia perfilman Jepang akan kembali menyajikan film
bermutu. Entah siapa yang akan kembali menyingkap fajar
perfilman di negeri matahari terbit itu. Kurosawa kini telah 72
tahun.
Bambang Bujono
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini