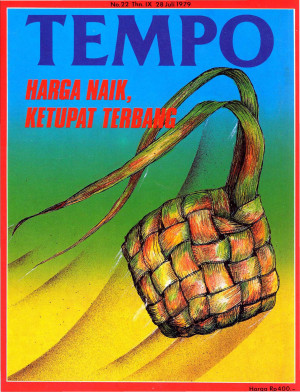LEBIH dari hanya rangkaian atau penggabungan gerak, sebuah karya
tari menuntut paduan sinambung -- sehingga kesatuan utuh yang
dihasilkan mampu menggugah perasaan penikmatnya. Akan lebih baik
lagi jika mampu mengajak penonton ke sebuah renungan mendalam.
Untuk mewujudkan itu semua memang banyak masalah yang harus
diatasi, dan tentu saja tidak setiap karya berhasil memenuhinya.
Misalnya dramatari topeng Somantri Gugur produksi ASTI Bandung,
garapan bersama Endo Suanda, Iyus Rusliana dan Toto Amsar di
Teater Arena TIM, 18 dan 19 Juli 1979.
Berbeda dengan Topeng Badawang yang sempat menimbulkan
perdebatan menarik dalam Festival Penata Tari Muda tahun lalu,
Somantri Gugur belum sempat mengendap. Pemakaian topeng yang
seharusnya membantu ekspresi, ternyata masih merepotkan bagi
sebagian besar penari. Para ponggawa, danawa, Togog dan
Sokasrana misalnya, belum mampu menghidupkan topeng yang
dipakai. Adakalanya bahkan menyulitkan bloking dan kerampakan
gerak. Pada adegan Rahwana kiprah, suasana yang seharusnya ramai
terasa kosong. Para pemeran raksasa tak mampu memberikan respon
terhadap kiprah Rahwana. Padahal, seorang Djana yang menarikan
Klana (Topeng Cirebon) dengan iringan gamelan dan senggak
gempita dari nayaga bisa menjadikan pentas terasa sesak, walau
ia sendirian menari.
Juga perkembangan alur dramatik dalam pementasan ini kurang
dipersiapkan. Beberapa adegan penting tak mencapai klimaks yang
diharap. Benang halus yang seharusnya merangkaikan satu adegan
dengan berikutnya tak sempat mewujud. Akibatnya seakan kita
selalu kembali dari awal pada setiap adegan baru.
Hal itu terasa sekali pada adegan matinya Sokasrana, yang tak
meninggalkan bekas karena tak didukung adegan-adegan sebelumnya.
Sedang iringan adegan perang terakhir -- antara Rahwana dan
Somantri -- yang merupakan klimaks, tak mampu menciptakan
suasana tegang karena musik mementingkan ornamentasi melodi
sehingga terdengar manis berbunga-bunga. Bodor, yang dalam
Topeng Cirebon terasa sekali menghidupkan suasana, dalam
tontonan ini tak begitu berperan.
Yang juga menggelitik hati adalah masalah busana tari yang
hampir seluruhnya berpola Jawa Surakarta. Di masa lalu memang
pernah ada pengaruh Istana Mangkunagaran terhadap Kabupaten
Priangan, tetapi tak diduga sedemikian kuatnya. Agaknya belum
juga terbersit niat seniman tari Bandung mencari kembali akar
tata busana yang lebih khas Pasundan.
Dramatari Topeng Somantri Gugur mengambil pola wayang wong
Pasundan, namun garapannya lebih mendekati langen-beksa (tari,
dialog dan vokal terpadu dalam bandingan seimbang) dengan materi
dan idiom yang ada pada khaanah kesenian Sunda dewasa ini.
Ceritanya tentang dua orang bersaudara putera Resi Suwandagni
Somantri dan Sokasrana. Yang satu cakap, satunya jelek bukan
buatan, tetapi keduanya sama-sama memiliki kelebihan dan saling
mengasihi. Dalam usahanya hendak mengabdi kepada Prabu
Harjunososro, Somantri menemui kesulitan ketika harus
memindahkan Taman Sriwedari -- dan sang adikpun datang
membantunya. Tetapi karena berwajah raksasa, Sokasrana diminta
agar pulang saja oleh Somantri. Dalam perselisihan inilah
Sokasrana mati di tangan kakaknya. Sesal kemudian tak berguna.
Akhirnya dalam sebuah pertempuran melawan Rahwana, Somantri yang
kemudian menjadi patih, tewas sebagai pahlawan. Kakak beradik
itu pun bertemu kembali, di alam baka.
Lutung Kasarung
Wayang orang Pasundan, menurut dugaan, berasal dari Cirebon.
Seluruh pemainnya berkedok atau memakai topeng mirip Topeng
Madura. Dialog dilakukan sang dalang dan bukan penari-penarinya,
kecuali -- sebagaimana di Bali -- peran-peran dengan kedok
setengah muka. Tontonan ini, yang berkembang di kalangan rakyat,
telah lama lenyap dari peredaran -- dan sebagai gantinya pada
akhir abad ke-19 muncul wayang priya, maksudnya wayang priyantun
(=bangsawan) karena didukung para menak atau bangsawan.
Perlahan-lahan topeng mulai ditanggalkan, dialog dilakukan para
penari sendiri dengan mengadaptasi wayang golek Pasundan. Wayang
Priya masih sering dipertunjukkan sekitar tahun 1940-an.
Usaha menghidupkan kembali wayang Pasundan yang sudah lenyap ini
tentu patut dihargai. Apalagi jika diingat, drama tari utuh
semacam yang dipertunjukkan ini di Bandung pementasannya dapat
dihitung dengan jari. Salah satunya, yang masih membekas,
adalah garapan Sendratari Ramayana yang disusun dalam rangka
Festival Ramayana Internasional 1971. Tahun 1974, Enoch
Atmadibrata -- yang pernah menggarap sendratari Lutung Kasarung
-- pernah pula menggarap sendratari dengan lakon Ramayana.
Tetapi setelah itu baru tahun lalu kita lihat Topeng Badaqlang
(Klana Tunjungseta) karya Endo Suanda, yang disusul Somantri
Gugur kali ini keduanya produksi ASTI Bandung.
Barangkali saya mengharap terlampau banyak setelah melihat
Topeng Badawang Endo yang berhasil.
Sal Murgiyanto
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini