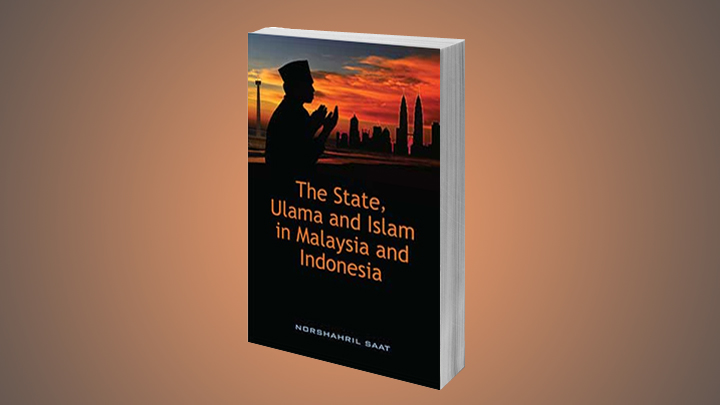Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sosok ulama menjadi sumber kehebohan di Tanah Air sejak penetapan calon presiden dan wakilnya pada Agustus lalu. Demi membentengi diri dari serangan kalangan Islam konservatif, sang inkumben Joko Widodo menggandeng KH Ma’ruf Amin, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Begitu pula Ijtima Ulama Kedua pada September lalu mengukuhkan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Malah elite partai Islam dari kubu penantang menggelari Sandiaga ulama, yang lantas memantik kegaduhan.
Buku yang diangkat dari disertasi Norshahril Saat di Australian National University ini menelisik lebih jauh kiprah ulama ”resmi”, yakni ulama yang menambatkan diri pada lembaga bentukan pemerintah di dua negeri serumpun, Indonesia dan Malaysia. Norshahril menelaah empat lembaga tempat para ulama resmi itu bernaung: Majelis Ulama Indonesia (MUI); Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (JKF-MFI); Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim); dan Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).
Kiprah ulama resmi itu diposisikan dalam relasinya dengan negara semenjak rezim Soeharto (1968-1998) dan Mahathir Mohamad (1981-2003). Menggunakan konsep capture (menguasai), yang dikenal dalam khazanah studi ekonomi-politik, Norshahril mengkaji seberapa jauh ulama resmi di kedua negara mengkapitalisasi pengkooptasian terhadap mereka demi menguasai negara dengan mempengaruhi hukum, kebijakan, pengangkatan, dan distribusi sumber daya.
Bagi Norshahril, relasi antara ulama resmi dan negara di kedua negara tidaklah sederhana. Umpamanya, meski semula terkooptasi, ulama resmi di Malaysia mampu membangun independensi dan agensinya serta menguasai beberapa bagian dari negara. Ini berbeda dengan ulama resmi di Indonesia, yang kurang berhasil menguasai negara.
Ada tiga faktor yang menentukan perbedaan ulama resmi di Indonesia dan Malaysia dalam menguasai negara: peran kelembagaan yang jelas, ideologi yang koheren, dan kohesivitas kelembagaan. Di Malaysia, ulama resmi sejak awal didayagunakan sebagai agen islamisasi sekaligus merespons gelombang gerakan Islam pada 1970-an. Inilah yang memberi kerangka institusional yang jelas, yakni meredam ancaman politis dari partai Islam seperti Parti Islam Se-Malaysia. Sebaliknya, MUI tak memiliki peran kelembagaan yang jelas mengingat ancaman politis partai Islam tidaklah sekuat di Malaysia.
Ulama resmi Malaysia secara institusional kuat karena kiprahnya dilambari kerangka ideologi yang mengusung kepentingan rezim ataupun kesultanan, yakni Rukun Negara dan Ketuanan Malayu. Sementara itu, ideologi Pancasila yang netral terhadap semua agama membatasi agenda ulama resmi dalam meluaskan islamisasi di Indonesia. Dengan kerangka kelembagaan yang kohesif, ulama resmi di Malaysia mampu menghadapi ancaman terhadap kepentingan dan otoritasnya. Sebaliknya, perselisihan ideologis dan persaingan internal yang mewarnai MUI telah melemahkan otoritasnya.
Lewat kewenangannya mengeluarkan fatwa, MUI menangani pelbagai perkara, dari sertifikasi halal hingga penetapan standar moral bagi dunia hiburan. Rupanya, ini setali tiga uang dengan yang diurus JKF-MFI. Akibatnya, bagi Norshahril, MUI meluaskan otoritasnya dalam ekonomi syariah, menangguk pemasukan lewat sertifikasi halal dan mendominasi wacana keislaman. Begitu pula ulama resmi di Malaysia mendominasi wacana keislaman, mempertahankan kekuasaannya dalam mempengaruhi kebijakan dan penunjukan pejabat, serta menggali beragam sumber pendapatan.
Pertanyaannya: apakah ulama resmi tetap terkooptasi setelah rezim politik berubah? Menurut Norshahril, lewat menteri agama, pemerintah Indonesia agaknya mengerem gairah islamisasi MUI dengan membatasi perannya sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa. Berbeda dengan ulama resmi di Malaysia, peran MUI yang lebih luas sulit dilakukan mengingat tak ada pijakan hukum yang jelas. Meski demikian, di Malaysia, keberadaan para mufti, yang kerap memberikan komentar terhadap perkara yang berkaitan dengan negara, kian sulit dikontrol pemerintah.
Kendati menyodorkan data yang rinci dan analisis kritis terhadap kiprah ulama di Indonesia-Malaysia, agaknya Norshahril mengabaikan koneksi antarulama di kedua negara karena tenggelam dalam ikhtiar melakukan perbandingan. Sebagai bangsa serumpun, tentu ada silang pengaruh antara ulama di Indonesia dan Malaysia. Apalagi selama ini Islam dan identitas kemelayuan menjadi perekat penting relasi kedua negara. Kemiripan sejumlah fatwa mengisyaratkan adanya silang pengaruh itu.
Demikianlah, ulama resmi senantiasa berada dalam medan kuasa. Agaknya, di Indonesia, mereka bakal meluaskan otoritasnya di tengah mulai menguatnya konservatisme Islam. Barangkali inilah respons ulama resmi terhadap kian maraknya organisasi Islam ataupun ”ulama tak resmi”, yang belakangan lebih nyaring menyuarakan identitas dan politik keislaman.
THE STATE, ULAMA AND ISLAM IN MALAYSIA AND INDONESIA
Penulis : Norshahril Saat
Penerbit : ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2018
Tebal : 254 halaman
BUDI IRAWANTO, PENELITI TAMU PADA ISEAS-YUSOF ISHAK INSTITUTE, SINGAPURA
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo