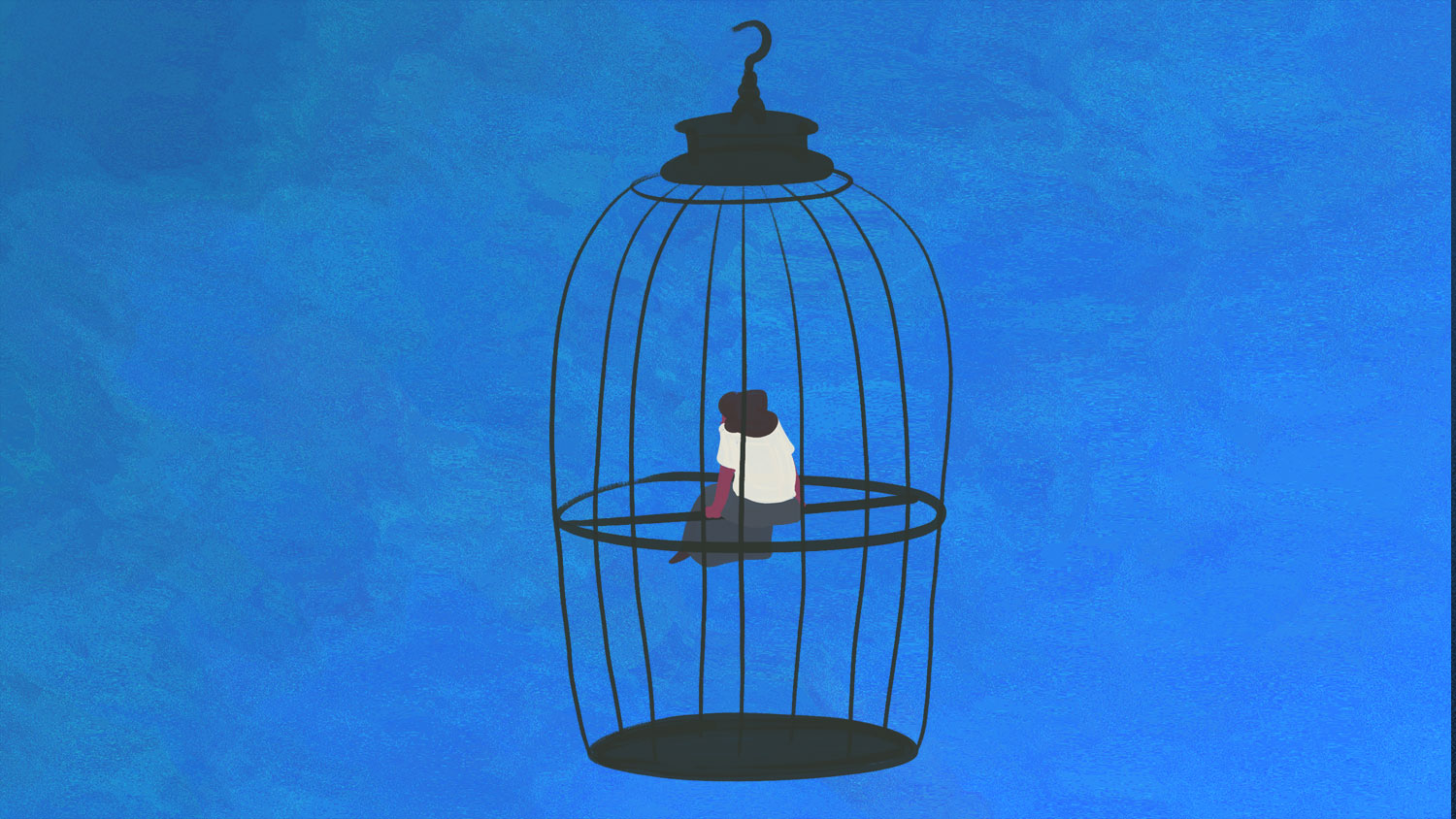DALAM puncak kesadarannya, Saiful Bahri berkesimpulan bahwa hidupnya "tidak apa-apa", justru ketika ia merasa ajalnya telah sampai. Kesimpulan yang diambil pensiunan mayor berusia 50 ini dibantah sendiri oleh istrinya, Murni. Di mata Murni, Bahri adalah tokoh masyarakat. Seorang yang telah berjasa bagi Nusa Bangsa, sampai Murni merasa tidak diperhatikan karena kesibukannya. Keresahan Bahri yang mengidap penyakit liver berat memang beralasan. Di pembaringannya, ia sudah merasakan kedudukannya di kantor mulai goyah. Majid, koleganya, mulai menggerogoti posisinya. Sementara itu, pengalaman masa lalunya menghantuinya. Ia pernah menjatuhkan hukuman mati terhadap Anwar, sahabatnya, dalam sebuah pengadilan medan perang. Anwar ia anggap membahayakan keutuhan perjuangan. Ternyata, di balik penghukuman itu tersembul cinta segi tiga: Bahri-Murni-Anwar. Ketika nyawa sudah sampai tenggorokan itulah, Bahri dihadapkan oleh kenyataan, atau ia seorang pembunuh atau ia seorang pahlawan. Dentingan suara hati nuraninya ini berhasil membawanya ke sebuah pengadilan. Suatu mahkamah yang keadilan dan kebenarannya tak tersangsikan. Suatu mahkamah yang tinggal di tiap hati nurani orang. Mahkamah Bahri mengadili Bahri . Lakon Mahkamah dipentaskan oleh Sanggar Pelakon selama 9 hari, dari 4 s/d 12 Maret ini, di Gedung Kesenian Jakarta. Ditulis dan disutradarai oleh Asrul Sani, Mahkamah dibangun dengan struktur yang kuat. Tanjakan alurnya mengesankan. Bisa memikat setiap sutradara untuk menanganinya. Terdiri atas tiga babak, lakon ini berlangsung di tiga tata panggung Babak pertama dan babak ketiga bermain di kamar tidur dan ruang tamu, berlangsung selama kurang lebih satu jam. Setelah mengambil jeda lima belas menit, muncullah babak kedua, merupakan ruang pengadilan, selama satu jam juga. Suatu adegan pengadilan yang bagi sejawat Asrul boleh jadi dapat melahirkan suatu pemandangan yang surealistis. Asrul tidak ke sana. Agaknya, ini hanya soal selera. Kelihatannya, Asrul tetap berpatokan bahwa "kesederhanaan adalah keindahan yang senyata-nyatanya" . Dan kesederhanaan penyutradaraan ini begitu menonjol. Hampir-hampir tanpa emosi. Agaknya, Asrul berketeguhan menyerahkan segalanya kepada penonton. Dan ia percaya pada kekuatan naskah. Adegan-adegan yang mampu mentransformasikan Bahri menapak begitu mulus. Dengan kendali yang ketat, lahirlah kekuatan Asrul. Dalam kesederhanaan itulah Asrul berhasil menukik. Terasa Mahkamah mampu mengetuk setiap hati nurani. Suatu diktum. Namun, bukannya tak terasa bekas tangannya pada sejumlah pemain yang jadi tulang punggung. Galeb Husein sebagai Bahri dan Mutiara Sani sebagai Murni haruslah dicatat sebagai pasangan yang pas benar. Pingpong dialognya begitu cekatan. Warna suara keduanya saling mengimbangi. Galeb yang berat dan Mutiara yang tajam telah membangun adegan kamar tidur begitu akrab sebagaimana keakraban suami-istri dalam menempuh kehidupannya sehari-hari. Perkembangan emosi Galeb, yang (sengaja) tak digarap, terasa berada dalam suatu kekekalan, sebuah daerah di antara hidup dan mati, yang manusia merasakannya hanya beberapa detikan. Mutiara begitu sadar akan kepiawaian akustik Gedung Kesenian. Lafaznya yang hampir-hampir berbisik telah sampai ke telinga penonton begitu jelas dan enak. Penonton telah melihat perjalanan jauh suami-istri, yang bukannya setiap saat tanpa konflik. Dan Mutiara kuncinya. Sutopo Hs dan Nizar Zulmi, sebagai Citra I dan Citra II, menentukan lakon ini. Di panggung barangkali kita mengenal kedua tokoh itu sebagai Rokib dan Atid, dua malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan kita. Mereka inilah yang menjemput Bahri. Di ambang ajalnya, ketika pengadilan berlangsung, Citra II bertindak sebagai Penuntut Umum dan Citra I sebagai Pembela. Permainan Zulmi mengesankan, hanya cara berjalannya agak bergaya. Berduet dengan Sutopo merupakan pasangan purbani yang isi-mengisi Zulmi, yang punya warna suara empuk, mampu menembaknya secara beruntun dengan baik. Gerak geriknya yang dapat menangkap situasi dengan tepat dapat dijanjikan sebagai pemain andal di hari mendatang. Sedang Sutopo, sebagai pemain alam, dengan polosnya mampu memegang peran apa saja. Di sini kepolosannya tetap muncul, tak dapat ditindih keintelektualitasan perannya. Apa Sutopo pernah bermain jelek? Sementara itu, Titiek Sandhora (Ny. Majid) dan Gito Rollies (Majid) perlu dikendalikan. Kedua peran ini begitu penting. Sayang kalau pesan yang dibawakannya tak begitu ditangkap penonton. Agaknya, tempo pengucapan dlalog perlu diatur, di samping membagi waktu secara tepat, untuk melahirkan suasana. Wajah Gito yang "kejam" dan membara sebenarnya modal yang kuat bagi peran im. Jadi, ia tidak perlu gerudak-geruduk. Edward Bahard, sebagai Kapten Anwar, cukup berpenampilan "diam". Ketika duduk sambil memutar-mutarkan kursi, intensitas permainannya jadi cair. Lalu Urip Arphan, sebagai Pratu. Somad, sungguh menjadi penyegar, karena lucunya. Gaya hidupnya sehari-hari dan perannya sudah menyatu, hingga rasanya tak perlu disutradarai. Jangan lupa, Harun Syarif (Pak Ahmad) dan Al Qarana (Dokter Ramli) harus dicatat sebagai kekayaan Sanggar Pelakon. Kedua pemain ini wajar bila di hari-hari mendatang mendapat peran yang lebih besar. Tata artistik yang ditangani Satari masih terbata-bata. Terutama pada tata panggung dan tata lampu. Lihat adegan pengadilan, yang cukup sulit untuk mencapai dimensi. Tetapi tata pakaian dan tata rias berhasil. Kostum Citra I dan Citra 11 merupakan keputusan artistik yang perlu dipujikan. Begitulah, Asrul-seperti menakik. Dan hasilnya apik. Seperti Teater Mandiri yang menggaet Warkop DKI dalam Front, Sanggar Pelakon seperti bisa membaca situasi penonton, dengan memanfaatkan tokoh-tokoh selebritis: Rosihan Anwar, Bob Sadino, Titiek Sandhora, dan Gito Rollies. Danarto
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini