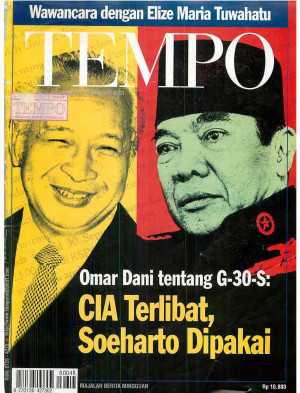DI MANA Bratasena menemukan diri? Di bawah samudra sebagai Dewa Ruci, dan juga—kini—di layar televisi dalam bentuk VCD. Menonton lakon wayang kulit sekarang tak mudah lagi. Pementasan tak jarang, tapi lakon memang kian surut. Kini suguhan lazim adalah dagelan berkepanjangan, sinden berpupur tebal menyanyikan lagu dangdut, ataupun pesan kerukunan. (Saat Orde Baru, pembangunan yang jadi tema pesan.) Tapi, mayoritas penonton tampaknya senang dengan keriuhan penuh warna ini.
Hanya segelintir yang masih mencoba menonton dari balik kelir. Hal ini pun sulit terpenuhi karena layar kini lebih sering dilekatkan ke tembok. Kondisi serupa juga datang lewat tayangan televisi. Akibatnya, roh pertunjukan, yang seharusnya muncul dari pergerakan bayangan dari balik layar, makin terpinggirkan.
Roh yang menguap itu kini dicoba dihadirkan kembali oleh rumah produksi Gelar dalam Dewa Ruci. Lakon yang menampilkan dalang Ki Manteb Soedharsono ini dikemas dalam bentuk VCD. Sepanjang durasinya, yang 60 menit, hampir semua pengambilan gambarnya dilakukan dari belakang layar. "Kami memang memilih pendekatan sinematik, agar benar-benar bisa jadi alternatif," kata Yanusa Nugroho, sutradara film ini, yang selama ini dikenal sebagai penulis cerita pendek.
Lakon klasik ini bercerita tentang pencarian identitas Bratasena (Bima). Ia merasa sudah menunaikan kewajibannya sebagai ksatria, tapi kehampaan juga yang terdekap. Ia pun menemui sang guru, Pendeta Durna. Sang guru bernasihat, keraguan tak perlu ada dalam hidup, asal niat jelas. Namun, untuk sampai ke tahapan tersebut, ada syaratnya. Bratasena harus mencari Kayugung Susuhing Angin di Gunung Candramuka, dan Tirta Pawitra di Samudra Minangkalbu.
Sesungguhnya, Durna berniat mencelakai muridnya. Namun, akhirnya Bratasena justru mendapatkan apa yang dicarinya. Di dasar samudra, ia bertemu identitasnya dalam wujud Dewa Ruci. Di sini, Bratasena mengetahui siapa, dari mana, dan akan ke mana hidup seorang manusia. Ia terbuai. Namun, karena ia masih makhluk berdaging, ia harus kembali ke bumi yang nyata.
VCD yang mulai dipasarkan akhir tahun lalu ini beroleh sambutan bagus. Edisi subtitle bahasa Indonesia, yang dicetak 1.000 keping dengan harga jual Rp 20 ribu, sudah hampir ludes. Padahal, penjualannya bergerilya. "Kalau ada di toko, itu pasti bajakan," kata Bram Kushardjanto, produser eksekutif. Meski laris, biaya produksi, yang sekitar Rp 100 juta, masih belum tertutup. Keuntungan diharapkan datang dari penjualan edisi subtitle bahasa Inggris, yang juga dicetak 1.000 keping dengan harga jual Rp 150 ribu. Sampai saat ini, sudah sekitar 200 keping yang terjual.
Proses produksi film ini sendiri tak kalah serunya dengan perjalanan Bima mencari identitas diri. Kesulitan yang sebelumnya tak terbayangkan menyundul berkali-kali saat syuting, Juni lalu. Misalnya, masalah akustik. Agar suara gamelan tidak tumpang-tindih, pengaturan susunan para pengrawit terpaksa tidak mengikuti pola baku. Hal ini agak menyulitkan, karena mereka terbiasa dengan susunan penabuh gendang sebagai pimpinan. Selain itu, minimnya kamera yang dipakai—cuma satu—juga menimbulkan masalah. Sang dalang terlihat kikuk saat mengulang satu gerakan untuk gambar close-up. Maklum, tak ada musik yang mengiringinya.
Kesulitan terbesar adalah pemadatan lakon filosofis dalam durasi yang relatif pendek. Masalahnya, struktur wayang kulit purwa (pathet enem, pathet sanga, dan pathet manyura), yang berisi perkenalan, masalah, serta penutup, tetap dipertahankan. Bahkan, adegan goro-goro juga tetap dihadirkan. Beruntung, sang Dalang punya sanggit (kelebihan) untuk menjawab tantangan ini. Namun, tak urung Manteb sempat jengkel saat muncul usulan sekiranya ia bisa memendekkan lakon sampai 50 menit saja. "Kenapa tidak minta dalangnya dibunuh sekalian," ujar Manteb.
Manteb tak perlu mati, bahkan ia boleh berbangga hati. Kelihaiannya menggerakkan wayang (sabetan), yang membuatnya berjuluk "dalang setan", menemukan medium yang tepat. Kerumitan lakon juga bisa ia siasati dengan cerdas. Misalnya, ketimbang berpanjang-panjang dengan dialog tentang nafsu yang dimiliki manusia, ia memilih menghadirkan bayangan naga-naga menari.
Sayang, puitisasi yang sudah tampil dinodai dengan proses pascaproduksi yang sangat mengganggu. Dalam adegan pertempuran, ada penambahan efek cahaya seperti yang biasa muncul dalam sinetron laga. Alih-alih dramatis, adegan ini justru membuat masygul. Tampaknya, keriuhan yang sudah telanjur melekat pada pertunjukan wayang kulit tak gampang untuk ditanggalkan.
Yusi Avianto Pareanom
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini