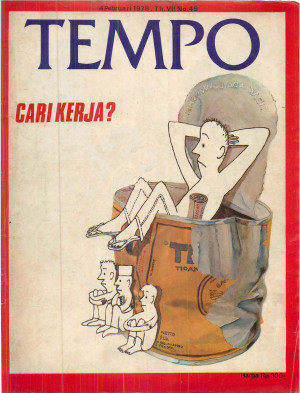MUS melepaskan dekapannya dari Anggora, tetapi lantas tidak
menghadap Wandi yang sekarang duduk bersila, nampaknya naik
pitam lagi, dalam keredupan kamar itu. Mus tidur terlentang,
matanya menengadah ke langit-langit kamar. Di sini tidak ada
cicak, komentar Mus).
"Apa kau masih ada kontak dengan bekas anak-anak laskar yang
tempo hari terus-terusan kau kuliahi tentang demokrasi dan hak
asasi? uh? Aku masih terus. Aku ongkosi sekolah mereka aku
bantu mereka cari kerja. Aku belikan mereka buku-buku."
Mus tidak menyahut. Dia melihat ratusan mobil yang macet,
berderet, dikempesi bannya ditempelin kaca-kacanya ......
ITU sepotong dari cerita pendekUmar Kayam, Kimono Biru Buat
Isten (Horison, Pebruari 1974) yang dibacakan Chaerul Umam, 23
Januari malam di Teater Arena TIM, di depan penonton yang
memenuhi separoh kira-kira tempat duduk. (Memang banyak yang
memastikan, kurangnya pengunjung untuk acara TIM juga disebabkan
karena para pembaca sebagian koran yang sedang dibreidel, tidak
mendapat informasi).
Setelah pembacaan puisi sejak beberapa tahun menjadi tontonan,
agaknya pembacaan cerita pendek segera menyusul.
Padahal sebetulnya bukan barang baru. Di Jakarta dikenal Pak
Dja'it (Mohammad Zahid) yang sering dipanggil keluarga yang
sedang berhajat entah apa, untuk membacakan hikayat. Pak Dja'it
telah tiada, dan kegiatan itu diteruskan anaknya, meski tak lagi
sepopuler dulu. Sementara itu kita sudah sejak lama mendengarkan
pembacaan cerpen di ladio Australia oleh Mohamad Diponegoro.
Juga pcmbacaan cerpen dari RRI Jakarta dan RRI kota-kota lain,
plus radio-radio non-RRI. Tapi agaknya menqang lain,
mendengarkan pembacaan cerpen lewat radio dan menghadiri
pembacaan cerpen.
Yang nertama jelas, kadar santainya bisa lebih bcsar. Orang bisa
mendengar kan sambil mencuci, menjahit, makan, atau juga
mengumpat-umpat Sementara duduk di Teater Arena mendengar Si
Umam membaca cerpen Kayam, memang dituntut untuk sedikit serius
-agar tidak mengantuk dan kehilangan Jalan cerita.
Tapi Mamang (nama panggilan bekas aktor drama yang sekarang
mencari nafkah sebagai sutradara film) memang tidak memberi
kesernpatan orang mengantuk. Volume suaranya enak. Tahu di mana
harus membaca keras, lambat, bersemangat walau berbisik. Bahkan
kalimat "sepotong lagu Garuda Pancasila" disambungnya dengan
menyiulkan sepotong lagu tersebut.
Dengan singkat, teater masuk di sini dan mengembangkan warna,
seperti juga bila orang menikmati pembacaan puisi oleh Rendra.
Arena Teater Arena yang hanya dilengkapi dengan sebuah kursi,
corong pengeras suara dan lampu penerangan biasa, berubah
menjadi medan imajinasi, di mana adegan-adegan cerpen silih
berganti terbayang. Maka tak urung hadirin tertawa jika memang
cerita yang dibaca sampai pada bagian lucu, dan tertawa dengan
nada agak lain jika sampai pada adegan "serem" (yang juga tak
sedikit). Bahkan seorang gadis tertawa terpingkal-pingkal sambil
tangannya memukul temannya yang duduk di sampingnya.
Memang mirip pertunjukan drama, meski mini. Kadang Mamang
merentangkan tangan, agak membungkuk, atau menghentakkan kaki.
Toh, secara visual dari sebuah pembacaan cerpen hanya sedikit
yang bisa ditonton. Karenanya cerpennya sendiri menjadi unsur
penting, di samping orangnya. Mamang sendiri bukan baru kali ini
membaca cerpen. Pertama kali ia tampil membawakan cerpen
Danarto, kedua cerpen Kuntowijoyo.
Tapi apa si schetulnya yang menarik orang mendengarkan
pembacaan cerpen? Apa karena kini orang malas membaca?
Barangkali. Tapi memang ada kenikmatan sendiri. Membaca sendiri
sebuah cerpen adalah menikmati suatu petualangan imajiner
sendirian, atau paling-paling bersama pengarangnya--secara
imajiner. Sementara mendengarkan pembacaan cerpen adalah
menikmati petualangan imajiner secara bersama. Ada semacam
pembagian kenikmatan. Dan itu juga berarti mendapat cara lain
untuk berhibur. Kan orang lagi pada tegang.
Bambang Bujono
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini