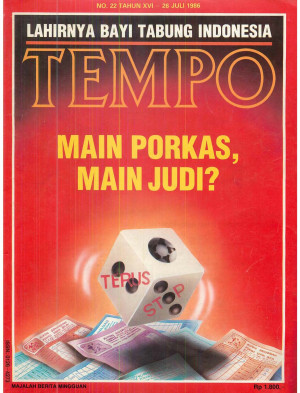OPERA JAKARTA Cerita: Titi Nginung Skenario & Sutradara: Sjumandjaja Pemain: Zoraya Perucha, Ray Sahetapy, Sukarno M. Noor, Deddy Mizwar, Rano Karno, Piet Burnama, Nani Wijaya, Adi Kurdi, Cok Simbara, dan lain-lain Produksi: PT Gramedia Film PALING sedikit ada empat cerita dalam film terakhir Sjumandjaja ini. Satu, cerita tentang Yoko (Ray Sahetapy). Yoko diperkenalkan kepada penonton sebagai bayi haram seorang babu yang bekerja di Jakarta dan berasal dari Desa Bekonang di pinggir Kota Surakarta. Ia tumbuh dengan bakat bertinju dan berkembang hingga menjadi petinju bayaran terkemuka di Jakarta. Tingkah laku aneh dan rebeli Yoko tampaknya bersumber pada riwayat hidupnya yang minus ayah dan ibu, dan dibesarkan penuh kemanjaan oleh neneknya yang miskin di tepi Bengawan Solo. Dua, cerita tentang Rum (Perucha), anak gadis yang hidup bebas dan tak kurang suatu apa. Anak perempuan ini juga aneh, meski sifat demikian barangkali saja muncul karena keluarganya yang kaya. Ia, misalnya, begitu saja meninggalkan mobilnya di persimpangan jalan ketika lampu merah sedang menyala. (Untung, polisi lalu lintas digambarkan simpatik mereka menderek mobil Rum ke rumah). Dalam sinopsis juga dikisahkan bahwa Rum punya banyak pacar, meski dalam film yang kita lihat lain. Ada beberapa lelaki yang senang kepadanya, memang, tapi sutradara hanya sempat meyakinkan kita untuk percaya bahwa Rum hanya mencintai Yoko. Tiga, cerita tentang seorang ayah (Sukarno M. Noor) dan konfliknya dengan salah seorang anaknya. Apa, siapa, dan bagaimana kegiatan usaha sang ayah tidak dijelaskan lebih jauh. Kita tampaknya diminta menerima saja asumsi umum dalam film Indonesia, yang selalu cenderung melihat hadirnya problem anak lawan orangtua dalam setiap keluarga kaya. (Orang kaya tentu sibuk, karena itu tidak punya waktu untuk anak. Nah, konflik timbul). Begitu hebat pertentangan anak-beranak ini, sehingga Himan (Rano Karno) sampai membangun satu kelompok bersenjata yang akhirnya sukses menteror pesta kawin kakak perempuannya sendiri. Adegan teror ini amat mengingatkan saya pada adegan yang sama dalam serial TV Amerika, Dynasty. Empat, cerita tentang Paman Jangkung, jenderal angkatan darat yang sepanjang film ini cuma sibuk mengurus Rum, keponakannya. Bersama sang jenderal juga ada dua wanita yang tampaknya istri-istrinya. Dari salah satu istri itulah para penonton boleh menduga bahwa Yoko sebenarnya anak haram Pak Jenderal dengan babunya yang dari Desa Bekonang itu. Bisa diterka, keempat "anak cerita" itu diharapkan menjadi kerangka dan titik tolak pembuat film ini untuk menyampaikan pesan. Maka, kalau tiap cerita bahkan belum merupakan sebuah kisah yang selesai, cerita rangkuman pada akhirnya tak lebih dari hasil usaha mengada-ada. Tengoklah, misalnya, adegan paling kritis film ini: larinya Rum dari kamarnya pada jam-jam menjelang perkawinannya. Jika saja cerita tentang Rum dan keluarganya digarap lebih utuh, tentulah sulit bagi kita menerima rencana perkawinan itu, setelah kepada penonton digambarkan Rum melakukan hubungan seks dengan Yoko -- dan bukan dengan calon suaminya -- di rumah keluarga Rum. Dari adegan itu tidak terlalu sukar menggambarkan watak Rum -- serta posisinya dalam keluarga -- yang menyebabkan gadis seperti itu, tentunya, tidak akan begitu mudah diminta menerima pemuda lain yang tidak dicintainya dan tidak pula digambarkan punya hubungan khusus dengan keluarganya. Terlalu banyak yang ingin disampaikan Sjuman, itu kesan yang sulit dihindarkan. Bukan cuma cerita, tapi juga cara menyampaikannya. Ini adalah film yang penuh kilas balik (flashback), bahkan kilas balik dalam kilas balik. Penonton yang kurang waspada dalam membedakan kilas balik kilas balik dalam kilas balik, dan narasi yang bukan kilas balik, bisa mendapat susah. Sjuman sendiri, dalam satu kesempatan, konon pernah menuturkan bahwa kali ini, agaknya lebih dari ketika ia membuat Atheis yang berdasarkan novel Achdiat Kartamihardja, ia mencoba setia kepada cara bercerita novel aslinya yang karangan Titi Nginung itu -- yang, menurut dia, menampilkan adegan-adegan yang tak urut walaupun secara keseluruhan padu. Ini memang berbeda dengan caranya ketika menangani Si Doel Anak Betawi, Kabut Sutra Unggu, maupun Budak Nafsu. Model alur seperti itu memang bisa lebih mudah memunculkan masalah -- setidak-tidaknya bila film ini, yang aslinya memakan waktu putar empat jam (menghabiskan 250 can film, sementara ia biasanya memakai rata-rata 100), oleh pertimbangan pemasaran dipotong menjadi hampir tiga jam. Dengan alasan apa pun, informasi tentang tokoh-tokoh maupun logika memang terganggu. Bayangkan bila film ini nanti, di tangan pemilik bioskop, mengalami pemotongan tambahan. Betapapun, Opera Jakarta sebuah eksperimen -- tak sulit ditebak. Sjuman bahkan melangkah lebih jauh: inilah film Indonesia pertama, dalam beberapa dasawarsa terakhir ini, yang menggunakan direct sound -- gambar dan suara direkam simultan. Cara seperti ini, dulu, nun di tahun lima puluhan, dipakai juga oleh Usmar Ismail di Perfini -- dan jauh lebih berhasil. Jika Anda menonton film ini dan banyak kali tidak menangkap percakapan para pemain, itu bukan lantaran kerusakan sistem suara di bioskop. Hasil rekaman suara film ini memang jauh dari memadai sedemikian rupa, sehingga untuk mengerti jalan cerita saja saya terpaksa menggunakan bahan tertulis yang disediakan produser. Juga musik. Iringan yang digarap Marusya Nainggolan terdengar cukup serius, tapi terasa berjalan tidak seirama dengan gambar. Fotografi, yang dikerjakan Sutomo Gandasubrata, tidak pula menghasilkan potret yang bernuansa. Ditambah dengan kerja kamera yang kurang rapi -- terutama kalau kamera bergerak di sekitar pemain -- dan terasa tidak seirama dengan ritme cerita, semua menunjukkan betapa tidak siapnya Sjumandjaja dengan sebuah eksperimen. Bahkan Norman Benny, editor yang baik, tidak bisa menolong film dan cenderung berpanjang-panjang pada banyak adegannya ini. Setelah Sjuman, salah satu dari sedikit orang Indonesia yang keluaran sekolah film, menyelesaikan banyak karya, membicarakan kelemahan tekms filmnya terasa menyedihkan. Yang mestinya jadi pokok pembahasan adalah cerita dan penyampaiannya. Apalagi karena sutradara yang almarhum ini terkemuka justru karena karya-karyanya yang selalu punya relevansi sosial. Kali ini, pada filmnya terakhir, Sjuman tidak hanya tergelincir dalam memilih cerita (aneh, memang, bagaimana ia bisa tertarik pada cerita yang begini vulgar), tapi juga dalam menyampaikannya. Padahal, dengan cerita ringan seperti Kabut Sutra Ungu Sjumandjaja bisa menghasilkan melodrama yang cukup baik. Memang, Opera Jakarta telah berhasil menampung satu sisi dari ambisi Sjuman tentang film besar: kesan gelombang besar penonton pada pertandingan tinju, atau demonstrasi besar para pelajar menuju kantor polisi, misalnya. Maka, yang masih tetap berharga dalam film ini (produksi Gramedia Film terakhir, setelah memutuskan untuk kembali menggarap film iklan yang dulu digelutinya dengan segala sukses), tentulah keberanian Sjumandjaja untuk bereksperimen. Yang terakhir ini mutlak dipelihara jika diinginkan suatu hari depan bagi film buatan kita sendiri. Dan kalau film ini bakal meraih Piala Citra, maka itu tentulah karena permainan Deddy Mizwar (Paman Jangkung) yang cantik tapi meyakinkan. Sebagai jenderal yang tampil tidak pernah dalam pakaian seragam, ia memberikan kepada kita bukan cuma sosok, tapi juga sejarah hidup yang panjang di belakangnya. Tapi Deddy, yang berasal dari dunia teater itu, memang selalu bermain baik -- dalam kira-kira separuh dari 15 film yang diloloskan Komite Seleksi Festival Film Indonesia kali ini. Salim Said
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini