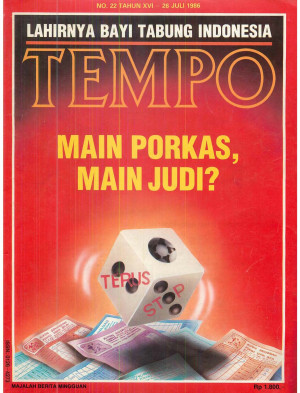KETIKA film Opera Jakarta baru selesai 45%, penyakit liver Sjumandjaja kambuh. Dokter, juga produser, menyarankan agar sutradara lulusan sekolah film Moskow itu beristirahat. Sjuman menolak dan terus bekerja tanpa mempedulikan kondisi badannya. Ia hanya berhasil menggarap filmnya hingga sembilan puluh sekian persen. Lalu meninggal, 19 Juli 1985. Innalillahi. "Saya tidak terkejut." Itu komentar Sutomo Gandasubrata, juru kamera yang mendampinginya dalam pembuatan Opera Jakarta. "Sjumandjaja sebenarnya sudah meninggal beberapa hari sebelumnya: cuma semangat saja yang menunda ajalnya," tambah Sutomo pula. Sutomo, seperti juga dokter dan pihak produser, tidak berhasil meyakinkan Sjumandjaja untuk mencoba memperlambat datangnya maut. Orang yang kenal Sjuman akan cepat mengerti cerita Sutomo. Sepanjang hidupnya sebagai seniman film, Sjumandjaja hadir dan menonjol justru karena tidak pernah bisa dipengaruhi untuk berbuat seperti orang lain. Di awal tahun tujuh puluhan, ketika film-film cinta remaja merajai dunia film Indonesia, Sjuman memulai kariernya sebagai sutradara lewat Lewat Tengah Malam, tontonan yang justru sarat dengan kritik sosial dan bertolak dari sebuah cerita nyata yang konon terjadi di Jakarta. Tatkala film itu siap ditonton, para pengamat pun sadar: Lewat Tengah Malam amat mengingatkan mereka pada The Thomas Cron Affairs. Sjumandjaja tidak menyangkal terpengaruh film Amerika itu. Pola asli campur pengaruh itu kemudian hampir jadi ramuan yang selalu ada dalam karya-karya Sjumandjaja, dalam kadar yang tentu tidak sama. Dalam Aheis, misalnya, ada adegan yang sangat mirip adegan dalam Potemkin, di samping juga ada yang mengingatkan kita pada Hiroshima Mon Amour. Sjumandjaja adalah orang yang bosan dengan idiom film-film Indonesia yang sudah memfosil. Di matanya, film kita sudah sebuah bahasa yang baku sehingga siapa pun akhirnya gampang bikin film. Adegan cinta mesti begini, adegan sedih harus begitu, penjahat tampak begini, orang baik terlihat begitu. Sjuman mau lain. Dan berjuang untuk itu. Maka, paling sedikit dalam hal corak dan jenis cerita, ia harus dikenang sebagai pemberontak dan pelopor yang berhasil membuktikan bahwa film Indonesia bisa menjadi media yang serius. Tentu saja Sjumandjaja sudah didahului Usmar Ismail tapi kita tidak boleh lupa bahwa Usmar kemudian berangsur-angsur mengkompromikan cita-citanya, ketika ia mengalami kepahitan pasar. Maka, ketika -- dalam sejarah film Indonesia -- ada saatnya orang putus asa untuk membuat film dengan konotasi sosial yang keras, di situlah Sjuman muncul. Sjumandjaja meninggalkan dunia dan film Indonesia dengan 15 karya jadi serta sejumlah besar skenario. Tidak semua filmnya bagus, memang. Dan kelemahannya justru kelebihannya -- dalam usahanya menemukan idiom yang lebih segar. Cerita-cerita dengan kritik sosial tidak dengan sendirinya menghasilkan film bagus karena pengucapan juga sama penting dengan yang diucapkan. Sjuman telah mencapai satu, yakni cerita, dan mencapai setengah dalam penyampaian. Yang terakhir ini karena ia mencari -- bukan karena ia telah menemukan. Dan satu setengah adalah angka yang lebih dari cukup untuk mencatat namanya Sjumandjaja dalam panteon film Indonesia. Salim Said
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini