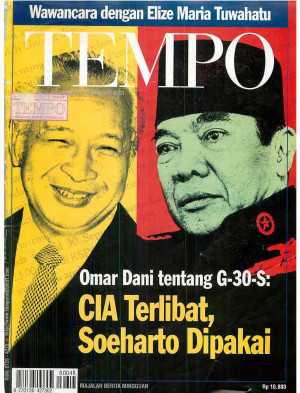Opium to Java: Jawa dalam Cengkeraman Bandar-Bandar Opium Cina, Indonesia Kolonial 1860-1910
Penulis : James R. Rush
Penerjemah : E. Setiyawati Alkhatab
Penerbit : Mata Bangsa, Yogyakarta, 2000 (bekerja sama dengan Ford Foundation dan Yayasan Adikarya Ikapi)
Tebal : 640 halaman
Sedangkan bagi seorang pengisap opium, kemalasannya bercampur dengan sikap masa bodoh. Satu-satunya hal yang disukainya adalah menghadapi sebuah lampu teplok sementara [ia] duduk di sebuah bale-bale sambil bertopang kaki dan [tangannya] dengan santainya memegang sebuah pipa madat… (Opium to Java, halaman 76, mengutip tulisan dari Paku Buwono IV dalam syair Wulang Reh—ajaran-ajaran tentang perilaku yang benar).
DENGAN penampilan yang anggun, buku ini menggunakan judul aslinya: Opium to Java. Tapi subjudul buku ini dalam bahasa Indonesia sesungguhnya lain sama sekali dengan subjudul buatan Rush. Dalam bahasa Inggris, subjudul Rush berbunyi Revenue Farming and Chinese Enterprise in Colonial Indonesia, 1860-1910 (Penghasilkan Pajak Pacht dan Usaha Cina di Indonesia Kolonial, 1860 1910). Sesungguhnya, subjudul asli buatan Rush tak sedemikian provokatif seperti subjudul bahasa Indonesia. Tapi justru subjudul asli itulah yang lebih mencerminkan isi buku.
Dari segi penerjemahan, bahasa buku ini terkadang kelihatan terasa kaku sehingga ada beberapa kalimat yang sukar dimengerti. Di beberapa bagian, bahkan terasa sang penerjemah kurang memahami sejarah, khususnya sejarah kolonial di Jawa selama bagian kedua abad ke-19. Sang penerjemah juga agaknya kurang memahami sistem penjualan opium dan pelaku-pelakunya. Hal ini terutama terungkap pada pilihan subjudul dalam bahasa Indonesia.
Adapun buku aslinya, yang diterbitkan oleh Universitas Cornell pada 1990, dibuat berdasarkan disertasi James R. Rush di Universitas Yale. Sementara Belanda menerjemahkannya hanya tiga bulan setelah buku itu terbit, Indonesia baru menerjemahkan buku ini 10 tahun kemudian. Ini menunjukkan sungguh terlalu lama ilmu kita ketinggalan dalam penerbitan dan penerjemahan buku-buku sejarah dan ilmiah sosial lainnya yang penting tentang Indonesia.
Karya Rush ini berkisah tentang pachter, yang diterjemahkan dalam buku ini sebagai bandar. Saya merasa bahwa istilah "bandar" sangat kreatif. Saya sendiri sebagai sejarawan sudah lama mencari istilah yang tepat bagi para pemegang pacht ini, tapi tidak menemukannya. Dalam bahasa Inggris, Rush menggunakan istilah aslinya, yaitu government farm. Istilah bandar akan menjadi tepat jika dijelaskan sebagai financier (cukong) dari pacht. Selain itu, sebaiknya sistem pacht yang diterjemahkan sebagai sistem bandar dijelaskan lebih dulu kepada pembaca, yang sayangnya tidak dilakukan oleh penerjemah buku tersebut.
Pachter atau pemegang pacht (dalam bahasa Belanda, istilah pachter paling sering digunakan untuk "penggarap" tanah, yakni petani yang menggarap tanah yang dimiliki orang lain) opium atau pacht candu menarik diteliti. Salah satu daya tariknya adalah penggarapan dan penjualannya tidak dilakukan oleh para "pemilik"-nya, yaitu pemerintah kolonial atau Hindia Belanda yang memiliki monopoli penjualan opium. Penjualan opium ke masyarakat itu tidak dilakukan oleh pemerintah sendiri secara langsung, tapi dijual kepada bandar-bandar. Sedangkan pemerintah Hindia Belanda mendapatkan opium atau candu itu dengan mengimpor dari India.
Penjualan opium atau candu di Hindia Belanda adalah monopoli negara. Maka, jika pemerintah yang melakukan penjualan itu, dengan sendirinya seolah-olah konsumsi opium dan penjualannya menjadi sesuatu yang legal. Penyelenggaraan penjualan opium ini dilakukan oleh government-farmer (dalam bahasa Inggris, atau pachter dalam bahasa Belanda, atau "bandar" dalam bahasa Indonesia). Monopoli negara atas penjualan candu dilakukan di depan umum dengan cara tender atau lelang. Para pemenang "tender" memperoleh pacht selama satu tahun dan memegangnya per distrik atau kabupaten yang sama luasnya dengan satu keasistenresidenan.
Adapun penjualan pacht ini dilakukan secara seremonial di pendapa kabupaten. Acara tawar-menawar dan persaingan antar-calon bandar ini disebut sebagai "peperangan antar-para raja". Para calon bandar itu jelas merupakan elite kaya di antara masyarakat Cina dan kolonial. Pelelangan pacht ini dihadiri dan diurus oleh pejabat-pejabat Belanda serta pribumi seperti bupati dan patih. Meski pacht dijual melalui tender, sistem KKN juga terselenggara sehingga seseorang bisa saja mendapatkan lisensi penjualan opium.
Bandar biasanya juga merangkap sebagai opsir Cina. Setiap golongan di Hindia Belanda diharuskan bermukim di kampung sendiri dan diurus oleh kepala-kepala yang diberi gelar opsir. Gelar militer ini tidak ada hubungannya dengan kemiliteran. Pada zaman itu tidak ada gelar lain bagi non-aristokrat kecuali militer. Gelar mayor atau kapten dan letnan Cina, Arab, dan seterusnya disamakan dengan doktor honoris causa (H.C.) pada masa kini. Bahkan, biasanya kekayaan menjadi dasar pengangkatan opsir sehingga kedudukan bandar dan opsir dirangkap.
Karena adanya sistem warisan di masyarakat Cina dan karena adanya keharusan terjadi hubungan baik antara pejabat Belanda dan opsir serta kepercayaan kepada bandar, ada kecenderungan bahwa kedudukan bandar dan opsir bersifat turun-temurun dalam keluarga Cina elite tertentu. Para keluarga opsir Cina bersama dengan keluarga pangreh praja, khususnya bupati dan pejabat setempat di kota-kota di seluruh Jawa (Madura)—golongan elite—itu disebut cabang atas. Maka, di setiap kota di Jawa ada keluarga opsir Cina yang kaya dan secara turun-temurun mencari nafkah sebagai bandar, misalnya di Semarang (Jawa Tengah) ada keluarga Be, Ho, Liem, sementara di Jawa Timur ada keluarga Han ,The, Tjoa.
Sistem pacht ini tidak hanya meliputi candu—meski pacht opium adalah yang paling penting dan paling banyak menghasilkan uang, baik bagi pemerintah maupun bagi bandar. Lembaga lain yang tak kalah penting dan menguntungkan adalah pacht pegadaian, yang juga merupakan monopoli pemerintah kolonial, yang dijual kepada para bandar Cina. Masih banyak pacht lain: pacht sarang burung di gua-gua pantai selatan Jawa, pacht penyeberangan sungai, dan puluhan pacht lainnya.
Sebenarnya, pada permulaan abad ke-19, monopoli garam sudah terselenggara dan bahkan pajak seperti pajak tanah dan pajak kepala ditenderkan kepada para bandar.
Selama abad ke-19, sistem pacht itu dikurangi penyelenggaraannya sedikit demi sedikit, lalu diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda sendiri dengan makin banyaknya pegawai Belanda di Jawa. Pada 1910, kedua pacht, yakni penjualan candu dan pegadaian, diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun itu dapat dikatakan bahwa sistem penjualan penghasilan negara kepada para bandar dihapus. Dengan demikian, tamat sudah sistem patronage (kedudukan sebagai bos bagi para opsir Cina kemudian juga dihapus atau tidak pernah pulih kembali).
Sampai tahun 1910, masih terdapat serangkaian peraturan yang membatasi gerak fisik orang Cina, misalnya permukiman di kampung Cina atau perjalanan antarkampung Cina memerlukan pas jalan. Para bandar dan agen-agennya bebas dari pembatasan gerak ini. Kebebasan itu kemudian digunakan untuk berdagang dan meletakkan jaringan usaha, yang sampai kini masih beroperasi.
Karena keuntungan yang diperoleh dari opium dan rumah gadai demikian besar, timbul juga penyelundupan candu dan rumah gadai ilegal. Singkatnya, masalah pacht menunjukkan dinamika perdagangan dan dunia usaha. Pejabat Belanda selama ini mencoba mengawasi kegiatan candu itu. Pejabat yang paling terkenal adalah Charles Ter Mechelen, yang laporannya mengungkapkan berbagai intrik dan dinamika bisnis candu ini.
Bandar opium terakhir dan yang paling besar adalah Mayor Oei Tiong Ham dari Semarang, yang kemudian menjadi lebih terkenal sebagai "Raja Gula". Oei Tiong Ham menjadi bandar hingga 1910 dan memiliki paling sedikit lima pacht di Jawa Tengah. Oei adalah orang relatif "baru" dan bukan berasal dari keluarga opsir tua seperti Be atau Liem. Krisis ekonomi pada 1880-an menyebabkan banyak keluarga tua bangkrut atau tidak mampu bersaing dalam pelelangan penjualan candu, sehingga orang kaya baru seperti Oei berhasil membeli lima bandar opium hingga di Yogyakarta. Munculnya orang kaya baru seperti Oei menunjukkan bahwa masyarakat Cina abad ke-19 tetap memiliki dinamika.
Ternyata, penjualan opium dan gadai tak hanya menghidupkan ekonomi masyarakat, tapi juga merupakan penghasilan pajak negara yang sangat penting. Bahkan, pernah dilansir bahwa seluruh anggaran belanja untuk korps pegawai negeri (Binnenslandsch Bestuur) Hindia Belanda dibiayai oleh penghasilan pajak dari sistem pacht ini. Pejabat yang paling hebat, cerdik, dan jujur seperti Mechelen ditempatkan sebagai inspektur opium.
Pemerintah kolonial sangat berkepentingan akan makin banyaknya penjualan candu ke masyarakat, tapi lambat-laun juga sadar akan kejelekan akibat pengisapan opium. Kesadaran tersebut juga timbul di kalangan Cina dengan pendidikan Barat (Belanda) seperti Dr. Sim Ki Ay. Zaman politik etis (1900) mempertebal kesadaran ini. Namun, menurut Rush, setelah 1910, penjualan opium diambil alih negara kolonial dan yang terjadi justru penjualan opium rupanya digalakkan dan diperbesar dibandingkan dengan zaman pacht. Candu, yang kini dilarang di Indonesia, pada zaman kolonial tidak dikutuk. Kedudukan candu pada zaman itu mungkin seperti tembakau dan rokok zaman sekarang—masyarakat dan pemerintah sadar bahwa rokok dan tembakau merugikan kesehatan, tapi tetap tidak melarang penjualannya karena negara serta pengusaha rokok dan tembakau mendapatkan untung besar.
Yang sangat menarik dari karya James R. Rush tentang opium di Jawa tersebut, buku ini tak hanya terbatas pada masalah opium, tapi juga meliputi munculnya kapitalisme Cina, yang menurut saya terletak pada masalah sistem warisan dan kepemilikan yang disamakan dengan hak milik Barat (hukum barat) dan bukan hukum adat. Selain itu, buku ini membicarakan pola KKN, perdagangan, dan jaringannya, yang hingga kini masih terlihat di Indonesia, sehingga buku ini menjadi relevan untuk memahami persoalan masa kini.
Onghokham, sejarawan
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini