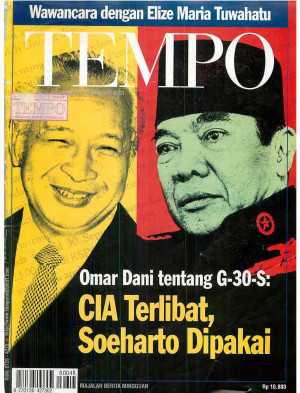Tuhan tak bermurah hati bagi demokrasi, atau demokrasi tak bermula dari rasa syukur. Pada suatu hari dalam sejarahnya yang purba, orang Bani Israel bercita-cita menjadi seperti bangsa-bangsa lain: mereka ingin punya seorang raja. Seakan-akan Tuhan menyimpan sebuah anugerah: akan selalu ada seorang pemimpin, seorang manusia yang, konon, seperti Presiden Republik Indonesia, ada malaikat di dadanya, dan sebab itu layak dapat dampar yang agung.
Tapi ada seorang alim yang sejak awal sudah mengingatkan bahwa kelak, setelah seorang raja dinobatkan, akan ada seseorang yang bisa membuat orang lain patuh kepadanya dan hal yang tak menyenangkan akan terjadi. Orang alim itu benar, tapi baru beratus tahun kemudian orang tahu ia benar. Demokrasi pun datang.
Ia datang melalui sebuah ritus yang menakutkan: setelah bertahun-tahun di bawah kesewenang-wenangan seseorang, darah pun sering harus tumpah, pemberontakan terjadi dan ada seseorang yang semula disebut "baginda" akhirnya disembelih lehernya. Di kepala manusia yang diciptakan Tuhan, baik ia seorang raja atau bukan, ternyata bersembunyi sebuah cela. Demokrasi bermula dari kesadaran bahwa cela itu akan selalu ada, ibarat sebuah liang hitam dalam harapan. Dengan kata lain: sesuatu keadaan yang negatif.
Sebab itu ide yang diwariskan Plato tentang "sang-raja-yang-filosof"?kombinasi antara ilmu yang tinggi dan kepemimpinan yang piawai dalam kepala seseorang, yang oleh orang Jawa disebut "pandhita-ratu"?adalah sebuah ide yang lahir di luar tradisi demokrasi. "Republik" Platonis adalah sebuah republik yang menampik negativitas. Di republik yang seperti ini, dibayangkan bertakhtanya seorang yang luar biasa, dan politik dilihat sebagai sesuatu yang bermula dari sebuah kepala?persisnya sebuah kepala yang padu dan utuh dan punya kelebihan. Seakan-akan dunia subyektif, yakni apa yang hadir dalam kesadaran akan selalu dapat diadaptasikan di dunia obyektif, dalam kenyataan yang terhampar di luar sana, yang rumit, rancu, selalu.
Dalam sejarahnya yang pendek, Indonesia sebenarnya telah menjalani ritus membatalkan harapan tua tentang pandhita-ratu. Sukarno jatuh, Soeharto jatuh. Orang ramai bertempik sorak. Tapi agaknya masih tersisa sebuah keyakinan yang melanjutkan apa yang mungkin juga bisa disebut Platonis: bahwa politik adalah soal kemampuan dunia subyektif untuk mengubah dunia obyektif yang terhampar di luar itu, dengan cara mengerahkan apa yang ada di dunia subyektif.
Di masa lalu, ketika "demokrasi terpimpin" diberlakukan antara 1958 dan 1965, pengerahan dunia subyektif itu dilakukan dengan mengharuskan seluruh negeri membaca "Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi" dan ajaran Sukarno. Di antara tahun 1966 dan 1998, usaha yang mirip berlangsung: orang harus mengubah isi kesadarannya dengan "Pancasila" dan beratus juta rupiah dihabiskan Soeharto untuk ratusan ribu penataran. Sejak 1999, tak ada Sukarno, tak ada Soeharto, tak ada indoktrinasi ataupun penataran, tapi orang tampaknya masih percaya bahwa apa yang ada di dalam diri manusia?dalam hal ini moralitas dan agama?akan bisa menyelamatkan dunia. Di sebuah sudut jalan di Jakarta pernah terpasang sebuah spanduk: "Takwa Adalah Solusi bagi Krisis Multidimensional".
Tapi benarkah? Mungkinkah kebersihan moral dan ketaatan kepada Tuhan?sesuatu yang berada di lubuk diri orang seorang, sesuatu yang bisa membentuk pribadi seseorang?menyelesaikan pelbagai krisis di dunia? Di sebuah negeri yang berulang kali menyaksikan begitu banyak dusta dan patgulipat, memang mudah tumbuh hasrat umum untuk membuat yang moral menjadi politis dan yang politis menjadi moral. Ada keyakinan bahwa jika keteguhan moral dan takwa seseorang disebarluaskan agar jadi sebuah mufakat, maka sebuah komunitas akan berubah jadi baik. Tapi benarkah demikian?
Saya tak yakin. Seperti orang-orang lain, saya telah menyaksikan bagaimana orang-orang yang memuliakan agama menghadirkan diri di ruang politik Indonesia: tak selamanya perilaku mereka terpuji. Tampaknya memang ada jarak antara kebajikan yang privat itu dan dunia orang ramai. Yang satu tak akan bisa identik dengan yang lain, bahkan yang satu bisa melahirkan negasi terhadap yang lain.
Di antara keduanya, pelbagai proses dialektika pun bersilang surup. Dialektika itu tanpa suatu pola yang stabil, seperti dikira kaum Marxis. Yang berlangsung dalam sejarah adalah "petualangan-petualangan dialektika". Di situ, dalam avontur yang tanpa kepastian itu, politik adalah sebuah tugas yang sedih. Politik itu terkutuk, kata Marleau-Ponty, "justru karena ia harus menerjemahkan nilai-nilai ke dalam dunia fakta-fakta". Lebih-lebih lagi karena nilai-nilai itu dibuat di sebuah dunia dan bukannya "dinubuatkan untuk dunia itu".
Di dunia itu juga sejarah berjalan, di wilayah yang lebat dan lindap, penuh tikus dan tikungan, lubang dan sampah, reptil busuk dan rawa payau. Seorang pendeta yang raja, seorang filosof yang pemimpin, seorang ulama yang presiden, mau tak mau tumbuh dan harus melangkah di teritorium yang seruwet itu. Mungkin ada malaikat di dadanya, tapi di perutnya juga ada lapar, dan tubuh itu juga punya bunyi dan bau yang jorok. Maka ketika yang moral berangkat untuk menjadi politis, ketika yang privat ingin menjelma menjadi yang publik, tak seorang pun tahu persis apa yang akhirnya akan tercapai. Sebab itu bisa saja seseorang di hari ini mengatakan bahwa "takwa adalah jawabannya". Tapi ingatkah ia apa pertanyaannya?
Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini