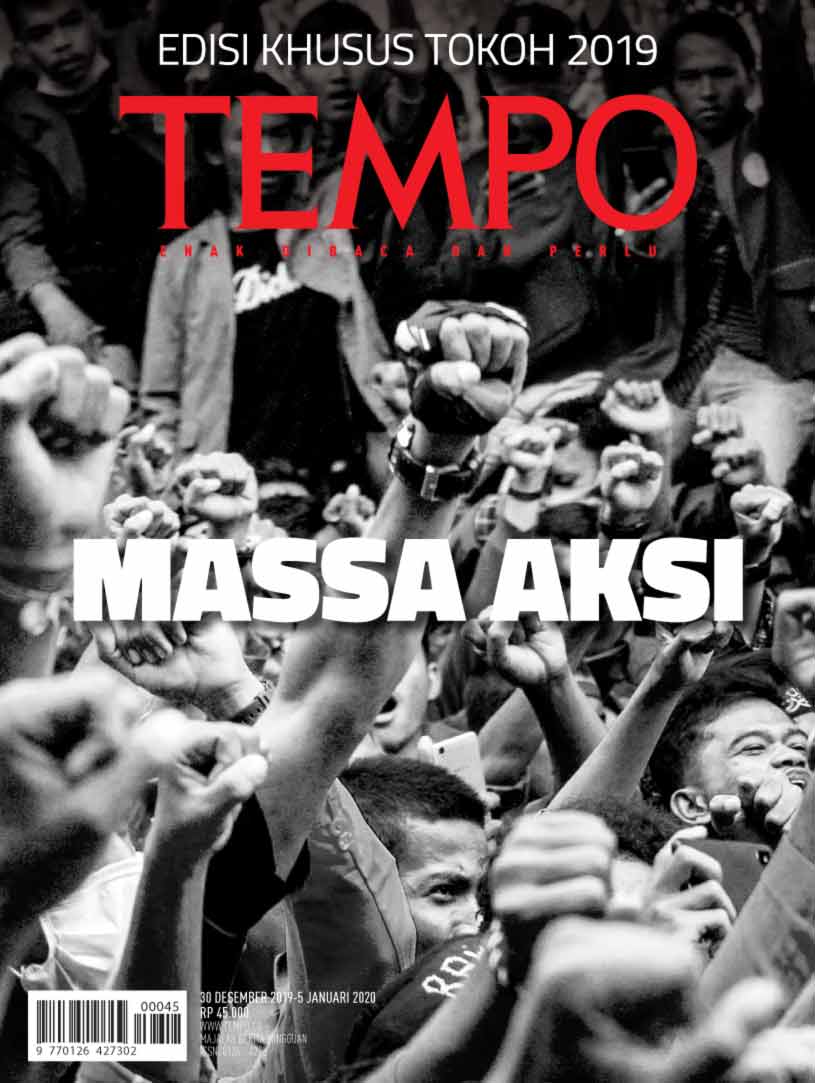Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Ugo Untoro
Pameran tunggal di Galeri Nasional Jakarta
TITEL karya Ugo Untoro itu Painting Series. Tapi ia sama sekali tak menyajikan kepada kita sebuah gambar. Satu karya menampilkan sejumlah lukisan yang direkatkan menjadi satu tumpukan. Lukisan itu disusun ke dalam sehingga yang tampak oleh mata adalah bagian kerangka belakangnya saja. Susunan tersebut dicemplungkan Ugo ke dalam sebuah boks kayu sehingga kita tak pernah bakal tahu wujud gambar di dalam kanvas itu. Bahkan, apakah betul di dalam kanvas itu ada corat-coret Ugo, hanya dia sendiri yang mengetahuinya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bukan itu saja. Untuk seri yang sama, Ugo membikin dua kerangka lukisan yang dia tempelkan ke bagian depan kanvasnya, atau ia menutupi sebuah lukisan dengan dua kerangka kayu berkanvas yang ditempel terbalik. Di seri yang sama, Ugo juga menampilkan obyek gulungan lukisan yang digantung di dinding dengan tambang. Bukan hanya kanvas yang dilinting di gulungan itu, melainkan juga kerangka kayunya yang diremuk-remuk. Lagi-lagi, ada atau tidaknya gambar di gelondongan kanvas itu menjadi rahasia Ugo.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Judul pameran itu sendiri sedikit aneh: Rindu Lukisan Merasuk di Badan. Apa yang dimaksud Ugo dengan kata “merasuk di badan” dalam pameran yang berlangsung sejak 20 Desember 2019 hingga 12 Januari 2020 di Galeri Nasional Indonesia ini? Bagaimana bentuk karya yang bisa merasuk ke seluruh tubuh itu? Apakah seperti seri karya di atas?
“Selama proses pameran ini, saya terus berpikir, apa sebenarnya melukis itu, dan seperti inilah hasilnya,” kata pria kelahiran Purbalingga, 49 tahun lalu, itu. Ugo merasa punya tafsir sendiri akan keindahan. Ia menganggap sebuah obyek indah justru bila sederhana: tak terlalu banyak terikat rambu-rambu. Bisa jadi sesuatu yang cantik muncul dari sebercak warna, sebuah garis, atau bahkan titik saja.
Menurut Ugo, sebagian besar dari 70 karya yang dipamerkan adalah hasil perenungannya dua tahun belakangan dalam perjalanan pulang-pergi antara Yogyakarta dan Purbalingga. Banyak hal dan peristiwa melintas di kesehariannya. Sebagian terekam dalam ingatan, tapi ada pula yang tercecer. Karena itu, belakangan ia melambatkan diri, sembari menyelami pikiran dan tubuhnya. Di tengah kecepatan informasi yang terus menggila, Ugo mengaku menemukan kenikmatan melukis tanpa terjebak pada posisi untuk merumuskan makna dalam lukisannya. Ugo membebaskan tangannya bekerja. Ia menganggap tak perlu ada pesan dalam garis dan warna, sebagaimana tak semua selera harus diseragamkan.
Dalam perenungan itu, Ugo berjumpa dan belajar soal Buddhisme. Mungkin, dari literatur-literatur Buddhisme, Ugo mendapat asupan, bagaimana makna itu sesungguhnya sesuatu yang nisbi. Bagaimana makna sejati itu, sebagaimana banyak diungkapkan sutra-sutra esoteris Buddhisme Mahayana, senantiasa mengelak untuk ditangkap. Tapi Ugo tak menjelaskan pergulatannya dengan Buddhisme. Ia hanya menyebutkan Buddhisme berhubungan dengan romantisisme karena sama-sama berusaha mendekatkan manusia dengan alam. Itu yang melatari Ugo membuat seri lukisan Sleeping Buddha.
Salah satu lukisan Sleeping Buddha menggambarkan sepasang kaki besar berwarna tembaga yang komposisinya tidak anatomis, dengan punggung kaki yang memenuhi hampir seluruh ruang kanvas. Sebelah kanan dan kiri kaki yang digambar dengan cat minyak itu terlihat melebur. Tak ada batas-batas spesifik. Sebab, seperti kata Ugo, alam tidak hanya dekat dengan hal yang transenden, tapi juga dengan manusia.
Kurator pameran, Hendro Wiyanto, menyebutkan, “Posisi tidak lagi penting bagi Ugo karena karya-karyanya ini justru pos-isi. Kita hanya perlu menikmati bentuknya secara artistik, tanpa perlu mengarang arti coretannya.” Mungkin baik Ugo maupun Hendro terlalu bermain-main dengan filsafat yang ada dalam benak sendiri, entah itu filsafat Buddhisme entah apa. Dan kemudian konsep filsafat itu digunakan untuk melegitimasi karya-karya yang “ganjil”, di luar kelaziman. Namun memang harus diakui karya-karya Ugo ini menghasilkan pengalaman estetis yang lain. Menurut Hendro, rekonstruksi ala Ugo sesungguhnya pada mulanya sebuah perlawanan untuk membuka rute baru seni rupa di Yogyakarta. Walau sejak 1990-an sampai sekarang tidak ada yang benar-benar baru dalam seni rupa, Ugo berusaha membuat karya-karya yang radikal ala dirinya sendiri.

Rain karya Ugo Untoro dalam pameran “Rindu Lukisan Merasuk di Badan”. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pemberontakan itu sendiri, sebagaimana diceritakan Ugo, tak senantiasa berlangsung dalam suasana diri serba “muram”, “meditatif”, penuh “perenungan”, tapi bisa penuh kejenakaan. Misalnya saat ia membuat bidang baru dari dua lukisan yang seolah-olah membelah: satu miring ke kanan, satu lagi ke kiri. Di tengah dua lukisan yang dipulas kuning itu, ada gumpalan sisa kanvas yang juga diwarnai. Ugo mengaku terkekeh saat membuat sisa kain kanvas menyembul di tengah. Begitu pula, saat ia menorehkan warna kuning dijon yang mentereng, yang menabrak kebiasaan aliran romantisisme yang identik dengan rona gelap, ia terpingkal-pingkal sendiri. “Ini komedi ala saya. Saat membikin ini pun saya ngakak sendiri,” katanya—meski menyaksikan lukisan itu, mustahil kita ikut terkekeh.
Sebuah karya yang dipandang oleh umumnya masyarakat seni rupa sebagai karya instalasi juga oleh Ugo disebut dengan istilah lukisan. Lihatlah karya yang disebut Ugo seri lukisan Rain. Salah satu sudut galeri disulapnya menjadi serupa ruang pamer mobil. Di situ terdapat tiga mobil yang berjajar, dibungkus selubung berwarna putih tulang. Begitu memasuki ruangan itu, kita seperti masuk ke dimensi waktu yang berbeda. Tiba-tiba saja terdengar suara hujan deras. Beberapa pengunjung sampai bertanya satu sama lain, apakah di luar sedang turun hujan. Padahal itu hanya suara hujan yang terputar dari rekaman. Bunyi itu direkam Ugo saat ia sedang berada di Yogyakarta. Ketika itu, hujan turun tak habis-habis, dan lahirlah ide untuk merekam suaranya.
Penyair Sapardi Djoko Damono, yang masyhur dengan puisi Hujan Bulan Juni, suatu ketika mengatakan bahwa hujan ada di luar dirinya. Namun Ugo merasakan sebaliknya. “Hujan ada di dalam saya, dan seperti inilah saat disajikan dalam bentuk painting,” ujar Ugo. Ia menyebutkan hadirnya audio dan obyek tiga dimensi dalam seri Rain ini tidak lantas membuat karyanya menjadi instalasi. “Ini tetap lukisan karena tidak lepas dari unsur garis dan warna.”
ISMA SAVITRI
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo