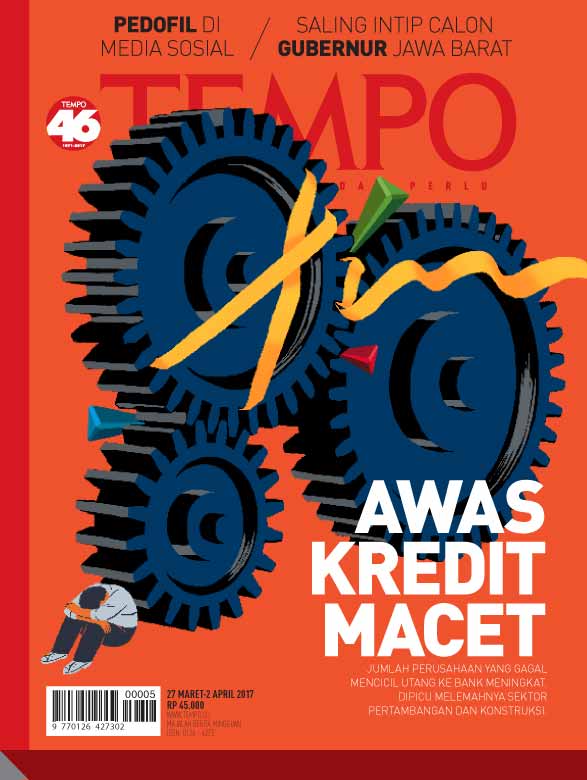Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
SEORANG laki-laki dengan rambut setengah kribo (Djarot B. Darsono) di panggung Teater Salihara terus-menerus menarik tali rafia yang menjulur dari atas. Tubuhnya statis. Hanya tangannya yang bergerak repetitif. Mulutnya menggumamkan kata-kata seperti merapal mantra. Di depannya, enam penari berkebaya model kutubaru menari. Ekspresi mereka tanpa senyum. Lelaki itu hanya melihat mereka. Melihat tanpa menghampiri.
Gerakan para penari itu sendiri-sendiri. Lembut tak beraturan. Sesekali mereka berusaha melakukan simbol kepakan sayap burung yang terbang di antara pepohonan di sekitar rumah. Para penari itu memainkan burung-burung prenjak. Adalah menarik memetaforakan prenjak dengan penari-penari berkebaya.
Tatkala duduk bersimpuh, para penari itu mengangkat semacam potongan bambu. Lubang bambu itu kita lihat memancarkan cahaya. Para penari itu menyorotkan cahaya ke mukanya sendiri dan ke berbagai penjuru ruangan. Mereka terus menari. Dari dalam lubang bambu itu, mereka menarik tali-tali plastik yang panjang.
Sabtu malam dua pekan lalu, Studio Taksu menampilkan garapan teranyar, Burung-burung Prenjak, di Komunitas Salihara, Jakarta Selatan. Lakon ini berkisah tentang priayi tua yang hidup sendiri di rumah bergaya kolonial. Suatu pagi dia duduk di terasnya, memakan semangkuk mi instan ditemani kicauan burung-burung prenjak yang seakan-akan memberi kabar bahwa seseorang bakal datang menjenguk. Ini sesuaidengan kepercayaan masyarakat Jawa tentang ngelmu titen atau firasat.
Namun bukan seseorang yang datang, melainkan kesadaran bahwa lingkungan tempat tinggalnya berubah. Kelompok teater dari Surakarta yang berdiri pada 1995 itu memang kerap mengangkat dampak kemajuan teknologi dan transisi ke masyarakat industri dalam karya-karya mereka.
Dalam ajang Helateater itu, penonton bisa menyaksikan bagaimana para penari tersebut mengubah geraknya. Juga membawa bambu berlubang cahaya dan mengeluarkan tali plastik yang merupakan simbol bagi ranting-ranting yang hilang. "Bagi saya, teknologi itu seperti cahaya. Dia begitu cemerlang dan memikat," kata Djarot B. Darsono, sutradara sekaligus pemeran lelaki tua--yang diandaikan berada di dalam loji itu.
Menurut Djarot, pertunjukan itu terinspirasi oleh puisi "Terbangnya Burung" (1994) karya Sapardi Djoko Damono. Tali rafia yang ditarik Djarot itu merupakan mi instan yang menemani pak tua sepanjang pagi. Gerak para penari yang semula seperti burung menjadi seperti robot, dan sebatang ranting yang bisa bersinar sebagai perumpamaan transisi kayu menjadi mesin.
Mesin-mesin yang digerakkan roda kapitalisme itu yang kemudian menjadi sangat menakutkan, lewat sorotan cahaya di wajah dingin para penari. Atau ketika para penari menghambur-hamburkan mi instan, kritik Djarot terhadap budaya instan kembali menggema. "Itu mi instan paling murah yang saya dapat di pasar. Kalau dimasak di warung, harganya jadi mahal sekali," ujar Djarot.
Tata cahaya yang remang dan suara sayup-sayup burung serta musik minimalis memunculkan suasana intens dalam pertunjukan ini. Tidak ada satu pun dialog sepanjang 55 menit pertunjukan. Djarot, misalnya, sejak awal menggumamkan kata-kata tak jelas mengacu pada vokal pedalaman Papua dan Mongol. Mulanya seperti merapal mantra, tapi semakin lama nadanya berubah, temponya semakin cepat.
Sebenarnya, apabila enam penari berkebaya itu digarap dengan gerak yang menjurus trance atau gerak-gerak ekspresi kesakitan yang menjeram tubuh, tentu kepedihan burung-burung dan kesepian orang tua tersebut lebih terasa. Sebab, gerak repetitif Djarot yang sepanjang pertunjukan hanya menarik tali rafia cukup kuat.
Para penari itu terakhir memukul gong-gong yang tergantung dengan tempo dari lirih kemudian agak keras. Sebelum akhirnya suara rekaman riuh penebangan pohon mengakhiri pertunjukan. Para penari mengakhiri pertunjukan dengan selembar pita plastik kuning bertulisan "do not enter". Pesan yang terakhir tadi terasa jelas: industrialisasi jangan sampai melampaui batas.
Amandra M. Megarani
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo