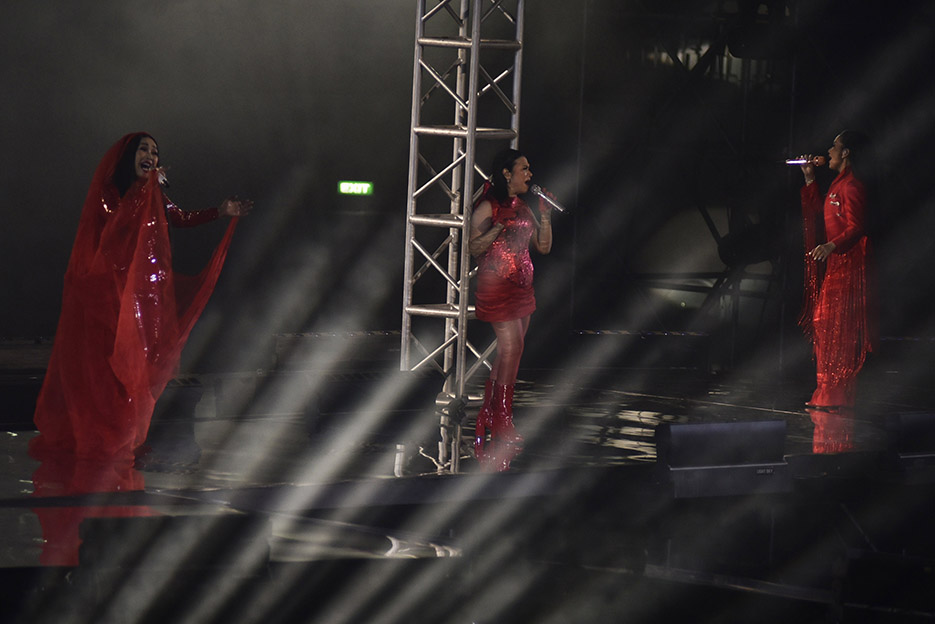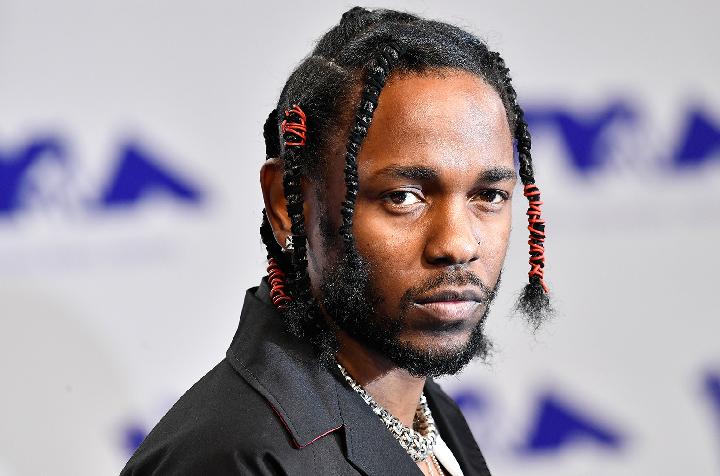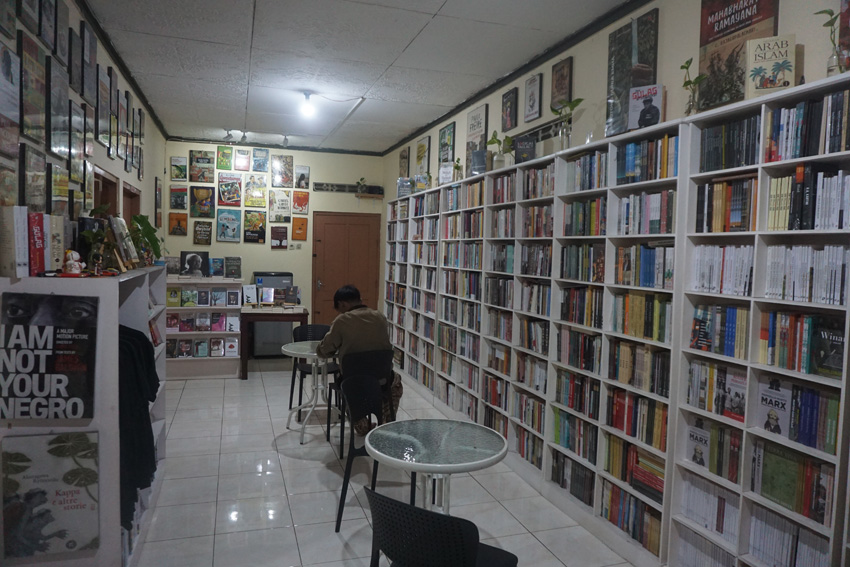THE INDONESIAN ECONOMY DURING THE SOEHARTO ERA.
Penulis: Anne Booth & Meter Mc Cawley (penyunting).
Penerbit: Oxford University Press, Kuala Lumpur 1981, XXVI, 329
hal., index.
BAHWASANYA Pemerintah Orde Baru berusaha sekuat mungkin untuk
memulihkan keadaan ekonomi yang cukup bobrok sebagai warisan
Orde Lama merupakan kenyataan yang tidak mungkin dipungkiri.
Stabilitas ekonomi yang terjamin telah membuahkan "single digit
inflation" selama periode 1969-1971. Ditambah dengan tekad untuk
melaksanakan anggaran berimbang serta ditopang oleh stabilitas
harga selama tahun 1977-1978, maka lengkaplah keyakinan akan
tidak adanya pesimisme dalam neraca pembayaran selama rezim ini
berkuasa.
Tanpa bersikap menggurui Anne Booth dan Peter Mc Cawley
menghimpun berbagai pandangan yang ditulis oleh ahli-ahli di
bidangnya masing-masing dengan tujuan menyoroti kebijaksanaan
ekonomi Orde Baru. Bukan mustahil akan ditemukan berbagai
masalah yang cukup membuat risi seperti, kenyataan bahwa
"absolute poverty" memang tidak bertambah, tetapi orang miskin
masih sangat banyak sementara kebijaksanaan untuk mengangkat
taraf hidup mereka sangat lambat pelaksanaannya. Alasannya,
tidak ada pengarahan bagi kebijaksanaan di bidang tenaga kerja,
sedangkan hal ini penting dalam hubungan dengan masalah
kemiskinan (hal. 319).
Selain itu penekanan pada pendapatan negara lewat pajak tidak
langsung yang akan mengenai golongan penduduk kelas menengah dan
miskin sudah barang tentu memperjauh asas pemerataan. Memang
pajak tak langsung lebih mudah ditarik daripada pajak langsung,
tetapi itu bukan tujuan utama pembangunan mestinya. Namun
begitu, keinginan Orde Baru untuk melakukan pembangunan ekonomi
secara baik tidak perlu disangsikan. Sikap terhadap prioritas
pembangunan ini tampak misalnya dari Pidato Kenegaraan Presiden
Soeharto yang lebih berorientasi pada masalah ekonomi dan bukan
masalah politik seperti sebelum tahun 1966. Bahkan dalam sistem
perekonomian, kita tidak lagi bersikap "inward-looking"
melainkan lebih mengarah pada "outward-looking".
Berbagai masalah tampaknya masih akan membayangi perekonomian
Indonesia di masa mendatang. Dualisme yang belum juga
terselesaikan. Pengusaha pribumi yang masih bersikap priayi
sampai dengan peranan pemerintah yang begitu besar dalam
perekonomian, sebagai warisan sistem kolonial, kelihatannya
masih tetap dipertahankan (hal. 17-19).
Masalah pengangguran dan kemiskinan juga dipersoalkan secara
mendalam. Bahkan tampaknya tema dari buku ini memang mengarah ke
sana. Entah karena penulis bagian ini Anne Booth sendiri (dengan
bantuan R.M. Sundrum) atau memang masalah satu ini yang dianggap
cukup rawan. Selain mempersoalkan sulitnya mendapat data yang
bisa dipercaya untuk menghitung distribusi pendapatan,
kekurangan tanah di Jawa dilengkapi dengan perbedaan pengeluaran
di daerah perkotaan untuk pulau ini, menimbulkan persoalan yang
sering meresahkan para pengambil keputusan.
Kenyataan tersebut mengantarkan pada suatu kesimpulan yang
ditulis secara berani oleh para penyunting Tbe Indonesian
Economy During The Soeharto Era dengan menyebutkan bahwa
Indonesia tidak akan pernah menjadi "welfare state". Alasannya
tingkat kesehatan dan nutrisi rendah, sehingga menyebabkan (dan
juga disebabkan) banyaknya golongan miskin yang semakin
bertambah. Lalu apa jawabannya? Bagian ke-9 yang ditulis oleh
Terence Hall dan Ida Bagus Mantra menekankan pentingnya program
KB dengan mengambil contoh keberhasilan di Jawa dan Bali.
Sementara Leon Mears dan Sidik Moelyono yang menulis bagian
mengenai "Food Policy" menawarkan perubahan dari sekedar Bimas
di Jawa menjadi program ekstensifikasi di luar Jawa. Selain itu
juga perlu dikembangkan strategi yang mengarah pada "spread
commodity risk" daripada "single commodity risk" seperti yang
dilakukan pada saat ini. Dengan demikian cita-cita "food self
sufficiency", dan bukan sekedar "rice self sufficiency" yang
menjadi harapan Orde Baru dapat menjadi kenyataan.
Pada dasarnya buku yang dihimpun oleh Anne Booth dan Peter Mc
Cawley ini menyebarkan harapan, meskipun diselingi
kecemasan-kecemasan di sana-sini. Para penyumbang makalah yakin
bahwa dalam tahun 1980-an masih dapat diharapkan terdapatnya
pertumbuhan dan stabilitas di Indonesia.
Sudah barang tentu beberapa perubahan harus diadakan. Misalnya
saja birokrasi harus lebih dipermudah agar program
industrialisasi dapat berjalan. Dengan kata lain harus dibuat
"industrial infrastructure" daripada keahlian dan kelembagaan
yang menunjang program tersebut (hal. 95-96). Di samping itu
perlu terus dipikirkan bagaimana meningkatkan pendapatan dari
sektor non-minyak, seperti yang menjadi perdebatan dewasa ini.
Perlu diingat bahwa hanya karena "oil boom" di awal tahun
1970-an neraca pembayaran kita membaik. Oleh karena itu perlu
dipikirkan sumber pendapatan yang lain. Salah satu di antaranya
memang sektor perpajakan. Tetapi perlu dicatat bahwa seharusnya
kita bukan sekedar menaikkan pajak, lebih dari itu -- yang
paling penting -- memperbaiki sistem administrasi perpajakannya
(hal. 156-157).
Merupakan suatu pertanyaan mendalam yang dilemparkan buku ini
kepada kita semua menyangkut bagaimana kekayaan dari luar,
khususnya yang masuk akibat berkah minyak, dapat digunakan
sedemikian rupa untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.
Pengertian akan pentingnya pemerataan pendapatan dan pengurangan
kemiskinan sudah merupakan kesadaran bersama. Tetapi karena
diungkapkan sekali lagi dalam buku ini, semakin terasa berhaa
untuk mengkaji kembali pengalaman selama ini. Dan ini pula yang
menyebabkan berbagai karangan yang dihimpun oleh Anne Booth dan
Peter Mc Cawley tersebut menjadi semakin berharga untuk dibaca.
Prijono Tjiptoberijanto
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini