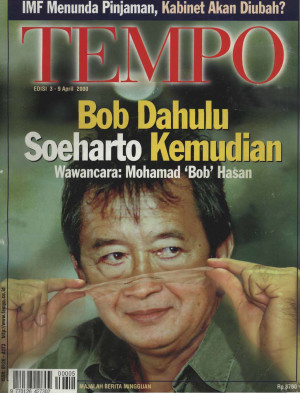Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Secara runut, dari hari ke hari—itu bisa dilihat dari tanggal pengambilan gambar—Amamiya terus bercerita di depan kamera. Lambat-laun tak ada lagi yang menjadi penghalang. Ia pun mengakui keterlibatannya dalam kehidupan lesbian bersama teman sekamarnya. Melalui filmnya, Tsuchiya Yutaka, 34 tahun, sang sutradara, menyuguhkan sebuah "pertentangan" antara dua pandangan: Amamiya sang ultranasionalis yang mengagungkan konsep kekaisaran dengan pemikirannya yang "kiri" progresif. Benturan ide ini kemudian bermuara pada sebuah pertanyaan: siapakah "Tuhan" yang baru di dunia ini?
The New God menjadi salah satu film yang menarik dalam pekan film dokumenter Asia yang diselenggarakan Teater Utan Kayu, Jakarta, akhir Maret silam. Selain tema yang diusung, cara pembuatan film ini pun tergolong unik. Untuk mendapatkan gambar yang kaya dan "ocehan" yang menarik, Yutaka memberi Amamiya sebuah kamera miliknya agar ia merasa bebas berbicara. Upaya itu berhasil. Film ini menjadi penuh warna meski tetap berpijak pada konsep dokumenter yang sesungguhnya, yakni rangkuman perekaman visual terhadap seseorang berdasarkan kejadian nyata dan akurat.
Film dokumenter yang diputar kali ini menyajikan banyak tema. Lina Yang Tian-yi, sutradara Cina, memilih berkelana ke dunia renta tempat tak ada lagi harapan. The Old Men, judul film ini, mengangkat keseharian manusia-manusia tua di Cina yang terbatuk-batuk, tergolek di ranjang, atau jalan terbungkuk.
Tema sosial dan konflik dengan segala dampaknya lazimnya menjadi kekuatan sebuah film dokumenter, seperti yang ditampilkan sutradara India, Anand Patwardhan, melalui dua filmnya: Father, Son and Holy War (1994) dan In the Name of God (1992). Dalam Father, Son and Holy War, Patwardhan, pemenang berbagai festival film, mengangkat konflik abadi antara golongan Islam dan Hindu. Melalui gambar-gambar yang kaya, hasil perjalanannya selama tujuh tahun, Patwardhan menampilkan sebuah dokumentasi yang lengkap tentang akar-akar kekerasan yang bersumber pada budaya partriarkat di sana. Ia tidak hanya sekadar mengabadikan gambar, tapi juga ikut menyatu dengan degup emosi dua kubu yang yang menjadi obyek filmnya. Sebuah film dokumenter yang ideal.
Itu hal yang tidak ditemukan dalam Child of Mermaid arahan Mohd Naguib Razak. Awalnya, film yang berdurasi 10 menit ini mencoba menampilkan kehidupan perajin perahu di Trengganu, pesisir timur Malaysia, yang makin renta digosok zaman. Lewat kumpulan gambar itu, sesungguhnya Naguib cukup berhasil memunculkan atmosfer kawasan tersebut. Namun, dalam upayanya menampilkan dokumentasi, ia kehilangan roh karena sang juragan perahu yang dibidik menjadi tokoh sentral lebih banyak mengunci mulut. "Dia orangnya low profile," kata Naguib. Itu kekurangan yang diakuinya terjadi karena ia tidak memiliki cukup waktu.
Bagaimana dengan film dokumenter sineas Indonesia? Mira Lesmana memilih mendokumentasikan kehidupan Sarinem, figur dari masyarakat kelas bawah di Jakarta, dalam film berjudul Sarinem. Hidup Sarinem dan suaminya yang sulit makin terpuruk dengan kenyataan dua anaknya mengidap talasemia. Mira mengaduk gaya dokumenter dengan sentuhan fiksi, yakni dengan menggunakan skenario dan plot cerita yang memikat.
Demikian pula film Tuti, arahan Riri Reza, yang mengetengahkan sosok Tuti, ibu kandung dari Yani Avri, aktivis yang menjadi korban penculikan. Sebagai film dokumenter, karena tema yang diangkat dekat dengan masyarakat Indonesia, keduanya berhasil menyentuh emosi. Misalnya saat kamera membidik linangan air mata Tuti yang meleleh di kedua pipinya. Kedua film ini dibetot dari kumpulan dokumentasi perubahan yang terjadi di Asia yang bertajuk Wind of Change.
Dari daftar film yang seharusnya diputar, terdapat beberapa yang urung, di antaranya Boys for Beauty, film dari Taiwan tentang relasi gay dengan keluarga di tengah masyarakat Konghucu. Sayangnya, beberapa film pengganti pun bukanlah barang baru, seperti Kabri Wali karya Nan T. Achnas, yang dicuplik dari kumpulan Anak Seribu Pulau, yang pernah diputar serentak di lima stasiun televisi swasta. Namun, film-film yang diputar telah memberikan gambaran sebuah wajah Asia mutakhir.
Irfan Budiman
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo