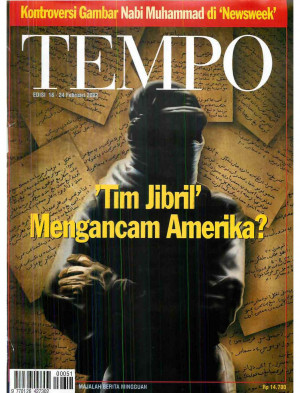SEBUAH pesawat Airbus A-310 rute Jakarta-Denpasar mengalami "patah sayap". Pesawat yang dioperasikan PT Awair International itu tidak bisa beroperasi selama tiga bulan mulai 8 Maret nanti. Yang ini bukan karena mendarat di Bengawan Solo atau tergelincir di tepi landasan. Maskapai penerbangan yang kelahirannya disokong mantan presiden Abdurrahman Wahid itu gagal bersaing dengan maskapai penerbangan domestik lainnya. Bagaimana bisa?
Mulai beroperasi Juni 2000, Awair harus berebut muatan dengan sekitar 15 perusahaan pemain udara. Sudah saingannya banyak, penumpang Awair malah semakin mengkeret. Pada 1996, 13 juta orang yang bepergian dengan burung besi hanya diperebutkan oleh lima perusahaan: Garuda, Sempati Air, Merpati Nusantara, Bouraq, dan Mandala Airlines. Pada tahun 2001, penumpangnya hanya 8 juta orang, tapi dikeroyok oleh pemain lama dan pemain baru seperti Lion Airlines, Bayu Air, dan Awair.
Tiupan angin makin keras menerpa Awair karena salah manajemen. Pesawat Airbus A-320 dan 310 dengan 175 tempat duduk yang menjadi pilihan Awair untuk dipakai, ternyata, tidak efisien untuk diterbangkan di Indonesia. Untuk langit Indonesia, pesawat yang paling cocok adalah pesawat kecil seperti Boeing 737-200 atau Boeing 737-300 yang berkapasitas 100 tempat duduk. Akibatnya, satu pesawat Awair harus diistirahatkan awal tahun lalu. "Airbus A-320 itu sekarang masih nongkrong di Cengkareng," kata Arifin Hutabarat dari Bagian Humas Awair.
Keputusan memarkir satu pesawat tentu saja berimbas pada pendapatan perusahaan, yang jadi berkurang. Sementara itu, argo leasing dan perawatan jalan terus. Setiap bulan Awair harus membayar sewa kepada Region Air, Singapura, sekitar US$ 250 ribu atau senilai Rp 2,5 miliar. Itu harga sebelum tragedi 11 September lalu. Sekarang nilainya membengkak.
Satu-satunya pesawat Awair yang masih terbang pun ikut oleng karena terbebani pengeluaran yang besarnya melebihi biaya untuk pesawat itu sendiri. Hitungannya, setiap pesawat per hari maksimal terbang delapan jam. Selebihnya dipakai untuk perawatan pesawat dengan biaya sekitar Rp 2,8 miliar per bulan. Ditambah asuransi per bulan sebesar US$ 100 ribu atau senilai Rp 1 miliar, plus biaya operasional, total pengeluaran satu pesawat per bulan sekitar Rp 11,5 miliar.
Sisi pendapatan makin tidak bisa diharapkan karena "buruknya cuaca" akibat perang tarif antar-maskapai penerbangan. Perang tarif makin intensif sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan batas maksimum tarif pesawat terbang. Untuk jurusan Jakarta-Surabaya, misalnya, ditetapkan batas maksimal Rp 778 ribu. Karena batas minimumnya tidak ditentukan, maskapai penerbangan mulai obral tarif. "Makin lama, tarif pesawat makin ngawur," kata Arifin.
Awair pun ikut membanting harga agar bisa bertahan. Tiket dari Jakarta ke Surabaya ditekan sampai Rp 400 ribu. Bayangkan, ini hanya berselisih Rp 140 ribu dengan tiket kereta api Argo Bromo Jakarta-Surabaya. Rute Jakarta-Denpasar dan Jakarta-Medan juga dipangkas sampai Rp 600 ribu. Dengan jumlah penumpang, menurut Arifin, rata-rata 50 sampai 60 persen sekali jalan, Awair hanya mampu meraup Rp 9 triliun per bulan. Akibatnya, Awair terpaksa melakukan "pendaratan sementara" dan tidak terbang selama tiga bulan.
Selama penantian, pihak Awair berjanji tidak akan mengurangi jumlah karyawan, apalagi gaji. Hanya, karena pesawatnya tidak terbang, uang saku kru pesawat tidak diberikan. "Waktu tiga bulan kami isi dengan mendidik karyawan agar lebih mengenal pesawat baru yang lebih kecil," kata Arifin.
Gonjang-ganjing semacam itu sebenarnya bukan hanya pengalaman Awair. Menurut Rudy Setyopurnomo, mantan Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association, Lion Airlines dan Kartika Airlines sudah oleng lebih dulu. Namun, mereka cepat mencari pegangan sehingga tidak sampai jatuh. Lion menggandeng Region Air dan Kartika merangkul perusahaan leasing-nya di Malaysia.
Goyahnya maskapai penerbangan itu, menurut Rudy, disebabkan oleh ketidaktahuan mereka tentang pasar. Jurus memberi harga rendah yang mereka tawarkan sebenarnya tak lantas menarik penumpang. Yang terjadi justru sebaliknya. Sebab, hanya 35 persen penumpang yang mempertimbangkan harga pesawat. Selebihnya tak menjadikan harga sebagai pertimbangan. Sebanyak 65 persen penumpang ini lebih melihat fasilitas dan kenyamanan. "Mereka tidak saja naik pesawat, tapi titip nyawa," ujar Rudy.
Menerbangkan pesawat rupanya tidak mudah karena bisnis ini keras, sensitif, dan harus bernapas panjang. "Asal kuat, ya, bisa jalan. Kalau napasnya pendek, alamat akan tutup," kata Direktur Utama Merpati, Wahyu Hidayat.
Agus S. Riyanto
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini