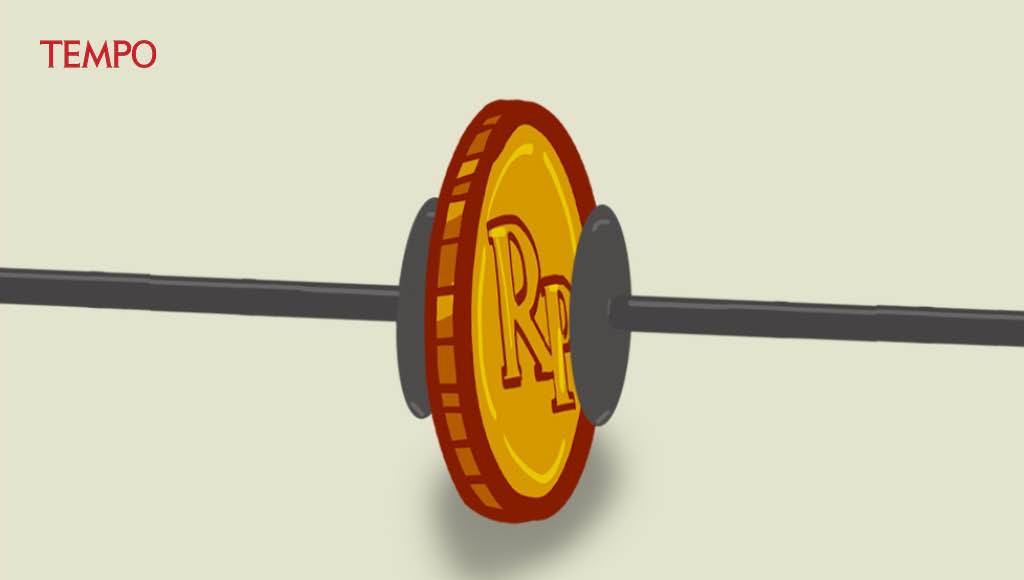PEMERINTAH hari-hari ini tampaknya harus mengeluarkan uang
milyaran rupiah untuk membayar restitusi MPO (Menghitung Pajak
Orang) kepada sejumlah perusahaan. Jika segalanya lancar,
restitusi itu, yang merupakan selisih antara kelebihan
pembayaran MPO dengan PPs (Pajak Perseroan), biasanya dibayarkan
kembali tiap bulan Maret. "Tapi hingga kini restitusi kami
selama dua tahun, meliputi Rp 2 milyar belum juga dibayar," kata
Jim Wiryawan, direktur pemasaran sebuah perusahaan distribusi
terkemuka di Jakarta.
Tunggakan restitusi yang diminta itu, menurut dia, jumlahnya
sama dengan 10% kebutuhan modal kerja tiap bulan. Tidak besar
memang. Tapi di saat kredit modal kerja dari pelbagai bank kini
mahal, dana sebesar itu "berharga sekali," katanya. Distributor
itu baru saja dapat kredit modal kerja dengan bunga 25% dari
Bank Central Asia. Dengan modal inilah, distributor itu -- yang
bertanggung jawab mengedarkan 28 macam produk dari kembang gula
sampai komputer -- antara lain menggaji karyawan, dan mengadakan
stok barang untuk masa 2 sampai 3 bulan.
PT Southern Cross Textile Industry (SCTI), yang antara lain
menghasilkan tekstil Caterina, juga sedang menunggu pengembalian
restitusi MPO yang berasa dari tiga tahun anggaran, sebesar Rp
400 juta. Kyohei Nishimi, manajer SCTI, secara terus terang
mengkritik lamanya jangka pengembalian restitusi itu. Sebabnya
"saya kira sistem birokrasi yang harus dijalani untuk
mendapatkan kembali restitusi itu," katanya kepada wartawan
TEMPO Minuk Sastrowardoyo.
Benarkah karena birokrasi? "Yang jelas ketika saya masih
menjabat menteri keuangan tidak ada instruksi untuk menghambat
pengembalian restitusi itu," kata Ali Wardhana, yang kini Menko
Ekuin dan Pengawasan Pembangunan, pekan lalu. Dia menolak
anggapan keterlambatan itu sengaja dilakukan karena pemerintah
membutuhkan banyak dana rupiah (kekurangan likuiditas). "Nanti
saya akan bicarahn soal ini dengan Pak Salamun (Dirjen Pajak),"
tambahnya.
Kabar dari Ditjen Pajak memang sedang ditunggu. Sebuah
perusahaan pekan ini sudah dijanjikan akan mendapatkan jawaban
mengenai pengembalian restitusi MPO itu dari kantor inspeksi
pajak setempat. "Tapi mungkin saja akan mulur, saya tidak tahu
pasti, sebab minggu ini banyak hari libur," kata salah seorang
direktur perusahaan yang berkantor di Gunung Sahari, Jakarta.
Pada hakikatnya memang MPO merupakan bagian dari PPs, yang
dibayar di muka. Jika penghitungan PPs baru bisa dilakukan
sesudah akhir tahun buku, yang jatuh Desember, maka MPO
biasanya dikutip bersamaan dengan saat penyerahan barang.
Sebuah perusahaan distribusi, yang mengambil barang dari
produsen biasanya dikenai jenis MPO wajib bayar. Besarnya MPO
tersebut untuk perusahaan dagang macam ini, sejak 1 Maret naik
dari 2% jadi 3%. Kenaikan tarif itu dilakukan pula terhadap MPO
impor dan ekspor untuk impor bahan baku dan ekspor hasil
produksi.
PT Unilever, misalnya, berhadapan dengan MPO pada dua proses
dalam usahanya. Pertama, dalam kedudukan sebagai wajib pungut,
perusahaan ini memungut MPO dari distributor ketika penyerahan
barang, yang kemudian disetorkan ke kantor pajak atas nama
distributor bersangkutan. Kedua, Unilever membayar MPO atas
bahan baku yang diimpornya.
Jumlah MPO impor yang dibayar perusahaan multinasional penghasil
pelbagai barang kebutuhan rumah tangga itu, rata-rata setiap
tahun antara Rp 1,2 - 1,3 milyar. MPO impor inilah sesungguhnya
merupakan sebagian pembayaran di muka PPs Unilever. Tahun 1981,
PPs yang harus dibayarnya mencapai Rp 12 milyar. Karena jumlah
PPs ini lebih besar dari pada MPO impor "maka pada kami tak ada
soal restitusi," kata Yamani Hasan, dirut Unilever. Sebaliknya
perusahaan ini setiap akhir tahun tentu harus membayar
kekurangan PPs, yang sudah dicicilnya dengan MPO. "Walaupun kami
jelas menghadapi MPO pada dua tahap usaha, menurut saya, itu
bukan merupakan pajak berganda," tambah Yamani.
Yang sering jadi perdebatan antara pengusaha dan pihak pajak
adalah mengenai besarnya PPs, yang harus dibayar wajib pajak.
Pihak pajak yang berpikir kritis, lazimnya menghendaki
pemeriksaan keuangan suatu perusahaan dilakukan oleh akuntan
publik, yang diakui pemerintah, misalnya, SGV Utomo. Tapi
pengusaha yang sengaja berusaha mengelakkan petugas pajak,
biasanya menghindari pemeriksaan itu dilakukan oleh akuntan
publik. Kalaupun petugas menghendaki koreksi atas laporan
keuangan itu, pengusaha macam ini lebih suka 'tahu sama tahu'
dengan memperkecil perolehan laba untuk menekan PPs yang harus
dibayarnya.
Bagi perusahaan seperti Unilever, yang sudah go public, karena
pembukuan terbuka, penghitungan PPs itu tidak sering menimbulkan
persoalan. Tapi bagi perusahaan yang belum go public, koreksi
kadang diminta pula oleh petugas pajak sekalipun pemeriksaan
keuangan sudah dilakukan akuntan publik. "Kami sudah memakai
jasa SGV Utomo, tapi pihak pajak ternyata masih juga meminta
laporan keuangan kami (ikhtisar rugi-laba, dan neraca tahunan)
dikoreksi," kata seorang direktur perusahaan distribusi. Cara.
demikian, kalau benar sungguh memperlambat proses pemasukkan
pajak ke kas negara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini