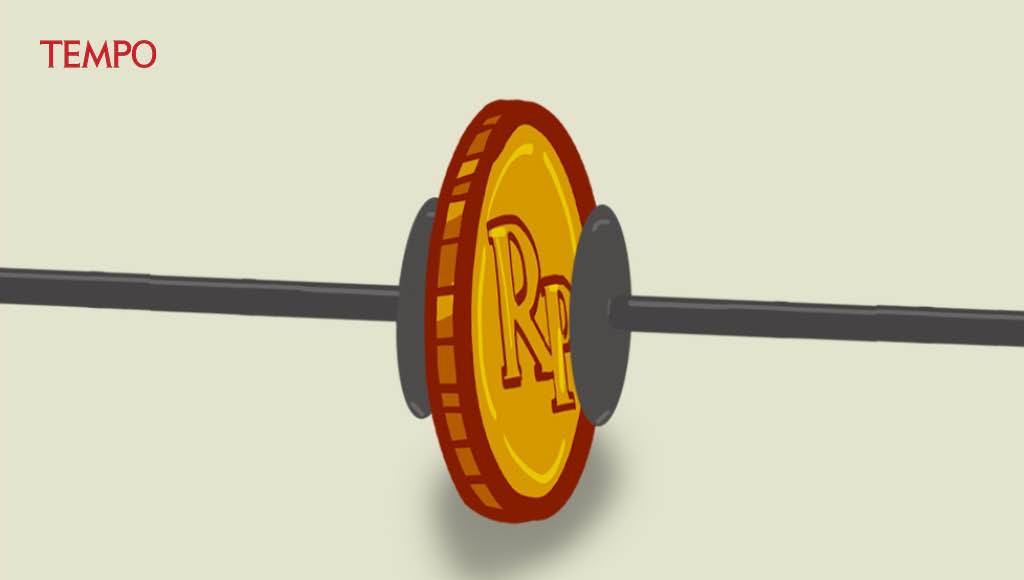Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
KANTUK menggorok Karti. Pedagang kelontong berusia 45 tahun di Pasar Cempaka Putih, Jakarta Pusat, itu terkulai bersandar di penyangga warungnya. Sesekali ia bangkit mengusir lalat yang merubung dagangannya. ”Pelanggan saya nyebrang,” katanya kepada Tempo, Selasa siang dua pekan lalu.
Di seberang yang ditunjuk Karti menjulang ITC Cempaka Mas, dua kilometer ke utara dari tempatnya duduk. Di sana orang berjubel. Pendingin udara kalah bersaing dengan hawa tubuh manusia. Sementara lorong-lorong Pasar Cempaka Putih lengang-lengau. Hanya pedagang yang mengobrol atau bergelimpangan di bangku panjang.
Karti dan teman-temannya tak menerima berkah menjelang Lebaran. Penerimaannya malah turun 50 persen dari hari biasa—yang itu pun sudah anjlok separuhnya lagi dibanding tiga tahun lalu.
Ketika itu ITC dan Carrefour di sebelah timur belum buka. Karti bisa membawa pulang Rp 3 juta sehari. ”Sekarang paling banter Rp 500 ribu,” kata pedagang yang sudah berjualan sejak 27 tahun silam itu. Tapi ia maklum, di ITC atau Carrefour barang lebih murah karena grosiran. Harga sebotol sirup saja bedanya Rp 600.
Pertarungan tak imbang membuat pedagang pasar terpuruk. Jumlah pasar tradisional menyusut 8 persen per tahun. Pada 1995, pasar tradisional di Jakarta masih 159. Sepuluh tahun kemudian jumlahnya tinggal 151. Dalam waktu yang sama, hipermarket dan supermarket bertambah 200 unit, menjadi 449.
Orang Indonesia yang royal belanja menjadi target gurih peretail besar. Menurut survei AC Nielsen, orang kita pergi ke pasar 24 kali dalam sebulan, paling sering di Asia. Jauh di atas kebiasaan orang Singapura, yang cuma lima kali sebulan.
Tahun lalu, duit yang berputar di pasar mencapai Rp 437,1 triliun—sama dengan penerimaan pajak—naik seratus persen dari 2001. Duit itu paling banyak berputar di pasar tradisional, dengan Rp 322,3 triliun. Tapi, pertumbuhannya lambat dibanding pasar modern, yang menangguk omzet Rp 80 triliun, naik 34 persen setiap tahun.
Data itu kian membuat risau Ibih Hasan, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI). Jika tak ada tindakan serius dari pemerintah sebagai pemilik, ”Umur pasar tradisional tak sampai sepuluh tahun lagi,” katanya. Ketika APPSI merayakan ulang tahun ke-2 di Senayan, Juni lalu, Ibih mengungkapkan kecemasannya di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Ia minta draf peraturan presiden tentang penataan pasar modern segera disahkan. Peraturan Menteri Perdagangan No. 107/MPP/Kep/2/1998 tak bertaji mengawasi pasar modern. Ratusan mal dan pusat belanja asing berdiri di kawasan pasar tradisional sejak 1997.
Padahal, retail besar harusnya didirikan di luar radius 2,5 kilometer dari pasar becek. Di Jakarta kini ada 50 pasar tradisional yang lokasinya berada dalam lingkar hipermarket. Menurut Ibih, setiap pasar menampung sekitar seribu pedagang.
Beleid itu nantinya mengatur tempat pendirian hipermarket. Tak boleh mematikan pasar tradisional atau berlokasi di permukiman. Izin pemerintah daerah baru dikeluarkan jika sudah ada studi dampak lingkungan. Hipermarket juga diwajibkan menjual 70 persen produk dalam negeri dan bermitra dengan pemasok kecil. ”Kami setuju dengan peraturan itu,” kata Handaka Santosa, Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia.
Ia optimistis aturan itu tak akan menghambat pasar modern yang bakal tumbuh 25 persen tahun depan. Tapi, ia menampik jika dikatakan pihaknya membunuh pedagang kecil. Tumbuhnya retail besar, kata Handaka, karena diminati pembeli. ”Ini seleksi alam di pasar,” katanya.
Agar persaingan berlangsung sehat, Handaka menyarankan pemerintah daerah menyerahkan pengelolaan pasar tradisional ke swasta. Ia menunjuk pasar di Bumi Serpong Damai, Puri Indah, dan Kelapa Gading, yang dikelola pengembang, bisa nyaman dan tetap hibuk kendati dikepung rimba beton retail besar.
Agaknya permintaan itu belum akan digubris. Pasar, dengan retribusi dan pungutan lain, masih menjadi andalan pendapatan pemerintah daerah plus nilai aset Rp 65 triliun. Pedagang seperti Karti, yang membayar Rp 116 ribu per bulan, menyumbang Rp 200 miliar ke kas pemerintah Jakarta.
Bagja Hidayat
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo