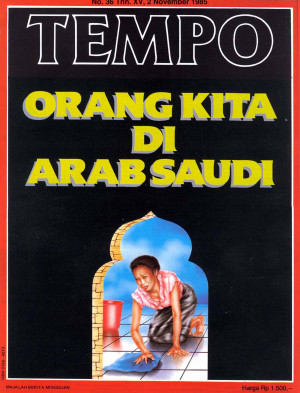AMERIKA tampaknya berhasil mengangkat keruwetan industri tekstil di sebuah daerah kecil menjadi persoalan banyak negara. Bayangkan, hanya karena ada 100 ribu buruh tekstil kehilangan pekerjaan di wilayah Georgia dalam empat tahun terakhir, 12 negara Asia sampai mengancam akan melakukan perang melawan Washington. Padahal, dari kawasan yang tumbuh paling pesat ini, volume perdagangan Amerika mencapai US$ 160 milyar setahun. Suasana panas menentang usaha AS melindungi industri tekstilnya dengan RUU Jenkins belum tampak di Jakarta. Tapi, pekan lalu, pertemuan ke-34 APCAC (Dewan Kamar Dagang Amerika se-Asia Pasifik) di Jakarta sengaja memasang tema cukup panas: membendung gelombang proteksionisme. Proteksi terhadap industri tekstil Amerika, tentu saja, jadi salah satu pokok pembicaraan menarik 17 delegasi kamar dagang itu. Mereka, yang mewakili penanaman modal Amerika sebesar US$ 30 milyar di kawasan ini, merasa prihatin dengan makin banyaknya pemunculan RUU proteksionistis. Dalam resolusinya kemudian, APCAC tetap menentang setiap bentuk rancangan untuk mengontrol masuknya tekstil dan produk tekstil impor, baik dalam cara pengenaan kuota maupun penghalang lain yang akan melanggar perjanjian bilateral dan multifiber arrangement. Suara APCAC menentang segala bentuk proteksi sudah mulai diperdengarkan Maret lalu, ketika mereka bertemu di Singapura. Salah satu rancangan yang banyak disebut di situ adalah tentang keharusan mobil-mobil impor menggunakan komponen bikinan Amerika dalam jumlah tertentu. Jika ketentuan itu tidak dipenuhi, maka semua mobil asing yang masuk ke Amerika akan kena bea masuk tambahan 25%. Dewan ketika itu sudah beranggapan, rancangan tadi bersifat counterproductive, dan akan mengundang pembalasan. Kalangan pengusul rancangan, tentu, punya alasan ketika mengajukan bentuk penghalang itu. Pada dasarnya, menurut penglihatan Menko Ekuin Ali Wardhana, ada dua alasan pokok yang mereka ajukan: soal kesempatan kerja dan defisit perdagangan. Mereka menduga hilangnya kesempatan kerja banyak disebabkan oleh membanjirnya barang impor, dan untuk memulihkannya penghalang perlu didirikan. "Langkah ini sebenarnya hanya akan makin mempersulit persoalan," katanya ketika membuka pertemuan APCAC itu. Menurut Menko Ali Wardhana, sukses penjualan pakaian jadi di pasar Amerika adalah karena eksportir menanggapi keinginan konsumen, dan bisa memberikan harga bersaing untuk barang berkualitas. Ancaman nyata buat Amerika bukanlah defisit perdagangan yang tahun ini diduga akan menggelembung jadi US$ 150 milyar, melainkan proteksionisme itu sendiri. Katanya, mengutip penelitian New York Federal Reserve Bank, pengenaan kuota dan bea masuk pada tekstil dan pakaian jadi, tahun lalu, menyebabkan konsumen harus mengeluarkan US$ 8-12 milyar. Defisit perdagangan, kalau soal itu dijadikan alasan sponsor, memang banyak mencerminkan terpukulnya industri Amerika di pasar internasional. Ekspor tekstil negeri ini, misalnya, diperkirakan akan turun dari US$ 3,6 milyar di tahun 1980 jadi US$ 2,5 milyar tahun ini. Sedang ekspor pakaian jadi turun dari US$ 1,2 milyar di tahun 1980 jadi US$ 800 juta tahun lalu. Juga ekspor pelbagai barang bikinan General Electric, pada periode yang sama, anjlok dari US$ 4,3 milyar jadi US$ 3,9 milyar. Penyumbang defisit terbesar kocek perdagangan Amerika, siapa lagi, kalau bukan Jepang. Dengan negeri ini, tahun lalu, defisit perdagangannya tercatat US$ 37 milyar dan tahun ini diduga akan mencapai US$ 50 milyar. Menurut Jerry L. Loupee, Presiden Amcham Taiwan, "Kalau diperhatikan betul, sasaran (300 RUU) proteksi sebenarnya Jepang." Negara-negara berkembang, yang mengharapkan bisa memperoleh dolar untuk mencicil utang mereka, ternyata ikut kesrempet. Padahal, perdagangan tekstil dan bahan baku antara Indonesia dan Amerika misalnya, hampir seimbang. Menurut Menmud Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Ginandjar Kartasasmita, tahun lalu ekspor tekstil dari sini US$ 280 juta (Departemen Perdagangan menyebut US$ 234 juta). Dari Amerika, Indonesia membeli kapas senilai US$ 150 juta dan bahan penolong US$ 75 juta. "Kedua negara sesungguhnya sama-sama memetik keuntungan," katanya. Baik Menko Ali Wardhana maupun Menmud Ginandjar sama-sama mengingatkan rencana menggolkan RUU Jenkins itu akan mengingatkan orang pada peristiwa 45 tahun lalu. Memang benar, diterimanya RUU SmootHawley yang proteksionistis ketika itu, bisa menyulap defisit menjadi surplus. Tapi dalam perjalanannya, tiga tahun kemudian, volume perdagangannya turun 26%. "Dan dunia terjebak dalam depresi," kata Menko Ali Wardhana. Kembalinya situasi menyakitkan itu, tentu, tak diingini semua negara. Untuk memperbaiki perdagangan Amerika, Menko Ali Wardhana punya beberapa usulan. Daripada mempromosikan proteksionisme, Amerika dianjurkan lebih baik mempromosikan perundingan perdagangan bilateral dan multilateral. Usaha menstabilkan sistem moneter internasional, dengan memperlemah nilai dolar, perlu dilakukan terus. Katanya, salah satu langkah penting memperkuat ekonomi Amerika adalah mengurangi defisit APBN, dengan menaikkan pajak. Sementara itu, APCAC kelihatan lebih suka jika pemerintah (Exim Bank) membantu menyediakan pembiayaan murah bagi pengusaha untuk mengekspor barang mereka. Rencana Presiden Reagan menyediakan US$ 300 juta untuk kredit ekspor agaknya banyak didukung. "Salah satu usaha Presiden adalah berupaya mendidik agar pengusaha Amerika bisa memanfaatkan kesempatan di pasar internasional," ujar Warren Williams, Presiden APCAC. Eddy Herwanto Laporan Bambang Harymurti & Yulia S. Madjid (Jakarta)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini