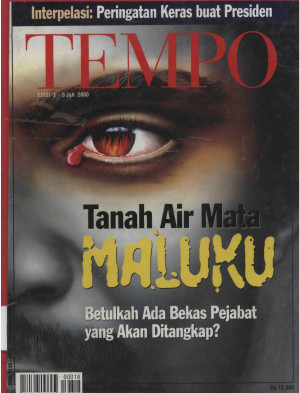Sampailah kita pada bagian tersulit: bagaimana membereskan sisa-sisa. Setelah emas dan kuningan habis terjual, kini tiba saatnya berurusan dengan loyang dan besi-besi tua….
Tampaknya, itulah yang dihadapi pemerintahan Gus Dur, ketika mengumumkan rencana penjualan aset-aset konglomerat yang "disita" pemerintah, akhir pekan lalu. Setelah bersusah payah melepas saham BCA dan pabrik mobil Astra International, kini pemerintah harus menguangkan saham perusahaan "kelas dua".
Menurut Kepala Bagian Penjualan Aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Dasa Sutantio, dalam dua bulan ke depan pemerintah akan menjual pabrik susu Indomilk, pabrik roti QAF, konglomerasi First Pacific, pabrik granit Karimun, dan gedung Wisma BCA. Setelah itu, akan segera menyusul pabrik kayu Kiani, pabrik ban Gadjah Tunggal, tambak udang Dipasena, gedung-gedung milik Grup Cakrawala, serta saham di perusahaan perkebunan.
Dibandingkan dengan BCA dan Astra, deretan perusahaan itu ibarat emas dengan kuningan. Jika BCA emas, Wisma BCA loyangnya. Jika Astra daging has, pabrik susu Indomilk tulang-belulangnya. Jika Astra dinilai pasar pada harga US$ 2,25 miliar, tak banyak di antara perusahaan itu yang dihargai lebih dari US$ 500 juta.
Tampaknya, di situlah letak persoalannya: jika melepas saham Astra dan BCA saja begitu sulitnya, bagaimana pula dengan nasib penjualan saham perusahaan-perusahaan kelas dua ini?
Semula BPPN bermaksud menambal kekurangan itu dengan menjualnya secara borongan. Baik atau buruk, besar atau kecil, aset-aset itu dikumpulkan dan ditawarkan dalam satu paket kepada para investor. Ketika menjajakan BCA akhir tahun lalu, Kepala BPPN Cacuk Sudarijanto menantang para investor Singapura. "Jangan cuma membeli Astra," katanya, "kalau berani kumpulkan dana sindikasi, saya berikan perusahaan apa pun yang kalian mau."
Tantangan Cacuk itu sempat disambut. Temasek Holding, salah satu perusahaan investasi milik pemerintah Singapura, sempat membentuk sindikasi. Mereka mengumpulkan dana dari sejumlah investor yang ingin mengincar perusahaan-perusahaan milik Salim. Tapi, apa mau di kata, tawarannya terlampau rendah. Aset Salim yang nilainya ditaksir sampai US$ 10 miliar cuma ditawar US$ 3 miliar.
Dengan siasat serupa, gedung-gedung milik Usman Admadjaya (Grup Danamon) juga sempat ditawar oleh sekelompok investor properti dari Singapura. Tapi, sebagaimana aset Salim, penawarannya juga masih terlampau rendah. "Mereka pasang harga semaunya. Diterima syukur, ditolak juga tidak rugi," kata seorang pejabat BPPN kesal.
Menghadapi persoalan itu, tampaknya BPPN mulai banting setir dengan menjual aset-aset itu secara ketengan. Memang akan muncul risiko. Aset-aset yang jelek, mungkin karena prospeknya kurang cemerlang atau terancam bangkrut, akan sulit laku—atau setidaknya ditawar dengan harga rendah. Tapi, untuk mendapat hasil yang maksimal, BPPN tampaknya sudah punya siasat: menjual semua aset itu dalam sebuah tender yang terbuka dan fair.
Melihat pengalaman penjualan Astra, tender terbuka sebenarnya tak menjamin hasil yang maksimal. Semula, ketika dijajakan secara diam-diam ke beberapa investor tertentu yang berminat, saham Astra ditawar konsorsium Newbridge Asia dan Global Equity Partners dari Amerika Serikat, dengan harga Rp 3.750. Tapi, setelah tender dibuka lebar-lebar, saham Astra malah cuma laku Rp 3.700. Konsorsium Newbridge yang semula berani call tinggi ternyata malah cuma mengajukan harga Rp 3.400.
Selain transparansi, persoalan paling rumit dari penjualan harta konglomerat itu akan bermuara pada satu hal: bagaimana menetapkan nilai secara wajar. Sebagai perusahaan yang sudah tercatat di pasar modal, pabrik roti QAF (Singapura), pabrik ban Gadjah Tunggal (Indonesia), dan konglomerasi multiusaha First Pacific (Hong Kong) tampaknya tak akan memicu banyak keributan soal nilai wajar ini. Ukurannya gampang. Tinggal melihat harga sahamnya di bursa Singapura, Jakarta, dan Hong Kong. Jika pemerintah berhasil menjual di atas harga pasar, masyarakat tentu sudah merasa lega.
Tapi bagaimana dengan perusahaan-perusahaan nonpublik yang selama ini menutup laporan keuangannya rapat-rapat? Penilaian harga wajar Wisma BCA, pabrik susu Indomilk, pabrik granit Karimun, properti milik Cakrawala, dan tambak udang Dipasena tentu akan memancing silang pendapat yang sangat seru.
Pertentangan soal nilai tambak udang Dipasena bisa menjadi gambaran yang jelas, betapa jauh selisih perhitungan nilai wajar itu. Sjamsul Nursalim bersama audit keuangan ternama yang disewanya dari luar negeri sepakat, nilai tambak udang terbesar di Asia Tenggara itu Rp 20 triliun. Tapi Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Kwik Kian Gie, bersama tim audit ulang dari BPPN ngotot menilai Dipasena tak lebih dari Rp 2 triliun. Pertanyaannya, dengan selisih bagaikan bumi dengan langit itu, berapa nilai wajar Dipasena.
Perdebatan nilai wajar ini akan menjadi sangat genting karena hasil penjualan aset-aset konglomerat akan menentukan jumlah pendapatan negara. Pada akhirnya, sukses-tidaknya penjualan perusahaan ini akan menentukan besar-kecilnya tambahan utang luar negeri yang harus diminta pemerintah untuk menambal defisit anggaran. Selain itu, perhitungan nilai wajar juga menjadi penting karena aset-aset konglomerat itu pada dasarnya sudah menjadi milik bersama, milik rakyat, yang hasil penjualannya akan menentukan nasib rakyat banyak.
Harus diakui, selama ini disposal aset konglomerat tidak bisa dibilang sukses. Tender penjualan Astra, misalnya. BPPN hanya berhasil menjualnya pada harga Rp 3.700, ketika jauh hari sebelumnya publik dan para analis memperkirakan nilai saham Astra bisa mencapai sedikitnya Rp 4.000. Penjualan BCA, yang dilepas melalui penawaran umum, juga sama saja. Semula, saham BCA diperkirakan bisa dijual pada harga dua kali nilai buku (modal bersih), tapi ternyata cuma laku 0,8 nilai buku.
Selain transparansi dan perdebatan nilai wajar, disposal perusahaan-perusahaan kelas "loyang" ini juga akan menghadapi ancaman yang menyangkut perusahaan-perusahaan kroni seperti industri kayu terpadu Grup Kiani. Bukan tak mungkin, di perusahaan yang pernah punya hubungan "luar-dalam" dengan kekuasaan seperti itu, akan banyak ditemui transaksi misterius yang sulit diungkap.
Apa yang terjadi pada Astra bisa jadi contoh. Perusahaan yang manajemennya terkenal bersih ini belakangan ketahuan memberikan pinjaman di bawah meja Rp 400 miliar kepada komisarisnya (Bob Hasan). Bayangkan, perusahaan sekelas Astra bisa menyembunyikan transaksi misterius sebesar itu selama bertahun-tahun dari mata publik dan akuntan. Bagaimana pula dengan Kiani, yang tidak cuma bukan perusahaan publik, melainkan juga bertahun-tahun hidup berkat koneksinya dengan kekuatan politik.
Tampaknya, Kepala Perwakilan Dana Moneter Internasional, John Dodswoth, benar. Penjualan aset di BPPN merupakan satu dari tiga problem ekonomi terbesar di Indonesia. Apalagi jika aset-aset itu bukan lagi emas, tapi loyang dan kuningan….
Dwi Setyo
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini