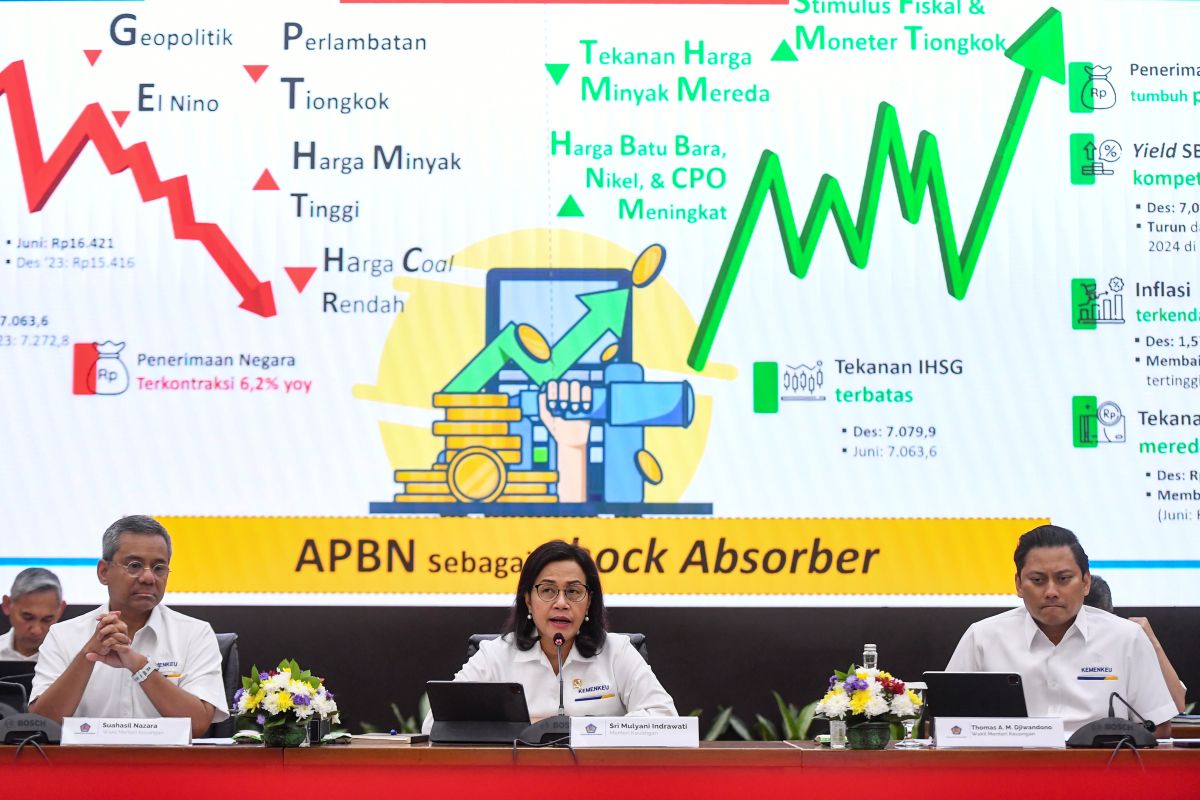HARGA minyak mencapai puncak tertinggi dalam tiga belas tahun terakhir: US$ 25 per barel. Padahal, tahun lalu si emas hitam itu terjun bebas di posisi US$ 9 per barel. Begitu buruknya harga tahun lalu itu, sampai tak seorang analis pun berani meramal harga tahun ini lebih dari US$ 15 per barel. Anggaran belanja Indonesia pun disusun dengan patokan harga minyak US$ 10,5 tiap barel.
Indonesia, dan semua negara anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC), harus berterima kasih kepada Rilwanu Lukman, Sekjen OPEC, atas sukses menjaga kuota. Pasokan minyak tahun ini dipatok hanya 87 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau ada negara yang berniat melanggar kuota, "Saya segera datang membujuk presidennya," kata Lukman. Sebenarnya, bujuk rayu saja tak cukup. Iklim dunia yang lebih cerah ikut mendorong harga itu. Permintaan minyak melonjak akibat mulai menggeliatnya aktivitas ekonomi di berbagai negara yang terkena krisis.
Nah, pasokan juga susut akibat ngambeknya Irak. Dua pekan lalu, Saddam Hussein mengancam menghentikan produksi bila embargo Amerika dan sekutunya tidak dicabut. Kontan, para petinggi negara maju—konsumen energi paling lahap—kebat-kebit. Harga minyak pasti melambung dan memacu inflasi gila-gilaan. Data Strategic Petroleum Reserve menunjukkan, setiap 10 persen kenaikan harga minyak berpotensi memacu 0,25 persen indeks harga konsumen di AS. Ramalan bahwa minyak bisa meroket sampai US$ 30 per barel tentu amat menakutkan.
Untungnya, para produsen minyak juga tak berminat ngebut memacu harga. Irak mencabut ancaman. Maklumlah, bila inflasi melonjak, daya beli konsumen dan perekonomian Amerika langsung turun, dan ujungnya gerak perekonomian dunia juga melambat. "Kami tak mau hal itu terjadi," kata Lukman, yang menegaskan bahwa kerja OPEC adalah mencari keseimbangan. Harga tetap berkibar tetapi tidak membahayakan perekonomian dunia.
Bagi Indonesia, kinclongnya minyak juga berwajah ganda. Yang merugikan, ongkos subsidi BBM terdongkrak. Tahun ini, APBN menganggarkan subsidi BBM Rp 9,9 triliun dan ternyata melambung sampai dua kali lipat akibat kenaikan harga. Sebagian besar subsidi digunakan untuk mengimpor minyak mentah—karena produksi minyak lokal langsung diekspor.
Namun, akibat yang menguntungkan, pundi-pundi negara memang menggelembung. APBN 1999/2000, misalnya, mematok penerimaan dari minyak dan gas Rp 21 triliun. Namun, realisasinya, minyak dan gas mengalirkan duit sampai Rp 44 triliun. Tentu saja, ini kabar gembira di tengah dahsyatnya pengeluaran, terutama menyongsong anggaran tahun depan yang lebih berat. Cicilan utang luar negeri, misalnya, mencapai US$ 5 miliar. Pemerintah masih harus menyediakan Rp 56 triliun—paling sedikit—untuk membayar bunga obligasi program rekapitalisasi perbankan. Belum lagi bila PLN kalah bertarung di arbitrase internasional, denda US$ 572 juta harus dibayar ke perusahaan pemegang proyek listrik swasta yang dibatalkan.
Beban ini bisa makin berat bila muncul beragam tuntutan. Gaji pegawai negeri sipil, jika mengikuti usul DPR, harus naik 100 sampai 300 persen. TNI pun tak ketinggalan. Panglima TNI Laksamana Widodo A.S. meminta anggaran militer enam persen dari total APBN. Artinya, anggaran militer naik 2-3 persen dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya. "Untuk kesejahteraan prajurit," kata Widodo.
Namun, dengan perekonomian yang seret, tampaknya tuntutan itu tak bakal terwujud semuanya. Itu pun dengan catatan berat, "Hanya mungkin jika ada pemangkasan subsidi," kata Menteri Keuangan Bambang Sudibyo. Soal ini memang sudah ada dalam letter of intent (LoI) antara pemerintah dan IMF—keduanya sepakat memangkas subsidi BBM dan listrik. Cuma, detail pemotongan masih dirundingkan, termasuk reaksi pemangkasan subsidi itu. Pihak yang kontra mencemaskan timbulnya ledakan sosial. Karena naiknya BBM pasti menyeret harga komoditas lain dan membebani masyarakat luas. Ujungnya, inflasi yang melonjak sanggup meletupkan keresahan sosial.
Namun, yang setuju subsidi dikurangi atau bahkan dihapus beranggapan bahwa subsidi itu selama ini salah alamat. Bambang Kusumanto, petinggi Badan Analisa Keuangan dan Moneter (BAKM) Departemen Keuangan, mencontohkan ihwal solar. Tahun lalu, solar disubsidi Rp 10,7 triliun atau 42 persen total subsidi BBM. Padahal, yang menikmati adalah pemilik mobil mewah atau pengusaha yang sengaja beralih menggunakan mesin bertenaga solar. Pos solar inilah yang paling mungkin dipangkas. Sebab, komponen solar hanya 3 persen dari seluruh ongkos produksi. Sehingga, kalau dihapus total, solar hanya membebani 6 persen ongkos produksi. "Jauh lebih kecil ketimbang komponen ongkos produksi seperti iklan," kata Bambang.
Sesungguhnya, ada alternatif lain: melarang pengusaha besar memakai pembangkit bertenaga solar—konsumsi terbesar solar dalam negeri. Bukankah dengan begitu industri kecil yang juga memakai solar akan tertolong? Namun, rupanya, pemerintah sudah sampai pada keputusan: biarpun minyak berkibar, subsidi harus dibonsai.
Mardiyah Chamim, Agus Riyanto, Dewi Rina, Leanika Tanjung
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini