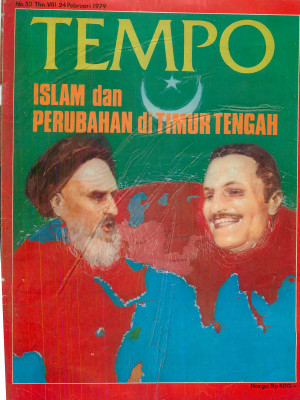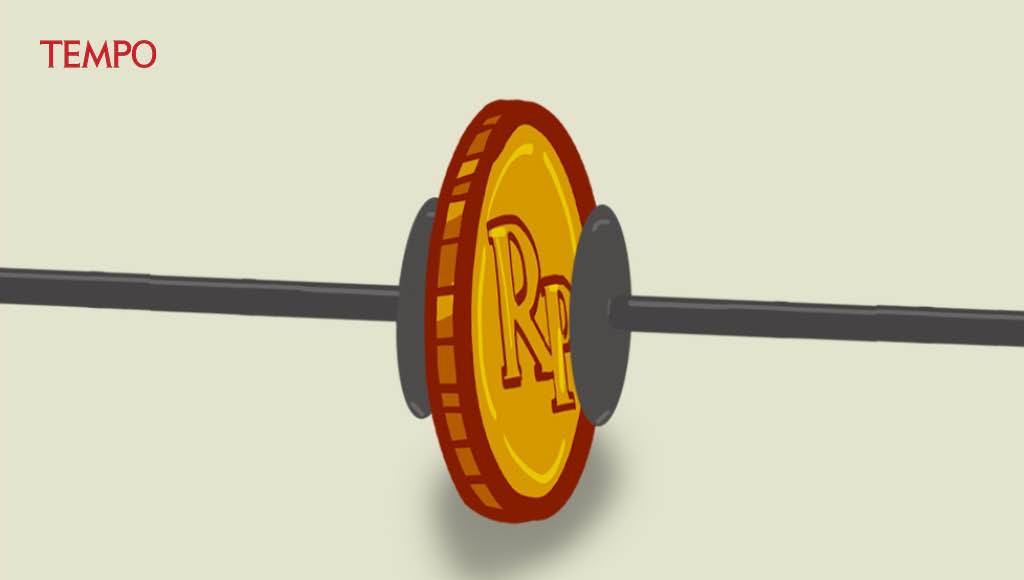JANCAN takut! Itu ucapan WakiI Presiden Adam Malik kepada
wartawan tiga pekan yang lalu. Dalam suasana kehidupan pers di
Indonesia seperti sekarang, pesan bekas wartawan Adam Malik itu
rupanya dimaksudkan untuk memberanikan pers mengungkapkan kritik
dan fakta yang selama ini setengah disembunyikan. "Takut apa,
memangnya ada setan ? " tanya Adam Malik.
Bagi banyak kalangan pers, ucapan Wakil Presiden ditanggapi
sebagai lelucon segar saja. Tokoh karikatur Kompas yang pintar
itu muncul esoknya menjawab Adam Malik. "Sungguh mati, pak Adam,
saya tidak takut sama setan konvensionil .... tapi sama setan
yang doyan ayam goreng."
Banyak wartawan nampaknya skeptis terhadap anjuran "jangan
takut" seperti itu. Beberapa pejabat penting, misalnya,
sebelumnya juga pernah mengatakan pers bebas menulis, asal itu
fakta. Namun dalam kenyataan para pemimpin redaksi kadang
menerima telepon dari kalangan pemerintah, agar tidak memuat ini
atau itu.
Memang dering telepon sensor ini relatif jarang. Tak setiap
bulan terjadi. Tapi toh bisa mengganggu -- karena kadang
membingungkan dan sebenarnya tak perlu.
Pangkopkamtib Sudomo kepada para pemimpin redaksi se-lndonesia
yang hadir di Jakarta untuk "Penataran P4 (Pedoman Penghayatan &
Pengamalan Pancasila") pekan lalu ternyata dengan terbuka
mengecam cara-cara larangan lewat telepon itu. Ia sendiri lebih
suka memanggil para wartawan, untuk diberi penjelasan serta
alasannya bila suatu berita dianggap tak boleh dimuat.
Sudomo, yang sehari-hari memang hampir tak pernah mengambil
jarak dari wartawan, ingin memberi contoh. Rasa saling percaya
antara penjaga keamanan dengan para wartawan agaknya diharapkan
tumbuh, sehingga pers tidak cuma dengan rasa terpaksa saja
mengikuti sensor -- yang sebenarnya ditiadakan oleh
Undang-Undang Pokok Pers. Tapi dalam kenyataan saling percaya
dan saling pengertian itu belum terjadi. Misalnya, pihak
wartawan jarang diberi kesempatan untuk menjelaskan, kenapa
suatu berita sebaiknya tak usah dilarang muncul.
Para pejabat memang? apalagi di daerah, umumnya tak hendak
dibantah. Mungkin karena kedua pihak belum biasa beradu
argumentasi secara leluasa. Tapi mungkin karena para wartawan
biasanya sudah menyadari posisinya yang lemah -- hingga lebih
baik akur saja dengan suatu larangan atau "himbauan" dari atas.
Padahal, keputusan seperti itu belum tentu sesuatu yang
bijaksana.
Apa boleh buat, 'kan SIT bisa dicabut? Dan ketakutan akan
dicabutnya SIT memang umumnya membayangi hampir setiap
penanggungjawab koran atau majalah. Sebab pencabutan SIT
merupakan suatu ancaman yang berat, dan kurang adil bila sebuah
penerbitan dimatikan, banyak orang tak bersalah yang bekerja di
penerbitan itu ikut jadi korban. Mereka ini seperti sandera.
Lagipula media yang ditutup itu tak dijamin untuk terlebih dulu
dapat kesempatan membela diri atau naik banding. Bahkan seperti
sejumlah koran yang ditutup tahun 1974, mereka tak bisa hidup
lagi.
Pemerintah sendiri tetap menganggap perlu keharusan sebuah
penerbitan mempunyai SIT. Dulu memang adanya keharusan ber-SlT,
seperti tercantum dalam Undang-Undang Pokok Pers, merupakan
keharusan masa transisi -- yang seharusnya sudah berakhir
setelah tahun 1971, setelah pemilu pertama. Tapi kini rupanya
ada pertimbangan lain. Kontrol pemerintah terhadap pers memang
p.lling efektif dengan melalui SIT.
Di samping itu, seperti dikatakan Menteri Penerangan Ali
Moertopo di depan para pemimpin redaksi pekan lalu, pada
dasarnya SIT hanyalah alat untuk mengembangkan pers nasional
supaya "ada keseimbangan". "Bukan bermaksud pemberangusan," kata
Menteri pula.
Ali Moertopo memang beberapa tahun yang lalu pernah dikutip
mengatakan bahwa baginya kemerdekaan pers adalah "mahkota" Orde
Baru. Harus diakui memang salah satu ciri pokok Orde Lama adalah
pers yang tidak bebas.
Boleh Kritik
Tak akan adakah kelak pembrangusan pers lagi? Belum pasti. Tapi
Presiden Soeharto mendapat tepuk tangan yang hangat, dan Menteri
Ali Moertopo yang duduk di sampingnya tersenyum. Ketika itu di
depan para pemimpin redaksi ia berkata jelas agar pers tak perlu
was-was "jika menyiarkan segala bentuk penyelewengan dan
ketidak-beresan dalam masyarakat, termasuk dalam tubuh aparatur
negara." Juga, kata Presiden, "tidak perlu ragu-ragu dalam
melontarkan kritik kepada pemerintah, baik yang di pusat maupun
yang di daerah."
Tentu saja, seperti ditambahkan segera oleh Kepala Negara, asal
kritik itu disampaikan dengan tanggungjawab. Harus diakui bahwa
pers bisa tanpa pikir panjang mengobarkan rasa permusuhan antar
kelompok agama atau ras. Bahkan ada yang atas nama "kritik"
melakukan pemerasan. Masalahnya ialah bagaimana kontrol terhadap
pers tak cenderung terperosok ke arah tindakan yang semena mena
-- seperti tempo hari.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini