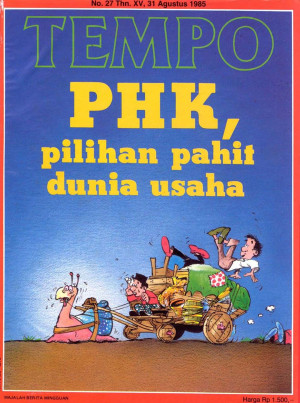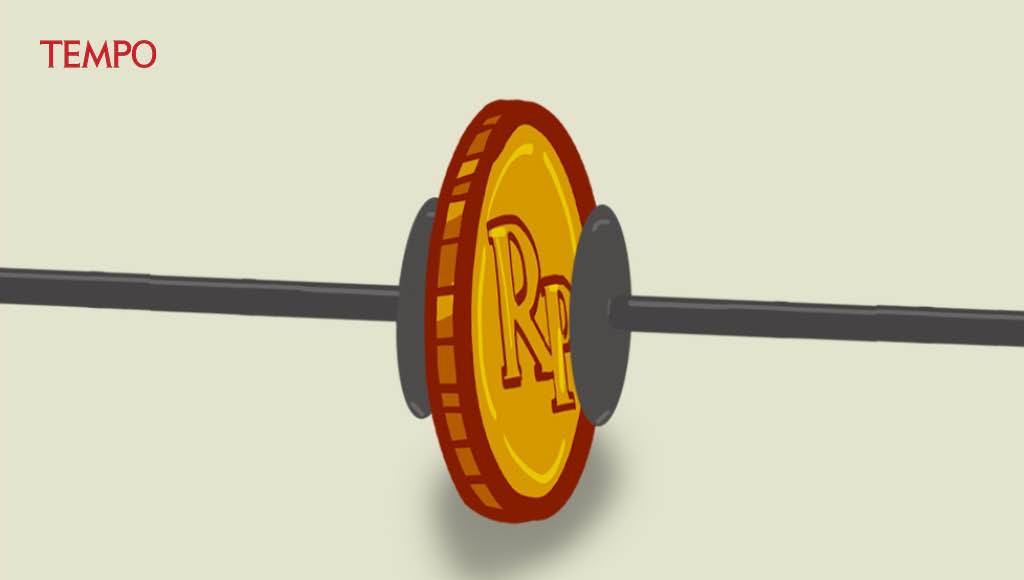BERITA hangat minggu-minggu ini tentang pemutusan hubungan kerja (PHK). Dan yang paling mengundang polemik adalah sikap Menteri Tenaga Kerja Sudomo, pekan lalu, ketika menyetujui pemecatan 700-an buruh PT United Can di Cengkareng - mereka dianggap bersalah karena menyandera sejumlah staf dan karyawan perusahaan, pada Maret 1984. Pemecatan ratusan buruh dari sebuah perusahaan itu, tampaknya, merupakan angka PHK terbesar tahun ini. Menurut catatan Depnaker, sejak Januari sampai Agustus, sudah 11 ribu buruh kehilangan pekerjaan karena, terutama, perusahaan mereka turun penjualannya. Kelesuan ekonomi, memang, jadi biang keladi lebih dari 90 ribu buruh yang kehilangan pekerjaan sejak 1982. "Dalam situasi seperti ini, sulit bagi pengusaha untuk menghindari PHK," seperti kata Iwan Jaya Azis, ekonom dari FE UI. Pihak Depnaker memperkirakan angka pemecatan itu akan makin menggelembung. Permohonan untuk melakukan PHK sebagian besar, agaknya, masih akan datang dari sektor industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, serta bangunan. Tiga sektor ini, memang, paling berat menahan pukulan resesi dunia, dan terhitung kurang gesit menyesuaikan diri mengimbangi lesunya permintaan pasar lokal. Tahun lalu saja. PHK dari ketiga sektor ini mencapai 18.500 atau hampir 85% dari angka pemecatan saat itu, baik karena kontrak sudah selesai mau pun lantaran perusahaan tutup. Sektor industri pengolahan, yang selama tiga Pelita memberikan sumbangan cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi, ternyata mempunyai dasar tidak begitu kukuh. Sebab, menurut Prof. Hendra Esmara, sektor ini masih banyak bergantung pada bahan baku dan penolong impor. Kata guru besar perencanaan pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas ini, sektor industri pengolahan juga tidak begitu efisien, berbiaya tinggi, dan padat modal. "Sehingga ketika terjadi resesi banyak yang ambruk," katanya. Siapa yang salah ? Mungkin pengusahanya sendiri. Atas permintaan sebagian besar penanam modal di sektor ini, memang, pemerintah memberikan perlindungan cukup besar kepada mereka. Menurut Iwan Jaya Azis, proteksi diberikan dengan mengenakan bea masuk tinggi terhadap barang-barang impor sejenis yang sudah bisa dihasilkan oleh industri lokal. Kemudian dengan sistem pembatasan impor (kuota). Dia mengibaratkan sektor industri ini bayi yang selalu digendong dan disuapi. "Sampai tua akhirnya bayi itu tidak bisa jalan sendiri, apalagi bisa bekerja efisien," katanya. Industri Pengolahan Yang terdengar paling awal terpukul di sektor ini adalah industri tekstil. Penjualan tekstil dan pakaian jadi di pasar lokal dan luar negeri mendadak mulai terasa macet di tahun 1982 lalu karena daya beli lemah dan negara pembeli memperketat kuota. Puluhan ribu buruh serta-merta terlempar dari puluhan industri tekstil di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Usaha menolong mereka, dengan melakukan restrukturisasi modal dan teknologi, ternyata hanya sampai di ruang-ruang seminar. Menurut sebuah tafsiran kasar, lebih dari 20 ribu buruh tersingkir dari sini. Kredit macet yang harus ditanggung bank-bank pemerintah, yang banyak menyalurkan pinjaman murah, makin menggelembung. Sebuah bank pemerintah, misalnya, dikabarkan punya utang macet di GKBI di atas angka Rp 20 milyar. Pengambilalihan manajemen kemudian banyak dilakukan bank pemerintah untuk mengatasi kemacetan penjualan itu. Toh, tidak menolong. Sebuah industri produk tekstil, yang baru awal tahun ini diresmikan pengoperasiannya, mendadak saja harus merumahkan lebih dari 100 karyawannya. Pande Radja Silalahi, pengamat ekonomi, tidak setuju dengan cara pengusaha mengatasi kelesuan dengan PHK. Kalau mereka ingin menekan biaya produksi, katanya, hendaknya jangan buruh yang selalu dikorbankan. Soalnya, persentase upah dari seluruh biaya produksi pada sektor industri pengolahan di sini rendah sekali. "Rata-rata hanya 11% dari seluruh biaya produksi," katanya. Menurut catatan Biro Pusat Statistik (BPS), upah tenaga kerja setiap buruh di tahun 1982, pukul rata, hanya Rp 700 ribu setahun, atau sekitar Rp 58 ribu sebulan. Di sektor industri tekstil, misalnya, upah setiap buruh per tahun hanya Rp 473 ribu, atau hanya sekitar Rp 39 ribu sebulan. Dengan angka-angka itu, Pande ingin menunjukkan bahwa tindakan PHK, yang dilakukan untuk menekan biaya produksi, tak akan banyak menolong. Pada tahun 1982 itu, sektor industri pengolahan mencatat perkembangan paling buruk: hanya tumbuh 1,2% - dengan kata lain sumbangannya terhadap produk domestik bruto cuma naik dari Rp 1.877 milyar jadi Rp 1.900 milyar. Salah satu bidang usaha lain, yang terpukul telak di tahun itu, adalah perakitan alat-alat berat. Penjualan alat-alat berat berangsur menurun setelah pemerintah, mulai 1980, melarang ekspor kayu gelondongan dari sini. Sesudah itu, volume pembangunan proyek-proyek besar juga mengendur. Sejak 1982 itu sampai tahun lalu, penjualan alat-alat berat Komatsu, misalnya, rata-rata turun 35%. Kata B. Subianto, presiden direktur PT United Tractor, penjualan Komatsu (buldozer, wheel loader, hydraulic excavator, dan motor grader), tahun ini diduga hanya akan 400 unit - sama dengan tahun lalu. Titik impas sudah bisa dicapai perusahaan ini jika bisa menjual 350 unit. Karena itu, perusahaan menganggap tidak perlu melakukan perumahan maupun PHK 1.700 karyawannya. Tapi penghematan tetap perlu dilakukan: membatasi jam lembur, menghapus uang bensin, dan meniadakan minuman kopi bagi karyawan. Usaha menaikkan penjualan produk industri ini akan sangat bergantung pada maju mundurnya sektor industri bangunan - bukan pada penebangan kayu (logging). Tapi, PHK cukup besar sudah dilakukan perakitan mobil dan motor (automotif). Dari perakitan motor saja sudah lebih dari 1.000 orang disingkirkan. Maret lalu, kedua bidang usaha ini minta izin pada Menteri Sudomo mem-PHK-kan 3.000 pekerjanya. Permintaan PHK paling besar tampaknya datang dari grup Harapan, agen tunggal dan perakit motor Yamaha. Sesudah dua tahun perusahaan itu merumahkan 1.060 karyawannya, PHK akhirnya diperbolehkan untuk sekitar 500 buruhnya saja. Dengan buruh yang sekarang masih 2.100 orang itu, efisiensi penuh masih belum bisa dilakukan. Menurut Soetrisno, direktur grup Harapan, masa kerja efektif mereka sesungguhnya hanya tiga hari saja, "Itu pun masuknya dibikin giliran, dan bagi yang tidak kerja paling-paling kebagian membersihkan pabrik, atau ikut penataran P4," katanya terus terang. Karena lesunya penjualan, dua bulan lalu, mereka pernah libur penuh selama dua minggu. Di antara para perakit motor, Harapan tampaknya masih cukup mujur, apalagi dibandingkan dengan perakit Binter, yang sampai menjual usahanya kepada kelompok Suzuki. Penjualannya tahun lalu hanya 60 ribu, padahal kapasitas perakitan Yamaha adalah untuk menghasilkan 200 ribu motor - dan baru bisa mencapai titik impas jika merakit 100 ribu per tahun. Penjualannya mulai terasa melorot setelah harganya naik gara-gara rupiah didevaluasikan. Tahun ini, harapannya untuk bisa menaikkan penjualan di Pedesaan dianggap gagal. "Produksi beras memang meningkat, tapi pendapatan petani tidak," ujar Soetrisno. Sialnya lagi, persoalan yang harus dihadapi bukannya makin ringan. Sekarang biaya produksi mereka lebih tinggi gara-gara mesin yang biasanya diimpor utuh kini harus dirakit dari komponen yang terurai. Mereka juga diharuskan mengimpor baja lewat PT Giwang Selogam, yang harganya lebih tinggi dan pengirimannya sering terlambat. PT Federal Motor, agen tunggal dan perakit motor Honda, juga menghadapi persoalan serupa. Hanya saja dibandingkan Yamaha, penjualannya tahun lalu cukup bagus: bisa 150 ribu. Belum ada satu pun dari 1.300 karyawannya yang dipecat. Kendati demikian, mereka sering hanya disuruh masuk kerja dua sampai tiga hari per minggu. Dengan cara bagitu, anak perusahaan Astra ini bisa menghemat pengeluaran perusahaan untuk membeli susu dan kacang hijau. Sekalipun pengaruhnya terbatas, serangkaian tindakan penyesuaian itu cukup lumayan dalam menekan pengeluaran. Memang, persoalan yang dihadapi bidang usaha otomotif cukup berat dibandingkan yang lain. Para penanam modal di sini misalnya, dikenai kewajiban untuk menanggalkan secara berangsur pemakaian komponen impor - hingga pada suatu saat nanti semua komponen yang digunakan merupakan bikinan lokal. Kewajiban itu mereka sambut dengan rasa optimistis manakala di tahun 1981 penjualan mobil dan motor mencapai puncaknya tak lama sesudah Indonesia mendapat rezeki besar dari kenaikan harga minyak. Tapi, tahun berikutnya penjualan mulai terasa menciut, setelah mobil berbahan bakar solar harus naik karena pajak penjualannya dinaikkan cukup tinggi. Pukulan berikut datang lagi, sesudah kenaikan harga tak bisa dihindari gara-gara devaluasi rupiah, dan pemerintah memperketat pembelian. Mulailah bidang usaha otomotif memasuki masa paling suram. Padahal, yang namanya proteksi tak kurang-kurang: dalam bentuk bea masuk tinggi bagi mobil yang diimpor secara utuh. Menurut taksiran kasar Bank Dunia, bidang usaha otomotif ini, tahun lalu, sesungguhnya menerima subsidi terselubung sekitar Rp 187 milyar - dalam bentuk tingginya bea masuk bagi barang impor dan infrakstruktur. Soal proteksi berlebihan, yang mendorong banyak bidang usaha jadi tidak efisien itu, kini sering dibicarakan para ekonom. Prof. Sumitro Djojohadikusumo, pekan lalu, kembali menyinggung soal ini dalam acara wisuda program M.B.A. di kampus Institut Pengembangan Manajemen Indonesia, Jakarta. Kata ekonom kawakan ini, pada tahap belajar, proteksi terhadap industri lemah memang bisa diterima. Secara bertahap hendaknya perlindungan ini dicabut, untuk memasuki tahap efisiensi ekonomi. Menurut catatan Prof. Sumitro, kadar proteksi cukup tinggi diberikan pemerintah untuk barang-barang konsumsi final dan hasil rakitan, tapi rendah sekali untuk bidang usaha yang menghasilkan barang modal serta bahan baku dan penolong. Situasi ini akhirnya mendorong investor menggunakan lebih besar modal dengan sedikit buruh. "Struktur dari proteksi itu merangsang menanamkan modal di sektor usaha dengan potensi terbatas dalam menyediakan lapangan kerja bagi buruh Indonesia," katanya. Bidang usaha otomotif dan elektronik agaknya bisa digolongkan dalam anggapan itu karena mendapat perlindungan cukup menyeluruh dalam menghadapi barang impor. Terbukti kemudian, cara seperti itu tidak menyebabkan bidang usaha tadi bisa bersaing - kecuali kalau mereka mencoba melakukan ekspor seperti ditempuh kelompok perusahaan National Gobel. Kata Jamien Tahir, wakil presiden direktur National Gobel, "PHK bukan merupakan jalan terbaik untuk mengatasi kesulitan pasar." Usaha menekan biaya produksi dilakukan kelompok ini dengan memperketat pemakaian dana. Pembelian komponen juga dilakukan semakin selektif: artinya, jika ada komponen lebih murah di Singapura dibandingkan mengambil di Jepang, "Maka kami beli yang di Singapura," kata Jamien. Usaha-usaha seperti itulah yang menyebabkan National tak melakukan PHK, bahkam tahun ini merencanakan menambah 60 karyawan. Gaji juga akan dinaikkan. Tidak semua bidang usaha di sektor industri pengolahan memang harus memecat buruh karena penjualannya loyo. PT Aneka Karya di Ceper, Jawa Tengah, misalnya, cukup sibuk melayani pesanan membuat sambungan pipa air minum dari baja tuang tahan karat (cast iron pipe fittings). Menurut H.M. Husnun, direktur utama Aneka Karya, tahun ini ada kenaikan pesanan 10% dibandingkan tahun lalu. Karena itu, perusahaan ini, yang bermula sebagai usaha kecil-kecilan, kini tiap bulan menghabiskan 80 sampai 100 ton besi tuang. Salah satu pelanggan tetapnya adalah Perusahaan Air Minum Jakarta. Usaha ekspornya sudah dimulai ke Sri Lanka, dan ke Malaysia sedang dirintisnya. Pekerjanya 105 orang. Husnun sudah merencanakan membangun pabrik kedua yang akan menghasilkan komponen serupa yang lebih piawai. Tentu saja jumlah industri macam begini tidak banyak. Buktinya, pertumbuhan industri pengolahan di luar pengilangan minyak dan pengolahan gas alam cair, tahun lalu, hanya 5,6%. Sedangkan pertumbuhan industri gas alam cair mencapai 33% lebih. Jadi, kalau tahun lalu pertumbuhan sektor industri pengolahan mencapai 12,8% (tahun 1983 hanya 2,2%), bukan berarti sektor ini baik-baik saja adanya - mengingat kenaikan terbesar ternyata berasal dari bidang usaha pengolahan gas alam cair yang padat modal. PT Bukaka Teknik Utama merasakan betul arti rendahnya pertumbuhan ini. Perusahaan pembuat mesin-mesin konstruksi dan kendaraan khusus itu, tahun ini, diperkirakan hanya akan mendapat volume pekerjaan 40% dari omset tahun lalu yang Rp 15 milyar. Sekitar 80% dari hasil produksinya dijual ke pemerintah. Kendati volume penjualannya menurun hebat, Bukaka tak berniat memecat 500 karyawannya karena khawatir jangan-jangan akan mendapat pesanan besar mendadak. Konsekuensinya, uang yang keluar belakangan lebih besar dibandingkan yang masuk. Menurut Fadel Muhamad, direktur Bukaka, perusahaan itu kini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda akan menggerogoti laba ditahan tahun lalu untuk menutup kebutuhan modal kerjanya. Diversifikasi usaha dalam kondisi begitu jauh dari harapan sekalipun usaha membuat rice mill plant sudah mulai coba-coba dilakukannya. Bisnis Bukaka, seperti juga bisnis sektor industri bangunan, biasanya sangat peka menghadapi perubahan kebijaksanaan pemerintah. Pendapatan mulai terasa mengecil ketika, Maret 1983, harga minyak OPEC turun dari US$ 34 jadi US$ 29 per barel. Usaha menghemat lewat APBN mulai terasa dilakukan pemerintah. Beberapa proyek besar, yang memakai dana campuran rupiah dan valuta asing, ditangguhkan. Rem semacam itu perlu diinjak agar neraca pembayaran tak mendapat tekanan, dan inflasi di dalam negeri tak meledak karena pembiayaan proyek itu akan berasal dari pencetakan uang baru - bukan dari dana masyarakat. Langkah pengetatan memang cukup luar biasa. Transaksi berjalan pada neraca pembayaran 1984-1985, yang semula diproyeksikan defisit sekitar US$ 4 milyar, hanya defisit US$ 1,9 milyar. Kecilnya defisit itu bisa dicapai karena impor barang konsumsi dan penolong dikendalikan cukup ketat. Secara keseluruhan neraca pembayaran tahun anggaran lalu bahkan bisa menyumbang tambahan devisa US$ 667 juta. Inflasi juga hanya 3,6%, padahal sebelumnya sampai 12,6%. Tapi ketatnya pemerintah mengawasi neraca pembayaran dan pemakaian anggarannya ini berakibat luas: beberapa bidang usaha sektor industri pengolahan terpukul cukup telak. Bidang usaha alat-alat berat, misalnya, menurun tajam volume penjualannya. Bagaimanapun, "APBN 'kan masih mempengaruhi ekonomi kita 30%," ujar pengamat ekonomi Pande Radja Silalahi. Pande beranggapan, dalam keadaan tingkat konsumsi yang tidak bergairah serta pengusaha juga dihinggapi lesu darah, sebenarnya pemerintahlah yang mempunyai kekuatan untuk memperbaiki suasana. Caranya: lancarkan arus dana. Dia yakin, ada masalah yang bisa diatasi di dalam negeri. "Ekonomi kita lain, keterbukaan paling-paling hanya 60%, jadi tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh fluktuasi perubahan ekonomi dunia," katanya. Nada serupa juga dikemukakan pengamat ekonomi Kaptin Adisumarta. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, menurut dia, yang menendang bola pembangunan bagaimanapun masih pemerintah. Jika pemerintah tega, bisa dicari akal dengan, misalnya, menswastakan sejumlah badan usaha milik negara. Dana yang sudah diinvestasikan, seperti untuk TVRI, hendaknya di manfaatkan seoptimal mungkin. "Pada jam tertentu, misalnya, bisa dipakai oleh swasta, terutama untuk promosi," katanya. Dengan cara begitu, TVRI bisa menutup anggaran keperluannya dan pendapatan pemakalan jam siaran untuk swasta. Lewat acara promosi itu secara langsung media elektronik ini berusaha merangsang terciptanya permintaan, tanpa harus menginjeksikan rupiah. "Ini kalau negara berkembang mau belajar," katanya. "Belajar itu sekali-sekali perlu loncat keras." Di pihak lain, Prof. Sumitro beranggapan - seperti dikemukakannya di IPMI - kebanyakan negara berkembang menganut kebijaksanaan memperbaiki ekonomi negerinya melalui perbaikan perdagangan dan transaksi berjalan. Untuk memperbaiki neraca perdagangan, mereka melakukannya dengan memotong barang-barang impor. "Sekitar tiga perempat bagian dari usaha memperbaiki neraca perdagangan merupakan usaha mengurangi impor," katanya. Memang pada akhirnya tindakan semacam itu akan memperbaiki transaksi barang dan jasa (transaksi berjalan) tapi pengaruh perbaikannya secara mendasar sesungguhnya kecil. Langkah penting yang dilihat Prof. Sumitro adalah melakukan penyesuaian struktural dengan menggeser komposisi produksi dan permintaan untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi ketergantungan impor. Tipe perubahan semacam ini dianggapnya lebih mendasar dan bukan sekadar perbaikan temporer. Sektor Pertambangan dan Penggalian Sejak harga patokan OPEC turun dari US$ 34 jadi US$ 29 per barel, mulai Maret 1983, kegiatan di sektor penambangan minyak kelihatan menunjukkan tanda-tanda mengendur. PHK di beberapa penyedia jasa penambangan minyak mulai terdengar. Sekarang jumlah pekerja di kontraktor-kontraktor masih sekitar 20 ribu, termasuk 1.225 tenaga kerja asing. Pertamina, yang mempekerjakan 50.300 orang, tak terdengar melakukan PHK. Lesunya kegiatan penambangan minyak itu juga tercermin dalam bentuk pengeluaran seluruh perusahaan minyak yang, tahun lalu, hanya US$ 2.890 juta dari rencana US$ 3.951 juta. Padahal, pengeluaran tahun sebelumnya masih mencapai US$ 3.953 juta. Karena prospek harga dan pasar minyak masih belum kencang juga, untuk tahun ini pengeluaran diperkirakan hanya akan sampai US$ 3.872 juta. Semua perkembangan kurang menggembirakan itu, tentu saja, berpengaruh cukup besar bagi penyedia jasa semacam Medco (Meta Epsi Drilling Company). Perusahaan yang menyediakan jasa pengeboran dengan menyewakan tujuh rig miliknya itu kini terpaksa berani tawar-menawar untuk mendapatkan calon penyewa. Sewa rig sekarang hanya US$ 8.000 per hari, padahal pada tahun 1983 masih US$ 12.000. "Dulu Pertamina dan kontraktor asing tidak pernah menawar," ujar Arifin Panigoro, direktur utama Medco. Menurunnya pendapatan sewa rig itu cukup merepotkan Medco. Sebab, cicilan tiga di antara tujuh miliknya - yang dibelinya dengan kredit US$ 5 juta sebuah - masih belum lunas. Beban bunga sebesar 10,5% per tahun atas pinjaman itu menyebabkan Medco harus menyisihkan US$ 2.000 untuk setiap rig per hari guna membayar bunganya saja. Tahun lalu, tujuh rig milik Medco, entah mengapa, tidak didatangi penyewa. Praktis cuma menganggur dimakan angin. Dalam situasi seperti itu, perusahaan masih menganggap tidak perlu melakukan PHK. Arifin merasa sayang jika tenaga-tenaga yang punya keterampilan khusus itu harus dipecat. "Satu saja dari mereka berkurang, pekerjaan bisa pincang," katanya. Dia optimistis, jasa pengeboran masih akan diperlukan. Tentu, bukan hanya karena kegiatan pencarian minyak lesu, maka pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian di tahun 1983 hanya 1,8%. Di tahun sebelumnya, bahkan, pertumbuhannya minus 12,1%. Jatuhnya harga timah dan nikel pada periode itu memang menyebabkan sumbangan devisa dari dua bahan galian utama itu jadi mengendur. PHK dari kegiatan penambangan timah dan nikel memang cukup besar. Lazimnya, sebelum sebuah perusahaan melakukan tindak PHK, pengusaha dan serikat buruh berunding untuk mengurangi biaya produksi - dengan mengurangi jam lembur. Jika cara itu masih dianggap belum bisa menekan pengeluaran, maka jumlah regu kerja dikurangi. Kalau masih belum berhasil, sebagian karyawan lalu dirumahkan, hingga sampai pada tindakan PHK. "Pengambilan keputusan PHK merupakan jalan terakhir setelah melalui titik paling sulit," ujar Sutopo Yuwono, sekjen Depnaker. Untuk memastikan benar tidaknya perusahaan menghadapi kelesuan, laporan keuangan perusahaan jika dianggap perlu akan diperiksa Depnaker. Kalau laporan keuangan itu sudah diperiksa akuntan publik, pemerintah akan percaya 100%. Sektor Bangunan Tahun lalu, pertumbuhan sektor bangunan minus 1,5%. Di tahun sulit seperti itu sektor ini paling banyak babak belur menghadapi pengetatan anggaran pemerintah dan neraca pembayaran. Dan serangkaian kebijaksanaan itu sudah cukup membikin kontraktor kecil di daerah menggelepar bagai ikan masuk bubu. Mereka yang kegiatan usaha konstruksinya bergantung pada kantung pemerintah, jelas tidak bisa berkutik. Karena uang yang mengalir ke masyarakat berkurang, otomatis penjualan rumah tanpa fasilitas BTN mengendur - apalagi di tahun itu orang sedang gandrung menyimpan dolar lantaran nilainya cenderung menguat melawan rupiah. Penjualan rumah PT Puteraco Indah di Bandung, misalnya, kuartal pertama 1985 rata-rata hanya tujuh buah setiap bulan. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu masih bisa mencapai 18 rumah setiap bulan. Turunnya penjualan rumah berharga Rp 15 juta sampai Rp 20 juta dengan kredit tiga tahun di Jalan Soekarno-Hatta itu, tentu, cukup memprihatinkan. Sebab, titik impas penjualan baru dicapai jika penjualannya setahun bisa 120 rumah. Mohamad S. Hidayat, presiden direktur Puteraco, jadi salah tingkah menghadapi semua persoalan itu. Di saat pendapatan berkurang, perusahaan dilarang mem-PHK-kan karyawan. Dalam situasi seperti itu yang bisa dilakukan perusahaan adalah mengurangi sejumlah tunjangan yang diberikan pada karyawan. "Mereka ternyata menerima," katanya. Sejak berdiri 1972, Puteraco hingga kini sudah membangun 1.100 rumah. Keadaan lesu akhirnya memaksa perusahaan ini menangguhkan rencana membangun ratusan rumah lainnya. Hidayat malahan terpaksa harus mendepositokan separuh dari modal usahanya untuk menyelamatkan diri. "Bebas pajak dan tak ada risiko. Apa boleh buat, daripada ambruk," katanya. Nasibnya masih lumayan dibandingkan 38 kontraktor anggota REI, yang sudah tak aktif sama sekali, dari 48 anggotanya di Jawa Barat. Lesunya beberapa sektor usaha itu menyebabkan pemakaian jasa biro iklan untuk melancarkan kampanye jadi berkurang pula. Dalam 13 bulan terakhir ini, Matari Advertising di Jakarta merasakan seretnya billing iklan. Kata Kenneth T. Sudharto, sebagian besar kliennya memangkas anggaran iklan mereka. Sebagian lagi ada yang menyetop sama sekali. Apa boleh buat, untuk menyesuaikan pengeluaran perusahaan dengan penghasilan, Matari terpaksa mem-PHK-kan 50 orang karyawan pendukung, sehingga kini karyawannya tinggal 148 orang. Penggunaan dana diperbaiki dengan membayar ke bank lebih cepat supaya dapat potongan ekstra dan menanamkan uang (deposito) jangka pendek, kemudian ditarik kembali. "Jadi, untuk ini perlu soal manajemen keuangan," katanya. Syukur, mulai Juli lalu, Matari bisa mencapai titik impas. Klien mulai beriklan rumah dan kendaraan mulai diiklankan dengan gencar. Pengusaha tampaknya mulai beranggapan, daya beli konsumen sudah mulai pulih. Benarkah? Eddy Herwanto Laporan Biro Jakarta dan Jawa Barat
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini