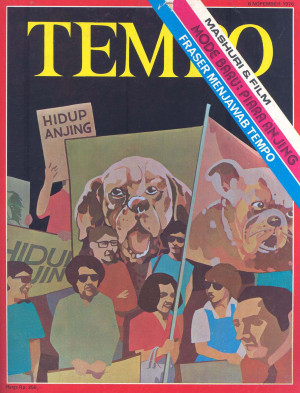USAHA meningkatkan mutu karet menuju SIR (Standar Indonesian
Rubber) sejak beberapa waktu lalu terasa macet. Gagasan yang
dirintis Prof. Sumitro Djojohadikusumo sewaktu masih menjabat
Menteri Perdagangan dulu, kini seakan terlantar. "Banyak di
antara mereka yang gugur di tengah jalan", kata seorang
pengusaha di Jambi. Di sana, di sepanjang sungai Batanghari,
memang pernah muncul tak kurang dari 11 pabrik crumb rubber
sekitar 6 tahun lalu, sebagai tindak lanjut dari keputusan
Menteri Perdagangan. Maksudnya untuk secara bertahap
meninggalkan pengolahan getah karet cara lama yang konvensionil
dan dipandang tak efisien itu. Sebelum itu, untuk mengolah getah
karet rakyat, juga sudah ada 47 buah rumah asap dan 6 buah rumah
penggilingan (remilling).
Tapi malangnya, segala keringanan berupa kredit dan pajak, yang
dilimpahkan untuk gagasan membuat karet bermutu itu, tinggal
beberapa yang bertahan. Dari sekian banyak rumah asap itu kini
hanya Firma Dallmar yang masih mampu mengekspor produksinya.
Namun pabrik crumb rubber tinggal 6 yang masih berputar. Seperti
PT Jambi Waras yang menurut lisensi berkapasitas 18.000 ton
setahun -- tapi mampu menghasilkan crumb rubber 25.000 ton
setahun. Atau pabrik Batanghari Tembessi yang tahun lalu bekerja
melebihi kapasitasnya yang 12.000 ton setahun.
N amun yang merosot produksinya lebih banyak lagi. Sebuah pabrik
crumb rubber milik PT Waringin Kencana memang memiliki kapasitas
produksi 21.000 ton setahun. Ternyata tahun lalu cuma pandai
menghasilkan separoh dari jumlah itu. Sedang punya PT Incrubi,
yang tahun lalu masih bekerja di bawah kapasitasnya, tahun ini
sudah tak ikut lelang karet lagi. Tapi yang paling parah adalah
sekawan pabrik: Panco Rubber, Super, Gumay dan Ureka Raya.
"Boleh dibilang mereka itu sudah terburu mati sebelum bekerja",
tutur Rudy Maukar pengusaha karet yang juga aktlf di Gabungan
Pengusaha Karet Indonesia (GAPKINDO).
Tapi kematian 4 pabrik itu rupanya lebih banyak disebabkan
kurangnya kegiatan. Seperti kata Maukar, "mereka cuma ingin
memanfaatkan fasilitas dari pemerintah saja". Sedang bagi mereka
yang masih bertahan -- selain pusing menghadapi berbagai
pungutan (TEMPO 24 Oktober) -- belum lagi mampu memanfaatkan
bahan baku yang berada nun di tengah hutan sana. "Sulit bagi
para petani untuk menyadap getah di tengah hutan", kata seorang
fabrikan. Selain letaknya jauh dari alur sungai Batanghari, dan
sarana yang kurang, "jalan setapak juga tak ada yang sampai di
tengah hutan", kata seorang penyadap. Itu pula sebabnya hutan
karet di Jambi yang belum terjamah tangan petani dikenal sebagai
'areal tidur'.
Tapi selain areal tidur yang kabarnya banyak dihuni macan itu,
yang agaknya paling mencemaskan para pengusaha karet di Jambi
adalah saingan pabrik-pabrik crumb rubber dari Padang dan
Palembang. Harga beli yang lebih bersaing ketimbang Jambi dengan
sendirinya memikat para produsen getah untuk menjual hasilnya ke
sana. Juga jalan lintas Sumatera yang licin memungkinkan tarif
angkutan yang lebih rendah. Angkutan jalan raya ke Padang dan
Palembang, tak serumit dari Sarko ke Jambi yang harus melalui
dua tempat penyeberangan sungai hingga membuat tarif jadi Rp
12,50 per kilo. Badaruddin kepala direktorat perekonomian
Jambi, beranggapan saingan yang timbul itu soal biasa. "Berbeda
dengan air, harga karet akan mengalir ke tempat yang lebih
tinggi", katanya. Masuk akal. Pelabuhan Jambi, yang belum bisa
dilabuhi kapal samudera, tentu berbeda dengan Padang dan
Palembang yang merupakan pelabuhan ekspor.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini