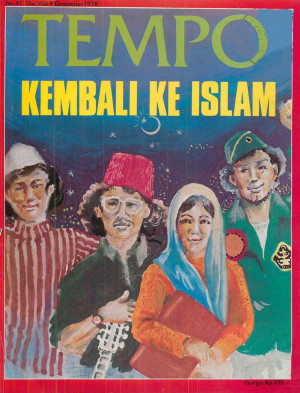DEVALUASI, kata yang kini populer itu, masih menjadi pembicaraan
orang. Tapi teori yang melatarbelakangi adanya devaluasi
barangkali belum banyak yang tahu. Winarno Zain, pembantu khusus
TEMPO, mengemukakan pendapat beberapa ahli:
Jauh sebelum 15 Nopember 1978, pembicaraan tentang perlu atau
tidaknya devaluasi rupiah sudah berlangsung ramai di antara para
pengamat ekonorml Indonesia, termasuk IMF dan Bank Dunia Pada
umumnya mereka bersikap "ya, tapi .... " Uraian mereka semuanya
bertolak dari pendekatan yang dalam ilmu ekonomi disebut
Purcbasing Power Parity.
PPP pada dasarnya merumuskan, apabila laju inflasi satu negara
berkembang jauh dari inflasi negara pasangan dagangnya, maka
suatu penyesuaian kurs diperlukan untuk memulihkan kcmbali norma
perdagangan. Dengan kata lain, misalnya apabila inflasi
Indonesia antara 1971 - Oktober 1978 mencapai 195%, sedangkan
inflasi di AS dalam kurun waktu yang sama "hanya" 57%, kerugian
akan diderita pihak eksportir Indonesia. Sebab kenaikan ongkos
yang lebih tinggi tak diimbangi penghasilan dari dollar,
berhubung selama jangka waktu itu kurs rupiah terhadap dollar
tetap 415.
Makin Merosot
Ada juga yang mengemukakan pendekatan PPP sebenarnya kurang
cukup untuk menjadi dasar putusan dilakukannya devaluasi. Salah
satu yang berpendapat demikian adalah Phyllis Rosendale dari
Departemen Ekonomi Universitas Nasional Australia (ANU). Dalam
Bulletin of Indonesia Economic Studies, Maret 1976, Rosendale
menulis pengetrapan PPP dalam kasus Indonesia harus
mempertimbangkan berbagai hal yang mempengaruhi permintaan dan
penawaran valuta asing, seperti aliran modal termasuk bantuan
luar negeri, penemuan sumber baru atau perbedaan dalam tingkat
produktivitas industri dalam negeri. "Selama lima tahun
terakhir, banyak perobahan terjadi di bidang ini di Indonesia,"
tulis Rosendale.
Di samping itu perlu juga diperhatikan bahwa perobahan dalam
neraca perdagangan akibat perobahan kurs tergantung dari
elastisitas harga atas penawaran dan permintaan beberapa
komoditi tertentu. Dan sudah umum diketahui bahwa elastisitas
ini untuk negara kurang maju seperti Indonesia adalah rendah.
Rosendale juga mengemukakan, sekalipun kurs rupiah terhadap
dollar tetap, tapi karena dollar mengalami depresiasi terhadap
mata uang lain, maka dalam jangka waktu tersebut, rupiah
sebenarnya juga mengalami devaluasi efektif. Dari data yang
dikumpulkann tentang perkembangan kurs rupiah terhadap 9 mata
uang negara partner dagang utama Indonesia, diketahui bahwa
antara 1971 dan 1975 saja, rupiah secara efektif mengalami
devaluasi sebanyak 21%. Devaluasi rupiah terhadap mata uang
utama ini makin merosot lagi, kalau diingat dalam waktu kurang
dari dua tahun nilai dollar turun dengan tajam.
Itu pula yang dikhawatirkan K. Gunadi, 60 tahun, tenaga ahli
pada Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Tenaga Kerja
dan Transmigrasi. Dalam sebuah tulisannya di majalah Prisma,
Juli tahun lalu, pengamat ekonomi yang aktif ini sudah
mensinyalir betapa kurs resmi dollar ketika itu sudah "tidak
realistis lagi dan pada hakekatnya menempatkan posisi moneter
Indonesia pada kedudukan yang labil."
Mengamati inflasi di Indonesia dan di AS selama 1971-1976,
Gunadi -- yang pernah mengepalai Departemen Ekonomi Citibank di
Jakarta -- berkesimpulan: " .... tidaklah tepat untuk
mempertahankan kurs dollar-rupiah sekarang pada tingkat yang
serupa dengan kursnya pada 1971. Sebab depresiasi yang dialami
rupiah selama 6 tahun adalah 122,7% atau 20,5"% setahunnya
dibandingkan dengan dollar sebesar 39,7ø/c atau 6,6% setahunnya."
Bertolak dari pendekatan yang sama Douglas Paauw -- ekonom yang
tak asing lagi bagi mahasiswa ekonomi di sini -- menunjukkan
bagaimana perbedaan inflasi yang membesar antara Indonesia dan
AS telah menimbulkan keganjilan paritas yang merugikan eksportir
Indonesia. Dimuat dalam buletin Ekonomi Keuangan Indonesia, Juni
1978, Paauw menunjukkan untuk mempertahankan tingkat keuntungan
eksportir Indonesia, kurs dollar pada Mei 1977 seharusnya sudah
Rp 695, sedangkan kurs riil yang diterima eksportir (sesudah
dikurangi beberapa pajak) hanya Rp 391 per dollar AS. Ini
berarti ketimpangan biaya yang dialami eksportir Indonesia yang
mengekspor barangnya ke AS mencapai 44%. Eksportir dari negara
tetangga seperti Malaysia, Pilipina dan Muangthai hanya
mengalami "kerugian" antara 6 dan 9% untuk ekspornya ke AS dalam
periode yang sama. Ini karena inflasi di negara tersebut jauh
lebih rendah dari inflasi di Indonesia. Malaysia malahan
melakukan apresiasi dollarnya terhadap dollar AS.
Apakah kemudian Paauw mengusulkan dilakukannya devaluasi rupiah?
Dia ragu-ragu. Dia hanya menulis "dalam situasi yang kompleks
seperti Indonesia, di mana neraca pembayaran didominir oleh
bahan ekstraktif (terutama minyak), di mana pertambahan cadangan
internasional terus terjadi, di mana kecondongan inflasi masih
ada dan di mana pengendalian impor dilakukan untuk keperluan
proteksi dan tujuan-tujuan lain, devaluasi menimbulkan masalah
serius di bidang politik dan ekonomi."
Seperti Rosendale, Paauw juga memikirkan kemungkinan
dilakukannya devaluasi parsiil, di mana si eksportir diberikan
semacam bonus atau premi untuk setiap dollar yang diperolehnya,
untuk terus merangsang usahanya. Ini berarti diadakannya kurs
tersendiri untuk eksportir yang berarti pula adanya kurs ganda
(multiple exchange rate), satu sistim yang pernah dipraktekkan
Indonesia sebelum 1971, tapi yang akhirnya dihentikan. Sistim
kurs ganda berarti campur tangan birokrasi besar sekali. Dan
hambatan administratif ini bisa menimbulkan manipulasi. Dari
segi administratif, keduanya mengakui, pelaksanaan kurs ganda
memang sulit sekali.
Namun, apabila data yang ada dikupas makin dalam nyatalah
argumen untuk melakukan devaluasi rupiah memang kuat sekali.
Benar cadangan devisa Indonesia masih kuat. Tapi itu sebagian
besar karena terjadinya bonanza minyak.
Angka cadangan devisa sebenarnya menyembunyikan betapa masih
rapuhnya industri ekspor bahan tradisionil non-minyak. Selama 7
tahun terakhir, ekspor Indonesia meningkat rata-rata dengan 44%,
tapi ekspor non-minyak hanya naik 29%. Inipun sebenarnya
sebagian besar berasal dari kenaikan harga (seperti yang terjadi
untuk kopi baru-baru ini), sedangkan volume ekspornya sendiri
tak menunjukkan peningkatan berarti.
Ini berarti satu pukulan bagi usaha pembukaan lapangan kerja.
Selama 7 tahun terakhir ini perkembangan sektor ekspor pertanian
yang umumnya bersifat padat karya, belum berhasil meningkatkan
lapangan kerja. Karena itu, cadangan devisa yang nampaknya baik
itu sebenarnya masih merupakan kedok yang bersifat sementara.
Pertumbuhan ekspor sektor pertambangan terutama minyak yang
menanjak cepat itu dimungkinkan karena menggunakan peralatan
padat modal yang menyerap sedikit tenaga kerja. Sumbangannya
terhadap penambahan tenaga kerja sangat minim.
Akhirnya satu kenyataan pahit harus dihadapi. Minyak makin turun
peranannya sebagai penghasil devisa. Penurunan kegiatan
eksplorasi, pertambahan konsumsi minyak dalam negeri yang cepat,
meningkatnya kesulitan pemasaran di luar negeri karena makin
banyaknya saingan, menyebabkan produksi dan ekspor minyak akan
turun, dan penurunan ini belum bisa ditutup dengan penerimaan
dari sumber lain.
Diperkirakan mulai 1980 titik balik akan terjadi pada neraca
pembayaran Indonesia. Dari surplus tiap tahun tadinya, neraca
pembayaran Indonesia akan menderita defisit sekitar US$ 800
juta. Defisit itu akan meningkat lagi menjadi US$ 1,7 milyar
pada 1982, satu prospek yang sangat mencemaskan pemerintah
Indonesia tentunya.
Tak heran kalau kemudian buletin mingguan Business Asia, sebulan
sebelum devaluasi rupiah menjadi kenyataan, meramalkan:
"Pemerintah Indonesia mungkin akan melakukan devaluasi rupiah
dengan 50% atau 100% dalam waktu dua tahun ini." Ternyata tak
usah menunggu begitu lama.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini