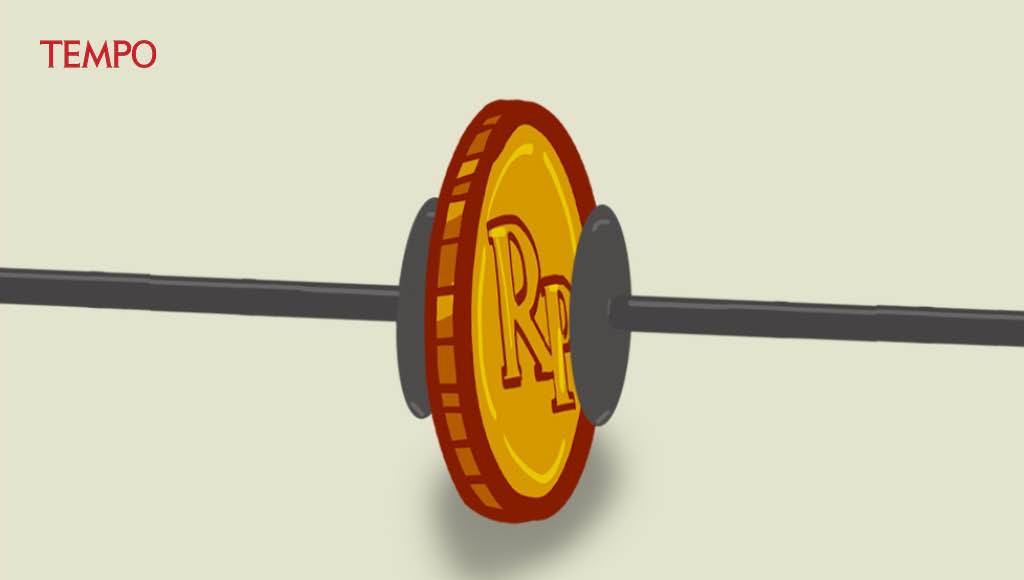Ini bukan pleidoi untuk Cendana. Tapi, boleh percaya boleh tidak, daftar penunggak utang kakap ternyata bukan cuma diisi oleh perusahaan milik anak keturunan dan kolega bekas presiden Soeharto. Banyak juga nama baru, asing, atau bahkan tak pernah terdengar gaungnya dalam rimba persilatan bisnis. Mereka tiba-tiba saja nongol serta membuat kita merasa kaget dan kecolongan: perusahaan "tanpa nama" itu bisa juga ikut membobol lemari bank.
Beberapa di antaranya memang punya jalur politik yang hebat. Tapi mereka yang tak punya beking pun bisa begitu gampang menjala kredit, kadang-kadang dalam jumlah yang begitu mengejutkan. Para pengurus bank seperti tak peduli. Walaupun kredit telah melampaui jumlah yang diizinkan, pinjaman baru tetap saja diberikan.
Kalau mau diurut-urut, para pengemplang utang kakap ini punya kecenderungan yang sama: nilai proyeknya terlihat terlalu sepele untuk mendapatkan kredit yang begitu besar. Apakah ini petunjuk bahwa para pengurus bank punya andil dalam menciptakan pengemplang utang? Wallahualam. Yang pasti, para penunggak utang ini biasanya punya hubungan yang mesra dengan pengurus bank.
Inilah profil beberapa penunggak utang kakap yang belum banyak diungkap itu. Ada yang agak misterius, aneh, dan mungkin juga lucu.
Kelompok Gerak Maju
Tak banyak yang mengenal Gerak Maju. Nama yang dinamis ini baru muncul di panggung bisnis Jakarta sekitar dua bulan lalu. Padahal, Gerak Maju inilah "juara pertama" dalam daftar 857 penunggak utang, dengan rekor tunggakan Rp 6,7 triliun lebih.
Usut punya usut, Gerak Maju berkaitan dengan PT Mantrust, perusahaan industri pertanian dan perdagangan milik Teguh Soetantyo. Adalah Johny Harry Sutantyo, anak Teguh, yang mewarisi Mantrust, setelah ayahnya meninggal, lima tahun lalu. Gerak Maju lantas digabung dengan PT Dian Aneka Sejahtera, perusahaan milik Johny, yang juga mewarisi utang Mantrust.
Menurut pengamat politik Harold Crouch, pada zamannya nama Teguh Soetantyo tergolong sakti. Awal 1960-an, Mantrust adalah pemasok logistik bagi Angkatan Darat. Ketika Badan Urusan Logistik (Bulog) dipimpin Achmad Tirtosudiro, Teguh menggaet kontrak-kontrak penting, misalnya impor beras US$ 2,5 juta dari Jepang di akhir 1960-an. Ternyata, Mantrust cuma membelanjakan US$ 1,8 juta. Sisanya? Tak pernah jelas. Skandal ini baru terbongkar setelah dua pejabat Mantrust ditangkap polisi Tokyo gara-gara melanggar aturan valuta asing (valas). Tapi kebusukan ini tak sempat merebak, setelah asisten pribadi Soeharto, Soedjono Hoemardani, berangkat ke Jepang dan membebaskan dua direktur Mantrust itu.
Kesandung di Jepang tak membuat kesaktian Teguh pudar. Mantrust berbiak menjadi 42 perusahaan multibisnis. Usahanya meliputi perdagangan, produksi kompos, agrobisnis, hotel, dan restoran. Tapi Teguh agaknya kurang pintar memanfaatkan kedekatannya dengan pusat kekuasaan. Menurut data Wilson Nababan, konsultan bisnis CISI Raya, 27 dari 42 perusahaan Mantrust bangkrut.
Bukan cuma itu. Sejumlah anak perusahaan Mantrust menyisakan tunggakan yang menggunung. Gerak Maju, pembuat pupuk kompos dan jamur, menebar utang di sejumlah bank BUMN dengan nilai Rp 4,2 triliun. Bali Raya, anak perusahaan Mantrust dalam bidang pengalengan ikan tuna, menunggak utang hingga Rp 1,2 triliun. Sedangkan Tuwuh Agung, perusahaan pembiakan jamur merang yang berpusat di Yogyakarta, mengemplang Rp 1,4 triliun. Total jenderal, Mantrust kini terbebani utang macet hingga Rp 6,8 triliun.
Bagaimana Johny akan menyelesaikan tunggakan utang itu? Entahlah. Ketika ditemui di kantornya di kawasan Senen, Johny tak ingin berkomentar banyak. Ia cuma menyerahkan segala urusan utangnya kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
Beberapa anak perusahaan Mantrust memang masih beroperasi normal. Tuwuh Agung, misalnya, hingga awal tahun ini masih rajin mengirimkan sejumlah sample ekspor jamur merang ke beberapa perusahaan makanan di Amerika Serikat. Tapi beberapa perusahaan yang lain sudah mati suri. Menurut Hendri Sutandinata, Ketua Asosiasi Perusahaan Pengalengan Ikan Indonesia, Bali Raya termasuk satu dari lima pabrik pengalengan tuna yang bangkrut akhir tahun lalu.
Multi Strada Arah Sarana
Reputasi Multi Strada sayup-sayup sampai. Kendati cuma terdengar lamat-lamat, utang kelompok usaha yang satu ini bukan main: Rp 2,3 triliun. Kalangan bisnis bertanya-tanya: sedahsyat apa gerangan kelompok usaha yang menduduki peringkat kelima dalam daftar penunggak utang kakap ini? Sampai kini, rasa penasaran belum kunjung terobati. Tak satu sumber pun bisa mengupas tokoh misterius di balik kelompok Multi Strada ini dengan tuntas.
Pelacakan TEMPO menunjukkan, kelompok usaha ini dimiliki kakak-adik Mulianto dan Hadi Wijaya Tanaga. Dalam bisnis perbankan, Tanaga bersaudara sempat terpeleset. Maret lalu, Indomitra Development Bank atau Indotrade milik duet ini dibekukan bersama 38 bank lainnya.
Dalam bisnis mobil, Tanaga sempat berjaya. Duet inilah yang menguasai saham Star Surya. Menggandeng Wearnes International, Star Surya memasok mobil supermewah—Daimlers, Rolls Royce, Bentley, dan Jaguar—ke Indonesia. Melalui Star Surya itu juga Tanaga mengimpor mobil-mobil luks untuk pelbagai konferensi internasional, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain di Asia Tenggara. Pada awal 1990-an, Star Surya menggandeng Daewoo untuk memasarkan mobil produksi Korea Selatan itu di Singapura, Australia, dan Indonesia.
Jerat terbesar yang akhirnya menelikung Tanaga adalah bisnis ban. Pada 1993, Star Surya menggandeng Pirelli untuk membuka pabrik bank di Indonesia. Pabrik yang diberi nama Oroban Perkasa ini terlihat perkasa dengan kapasitas produksi sampai 1,1 juta ton.
Sialnya, penjualan Oroban terus terseok-seok. Pangsa pasar Oroban cuma 2 persen dari konsumsi ban di Indonesia. Rekor ini menempatkan Oroban pada posisi paling buncit di antara delapan pabrik ban lainnya. Pada 1997, produksi Oroban cuma 22 ribu atau 2 persen dari kapasitas produksi terpasang. Dengan beban kapasitas nganggur sebesar itu, kondisi finansialnya jelas kembang-kempis. Upaya Star Surya menggaet Continental Jerman tak banyak mengubah nasib Oroban.
Kini operasi pabrik Oroban—sudah berganti nama menjadi Multi Strada—di kawasan Lemahabang, Bekasi, seperti mati suri. Dari belasan gedung di pabrik 46 hektare itu, cuma satu cerobong yang tampak berasap. Rumput di sekeliling pabrik itu sudah meliar dan meninggi lebih dari semeter. "Dulu, pabrik ban ini ramai. Ribuan karyawan menghambur keluar saat makan siang. Truk juga hilir-mudik. Kini sepi," kata seorang tukang ojek di kawasan itu.
Lalu, untuk apa gerangan kredit triliunan tadi mengucur? Tak ada jawaban yang memuaskan. Petinggi Bank Bumi Daya (BBD) yang memberikan bagian kredit terbesar kepada Multi Strada mengaku tak punya data rinci. Hanya, petinggi BBD ini mencatat, itikad buruk Tanaga sudah lama tercium. Awal 1990-an, cicilan bunga kreditnya sudah jarang dibayar.
Meskipun begitu, ia mengakui, BBD sulit mengambil tindakan. Soalnya, Tanaga tergolong cukup piawai membingungkan administrasi BBD. Dalam hal pengajuan kredit, misalnya, Tanaga tak pernah menggunakan nama Multi Strada. "Dia selalu memakai Oroban, yang sudah mati. Partner asing pun sering berganti tanpa penjelasan. Ini menyulitkan," kata sumber ini. Siasat Tanaga tampaknya disokong oleh sistem administrasi data BBD yang, kabarnya, amburadul. Akibatnya, dengan gampang uang Rp 2,3 triliun digangsir.
Susahnya, sejak Indotrade dibekukan, duet Tanaga seperti menghilang. Pelacakan TEMPO ke rumah Hadi Wijaya di Pondok Indah tak membuahkan hasil. Rumah mewah seluas 4.000 meter persegi yang dilengkapi kolam renang itu tampak sepi. Menurut keterangan penjaga rumahnya, Hadi Wijaya sekeluarga "mengungsi" ke Singapura, sepekan menjelang pemilu. "Sejak itu, mereka tak pernah pulang," katanya. Ke rumah saja tidak, apalagi ke BPPN!
Margabumi Matraraya
Kantor Margabumi Matraraya tak seheboh nilai utangnya. Perusahaan konstruksi yang berkantor di rumah toko (ruko) empat lantai berukuran 10 x 15 meter persegi di kawasan Roxy Mas, Jakarta Pusat, ini tercatat punya tunggakan utang hampir Rp 2,9 triliun. Tak ada papan petunjuk atau papan nama yang menandai kantor pengelola jalan tol ini.
Menurut Wilson Nababan, Margabumi sudah kacau sebelum lahir. Perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki pengusaha tak terkenal Moertomo Basoeki ini mengelola tiga jalan tol di Jawa Timur. Tapi sebagian proyek itu sudah menemui banyak "kejanggalan" sejak perencanaannya.
Nilai proyek jalan tol Surabaya-Gempol, misalnya, tiba-tiba melambung dua kali lipat dari rencana semula: Rp 133 miliar menjadi Rp 272 miliar. Kemudian, setelah jalan itu beroperasi pun, pada 1985, hambatan menghadang. Jalan tol itu ternyata begitu sepi. Proyeksi awal menyebut arus lalu-lintas harian sampai 5.000 mobil, tapi ternyata mobil yang lalu-lalang tak lebih dari 1.000. Akibatnya, penghasilan Margabumi jeblok. Boro-boro untuk melunasi utang, untuk sekadar membayar gaji pegawai, memelihara jalan, dan menanggung biaya operasional saja Margabumi sudah kewalahan.
Untuk menutupi pendarahan itu, Bank Exim, pemberi utang Margabumi, mencari jalan keluar. Exim "mengajak" Margabumi bermain valas. Dengan jalan pintas itu, penghasilan bisa digenjot sehingga utang bisa cepat lunas. Modalnya sepele, cuma menaruh simpanan US$ 20 juta, nanti Bank Exim yang memainkannya. Magabumi setuju. Inilah awal dari drama Exim Margabumi yang tragis itu.
Ketika itu, Agustus 1997, badai krisis mulai bertiup. Berbekal keyakinan, "fundamental perekonomian yang kuat", dan optimisme otoritas moneter bahwa serangan terhadap rupiah cuma sementara, Exim terus menjual dolar dalam kontrak forward pada harga miring. Tapi, apa mau dikata, "fundamental ekonomi" ternyata cuma slogan di bibir. Menghadapi serbuan juragan duit kelas kakap dari luar negeri, rupiah kolaps.
Ketika harga dolar makin tinggi dan potensi kerugian makin membesar, Exim tak juga mau menutup kerugian. Malah, sebaliknya, dengan alasan tugas bank sentral untuk terus mengintervensi pasar dengan "menjual dolar", kerugian makin hebat. Akhir cerita, Bank Exim merugi triliunan rupiah. Margabumi, yang terpaksa ikut menanggung renteng, ikut dibebani utang baru. Ditambah kekalahan main valas, total utang Margabumi menjadi Rp 2,9 triliun. Padahal, kekayaan perusahaan ini tak lebih dari Rp 400 miliar!
Lalu, apa yang harus dilakukan sekarang? Inilah yang agaknya sedang jadi soal. Menurut Margabumi, sejak November lalu, Bank Exim sudah menyepakati perjanjian penjadwalan pelunasan utang. Menurut perjanjian itu, utang dilunasi dengan sistem bagi hasil selama masa konsesi pengelolaan jalan tol, yang berakhir pada tahun 2016. Komposisinya, 93,5 persen penghasilan jalan tol diserahkan kepada Bank Exim, baru sisanya yang 6,5 persen untuk Margabumi.
Sistem pelunasan ini sebenarnya tak berbeda dengan model membayar utang dengan kepemilikan saham alias debt to equity swap. Dengan perjanjian pelunasan utang ini, 93,5 persen saham Margabumi pada dasarnya sudah menjadi milik Bank Exim. "Kami bekerja untuk Bank Exim yang membayari kami gaji," kata Glenn Gouw, Direktur Keuangan Margabumi.
Yayasan Karyawan BDN
Kendati utangnya cuma Rp 1 triliun, persoalan yang membelit Yayasan Karyawan Bank Dagang Negara (BDN)—lazim disingkat YKP—tak kalah rumit. Saking ruwetnya persoalan itu, pengurus yayasan ini ogah meneken surat sanggup yang disyaratkan BPPN untuk mengikuti program restrukturisasi utang. "Ada beberapa ganjalan dalam surat sanggup itu," kata Samsul Arifin, ketua ex officio YKP.
Beberapa di antara ganjalan itu adalah kesanggupan menyetor tambahan modal, membayar ongkos konsultan dari BPPN, dan membayar berbagai biaya restrukturisasi utang. YKP menolak membayar rangkaian ongkos yang tak sedikit itu karena, "Kami sudah tak punya uang." Kas yayasan, rencananya, akan dipakai untuk membayar pesangon karyawan yang terkena pemecatan akibat bergabungnya BDN ke dalam Bank Mandiri.
Urusan YKP ke BPPN berawal dari upaya menggemukkan kas. Bersama PT Dana Pensiun dan PT Usaha Gedung BDN, yayasan karyawan ini membentuk badan usaha bernama PT Staco Graha. Kedekatan dengan para direksi bank BUMN membuat Staco tergiur memanfaatkan kemudahan kredit. Dengan pinjaman Rp 689 miliar dari BDN, plus Rp 200 miliar dari Exim (total jenderal hampir Rp 900 miliar), Staco membangun Hotel Park Lane di terusan Jalan Satrio di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Sayang, sebelum hotel itu rampung 100 persen, badai krisis moneter melanda.
Kalaupun hotel itu akhirnya bisa beroperasi, persoalan Park Lane tak otomatis rampung. Menurut sejumlah pengamat, nilai proyek hotel bintang empat itu tak sebanding dengan jumlah kredit yang dicairkan. Konsultan properti, Panangian Simanungkalit, misalnya, yakin investasi Park Lane tak sampai Rp 1 triliun. Menilik lokasi yang bukan kelas satu, ia memastikan nilai hotel ini cuma Rp 408 miliar. Untuk itu, ia mengingatkan agar BPPN perlu ekstra-hati-hati menilai aset Staco Graha. "Indikasi mark-up terlihat jelas," katanya.
Kejadian serupa muncul dari yayasan karyawan BBD, yang mendirikan PT Estika Yasakelola. Perusahaan ini terjerat tunggakan macet Rp 490 miliar lebih, yang tak jelas entah untuk proyek apa. Yang pasti, Estika (dan juga Staco) merupakan pemegang saham PT Chandra Asri Petrochemical, dengan setoran modal (kala itu) US$ 54,8 juta. Boleh jadi setoran modal Estika ini merupakan hasil konversi utang Chandra Asri ke BBD. Ketika itu, bank memang dilarang memiliki saham di perusahaan non-keuangan. Sebagai ganti, Estika mengambil alih utang "Chandra Asri" dengan bayaran saham.
Dengan posisi kuat seperti itu, Estika merasa tak perlu meneken surat sanggup. Tentang penolakan ini, Direktur Internal Estika, Slameto, hanya berkata singkat, "Kami ini anak perusahaan BBD. Masa, diperlakukan sama seperti debitur lain?"
Apa kalau sudah "anak kandung" harus ada perlakuan istimewa?
Mardiyah Chamim, Ali Nur Yasin,Wens Manggut, Iwan Setiawan
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini